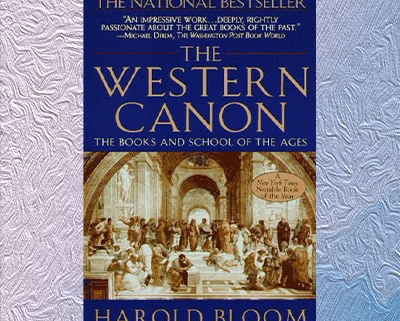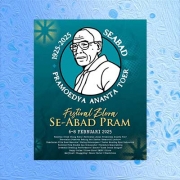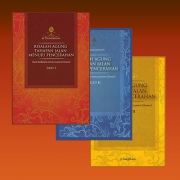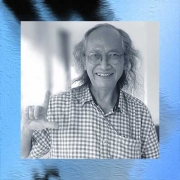Cultural Studies: Mendebat Kanon Sastra
Oleh: Walang Sungsang*
Pengertian teks kanon awalnya muncul dari tradisi otoritas Kristiani. Vatikan membedakan adanya teks-teks sakral yang asli dan dapat dipercaya kebenarannya dengan teks-teks tak asli yang masih diragukan kebenarannya. Teks-teks asli yang ditetapkan Vatikan sebagai sumber kebenaran disebut sebagai teks kanon. Dan teks-teks religi yang diragukan keasliannya dan tak dipakai sebagai rujukan resmi dikategorikan sebagai teks-teks apokrif.
Artikel berjudul Literature, Culture and Canon yang menjadi bagian dari buku karya Andrew Milner: Literature, Culture, Society yang diterbitkan Universitas Monash secara menarik membahas tentang masalah kanon sastra Inggris dalam perspektif Cultural Studies. Milner melihat adanya pergeseran atau pembalikan dari studi sastra biasa ke Cultural Studies membuat terjadinya dekonstruksi atau perubahan cara pandang dalam memahami sastra dan kebudayaan secara elementer. Secara informatif Milner dalam artikel tersebut menguraikan teoritisi-teoritisi mana yang tetap mempertahankan kanon sastra dan menganggap kritik sastra yang bertolak dari standar karya-karya kanon tetaplah penting. Miller juga memberikan peta pemikiran teoritisi-teoritisi mana yang telah membuang paradigma kanon dalam sastra.
Secara umum apa yang tergolong karya-karya kanon sastra Inggris menurut Milner adalah karya-karya otentik dan imajinatif yang mampu memberi pengaruh besar terhadap karya-karya sastra sesudahnya seperti misalnya karya Shakespeare, T.S Elliot atau Goethe. Kanon sastra dipandang adalah karya sastra yang mampu menyajikan nilai-nilai secara dalam dan kompleks. Menurut Milner di dunia akademis, studi sastra Inggris konvensional yang mempelajari naskah-naskah klasik dan studi sastra bandingan (comparative literature) adalah studi-studi yang mempertahankan paradigma kanon ini. Universitas Cornell sudah mengajarkan sastra bandingan sejak 1871, Universitas Michigan sejak 1887 ,sementara Universitas Harvard sejak 1890. Disusul kemudian universitas-universitas di Australia, Artinya studi mengenai kanon sastra telah tertanam sejak lama.
Salah satu akademisi yang mempertahankan habis-habisan pentingnya kanon sastra menurut Milner adalah F.R Leavis. Bagi Leavis, sebuah kanon sastra dapat menjadi identitas kebudayaan nasional sebuah negara. Para pembaca kanon sastra dapat menemukan hal-hal otentik dan pemaknaan tertentu dari pergulatan sang pengarang kanon sastra terhadap sejarah bangsanya. Kebudayaan nasional yang sehat menurut Leavis sedikit banyak juga ditentukan oleh banyaknya apresiasi dan studi-studi terhadap kanon-kanon sastra. Dalam mendekati karya-karya kanon, Leavis lebih menekankan analisis terhadap internal teks atau unsur-unsur intrinsik dalam teks. Dia melihat pendekatan demikian adalah pendekatan yang organik.
Dia maka dari itu menolak pendekatan-pendekatan telaah sastra dari perspektif sosiologi atau antropologi. Dalam hal ini sosiologi sastra atau antropologi sastra. Bagi Leavis pendekatan-pendekatan demikian adalah pendekatan eksternal dalam menghampiri karya sastra. Leavis juga sangat membedakan antara karya sastra dan sastra populer. Ia menolak memasukkan karya-karya sastra populer ke dalam kajian karya sastra karena menurutnya tidak menampilkan kualitas yang tinggi secara organik. Bagi Leavis, karya sastra berkualitas secara kodrati di kebudayaan manapun selalu muncul dari minority culture.
Pandangan-pandangan F.R Leavis inilah yang dalam perkembangan teori sastra selanjutnya disangkal dan diruntuhkan oleh para ahli. Terutama ketika munculnya pada tahun 1960-an gagasan-gagasan Post Modern dan kemudian Culture Studies. Gagasan-gagasan Leavis dianggap diskriminatif. Dua akademisi pelopor yang berusaha meruntuhkan status Istimewa kanon dalam sastra Inggris adalah Raymond Williams dan Richard Hoggart. Dalam bukunya Culture and Society (1958) dan The Long Revolution (1961), Williams memberi perhatian besar terhadap kebudayaan massa. William menolak peran sastra sebagai High Culture atau elitisme dalam kebudayaan. Sebuah kebudayaan menurut Wiliams bukan hanya diciptakan oleh kelompok minoritas intelektual dan hanya berupa karya-karya imajinatif. Dalam bukunya itu kebudayaan dipahami Wiliams sebagai pola-pola kebiasaan cara berpikir, perkembangan intelektualitas seluruh masyarakat termasuk seni dan keseluruhan cara hidup – the way sebuah kelompok masyarakat. Menurut Williams konsep kebudayaan memainkan peran sangat krusial dalam mendefinisikan seni sedari awal. Williams memperluas konsep kebudayaan. Dia melihat revolusi industri dan revolusi demokratik kebudayaan memperluas demokrasi komunikasi.
Salah satu pandangan prinsipil Raymond Williams yang membedakannya dengan pandangan F.R Leavis dan akademisi lainnya yang mengkaji sastra secara tradisional adalah hakikat karya sastra. Bagi F.R Leavis dan kaum tradisional, sebuah karya sastra apalagi kanon secara estetis adalah abadi atau timeless. Sementara bagi Williams, kebudayaan adalah selalu merupakan konstruksi sosial. Ia tak abadi. Jika kebudayaan adalah sebuah konstruksi sosial maka teks apapun harus dilihat dalam konteks ketidaksetaraan (inequality) kelas sosial. Juga teks sastra termasuk yang dianggap sebagai kanon-kanon.
Dengan munculnya pandangan kebudayaan Raymond Williams maka antropologi dan sosiologi kini menjadi relevan kembali sebagai alat untuk mengkaji sastra. Sebab objek studi antropologi dan sosiologi sesungguhnya adalah “ a whole way of life.” Teori-teori kebudayaan dari Emile Durkheim, Talcot Parson sampai sosiologi kritis Max Horkheimer, Zygmunt Bauman sampai Walter Benyamin menjadi berguna untuk memahami dan melihat jernih bahwa sastra adalah bagian dari kebudayaan. Benyamin misalnya mengupas tentang adanya “barbarisme “dalam ketidaksetaraan sosial.
Selama ini F.R Leavis beranggapan bahwa analisa antropologi dan sosiologi akan menjadi ancaman bagi sastra karena disiplin-disiplin itu akan “meruda paksa” sastra dengan telaah yang terlalu eksternal. Ia melihat pendekatan-pendekatan semacam itu bagian dari pendekatan empirisme postivisme yang akan menindas nilai-nilai sastra sendiri. Sedemikian ketakutannya sampai ia memunculkan istilah Technologico-Benthamite untuk menunjuk pendekatan-pendekatan eksternal dalam sastra. Benthamite diambil dari istilah filsuf Jeremy Bentham tentang perlunya ruang-ruang kontrol – panoptisme untuk selalu mengawasi masyarakat. F.R Leavis ketakutan bahwa pendekatan-pendekatan atau pembedahan dari sisi eksternal itu – yang tidak menganggap sastra sebagai karya special – kurang mampu untuk menyelami keindahan-keindahan dan nilai-nilai kemanusiaan yang muncul secara organik dari dalam novel-novel atau puisi-puisi sendiri.
Kajian-kajian Cultural Studies dan Post Modernisme yang menampik adanya pentasbihan kanon-kanon sastra namun tidak terbendungkan. Salah satu teoritikus yang melengkapi pandangan Raymond Williams adalah Richard Hoggart. Pada tahun 1957, Hoggart lebih dahulu dari Williams – menerbitkan buku The Uses of Literacy. Buku ini adalah titik awal yang menandaskan pergeseran studi sastra ke kebudayaan. Hoggart melalui bukunya membongkar pandangan-pandangan F.R Leavis sebagai elitisme dan nostalgik. Hoggart dan Williams sama-sama memperluas kajian sastra agar tidak menuju eksklusivisme. Keduanya memasukkan kebudayaan popular sebagai subyek studi baru. Hoggart pada tahun 1964 mendirikan The Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies. Kajian kebudayaan popular yang dilakukan lembaga Cultural Studies ini sampai meliputi pembacaan terhadap progam-progam televisi, soap opera – opera-opera sabun, film-film James Bond, Superman, komik-komik, Cyber Punk dan sebagainya.
Perkembangan pesat Cultural Studies juga didukung munculnya filsuf-filsuf progresif di tahun 70-80 an yang secara tidak langsung, pandangan-pandangannya mendukung asumsi-asumsi Cultural Studies. Pierre Bordieu, filsuf Perancis misalnya dikenal memiliki pemikiran yang menolak elitisme kebudayaan. Secara politis cultural studies juga dekat dengan politik-politik radikal yang membela yang lemah atau tersingkirkan. Studi sastra konvensional menurut Cultural Studies cenderung melegitimasi politik konservatif. Sebaliknya Cultural Studies seirama dengan political dissent, kaum yang memiliki pendapat berbeda dalam politik.
Betapapun serangan bertubi-tubi dari Cultural Studies melemahkan argumentasi-argumentasi kalangan akademisi yang mempertahankan perlunya kanon-kanon dalam sastra, dari Universitas Yale Amerika tetapi tahun 80 an muncul seorang pemikir dan teroritisi besar sastra yang membela pentingnya kanon-kanon sastra. Dia dapat disebut menghidupkan kembali pandangan-pandangan F.R Leavis. Namanya Harold Bloom. Dia menullis buku berjudul: The Western Canon. Bloom adalah seorang akademisi yang dikenal mendekati karya sastra dengan pisau bedah yang sangat terpengaruh psikoanalisa Freudian. Ia juga menggunakan metode dekonstruksi Jacques Derrida. Harold Bloom dikenal sebagai seorang ahli yang menyebarkan post-strukturalisme dan dekonstruksi di Amerika Utara. Ia bahkan pernah bekerja sama dengan Jacques Derrida dan memberikan kesempatan Derrida selama beberapa tahun mengajar di Yale.
Dalam buku The Western Cannon, Bloom mempertahankan kanon sastra. Dengan menggunakan perangkat analisa psikoanalisa sampai post strukturalisme, ia membedah kanon-kanon sastra barat. Ia menganggap kanon sastra seperti karya-karya Shakespeare adalah tetap sebuah literary excellence.Tujuan studi sastra adalah mencari nilai-nilai yang dapat mentransendir atau mengatasi prasangka-prasangka partikular. Dan itu dapat ditemukan pada karya-karya Shakespeare. Karya-karya sastra Shakespeare menurutnya universal dan menampilkan primal aesthetic value. Tanpa kanon dan tanpa ulasan atau kritik terhadap kanon menurut Bloom mengeritik pendekatan-pendekatan dekonstruksi Derridean atau teori kontemporer lain yang sebaliknya menggunakan pendekatan itu untuk membunuh atau menghancurkan kanon-kanon sastra. Bloom sampai menjuluki pendekatan-pendekatan kontemporer seperti Feminisme, Lacanian, Dekonstruksi, Semiotik, New Historisisme, Marxis yang cenderung membunuh kanon sastra sebagai “School of Resentment.” Bloom khawatir sekali di masa depan studi mengenai sastra barat akan didominasi oleh studi kebudayaan populer dan karya-karya di luar sastra klasik. Sebagaimana dikutip Milner, Bloom menyatakan kerisauannya: “What are now called “Departments of English” will be renamed departments of “Cultural Studies” where Batman comics, Mormon themes park, television, movies and rock will replaces Chaucer, Shakespeare, Milton, Wordsworth, Wallace Stevens. “
Kemunculan Harold Bloom membuat pemikir-pemikir sastra yang tak sepakat dengan adanya kanon – merespon dengan melahirkan argumentasi-argumentasi tandingan. Dari Amerika sendiri mengemuka Terry Eagleton. Dia kritikus sastra yang beraliran Marxis. Dia menyanggah pendapat Bloom dan mereka lain yang membela kanon. Menurut Eagleton tidak ada karya sastra klasik maupun modern yang bernilai dalam dirinya sendiri. Semua membutuhkan penerimaan dan tanggapan masyarakat yang membacanya. “Whatever the literature maybe, it is fundamentally a social construct and moreover in historical terms a comparatively recent such construct at that.” Muncul juga akademisi Tony Bennet. Teoritisi sastra dari Australia ini menulis buku Outside Literature. Ia seorang Post Modernisme Relativism. Ia mengritik baik pendekatan Harold Bloom, pendekatan marxisme Terry Eagleton maupun Cultural Studies. Menurut Bennet kajian-kajian filsafat estetika salah memahami sastra dan penilaian artistiknya sebagai sesuatu yang universal. Padahal menurutnya dalam realitas selalu ada aturan-aturan partikular antar bidang-bidang spesifik. Wacana estetikdalam sastra misalnya menurutnya hanyalah salah satu dari parameter nilai yang tak menjadi wacana utama dalam bidang kuliner atau olahraga.
Dari artikel Andrew Milner ini kita dapat melihat perdebatan-perdebatan antara mereka yang mempertahankan pentingnya kanon dalam sastra dan mereka yang menolaknya. Kita dapat melihat perspektif yang berbeda antara studi sastra konvensional dan Cultural Studies. Andrew Milner sendiri berpendapat bahwa kajian-kajian Cultural Studies tak terelakkan untuk memahami aneka dimensi kebudayaan kontemporer. Dia juga tak melihat bahwa kajian-kajian Cultural Studies akan membunuh kanon sastra namun justru secara kreatif bisa mendekati kanon sastra melalui jalan-jalan yang tak terduga serta menarik bukan hanya jalan yang bagaikan agama mengkultuskannya – yang menjadikan pendekatan sastra bak quasi-religious worship. Demikan pasasi Milner: We should take all aspect of our contemporary culture very seriously, including film and television. And secondly, it insist there are more interesting way to approach canonical “literary” text than through acts of quasi religious worship.”
*Penulis penyuka sastra, tinggal di Desa Pager Gunung, Magelang