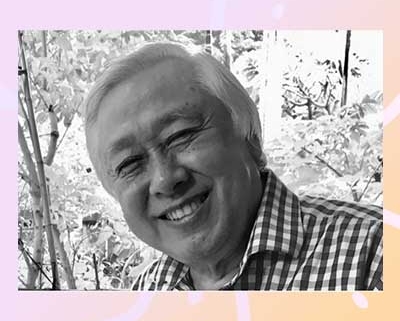In Memoriam Siti Farida Srihadi: Intelektual Seni dan Pendamping Sejati
Oleh Agus Dermawan. T
Pada hari Senin, 6 Maret 2023 pagi, saya mendapat berita yang menyesakkan dada: Dra Hj Siti Farida Binti Abdullah Nawawi, M Hum meninggal dunia di rumahnya, Jalan Bukit Arco, Cipete, Jakarta Selatan. Saya tahu Farida sudah sakit agak lama, setidaknya sejak beberapa bulan setelah sang suami – pelukis Srihadi Soedarsono – tutup usia pada 26 Februari 2022. Namun sakit itu pelan-pelan relatif membaik. Sehingga keluarga, dokter dan suster lebih tenang menjaganya. Namun dalam ketenangan itulah perupa dan pemikir seni kampiun ini pergi.
“Mami wafat dengan posisi sempurna. Wajahnya tenang, dengan kedua telapak tangan berada di dada tangannya seperti berdoa. Mami seperti tahu ada yang akan menjemput. Persis seperti Papi setahun lalu,” kisah Krisnamurti Syailendra, puteranya.
Pada Minggu, 12 Maret 2023 kemarin segenap keluarga dan kerabat menghelat pembacaan Surat Yasin, doa dan tahlil untuk mengenang 7 hari wafatnya. Acara diselenggarakan di Masjid Baiturrahman, Depok Timur. Sebuah rumah ibadah yang pendiriannya banyak didukung oleh Farida dan Srihadi sebagai perupa filantrop.

Siti Farida ketika muda. (Foto: Arsip Penulis)

Farida dan Srihadi. (Foto: Arsip Penulis)
Selebar mata-angin
Farida selama ini dikenal sebagai pendamping utama pelukis Srihadi Soedarsono. Ia disebut sebagai manajer, sosialisator, promotor, aktualisator, bahkan kurator setiap pameran karya-karya suaminya. Upayanya dikenal cerdas dan bermartabat, sehingga Srihadi menempati posisi yang sangat penting dalam sejarah seni rupa Indonesia. Dengan karya-karya yang terjaga mutunya, dengan harga lukisan yang tinggi nominalnya. Beruntun dengan itu, sebagai figur Srihadi jadi sangat dihormati oleh berbagai kalangan. Meskipun Farida agak menolak sebutan peran itu. “Mas Sri menjadi besar karena dirinya sendiri,” katanya.
Namun sesungguhnya Farida layak dikenang tidak sekadar sebagai pendamping dan penjunjung Srihadi saja. Karena dalam dunia seni rupa, kiprah pemikiran dan praktik seni Farida juga harus dicatat dengan tinta tebal. Ia malang-melintang di medan seni selama setengah abad tanpa jeda.
Saya mengenal Farida sejak 40 tahun silam. Perkenalan saya dengan Bu Farida – begitu saya selalu memanggil – bersamaan dengan perkenalan saya dengan Srihadi Soedarsono.

Farida ketika muda dengan anak-anak Bali. (Foto:Arsip Penulis)
Perjumpaan saya dengan Farida tidak terhitung. Dalam tiap kali pertemuan, obrolan seru selalu mengalir. Farida saya kenal sebagai wanita pelukis yang memiliki pemikiran luas dan mendalam. Namun di balik keseriusannya dalam seni, ia suka mengobrol hal ihwal sehari-hari. Bahan pergunjingan master humaniora ini acapkali justru bukan soal seni rupa. Ia bisa mendadak membicarakan tenun ikat Lombok, topi Melania Trump, imitasi tas Fossil Satchel dan Gucci, bintang film Audrey Heburn, riwayat industrialis otomotif Henry Ford, lagu-lagu ABBA sampai songket dan empek-empek Palembang. Pada lain kesempatan ia bisa membahas naiknya harga kedele, sampai yang “sangat penting” seperti nuansa warna arowana. Pengetahuan Farida yang selebar mata-angin seperti ditenteng ke mana-mana, dan dijadikan bahan bicara yang asyik punya.
Farida lahir di Baturaja, Sumatera Selatan 9 Juli 1942. Bakat seninya datang sebagai warisan turun temurun. Neneknya bernama Putri Sri Ayu Intan. Sementara saudari neneknya, Putri Sri Manggis, yang dikenal luas sebagai pejuang perang sekaligus ahli merancang sulam sungkit benang emas yang tiada bandingannya.
Farida adalah pelajar yang serius, sehingga reputasi sekolahnya bagus sejak awal. Selulus dari SMA Regina Pacis Bogor ia terpilih sebagai salah satu siswi program pertukaran pelajar American Field Service. Sepulang dari Amerika pada 1962 Farida mendaftar di jurusan seni rupa ITB. Nah, di sinilah ia bertemu dengan Srihadi Soedarsono, dosennya. Setelah dua tahun bertaut asmara, Farida dan Srihadi menikah pada 23 Februari 1964. Dan menetap di Bandung.
Lantaran kuliah sambil berumah-tangga, Farida baru lulus sarjana tahun 1973. Tak apa. Namun biar telat, prestasinya tetap saja memikat, sehingga mendorong banyak pihak untuk memberinya beasiswa. Ia pun didorong untuk belajar di Gerrit Rietveldt Kunst Academie di Amsterdam, atas beasiswa dari Ministerie van Culturele & Recreatie Maatschappelijk, Belanda. Tahun 1978 ia lompat kuliah ke University of London – Departement of Education, atas beasiswa dari The British Council, Inggris. Dari Inggris Farida terbang ke Amerika Serikat untuk belajar di Ohio State University – Departement of Art. Bahkan di sini ia sempat diangkat sebagai asisten dosen.

Farida dan Srihadi di Jepang. Selalu bersama dalam kerja dan tualang seni rupa di belahan dunia. (Foto: Arsip Penulis)
Hasrat belajarnya tak pernah pupus! Dalam usia menjelang 60 ia masih bergembira kuliah. “Luar biasa lho, saya menyelesaikan Master Filsafat dari Universitas Indonesia pada 2003. Dan saya menyandang gelar Master Humaniora tertua….” ujarnya setengah bercanda.
Farida memang wanita aktif yang tak ada lelahnya. Dan ia pun dikenal sebagai intelektual seni yang selalu siap dan mau ditugasi apa saja. Padahal tugasnya sering berkelok-kelok bahkan menyimpang dari bekal pendidikan yang ia miliki. Simak : pada suatu kali ia mau saja diminta menjadi koordinator Beautification and Decoration dalam PATA Conference West Java. Menjadi bagian dari tim pembuatan elemen estetis Proyek Kapal Penumpang Kerinci. Menjadi pembicara dalam seminar Apresiasi Film & Teater. Menjadi moderator dalam seminar Protection on the Intelectual Property Rights in Arts. Juga menjadi pembicara seminar Busana untuk Artis Penyanyi oleh TVRI Bandung. Meski yang terakhir ini sesungguhnya sangat berkait dengan dirinya, karena Farida ternyata juga seorang model dan peragawati penampil busana tradisional.
“Kalau disimak kembali, banyak pekerjaan ganjil yang saya lakukan. Tapi alhamdulillah semua dengan baik saya kerjakan,” tuturnya.
Sementara sebagai pelukis Farida sangat sering mengikuti pameran bersama sejak tahun 1975. Pameran itu diselenggarakan di Bandung, Jakarta, Fukuoka, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Bandar Sri Begawan, Manila, Washington, Teheran dan sebagainya. Sedangkan pameran tunggal telah ia gelar di Chase Manhattan Bank, Jakarta pada 1978 dan di University of London, Departement of Art Education, London, 1983. Farida juga banyak menghasilkan karya tulis berupa artikel, makalah dan tulisan ilmiah, yang kebanyakan dibuat kala ia ditunjuk sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan penerbitan buku.
Atas aktivitasnya itu Farida memperoleh sejumlah penghargaan. Antara lain piagam dari Pameran Internasional Seni Rupa Asia VII tahun 1992. Cultural Award dari pemerintah Australia tahun 1995. Piagam dari Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya Republik Indonesia tahun 1998. Dan Piagam Jasa dan Pengabdian, dari Institut Kesenian Jakarta, 2003.

Lukisan abstrak Farida Srihadi, “Matahari Terbit”, 1996. (Foto: Arsip Penulis)
Oleh katrena itu agak mengherankan ketika buku Indonesia Women Artists terbitan Yayasan Seni Rupa Indonesia 2007 tidak mencantumkan nama Farida di antara 34 perupa wanita Indonesia. Padahal Farida rasanya bukan sekadar perupa perempuan biasa.
Kenangan sejarah
Farida adalah pengingat sejarah. Tidak hanya yang menyangkut pribadinya, tetapi juga yang berkait dengan spirit sosial, budaya, seni dan adat negeri asalnya, Palembang. Karena itu ia selalu menyesali surutnya kebudayaan tradisional Palembang yang sejak abad 18 berusaha dikikis oleh Belanda lewat berbagai cara. Karena Belanda tahu bahwa kebudayaan itulah yang menjadikan rakyat Kesultanan Palembang Darussalam bersatu dan memiliki semangat untuk melawan.
Dan dalam satu kesempatan Farida bercerita bahwa persekutuan dirinya (yang wanita Palembang) dengan Srihadi (yang pemuda Solo) juga didorong oleh semangat sejarah Palembang yang berabad-abad itu. “Seperti fiksi kedengaran, tapi itu nyata,” tuturnya. Dan sejarah itu ia ceritakan begini.
Pada tahun 1568 kerajaan Pajang yang dipimpin Sultan Hadiwijaya atau Pangeran Jaka Tingkir mengalahkan kerajaan Demak. Kekalahan itu menyebabkan 24 petinggi Demak bermigrasi ke Palembang, untuk kemudian tinggal di Kuto Gawang, yang terletak di sekitar Kampung Palembang Lamo. Di antara yang bermigrasi itu adalah Pangeran Trenggono, yang tercatat sebagai putera dari Raden Patah. Sementara Raden Patah adalah anak dari Prabu Kertabhumi atau Raja Brawijaya V, dari isterinya yang Puteri Cina.
Pangeran Trenggono dan segenap anak buahnya hidup menyatu dengan masyarakat Palembang sampai berkurun-kurun tahun. Bahkan ketika Belanda terus mengusik Kesultanan Palembang pada abad 18, keturunan jauh Trenggono ini menjadi bagian dari masyarakat yang ikut maju perang membela Palembang.
“Menyatunya masyarakat Jawa Demak dengan masyarakat Melayu Palembang seperti menyatunya hati saya dan Mas Sri,” kata Farida sambil tersenyum.

Farida dan Srihadi merayakan ulang tahun perkawinannya yang ke-56 di rumahnya, Jalan Ciumbuleuit, Bandung. Rumah yang akan dijadikan museum. (Foto: Arsip Penulis)
Farida adalah keturunan ningrat Palembang. Keningratan itu dibawa dari nenek-moyangnya yang memang priyai (yang hirarkinya di atas miji atau senan, atau rakyat biasa). Dan silsilah itu ditegaskan lewat Kakek dari garis Ibunya, Pangeran Singajaya, legenda dalam perjuangan melawan Belanda. Dan dikenal sebagai pendekar sakti dari Maribaya Ilir, yang sekarang konon dianggap menjelma jadi pohon gaib. Ia merasa tergugah dan bangga dengan kisah legenda kakeknya itu.
Ketika masa kanak-kanak, Farida tentulah diperlakukan sebagai putri ningrat oleh keluarganya. Ia masih mengingat semua kejadiannya dengan cermat.
“Pada setiap tahun di Musi Ilir Banyuasin selalu ada rapat adat yang diikuti oleh para Pangeran dari Ulu Palembang. Mereka masing-masing datang dengan perahu lancang kuning yang artistik itu. Dan para Pangeran selalu hadir dengan pakaian adat yang bukan main menariknya. Bayangkan, setiap busana Pangeran berbeda, karena tiap wilayah yang dikuasai punya budaya dan seni sendiri. Pada saat itu saya sebagai anak perempuan diberi busana adat istimewa dengan menyelipkan keris tombak lado di pinggang. Tombak lado adalah keris tumpul yang terbuat dari perak, dengan ukiran estetik. Dan saya serta puteri-puteri lain diminta untuk menari. Ah, indah sekali,” kisahnya.
Sedangkan sebagai gadis ia diwajibkan oleh adat untuk memakai kerudung, yang modelnya mirip kerudung pashmina India. Dan itu digunakan setelah para puteri mandi sore di rumah permandian khusus yang dinamai rumah lanting. Sebentuk rumah apung yang kemudian diadopsi di beberapa wilayah yang bersungai luas.
“Itu sebabnya, pada sore hari saya selalu tampil lebih cantik dari jam-jam sebelumnya,” katanya. Ia menambahkan, perjumpaannya dengan para pangeran itu seharusnya membuat dirinya terpikat. Tapi kok tidak. “Mungkin karena ada orang Solo yang diam-diam menunggu saya di Bandung,” tuturnya dengan nada romantis.
Sebagai Ibu ia memiliki reputasi istimewa. Farida (dan tentu bersama Srihadi) sukses mengentaskan anak-anaknya menjadi figur utama. Anak pertamanya, Dr Tara Farina Srihadi, MSc, B App Sc. adalah alumnus University of Technology Sydney, Australia dan Institut Pertanian Bogor. Anak keduanya, Rati Farini Srihadi, SH, LLM adalah alumnus American University, Washington DC, Amerika Serikat. Anak ketiganya, Drs Tri Krishnamurti Syailendra Srihadi, MBA adalah sarjana hubungan internasional Universitas Indonesia dan master bisnis internasional dari George Washington University, Amerika Serikat.
Lucu juga, dari ketiga anaknya tidak satu pun yang berminat menjadi seniman. “Waktu itu saya dan Mas Sri memang sering bercerita betapa jadi seniman itu sangat repot jalan hidupnya. Mereka rupanya cermat mendengarkan. Lalu mereka pun mencari profesi yang lain,” kata Farida.

Farida, Agus Dermawan T, dan Srihadi Soedarsono di studio Srihadi, Bandung. (Foto: Penulis)
Farida telah wafat. Kepergiannya menyebabkan banyak orang kehilangan seorang teman yang selalu khusyuk dalam percakapan. Sementara di dunia abadi Farida justru menemukan kembali sahabatnya yang paling sejati, Srihadi. Walaupun tempat peristirahatan mereka terpisah, atau tidak dalam kebersamaan seperti yang mereka inginkan. Almarhumah Ibu Farida di Makam Tanah Wakaf Sebrang, Gandaria, Jakarta. Sedangkan almarhum Srihadi Soedarsono di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. *
*Agus Dermawan T. Penulis Buku “Lelakon Srihadi – Mozaik Riwayat Seniman Besar, Pejuang Perang, Pendidik dan Mahaguru” (Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.)