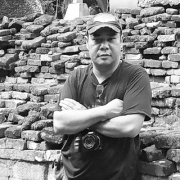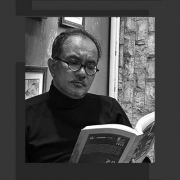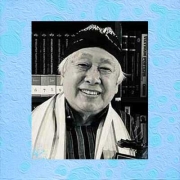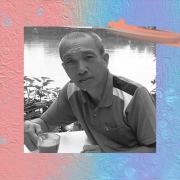Tari sebagai Simbolisme Kultural dan Viralitas Tubuh di Era Digital
Oleh Purnawan Andra*
Menjelang peringatan Hari Tari Dunia tanggal 29 April, ia menjadi ruang reflektif untuk memahami kembali esensi tari sebagai bagian dari denyut kehidupan kultural manusia. Tari tidak sekedar tubuh yang bergerak, tapi narasi penuh simbolisme yang menyampaikan nilai, sejarah, dan identitas bersama.
Beberapa hari yang lalu, seorang sahabat di kampung saya di Magelang, mengirimkan link jagat maya. Ia berupa sebuah reels joged Sadbor—sebuah tarian nyeleneh ala penduduk kampung di Sukabumi yang viral lewat TikTok. Mereka, yang kebanyakan adalah petani pengolah tanah dan ibu-ibu rumah tangga, bergerak spontan, lincah, kocak, dan kadang absurd dalam kelompok-kelompok di hadapan kamera yang merekam aksi mereka tersebut. “Sebagai seorang penari, bagaimana pendapatmu tentang ini?”, begitu pertanyaan sahabat yang merupakan seorang broadcaster ini.
Saya jadi tertegun sambil bertanya pada diri sendiri: apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan tari kita? Apakah kita sedang kehilangan kekayaan makna yang pernah melekat dalam setiap gerakan tari, atau justru sedang menciptakan bentuk baru dari ekspresi kolektif yang mendesak untuk diinterpretasikan kembali dalam era digital kini?
Ekspresi Simbolisme Komunal
Secara antropologis, tari dalam khazanah Nusantara tidak pernah hanya tentang tubuh yang bergerak indah. Tari adalah ritus, medium spiritual, dan simbol interaksi antara manusia dengan alam dan yang transenden. Setiap gerakan, bagaikan tarian suci, mengandung simbol-simbol yang mencerminkan tatanan kosmologis dan identitas kultural.
Dalam tradisi Bali, misalnya, tari Legong bukan sekadar hiburan, tapi persembahan. Dalam kerangka ini, tubuh penari adalah medium, bukan pusat. Tari menjadi bagian dari sistem simbolik, ruang mediasi antara dunia nyata dan tak kasat mata, antara individu dan komunitas.
Dalam konteks ini, gerakan tari adalah bahasa non-verbal yang mengekspresikan nilai-nilai kolektif dan memelihara ingatan historis. Para penari tidak sekadar bergerak, melainkan mengaktualisasikan ritual yang bersifat komunal—sebuah tindakan yang menguatkan kohesi sosial dan keberlanjutan tradisi.
Tari dalam masyarakat tradisional bukan untuk ditonton, melainkan untuk dijalani. Ia adalah bagian dari siklus hidup: lahir, panen, hujan, perang, hingga kematian. Gerak tubuh dalam tari adalah bahasa yang memuat nilai, petuah, sejarah, dan relasi kuasa yang berlapis. Maka estetika tari dalam konteks ini tidak semata-mata soal indahnya gerakan, tetapi bagaimana ia merepresentasikan keterhubungan dan ketundukan pada kosmos dan komunitas.
Dari Ritual ke Viral: Logika Perubahan Kultural
Dalam konteks pembicaraan, fenomena joged Sadbor dan berbagai varian flash mob TikTok hanya contoh dari sekian tanda zaman: tubuh yang bergerak kini tidak lagi dipandu oleh etos spiritual-komunal, tapi oleh kalkulasi algoritmik—apa yang bisa lucu, aneh, mudah ditiru, dan cepat menyebar. Dalam logika cultural studies, kita melihat bagaimana kebudayaan bukan entitas tetap, melainkan arena kontestasi makna. Tari pun, dalam medan ini, menjadi ruang di mana nilai-nilai baru dinegosiasikan: antara ekspresi dan eksposur, antara makna dan monetisasi.
Tari yang dulunya bagian dari “ritual” kini berubah menjadi bagian dari “ritual digital”. Clifford Geertz pernah menyebut bahwa budaya adalah sistem makna yang diwariskan secara simbolik. Tapi hari ini, makna itu bisa muncul secara dadakan, tanpa akar, tanpa warisan. Joged Sadbor adalah bentuk kontemporer dari “ritual baru”: tubuh bergerak tidak lagi untuk memanggil hujan atau arwah leluhur, tetapi untuk memanggil like, share, dan followers. Apa yang ditawarkan bukan kesakralan, tapi kesementaraan—dan justru dari situlah tarikannya berasal.
Dari sisi filsafat gerak, Maurice Merleau-Ponty mengajukan bahwa tubuh adalah medium dasar dalam berinteraksi dengan dunia dan menyampaikan pengalaman eksistensial. Tari, dengan segala kompleksitas geraknya, merupakan manifestasi dari tubuh yang menyatakan kehadirannya di dunia. Namun, dalam fenomena joged flash mob seperti Joged Sadbor, logika gerak tampak terfragmentasi.
Gerakan menjadi serangkaian aksi yang terprogram untuk memenuhi standar tertentu—untuk viral, untuk mendapatkan like, bukan untuk mengungkapkan ekspresi batin yang mendalam. Sejenis degradasi makna tubuh. Ia bukan ekstensi dari kesadaran-dalam-dunia, melainkan hanya pengulangan dari pola-pola visual yang mendaur-ulang diri sendiri demi konsumsi massal. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai estetika dan eksistensial dari tari tradisional terus tergerus oleh imperatif digital yang menuntut kecepatan dan kemudahan reproduksi.
Tubuh yang Dieksploitasi Algoritma
Fenomena ini juga menunjukkan bahwa tubuh, dalam konteks budaya digital, bukan lagi milik individu, melainkan milik publik yang dikuasai algoritma. Tari menjadi bentuk kapital yang bisa dijual, diduplikasi, dan dimerchandise. Tubuh bergerak demi eksistensi digital. Ada relasi kuasa baru di sini: tubuh tunduk bukan pada tradisi, tapi pada logika viralitas. Dan dalam konteks itu, siapa pun bisa menjadi penari—tanpa pelatihan, tanpa makna, tanpa konteks, tapi tetap mendapatkan panggung.
Para pemikir kontemporer seperti Slavoj Žižek telah menunjukkan bahwa efek estetis dalam karya seni modern mampu mengungkapkan kontradiksi antara tampak dan tersembunyi. Dalam konteks “Joged Sadbor”, estetika tampak pada gerakan yang mudah diakses dan dikenali massal, namun kehilangan lapisan makna yang selama ini menyiratkan hubungan manusia dengan nilai-nilai komunal. Gerakan yang terkesan luwes dan spontan dalam flash mob tersebut menyediakan hiburan sementara, namun mengaburkan sejarah panjang tarian sebagai ritual penyatuan dan pengekspresian makna budaya. Esensi estetika tradisional yang seharusnya mengundang penonton untuk merenungkan sejarah dan nilai-nilai leluhur kini tampak digantikan oleh pencarian popularitas melalui konten singkat yang dioptimalkan untuk algoritma digital.
Di ranah paradigma cultural studies, kita dapat menginterpretasikan pergeseran ini sebagai bagian dari proses hibridisasi dan komodifikasi budaya di era globalisasi. Pemikir seperti Arjun Appadurai telah menggagas konsep “scapes” budaya, yang menunjukkan bahwa identitas budaya selalu berada dalam proses perundingan antara tradisi dan modernitas. Joged Sadbor, sebagai bentuk flash mob TikTok, merupakan salah satu contoh di mana unsur tradisional diangkat ke ruang digital dan disaring melalui mekanisme pasar media.
Namun, apa yang terjadi adalah transformasi dalam makna: nilai ritual dan simbolik yang dulu melekat pada tarian kini harus bermetamorfosis untuk menyesuaikan dengan kecepatan konsumsi informasi dan dominasi logika pasar. Tarian yang pernah menjadi bahasa perlawanan dan penghormatan terhadap alam dan leluhur kini tereduksi menjadi gerakan yang dibuat-buat untuk mencapai popularitas, mengorbankan kedalaman makna demi komersialisasi.
Yang menarik dan perlu direnungkan adalah: apakah kita sedang menyaksikan kematian dari tari yang bermakna, atau kelahiran bentuk baru dari ekspresi tubuh yang lebih demokratis? Apakah ini krisis atau perluasan? Ataukah ini keduanya sekaligus?
Pembangunan dan Pemajuan Kebudayaan
Dalam konteks pembangunan dan pemajuan kebudayaan, pertanyaan-pertanyaan ini krusial. Negara melalui UU Pemajuan Kebudayaan telah menggariskan pentingnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap unsur budaya, termasuk seni tari. Tapi bagaimana strategi kebudayaan kita merespons transformasi makna yang terjadi di lapangan digital ini? Apakah masih relevan bicara tentang pelestarian tari tradisional ketika anak-anak lebih mengenal joged Sadbor ketimbang tari Golek?
Dalam kerangka pembangunan kebudayaan, fenomena ini mencerminkan tantangan dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin menekan identitas lokal. Pembangunan budaya seharusnya tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan popularitas semata, melainkan juga mempertahankan integritas nilai-nilai historis dan ritual yang telah membentuk jati diri masyarakat. Di era di mana konten digital mendominasi, tantangan kita adalah menemukan kembali keseimbangan antara inovasi dan pelestarian. Bagaimana caranya agar ekspresi tari—sebagai warisan kultural yang kaya makna—tidak diubah menjadi sekadar hiburan instan tanpa konteks?
Di sinilah pentingnya pendekatan yang tidak normatif. Tari tidak bisa sekadar dimuseumkan sebagai artefak, tapi harus diajak berdialog dengan dunia hari ini. Artinya, pemajuan kebudayaan harus membuka ruang bagi mediasi antara nilai lama dan ekspresi baru. Joged Sadbor bisa jadi absurd dan artifisial, tapi ia menyimpan potensi: gerak tubuh kolektif yang masih bisa diolah menjadi bentuk baru ekspresi sosial.
Sementara itu, fenomena joged Sadbor juga harus dilihat sebagai refleksi dari pergeseran cara masyarakat mengakses dan memproduksi budaya di era digital. Popularitas TikTok dan media sosial mengubah medan pertempuran antara tradisi dan modernitas, di mana setiap gerakan kini bisa diukur dari seberapa cepat ia menyebar dan menghasilkan keuntungan. Hal ini menciptakan paradoks, di mana energi kreatif yang seharusnya menjadi ekspresi kebebasan dan identitas kolektif malah terjebak dalam logika viralitas dan komersialisasi.
Dengan demikian, pergeseran ini tidak harus dianggap sebagai kemunduran, tetapi sebagai dinamika baru yang menuntut refleksi kritis untuk menemukan cara beradaptasi tanpa mengorbankan nilai inti yang pernah menjadi jiwa tari itu sendiri. Kita tidak harus menolak bentuk baru semata karena ia tidak sakral. Yang perlu kita cermati adalah bagaimana bentuk-bentuk baru itu bisa diarahkan pada penciptaan makna baru.
Joged Sadbor adalah gejala zaman, bukan sekadar kelucuan TikTok. Ia adalah panggilan bagi kita untuk memikirkan ulang apa makna tari dalam era di mana tubuh adalah konten dan gerak adalah komoditas. Daripada menolak atau meratapinya, kita perlu mengajukan pertanyaan lebih jauh: bagaimana agar tubuh yang bergerak tetap bisa menjadi ruang ekspresi, bukan sekadar tontonan? Bagaimana tari bisa kembali menjadi bahasa yang menyentuh, bukan hanya menghibur?
Karena Hari Tari Dunia bukan hanya soal merayakan gerak, tapi merayakan makna dari gerak itu sendiri. Dan barangkali, dari balik joged-joged kocak di layar kecil kita, ada potensi percikan baru dari kesadaran tubuh yang masih mencari tempatnya di dunia yang makin cepat, makin dangkal, dan makin haus akan perhatian. Di sinilah tugas kita: menjaga agar gerak tidak kehilangan arah.
—-
*Purnawan Andra, alumnus Governance and Management of Culture Fellowship Program di Daegu Catholic University Korea Selatan.