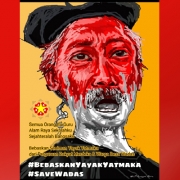Puisi-puisi Abdul Wachid B.S.
BALADA DALANG JEMBLUNG
1.
Gemblung… gemblung…
Meja kecil berderak pelan di desa Jumpoh,
Kudhi menari di tangan dalang,
Iket menahan kening dari angin khayal,
Batik menempel di lutut yang bersila,
Warga duduk menunggu tawa dan pelajaran.
(Meja goyang di tepi sawah,
Kudhi menari sambil lompat,
Selop nyebur masuk parit,
Iket menahan dahi, gemblung… jenjem!)
2.
Dari riwayat Majapahit hingga Plered,
Dalang Mocokondo lahir di Sukaraja,
Raja Amangkurat Arum mengerutkan dahi,
Tapi di balik tirai istana, tertawa pecah.
Gemblung… jenjem… gila tapi tenang,
Sejak itu nama Jemblung menempel di udara.
3.
Dua sampai empat, duduk saling berhadapan,
Meja kecil jadi kerajaan khayal,
Kudhi jadi tongkat perang pura-pura,
Selop ikut menari, bantal menahan tawa,
Surjan menempel di bahu, iket menahan angin.
Setiap benda sederhana punya cerita,
Setiap adegan penuh imaji dan banyolan.
(Dua kaki di lantai, dua di udara,
Kudhi menari, selop pun bergoyang,
Bantal menahan tawa warga,
Gemblung jenjem, hati pun riang.)
4.
Gemblung… gemblung…
Dalang berbicara sendiri,
Suara mirip orang gila,
Tapi setiap kata membawa pelajaran,
Setiap tawa terselip sindiran halus,
Warga tersenyum, anak-anak meloncat,
Hati belajar bersuka tanpa kehilangan akal.
5.
Pak Slamet mencuri jajan,
“Gemblung! Jangan ketahuan!”
Anak-anak menahan tawa,
Dalang menyisipkan ajaran:
Lucu itu boleh, tapi hati harus jujur,
Bermain itu penting, tapi etika lebih penting.
(Pak Slamet lari ke pohon mangga,
Ayam ngejar sambil berlari,
Kucing berseru “aduh lega!”,
Gemblung jenjem, tawa pun menari.)
6.
Saat hajat desa datang, Jemblung dipanggil,
Meja kecil dibawa, kudhi di tangan,
Warga duduk mengelilingi panggung sederhana,
Tawa pecah, tangis kecil ikut,
Setiap banyolan mengajar kehidupan,
Setiap tawa mengingatkan,
Bahwa hidup itu gembira tapi ada aturan.
(Anak cilik sumringah senang,
Dolanan bocah riang tak henti,
Ati ora kena pecah, tetap terang,
Gemblung jenjem, hati pun murni.)
7.
Anak-anak menatap, mata terbuka lebar,
Belajar dari gila yang lucu,
Setiap kata jatuh seperti manik,
Dirangkai humor, dibalut ajaran,
Hidup bukan hanya serius,
Tapi harus cerdas, bijak, dan berani tertawa.
8.
Gemblung… gemblung…
Tangan menepuk meja, kaki menendang irama,
Dalang menyanyi, suara berpadu canda,
Warga ikut, tubuh bergerak, kepala mengangguk,
“Balada Jemblung” jadi musik hidup,
Tawa dan pesan berpadu, tidak terpisah.
(Gemblung gemblung tepuk meja,
Selop menari tinggi di udara,
Bantal melompat ikut gembira,
Jenjem gemblung, riang terasa nyata.)
9.
Di meja kecil, muncul kerajaan khayal,
Raja kucing melompat, permaisuri ayam menari,
Kudhi jadi tongkat, selop jadi pedang,
Dalang tertawa, pemain ikut bingung,
Gemblung… gemblung… dunia pura-pura,
Tapi setiap adegan ada ajarannya.
10.
Si Gemblung bicara sendiri,
“Warga desa, jangan sombong!”
Tapi semua tersenyum,
Karena gila itu santai, tapi kata-katanya tepat,
Kehidupan di desa terlihat jelas dalam banyolan,
Hukum alam tersirat di celoteh lucu.
11.
“Pak RT, jangan selalu marah,
Anak-anak hanya bermain dengan kata.”
Gemblung… jenjem…
Dialog sederhana tapi menusuk,
Sindiran halus terselip di tawa warga,
Hidup jadi bahan cerita, cerita jadi pelajaran.
(RT bengong di depan rumah,
Anak lari meloncat ke sungai,
Gemblung ketawa sambil melompat,
Kucing pun nyanyi, riang menyertai.)
12.
Kudhi diangkat, selop menendang udara,
Raja kucing berlari, ayam perang menari,
Anak-anak bersorak, warga menahan tawa,
Dalang tersenyum, gemblung… gemblung…
Perang pura-pura mengajar strategi dan kesabaran,
Hidup bukan hanya menang atau kalah,
Tapi mengerti permainan dunia.
13.
Setiap banyolan menempel di kepala,
Anak-anak menirukan, warga tersenyum,
Dalang gemblung tertawa,
Kata-kata jatuh, pesan terselip,
Lucu tapi tidak kosong,
Gila tapi ada hikmahnya.
14.
Dalang berjalan di desa khayal,
Meja kecil jadi jembatan antar-cerita,
Kudhi menari, selop menendang bayangan,
Gemblung… gemblung…
Setiap langkah membawa pelajaran,
Setiap lompatan mengajar kesabaran.
15.
Angin meniup iket, daun menari,
Burung ikut menatap panggung sederhana,
Gemblung tersenyum, bumi ikut tawa,
Balada Jemblung bukan hanya untuk manusia,
Tapi untuk alam yang diam namun mengerti,
Pesan moral tersampaikan, dunia ikut tertawa.
16.
Warga ikut bernyanyi, ikut bertepuk tangan,
Anak-anak menirukan gerakan,
Gemblung… jenjem…
Setiap orang jadi bagian cerita,
Balada bukan monolog,
Tapi dialog antara dalang dan desa.
17.
Setiap banyolan ada falsafah,
Setiap tawa ada etika,
Dalang mengajar tanpa menggurui,
Gemblung bicara, tapi warga menyerap,
Hidup di desa belajar dari yang gila,
Yang gila tapi bijak, jenjem tapi gemblung.
18.
Selop menendang meja, kudhi jadi bunga,
Raja kucing menikahi ayam, permaisuri menari,
Anak-anak bersorak, warga tertawa,
Gemblung… gemblung…
Setiap hajat desa terselip pelajaran,
Bahwa pesta adalah guru kesabaran dan kebersamaan.
(Bunga melayang di udara pagi,
Kudhi menari di atas meja,
Raja kucing nari penuh arti,
Ayam ikut, gemblung jenjem gema.)
19.
Gemblung tertawa, warga menahan napas,
Setiap banyolan jadi obat hati,
Sindiran halus menenangkan emosi,
“Balada Jemblung” mengajarkan
bahwa humor adalah guru,
Yang menguatkan hati tanpa menyakiti.
20.
Dalang menunduk, kudhi tersenyum,
Meja kecil diam, selop kembali ke lantai,
Iket menempel, batik luruh di lutut,
Gemblung… gemblung… cerita selesai,
Tapi tawa dan pelajaran tetap tinggal,
Di hati anak-anak desa, kecil namun hidup,
Seperti balada yang tak pernah usai.
(Gemblung jenjem, crita wis rampung,
Tawa lan piwulang tetep nempel,
Hati anak-anak jadi terang benderang,
Aja lali, kanca-kanca tetep ngumpul.)
2025
Gemblung – tampak gila atau melantur, tapi sarat hikmah.
Jenjem – nakal cerdik, usil, tapi menyimpan kecerdikan.
BALADA BAWOR
Bawor tidak datang dari istana,
ia lahir dari tanah
yang retak oleh cangkul
dan tawa yang tak sempat dirapikan.
Tubuhnya besar,
jalannya tak tahu tata cara,
bahasanya tiba lebih dulu
daripada niat untuk sopan.
Ia bicara
sebelum kata disisir,
tertawa
sebelum izin diminta.
Orang-orang menyebutnya kasar,
padahal ia hanya
tidak pandai menyimpan.
Di hadapan raja,
Bawor tidak membungkuk terlalu dalam.
Bukan karena kurang ajar,
melainkan karena tanah
sudah lebih dulu memegang kakinya.
Ia menyapa kuasa
seperti menyapa tetangga:
tanpa gelar,
tanpa jarak.
Dan di situlah kegaduhan bermula.
Para bangsawan
menertawakan perutnya,
mengolok jalannya,
mengerdilkan pikirannya
agar lupa pada satu hal:
bahwa suara jujur
selalu terdengar aneh
di ruang yang terbiasa berlapis.
Bawor dijadikan badut,
agar kata-katanya
kehilangan bobot.
Ia ditempatkan di pinggir,
agar pusat merasa aman.
Padahal
setiap ucapannya
jatuh tepat di tengah.
Ia menyebut lapar
ketika yang lain berbicara tata negara.
Ia menyebut takut
ketika pidato menyebut keberanian.
Ia menyebut kenyang
ketika pujian sedang dibagi.
Bukan karena ia bodoh,
melainkan karena ia
tidak pandai berpura-pura.
Blaka suta
tidak ia pelajari,
tetapi ia hidupi.
Ia tidak tahu bahwa kejujuran
harus berpakaian.
Ia tidak paham bahwa kebenaran
perlu izin waktu.
Bawor berbicara
seperti tanah retak berbicara pada hujan:
langsung,
tanpa kiasan.
Karena itu
ia sering disalahmengerti.
Sejarah mencatatnya
sebagai pelengkap tawa,
bukan penyangga makna.
Padahal
di balik kelucuan yang disusun orang lain,
ia menyimpan luka
yang tidak sempat diberi nama.
Jika Bawor tampak gemuk,
itu karena ia menanggung
apa yang orang lain sembunyikan.
Jika Bawor tampak gaduh,
itu karena ia menolak
diam yang dipaksakan.
Ia bukan lambang,
ia peringatan.
Bahwa kebijaksanaan
tidak selalu lahir dari kehalusan,
dan kebenaran
tidak selalu berwajah rapi.
Bawor berdiri
di antara tawa dan kesadaran,
menjaga agar dunia
tidak terlalu serius berbohong.
Dan selama masih ada
orang yang berani bicara
tanpa kamus kuasa,
Bawor belum selesai.
Ia hanya
terus disalahpahami.
2025
BALADA CALUNG BANYUMASAN
Bambu tidak berniat menjadi lagu,
ia tumbuh saja
di tepi ladang,
di sela angin,
di antara kerja dan jeda.
Tangan petani memotongnya pelan,
bukan karena lembut,
melainkan karena tahu
bunyi tidak suka dipaksa.
Dari carang pring wulung
lahir nada,
bukan dari sekolah,
melainkan dari waktu
yang sabar menunggu kering.
Calung ditata
seperti sawah ditata:
tak sama panjang,
tak sama suara,
namun saling membutuhkan.
Satu bilah tidak pernah merasa utama.
Ia tahu,
tanpa yang lain
ia hanya kayu yang sunyi.
Tabuhan dimulai
bukan dengan aba-aba,
melainkan dengan anggukan tubuh.
Kaki menghitung tanah,
tangan mengikuti detak dada.
Dheng …
dhung …
dhang …
Irama tidak berlari,
ia berjalan
seperti orang pulang sore
membawa lelah
dan senyum tipis.
Calung tidak mengajak lupa,
ia mengajak ingat:
pada kerja yang belum selesai,
pada tawa yang pernah jujur,
pada hidup yang mesti dijalani bersama.
Sindhen bernyanyi
bukan untuk memikat langit,
melainkan menyentil bumi:
tentang perut yang kadang kosong,
tentang janji yang sering molor,
tentang kuasa yang perlu diolok
agar tidak terlalu percaya diri.
Lengger bergerak
di antara riang dan waspada,
tubuh menjadi cermin
bahwa hidup
tak pernah satu wajah saja.
Calung tertawa keras,
tapi tidak lupa arah.
Energinya meloncat,
namun kakinya tetap
menyentuh tanah.
Ia bukan musik istana,
ia musik halaman.
Bukan untuk dipuja,
melainkan untuk dipakai.
Di sela tabuhan,
orang-orang saling pandang
dan tahu:
kita ini berbeda bunyi,
tapi satu irama.
Ketika lagu selesai,
tidak ada tepuk tangan berlebihan.
Yang ada
napas lega,
dan kesadaran
bahwa bambu telah mengingatkan
cara hidup
tanpa harus berkhotbah.
Calung Banyumasan
terus berbunyi
selama ladang masih ada,
selama bambu masih tumbuh,
selama manusia
belum lupa
bagaimana caranya
bersama.
2025
Carang pring wulung: pucuk bambu wulung yang dipotong dan diraut sehingga menghasilkan suara nyaring.
BALADA GENDING BANYUMASAN
Gending tidak lahir dari panggung besar,
ia tumbuh dari halaman,
dari suara orang bercakap
sambil ngudud dan menunggu sore.
Nada dibunyikan
bukan untuk mengawang,
melainkan supaya kaki
tetap ingat tanah.
Irama Banyumasan
tidak suka berputar-putar,
langsung maju,
kadang nyeletuk,
kadang tergelak.
Di sela kendhang dan kenong,
parikan muncul
seperti orang nyeletuk di tengah obrolan:
Tuku tempe nang Pasar Pon,
Tempe panas dicampur mendoan.
Urip angel aja kakehan respon,
Ketawa disit ben ora kakehan beban.
Orang-orang tertawa,
bukan karena lucunya saja,
tetapi karena merasa
itu dirinya sendiri.
Gending lalu berjalan lagi,
mengajak semua suara setara:
yang tua dan yang muda,
yang kaya dan yang papa,
semua mendapat tempat.
Nada tidak menasihati dari atas,
ia duduk sejajar,
mengajak hidup
dibaca sambil bercanda.
Ketika lagu hampir rampung,
parikan kembali dibunyikan,
lebih pelan,
lebih dalam:
Tuku gethuk ning Sokaraja,
Mangan bareng karo tangga-tangga,
Urip susah aja kakehan gaya,
Sing sederhana malah luwih mulya.
Tidak ada tepuk tangan mewah,
yang ada anggukan pelan,
seolah semua sepakat
tanpa perlu kata panjang.
Gending Banyumasan selesai
tanpa merasa selesai,
sebab ia tinggal
di dada orang-orang
yang pulang membawa
tawa kecil
dan hidup yang lebih legawa.
2025
BALADA SHALAWATAN
Shalawat tidak lahir dari panggung,
ia turun pelan
dari dada
yang lelah menyebut dunia.
Di langgar kecil,
lampu menggantung rendah,
kitab dibuka
dengan napas yang ditertibkan.
Trebang dipukul
bukan untuk memanggil lagu,
melainkan menjaga
agar dzikir tidak tercecer.
Dung …
tak …
dung …
Bukan irama yang dicari,
melainkan getar
yang membuat hati
berani menunduk.
Syair dibaca
tanpa ingin didengar jauh,
cukup sampai
ke ruang yang paling dalam.
Nama Kanjeng Nabi disebut
seperti menyebut jalan pulang,
tanpa tergesa,
tanpa hiasan suara.
Di sela shalawat,
orang-orang diingatkan
bukan tentang siapa dirinya,
melainkan
ke mana akhirnya.
Trebang terus berdetak,
menjaga malam
agar tidak runtuh
oleh gaduh pikiran.
Dan ketika suara makin lirih,
nasihat lama itu pun turun
seperti embun
di atas kesadaran:
Eling-eling sira manungsa,
nemenana anggonmu ngaji,
mumpung durung katekanan,
Malaikat juru pati.
Tidak ada ancaman,
hanya ingatan
bahwa waktu
tidak suka menunggu.
Panggilane Kang Maha Kuasa,
gelem ora bakal digawa,
disalini sandangan putih,
yen wis budal ra isa bali.
Dunia dilepas
tanpa upacara besar,
karena sejak awal
ia memang titipan.
Tumpakane kreta jawa,
ruda papat rupa manungsa,
jujugane omah guwa,
tanpa bantal tanpa klasa.
Tubuh kembali sederhana,
seperti pertama kali
ia datang
ke tanah.
Tangga-tangga padha nyambang,
tangisane kaya wong nembang,
yen ngaji arang-arang,
pratanda imane kurang.
Nasihat itu tidak berteriak,
ia duduk diam
di hati
yang mulai waspada.
Shalawat pun selesai
tanpa tanda akhir,
doa dibiarkan menggantung
seperti tangan
yang enggan turun
setelah salam.
Dan di situlah
Balada Banyumas
menyelesaikan dirinya:
bukan dengan kata pamit,
melainkan
dengan eling
dan pasrah.
2025
Abdul Wachid B.S., lahir 7 Oktober 1966 di Bluluk, Lamongan, Jawa Timur. Wachid lulus Sarjana Sastra dan Magister Humaniora di UGM, lulus Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, dan menjadi Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Buku terbarunya : Kumpulan Sajak Nun (CV. Cinta Buku, Yogya, 2018), Dimensi Profetik dalam Puisi Gus Mus: Keindahan Islam dan Keindonesiaan (Nuansa, Bandung, 2020), Kumpulan Sajak Biyanglala (CV. Cinta Buku, Yogya, 2020), Kumpulan Sajak Jalan Malam (Basabasi, Yogya, 2021), Kumpulan Sajak Penyair Cinta (Jejak Pustaka, Yogya, 2022), Kumpulan Sajak Wasilah Sejoli (Basabasi, Yogya, 2022), Kumpulan Sajak Kubah Hijau (CV. Cinta Buku, Yogya, 2023), Sekumpulan Esai Sastra Hikmah (Pustaka Jaya, Bandung, 2024), Buku Puisi Balada Kisah untuk Anak Cucu (Diva Press, Yogya, 2025). Melalui buku Esai Sastra Pencerahan (Basabasi, Yogyakarta, 2019), Abdul Wachid B.S. menerima penghargaan Majelis Sastrawan Asia Tenggara (Mastera) sebagai karya tulis terbaik kategori pemikiran sastra, pada 7 Oktober 2021 (tepat di ulang tahunnya yang ke-55).