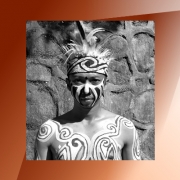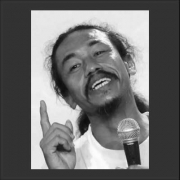Tikus sebagai Imajinasi Sosial
Oleh Purnawan Andra*
Dalam berbagai kebudayaan, tikus bukan sekadar hewan pengerat yang menjengkelkan. Ia menjelma simbol. Tikus adalah metafora tentang kerakusan, kelicikan, kelangsungan hidup yang licin, dan bahkan kelaliman tersembunyi yang merusak dari dalam.
Dalam konteks Indonesia, kehadiran tikus tidak hanya relevan dalam ranah biologis atau ekologis, tetapi juga dalam lanskap sosial-politik dan imajinasi kultural kolektif. Tikus adalah tanda. Ia penanda dari sistem yang bocor, institusi yang rapuh, dan kekuasaan yang membusuk.
Secara antropologis, tikus sering dimaknai sebagai simbol ambivalen. Dalam kepercayaan Hindu, misalnya, tikus adalah wahana dari Dewa Ganesha—dewa kebijaksanaan. Ini tampaknya paradoksal, tetapi sesungguhnya sarat makna.
Tikus, dalam tafsir ini, melambangkan kemampuan untuk menyusup ke ruang-ruang paling sempit, menembus batas-batas yang tak terlihat, dan mewakili kecerdikan dalam menembus hambatan. Simbolisme tikus bahkan menjalar ke dalam narasi-narasi rakyat. Dalam cerita-cerita lisan di desa-desa agraris Nusantara, tikus sering dihadirkan sebagai tokoh yang pintar tapi tidak bijak, yang lihai mengambil kesempatan, tetapi tidak peduli akibatnya bagi yang lain.
Dalam ungkapan budaya Jawa, ia melambangkan kerakusan dan penggerogotan dari dalam. Tikus adalah hewan kecil, tetapi kekuatannya terletak pada kemampuannya menggerus dari dalam—pelan, konsisten, dan tak terlihat. Ia merusak lumbung padi, membolongi fondasi rumah, dan menyebarkan penyakit—secara diam-diam.
Kita mengenal tikus, yang tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai binatang pengerat, berbulu, berekor panjang, yang termasuk suku Muridae. Secara biologi, tikus adalah hewan yang cerdas dan adaptif. Mereka mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak bersahabat, mencari makan di tempat-tempat yang tak terduga, dan berkembang biak dengan cepat.
Namun, sifat-sifat tersebut juga membawa konotasi negatif: tikus sering dikaitkan dengan kotoran, penyakit, dan kerusakan. Tikus dikenal sebagai hama yang mendatangkan kerugian, baik di rumah maupun di sawah.
Dalam banyak budaya, tikus dianggap sebagai hama yang harus diberantas karena mengganggu keseimbangan ekosistem, mencemari makanan, dan membawa wabah. Di negara agraris seperti Indonesia, tikus telah dikenal menjadi musuh petani sejak lama.
Bandung Mawardi (2013) menyitir isi Kitab Mujarobat, kitab tentang jimat rajah, mantra, doa hasil racikan Islam dan Jawa. Tertulis doa menanam palawija, doa memetik padi, doa pembungkam ular, jimat rajah pencegah babi hutan dan tikus, rajah penolak belalang. Di dalamnya terdapat tuntunan bagi orang Jawa untuk menuliskan selarik doa dalam huruf-huruf Arab, diletakkan di sekian penjuru area sawah. Ritus itu ampuh mengusir tikus. Namun tikus tetap menjadi hama mengerikan yang harus dibasmi.
Makna Lain
Tidak semata nama hewan, tikus juga punya makna lain. Kita mengenal istilah jalan tikus yang digunakan untuk menyebut jalan tembus guna menghindari ruas jalan tertentu. Dalam beberapa kasus, jalan tikus juga sering dimanfaatkan untuk menghindari polisi yang sedang melakukan pengawasan atau razia. Jalan tikus di wilayah perbatasan bahkan kerap digunakan sebagai jalur penyeludupan barang, manusia ataupun narkoba.
Namun dalam konteks budaya Indonesia, tikus cenderung hadir sebagai simbol “kenakalan yang membusuk”—ia bukan sekadar licik, tetapi juga destruktif. Kita mengenal istilah “tikus kantor”—sebuah ungkapan populer untuk menyebut koruptor.
Analogi ini tampaknya sangat pas untuk memahami bagaimana birokrasi korup, elite politik oportunis, dan jaringan kekuasaan gelap bekerja di negeri ini: bukan melalui ledakan frontal, tetapi lewat pembusukan sistematis yang tak kentara.
Namun, istilah ini bukan sekadar sebutan eufemistik; ia adalah kritik keras terhadap struktur yang memberi ruang hidup bagi watak parasit. Seperti halnya tikus di lumbung, para “tikus manusia” ini tidak hidup di luar sistem, tetapi justru memanfaatkan sistem dari dalam.
Mereka menyaru sebagai pelayan rakyat, pejabat negara, atau profesional institusi, tetapi menjalankan praksis penggerogotan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, simbolisme tikus menjadi semacam “totem terbalik”—ia bukan lambang yang diagungkan, melainkan dijadikan peringatan akan kehancuran yang mengintai.
Tokoh tikus dalam dongeng adalah gambaran orang yang pandai memanfaatkan celah hukum, cerdas secara teknis, tetapi nihil secara etis. Ini adalah citra koruptor yang familiar di ruang publik kita: mereka terdidik, memiliki akses ke kekuasaan, dan tahu bagaimana menyiasati sistem, namun tidak punya tanggung jawab sosial.
Entitas Politik
Di sinilah tikus menjadi entitas politik. Ia menyimbolkan dilema negara modern: bagaimana menghadapi kerusakan struktural yang tak terlihat secara kasat mata, namun terus bekerja dari dalam? Ketika hukum dibuat tetapi tidak ditegakkan, ketika institusi publik dirancang untuk melayani tetapi justru dijadikan ladang eksploitasi, maka ruang hidup tikus-tikus ini makin subur. Dalam kondisi seperti ini, negara bukan lagi pelindung warga, melainkan semacam rumah tua yang penuh rayap dan tikus—rapuh, keropos, dan tak lagi memberikan rasa aman.
Fenomena ini semakin jelas belakangan ini, seiring dengan meningkatnya kasus korupsi di berbagai sektor pemerintahan dan swasta. Sistem birokrasi yang seharusnya melayani kepentingan publik telah dirusak oleh individu-individu yang mengutamakan keuntungan pribadi di atas kepentingan bersama. Orang-orang bermental semacam ini lebih gawat daripada tikus sawah atau tikus got dan tidak bisa begitu saja diusir dengan doa-doa atau persembahan sesaji.
Jika kita ingin lebih jujur, persoalan tikus bukan hanya soal individu rakus, melainkan struktur yang membiarkannya tumbuh. Dalam ekologi sosial, tikus hanya bisa berkembang biak dalam lingkungan yang kotor, penuh sisa makanan, dan minim predator.
Demikian pula dalam masyarakat: tikus-tikus kekuasaan hanya subur dalam sistem yang impunitasnya tinggi, pengawasan lemah, dan budaya kritis yang tumpul. Artinya, kita tidak bisa hanya menyalahkan satu atau dua orang. Yang perlu kita bongkar adalah keseluruhan ekosistem politik dan budaya yang memungkinkan tikus menjadi raja dalam sistem.
Objek Kritik
Dari perspektif estetika, tikus juga menjadi objek kritik dalam karya-karya seni. Dalam seni rupa kontemporer, kita bisa melihat bagaimana tikus digambarkan sebagai ikon urban decay—kehancuran kota yang perlahan tapi pasti. Dalam seni pertunjukan atau sastra, tikus menjadi simbol dari watak munafik, kekuasaan gelap, atau ketamakan yang menyaru dalam jubah moralitas. Tikus tidak pernah hanya menjadi hewan—ia menjadi alegori.
Dalam konteks kekinian, penting untuk merevitalisasi simbolisme tikus dalam praktik kewargaan. Kita perlu mendeteksi tikus-tikus dalam sistem pendidikan, mengenali tikus dalam dunia pelayanan kesehatan, dalam pengelolaan dana desa, dalam pengadaan proyek infrastruktur.
Tikus dalam hal ini bukan soal siapa, tetapi soal bagaimana: bagaimana watak tikus menjelma dalam bentuk manipulasi data, pembengkakan anggaran, atau pemotongan hak rakyat kecil.
Dengan kata lain, yang lebih berbahaya dari kehadiran tikus adalah jika masyarakat tidak lagi marah terhadap tikus. Ketika orang mulai terbiasa melihat tikus berkeliaran di rumah sakit, di kantor desa, di gedung parlemen, dan tak merasa terganggu, maka yang rusak bukan hanya sistemnya—melainkan kesadaran etik kita bersama. Ketika watak tikus menjadi hal wajar, maka kita sedang menyambut kehancuran sebagai kebiasaan.
Tugas kita bukan hanya berburu tikus, tetapi juga membersihkan rumah. Tugas kita bukan hanya menjerat individu yang rakus, tetapi menata ulang sistem agar tak memberi ruang tumbuh bagi sifat rakus. Dalam hal ini, simbol tikus mengandung ironi yang tajam: makhluk kecil ini mengajari kita tentang pentingnya kebersihan kolektif, bukan hanya fisik, tetapi juga moral dan institusional.
Jika kita tidak belajar dari simbolisme tikus, lalu berapa banyak lagi lumbung yang harus kosong, rumah yang ambruk, dan rakyat yang terinfeksi penyakit sosial, sebelum kita sadar bahwa persoalan sesungguhnya bukan pada tikus, tetapi pada diri kita yang membiarkannya terus hidup dan beranak pinak?
—-
*Purnawan Andra, alumnus Governance & Management of Culture Fellowship Program di Daegu Catholic University Korea Selatan.