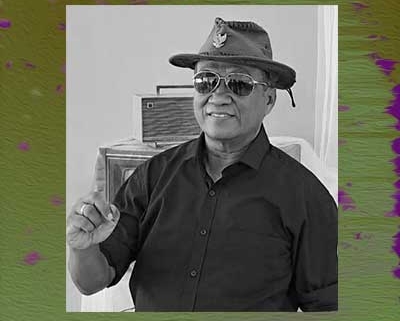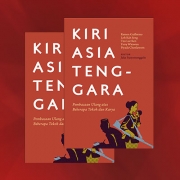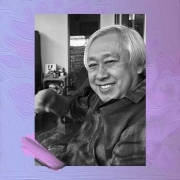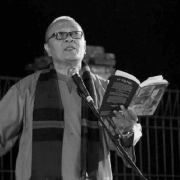Tembang-tembang Didi Kempot: Dari Estetika Pedalaman dan Spirit Warung Kopi
Oleh Tjahjono Widijanto*
Didi “Kempot” Prasetyo, maestro kondang lagu-lagu Jawa yang dijuluki kaum milenial sebagai “God Father of Broken Heart” baru saja berpulang, Didi Kempot disebut-sebut memulai kariernya dengan genre campursari. Tidak ada referensi yang pasti dan jelas tentang siapa dan kapan genre campursari ini ditemukan. Fenomena awal musik ini muncul di era 1970-an lewat pertunjukan wayang oleh Ki Narto Sabdo pada adegan goro-goro yang memodifikasi gamelan karawitan Jawa dengan unsur musik Barat yaitu gitar, drum dan keyboard, yang kemudian modifikasi ini sering dipakai pula dalam pentas-pentas lawak Basio. Pada perkembangan selanjutnya, genre ini menjadi sangat populer di tangan Manthous alias Anto Sugiartono pemusik asal Gunung Kidul Yogyakarta dan selanjutnya menjumpai era emasnya di tangan Didi Kempot.
Campursari merupakan hibridisasi cerdas seniman pemusik yang awalnya berbasis tradisional. Hibridisasi ini merupakan upaya menyiasati pasar dengan “seenaknya” mencampur jenis intrumen gamelan rakyat tradisional dengan instrumen Barat. Hibridisasi alat musik ini berarti pula “mengoplos” pentatonis dan diatonis, gamelan pelog dan slendro yang pentatonis digabung dengan instrumen Barat yang diatonis. Hibridisasi ini pada mulanya dianggap sebagai sesuatu yang mustahil dan disharmoni, karena menurut tokoh karawitan (alm) Tjokrowasito, musik Jawa atau pentatonis tidak dapat digabung dengan musik barat yang diatonis karena memiliki perbedaan tajam pada tangga nada, aksentuasi, warna suara dan sejarahnya. Tjokrowasito menegaskan bahwa gamelan karawitan tidak seemata-mata bunyi namun memiliki hubungan erat dengan religius dan fungsi sosial. Penggabungan antara gamlan dan alat musik Barat ini dikhawatirkan oleh Tjikrowasito akan menghilangkan keluhuran musik induknya yaitu gamelan. Namun pada perkembangan selanjutnya genre ini dapat diterima dan digemari pada masyarakat bawah dan menengah dengan peambahan baru yaitu ragam dangdut dan keroncong.
Keberhasilan utama Didi Kempot dibanding para pendahulunya adalah ia dalam menyiasati pasar musik melakukan dua hal sekaligus, yaitu satu sisi melakukan kompromi terhadap identitas tradisi dan modern, namun di sisi lain memberikan penguatan pada identitas tradisonal. Dengan kata lain, Didi Kempot melakukan dekonstruksi sekaligus upaya pengukuhan. Dekonstruksi dilakukan dengan bentuk penulisan lirik-lirik lagu Jawa yang tidak lagi mementingkan kerumitan bahasa tetapi lebih mementingkan (menggunakan) bahasa Jawa yang pasaran, egaliter, sederhana, cenderung pedalaman atau ndeso. Di sisi lain, ia juga dengan sengaja tetap mempertahan dan menonjolkan identitas ke Jawaan yang formal dengan sering menggunakan beskap (pakain Jawa) sebagai kostum performancenya. Tradisi Jawa dalam siasat kesenian Didi Kempot pada satu sisi menjadi sangat cair dan pada sisi lainnya selalu dikukuhkan.
Lirik-lirik syair lagu Didi Kempot semuanya benuansa khas pedalaman (pedesaan) yang sederhana, polos, lugu, penuh dengan aroma kesengsaraan, kemiskinan dan kesedihan. Kesengsaraan, kemiskinan dan kesedihan yang ditampilkan lagu-lagunya sekaligus dihayati dengan sikap dan perasaan khas Jawa yang menerima kegetiran dan kesusahan hidup dengan suasa hati yang tidak cengeng, namun diterima jenaka, atau bisa juga satire.
Hal ini misalnya dapat ditemui pada lagu Kuncung yang berkisah kehidupan masa kecilnya yang sengsara: cilikanku rambutku, dicukur kuncung/ kathokku, saka karung gandum/ klambiku, warisane mbah kakung/sarapanku sambel korek, sega jagung../ Kosokan watu nengkali nyemplung neng kedhung (byur)/Jaman disik durung usum sabun (pabrike rung dibangun)/ Andukku mung cukup anduk sarung/ Dolananku motor cilik saka lempung/ Rekasane saiki wis (Pis holopis kontul baris)/ Gegere gek ndang uwis/ Tanggal limalas padhang jinggalng bulane bunder (ser)/ Aku dikudang suk gedhe dadi dokter (sing nudang mbok e)/ Tanggal limalas padhang jingglang mbulane bunder (ser ser)/ Bareng wis gedhe aku disuntik bu dokter/ Hanacarakan datasawala/ Iki crita jaman semana/ Padhajayanya magabatanga/ iki crita saka wung tuwa/. Dalam lirik ini penderitaan hidup harus tetap dilakoni karena hidup betapa sengsaranya adalah anugerah yang indah.
Meskipun Didi Kempot dijuluki sebagai “God Father of Broken Heart”, namun suasana lagu-lagu bertema percintaan patah hatinya sebenarnya jauh dari hiperbola yang mendayu-dayu, cengeng dan pesimis, namun justru nuansa patah hatinya adalah patah hati yang tetap otimis dan kesadaran menerima sebagai sebuah kenyataan yang harus dihadapi dengan pasrah tapi optimis. Simak saja misalnya lagu Suket Teki, lagu itu menyampaikan pesan bahwa kegagalan cinta tidak berarti runtuhnya dunia: Aku tak sing ngalah, trima mundur timbang lara ati/ Tak oyako wong kowe wis lali, ora bakal bali/ Paribasan awak urip kari balung lila tak lakoni/ Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra bisa digugu/…../.
Demikian juga lagu Stasiun Balapan , Sewu Kutha,Banyu Langit,Pantai Klayar dan lain-lain, meski bertema patah hati namun nuansanya jauh dari rasa cengeng, bersakit-sakit berlebihan atau putus asa. Ini semua menyiratkan sikap khas orang Jawa yang memaknai penderitaan identik sebagai ketabahandan keihlasan. Dalam pandangan Jawa hal ini dikatakan sebagai urip iku pancen angel lan ngrekasa, nanging tetep kudu dilakoni (hidup itu memang sulit dan berat tapi harus tetap dijalani).
Lagu-lagu Didi Kempot mudah sekali diterima di masyarakat karena berbicara berbagai persolan, mulai dari persoalan sosial hingga personal dengan menggali spirit pergaulan “warung kopi” yang akrab dalam masyarakat Jawa . Dalam spirit arena warung kopi ini setiap orang merasa nyaman, betah untuk nongkrong dalam suasana yang ringan, akrab, familiar dan demokratis. Spirit warung kopi adalah arena yang menghindarkan prestise dan eklusif, arena yang memberikan ruang dialog dengan gaya akrab, seenaknya, apa adanya tanpa beban basa basi atau beban aturan yang terlampau ketat. Perbicangan dan pertemuan yang terjadi dalam warung kopi adalah bertumpu atau didasarkan pada rasa atau perasaan kebersamaan.
Warung kopi sebagi sebuah subkultur dapat dipandang sebagai discursive practice yang khas dimana rasa dan perasaan kebersamaan menjadi faktor penting untuk memahami hakikat realitas dalam arenanya. Rasa dan perasaan kebersamaandalam satu arena sosial ini dalam pandangan filsuf dan sosiolog Perancis, Pierre Bourdieu, dapat dipahami sebagi proses produksi dan reproduksi wacana-wacana yang menghadirkan format eksistensi dan reproduksi sosial. Karena itu dalam spirit arena warung kopi akan senantiasa dapat didengar dan ditemukan perbincangan tentang beragam tema, beragam isu sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik yang berlangsung demikian cair, bebas, enjoy dan penuh keakraban.. Sebuah perbincangan rakyat kecil, masyarakat bawah yang bahkan mungkin saja dapat terlihat dan terdengar nyleneh karena lahir dari logika masyarakat kecil yang jauh dari kehendak eklusif dan gaya elitis.
Spirit warung kopi yang nyantai, akrab, perasaan kebersamaan, sengaja diusung oleh lagu-lagu dan performance Didi Kempot sehingga berhasil membentuk Sobat Ambyar yang memiliki kekuatan consumer intimacy dengan gaya santai, akrab dan terbuka sehingga orang dapat keluar dan membebaskan diri dari sekat-sekat ideologis, sekat sosial, dan bersama membebaskan diri dari kepenatan dan rutinitas hidup bahkan dengan cara meratapi sekaligus menertawai nasib secara personal sealigus bersama-sama.
Namun berhadapan dengan kekejaman pasar yang berorientasi keuntungan yang menuntut siasat komersialisasi dalam mencipta lagu, sosok Didi Kempot sekali waktu pernah ‘tergelincir’ mengaburkan “keluhuran” campursari dengan memcipta lagu Cucak Rawa yang dalam konteks telinga kebayakan orang Jawa terdengar saru dan terlampau senonoh karena sarat dengan aroma asosiasi seksual. Secara manusiawi hal ini dapat dipahami karena ketika harus berhadapan dengan kejamnya tuntutan pasar sekali waktu seorang seniman atau pekerja seni tidak dapat selalu berdiri di atas tuntutan “keluhuran” dan terpaksa kompromi dengan selera pasar.
****
*Penulis adalah penyair dan kandidat Doktor Pendidikan Bahasa sastra Indonesia, UNS Surakarta.Tinggal di Ngawi Jawa Timur.