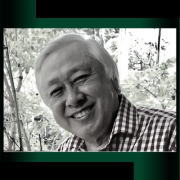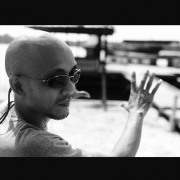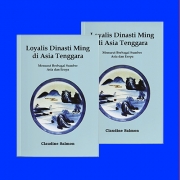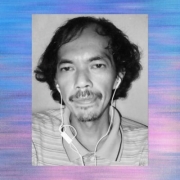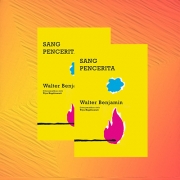Telaah Kritis Karya Aries BM “Panca Wasta” Belaj(art) dari Pacul: Internasionalisme? Yang Bagaimana Kiranya?
Oleh: Brian Trinanda K. Adi*
Pada 21 Juni hingga 31 Agustus 2025 sebuah pameran digelar di ISI Yogyakarta. Pameran tersebut bernama YICAF, Yogyakarta International Creative Arts Festival, yang nampaknya sudah diselenggarakan ketiga kalinya. Sepintas, YICAF#3 2025 yang diharapkan untuk dapat menjadi wadah untuk mendorong kolaborasi dan pertukaran pikiran antar seniman dari latar belakang yang berbeda sekaligus menjadi arena untuk mengukuhkan ISI Yogyakarta sebagaikampus seni bertaraf internasional nampaknya cukup berhasil. Pasalnya, pameran ini dihadirioleh peserta dari 11 negara berbeda, termasuk Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, China, Inggris, Hongaria, Jepang dan Austria, juga didukung oleh kerjasama internasional, yakni project 11 Australia. Namun sesungguhnya, jika saya diizinkan bertanya, apa yang sebetulnya sedang digadang-gadang oleh sebuah kampus untuk menjadi“internasional.” Apakah keterlibatan peserta dari berbagai negara sudah menjadi satu indikator yang cukup sebagai tolak ukur melihat sebuah penyelenggaraan acara, atau kampus ISI dalam konteks ini, sebagai kampus internasional?
Saya memandang internasionalisme dengan cara yang berbeda. Dalam benak saya, internasionalisme tidak sekedar keterlibatan internasional, yakni, dalam konteks pameran seni, sudah cukup dengan cara mengundang seniman-seniman dari luar negeri saja. Internasionalisme lebih dari sekedar memperluas undangan partisipasi, yang mana jika tidak hati-hati justru malah dapat berdampak kurang baik, seakan-akan karya-karya seniman lokal tetaplah berderajat lokal jika tidak disandingkan dengan karya-karya seniman dari luar negeri, yang karyanya belum tentu lebih baik dari karya-karya seniman lokal. Jika ini yang terjadi, sama saja kita sedang memupuk inferioritas, kerendah dirian sebagai sebuah bangsa.
Internasionalisme, bagi saya, harus dipandang sebagai sebuah wahana untuk menyetarakan subjektivitas. Dalam ranah seni, hal ini perlu diwujudkan tidak hanya dalam konteks partisipasi, namun dalam kesejajaran sepenuhnya, yakni dari dasar pemikiran, pengolahan abstraksi ide tersebut, hingga pada tahapan proses perwujudan karya, dan puncak representasinya. Dalam hal ini karya seniman lokal harus dilihat seutuh-utuhnya, dari bagaimana ia bermuasal, disusun, hingga direperesentasikan, sepenuhnya bersanding setara dengan karya-karya dari seniman luar negeri.

Dalam pandangan ini, maka karya Panca Wasta oleh Aries BM punya kesempatan yang besaruntuk ditonjolkan. Karya Aries berbasis lokal, jelas, karena ini adalah karya kriya, yang dibuatdengan pendekatan ke-kriya-an tradisional Nusantara, atau dalam konteks ini khususnya Jawa. Aries piawai mengolah keramik, logam, dan kayu. Material-material utama dalam studi kriya yang diperlakukan bahkan tidak hanya sebagai benda material, melainkan sebagai materi denganunsur-unsur elemental yang penuh dengan nilai-nilai filosofis. Menjadi Internasional seharusnya adalah melihat keutuhan Aries sebagai pribadi, seorang kriyawan, lengkap dengan proses pengkaryaan, juga tentu karya-karyanya, sebagai satu hal yang setara (atau bila perlu dipandang sebagai lebih baik) dibanding dengan seniman, proses penciptaan karya, serta karya dari senimanluar yang terlibat pada pameran internasional ini.
Tengoklah lebih teliti karya Panca Wasta, Aries BM. Di mana dengan piawai ia telah sedemikian rupa menstranformasi alat pertanian yang sangat sederhana khas nusantara—atau jawa?—paculatau cangkul. Sebuah alat sehari-hari yang sungguh sangat sederhana, dan dapat diketemukan di mana saja di wilayah pedesaan Jawa. Apa yang spesial dari pacul ini selain hanya sebagai alatuntuk mengolah sawah? Bukankan bahkan dalam dunia pertanian, alat ini sungguh sudah ketinggalan zaman? Pertanian modern sudah menggunakan peralatan-peralatan yang jauh lebihcanggih, berbasis mesin. Dengannya, seperti banyak ditemui di Eropa, berhektar-hektar tanah pertanian bisa dikerjakan oleh seorang petani saja. Petani pun sudah tidak perlu lagi mengotori tangan dan kakinya, berpeluh keringat mengolah sawah dengan paculnya. Dengan mengunakan mesin-mesin pertanian modern, petani tinggal duduk manis saja di atas jok yang empuk sembari memutar-mutar tuas. Diperbandingkan dengan teknologi canggih semacam ini, pacul tak lebih dari sekedar artefak primitif, bukan? Belum tentu, tunggu dulu, Kawan!
Bagi saya, cara pandang semena-mena melihat kemajuan teknologi, dan modernitas pada umumnya, yang sering kali bertumpu pada kedigdayaan barat, sebagai satu-satunya indikatoradalah satu dari sekian contoh sebuah kegagalan sikap internasionalisme! Keminderan yang bersembunyi di balik sebuah jargon, “kemajuan teknologi!” Sekedar untuk melengkapi diskusikali ini, apa anda pernah mendengar istilah “Jungle Asian?” Sebuah stereotype yang lekatdengan anggapan “savagery” dan “masayarakat belum berkembang” sebagai asosiasi sebagian besar bangsa di wilayah Asia, terutama Asia Tenggara, selain Singapura sebagai pengecualian. Kenapa Singapura dikecualikan? Karena di Asia Tenggara dia adalah negara yang paling sukses menginjeksikan gaya hidup barat dalam kultur kesehariannya. “Jungle Asian” diasosiasikan terutama pada bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dianggap tak mampu beradaptasi dengan majunya peradaban modern. Contoh paling sederhana dari stereotype “Jungle Asian” adalah penilaian negatif pada tata cara makan langsung dengan tangan, khas masayarakat Asia Tenggara, yang jauh berbeda dari citra cara makan “table manner” yang dianggap “high class” lengkap dengan garpu dan pisau, yang menjadi cara makan umumnya orang-orang di negara-negara barat. Tetapi apakah makan langsung dengan tangan benar-benar mencerminkan sebegitu rendahnya cara hidup bangsa kita, dalam hal ini bangsa Indonesia? Kalau benar begitu, maka pacul pun sama pula nasibnya. Sebagaimana makan langsung dengan tangan, ia adalah representasi mutlak cara hidup “Jungle Asian” yang primitif, khas masyarakat yang “savage”dan “underdeveloped.” Apakah cara pandang ini terasa adil? Jika tidak, maka disitulah anda harus berdiri kukuh dengan sebuah sikap, yang kita sebut sebagai internasionalisme.
Kembali pada subjek utama kita, pacul atau cangkul. Saya ingin mengajak anda untuk sejanak masuk pada satu diskusi lain (yang beririsan); pernahkah anda mendengar permaculture? Jika belum coba searching pada mesin pencari di gawai anda masing-masing. Tanyakan pula padanya, siapa penemu permaculture? Ya, jawabnya adalah Bill Mollison, seorang peneliti dari Australia, yang dikenal dengan temuannya atas sistem desain yang terinspirasi oleh alam untuk menciptakan sistem pertanian dan budaya manusia yang permanen dan berkelanjutan. Sederhananya, permaculture adalah sistem pertanian yang ramah lingkungan. Pada prinsip utama praktisnya, kesehatan tanah adalah rujukan utama dalam melakukan permaculture. Dengan kata lain, semakin sehat tanahnya, semakin sehat pulalah hasil pertaniannya. Oleh karena itu kerja awal permaculture seringkali dimulai dengan pertama-tama mengembalikan kesehatan tanah yang hendak dikelola sebagai lahan pertanian, baru kemudian dimulailah proses pengolahan lanjutan Di sinilah pacul atau cangkul menemukan peran pentingnya. Yakni untuk mengolah tanah dengan “minimal dig,” seminimal mungkin menyebabkan gangguan terhadap tanah dan ekosistem; satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh alat-alat pertanian modern seperti tractor dan cultivator yang berpotensi merusak struktur lapisan tanah. Lalu jika pacul dan keseluruhan sistem pertanian manual semacam ini sesungguhnya sangat khas dengan masyarakat Nusantara, Jawa khsususnya, kenapa kita harus jauh-jauh belajar ke Australia, pada sang ahli permaculture, Bill Mollison, hanya untuk belajar tentang sistem pertanian yang baik dan ramah lingkungan? Jawaban cepatnya adalah karena kita mulai kehilangan sistem pertanian ramah lingkungan, juga oleh karenanya, semakin ditinggalkannya pacul—atau setidaknya, nilainya.
Jawaban panjangnya erat kaitannya dengan apa yang saya sebut sebagai “kegagalan cultural porosity,” dengan kampus di antaranya sebagai salah satu biang keladinya. Sebagai salah satuarena utama cultural porosity, yakni sebagai ruang produksi dan reproduksi budaya, kampus-kampus di dunia pasca-kolonial seperti Indonesia masih terus menerus berperan dalam melanggengkan budaya kolonial dalam berbagai bentuk yang sering kali tidak disadari. Di antaranya hadir dalam struktur pengetahuan dan kurikulum. Kampus sering kali masihmenggunakan epistemologi Barat sebagai tolok ukur utama pengetahuan. Ada beberapa aspek yang dapat kita tinjau sebagi ranah praktiknya, pertama ilmu pengetahuan dianggap sah jika sesuai dengan model rasionalitas dan metodologi Eropa, serta pengetahuan lokal, praktik adat, dan kebijaksanaan tradisional yang sering dianggap “tidak ilmiah” atau “kurang modern.”Akibatnya, mahasiswa diajarkan untuk berpikir dan menilai dunia dengan kerangka kolonial—the coloniality of knowledge (meminjam istilah Aníbal Quijano). Kedua, bahasa pengantar dan sumber bacaan utama sering berpusat pada literatur berbahasa Inggris. Dampaknya, bahasa lokaldan ekspresi kultural daerah menjadi subordinat. Representasi sejarah dan budaya pun sering diambil dari perspektif kolonial—misalnya, sejarah Indonesia ditulis dengan narasi“modernisasi” ala Eropa, bukan resistensi atau agensi lokal. Ketiga, secara fisik dan simbolik, kampus banyak mewarisi bentuk arsitektur, tata ruang, bahkan ritual akademik yang berasal darisistem universitas kolonial. Upacara wisuda, toga, struktur fakultas, hingga sistem hierarki akademik adalah warisan sistem Eropa abad ke-19. Kampus juga menjadi ruang yang “modern” tapi dalam arti yang ditentukan oleh paradigma kolonial. Keempat, kampus juga sering memperkuat stratifikasi sosial yang diwariskan kolonialisme. Pada sisi ekstremnya, akses pendidikan tinggi sering masih elitis—yang bisa masuk dan sukses adalah mereka yang sudah punya modal kultural dan ekonomi. Akibatnya, universitas menjadi tempat reproduksi kelas menengah terdidik yang juga kemudian berperan melestarikan sistem sosial kolonial-modern tersebut. Terakhir, kampus di era sekarang juga terlibat dalam jaringan global yang sering mereproduksi neo-kolonialisme pengetahuan. Standar internasional, akreditasi, dan ranking dunia membuat universitas di Selatan Global harus menyesuaikan diri dengan logika akademik Barat. Begitupun riset diarahkan untuk memenuhi agenda donor asing atau lembaga internasional, bukan kebutuhan lokal. Dengan kesemua itu, maka perlu pula kiranya disadari bahwa kampus juga berperan sebagai cultural posity, yakni bukan hanya hadir sebagai tempatbelajar, tetapi juga mesin kultural yang terus mengulang struktur kolonial—melalui bahasa, pengetahuan, simbol, dan kekuasaan. Namun, ini tidak berarti kampus sepenuhnya kolonial; kampus juga bisa menjadi ruang perlawanan dan dekolonisasi bila disadari dan diintervensi secara kritis. Di mana kemudian letak “internasionalisme” ISI Yogyakarta dalam persoalan ini? Mengulang kegagalan kampus-kampus pasacakolonial sebagai cultural porosity yang pro dengan warisan kolonialisme atau berani mengambil lahkah yang berbeda?
Saya berharap karya “Panca Wasta” Aries BM dengan “pacul”-nya dapat menjadi tiang pancangkampus—dalam hal ini besar pula harapan saya pada kampus-kampus seni di Indonesia, ISI Yogyakarta, ISI Surakarta, ISI Denpasar, ISBI Bandung, dan lainnya—sebagai cultural porosity yang menawarkan nilai-nilai dekolonial. Seperti “Panca Wasta” yang dengan anggunnya mengubah kesederhanaan pacul sebagai sebuah artefak bermuatan spiritual yang menuntun kitamemahami kembali relasi antara manusia, kerja, dan kehidupan. Melalui pahatan lima simbol: burung, perempuan, rumah, keris, dan kuda, ia menghidupkan ajaran Jawa tentang nilai-nilai luhur yang membentuk sosok ideal seorang manusia Jawa: tanggung jawab, keseimbangan, keberanian, pengetahuan, dan pengabdian. Namun, lebih dari sekadar representasibudaya, Panca Wasta mencoba berbicara kepada dunia yang sedang kehilangan arah. Ketika modernitas mendorong manusia menjauh dari tanah dan kerja manual, Aries menghadirkan pacul sebagai medium refleksi: alat untuk menggali bumi, sekaligus dalam hal ini, turut menggali batin.
Karya ini turut pula mengajak kita untuk meninjau ulang konsep kerja dan maskulinitas dalam konteks global. Alih-alih menampilkan laki-laki sebagai sosok dominan, Aries menampilkan figur yang lembut namun tangguh—seorang pria yang menemukan kekuatan dalam welas asih dan keseimbangan. Dalam dunia yang tengah bergulat dengan krisis identitas, Panca Wasta menawarkan paradigma baru: spiritual masculinity yang menyatukan etos kerja dengan kesadaran diri, pada harmoninya, bahwa maskulinitas tidaklah serta merta anti feminis—seperti yang acapkali didengungkan dalam diskursus modern.
Lebih jauh, Panca Wasta menempatkan kriya Indonesia dalam percakapan global. Aries tidak sekadar menampilkan keindahan material—kayu, besi, dan keramik , tetapi menjadikannya bahasa filsafat material. Kriya di tangannya bukan lagi “kerajinan”, melainkan cara berpikir: sebuah metode memahami dunia melalui kerja tangan dan hubungan dengan alam. Dalam ruang kritisnya atas modernitas, karya ini dapat dibaca sebagai kritik terhadap kapitalismekerja, yang mengubah manusia menjadi mesin produksi tanpa makna spiritual. Melalui simbol pacul, Aries menegaskan kembali nilai kerja sebagai laku etis—bukan hanya menghasilkan, tetapi juga menumbuhkan. Lalu, sebagai pamungkas, Panca Wasta menjadi penting bagi dunia karena ia mengingatkan kita pada akar kemanusiaan universal: bahwa teknologi tanpakebijaksanaan akan kehilangan arah, dan kemajuan sejati hanya dapat tumbuh dari tanah yang digarap dengan hati. Sebagaimana Aries BM, dengan belajar dari pacul, bangsa Indonesia, juga kampus—terutama kampus-kampus seni, sebagai agen cultural porosity sesungguhnya dapat benar-benar mengartikan dan menjunjung motif internasionalisme-nya yang lebih berkeadilan dan beradab.
—
*Brian Trinanda K Adi, lahir di Pati, Jawa Tengah, adalah seorang etnomusikolog dan peneliti/aktivis budaya. Ia meraih gelar Etnomusikologi dari Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, dan gelar magister dari Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2019, ia meraih diploma dalam Studi Antar-agama Lanjutan dari Institut Ekumenis di Chateau de Bossey, Swiss. Sejak tahun 2022, ia telah menjadi kandidat doktor di Universitas Amsterdam (UvA), Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA). Brian juga merupakan pendiri beberapa festival musik dan/atau budaya serta menjabat sebagai Ketua Festival Muria Raya dan Lesbumi PCINU Belanda.