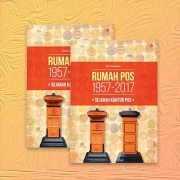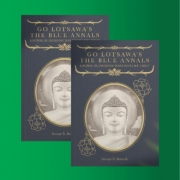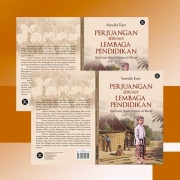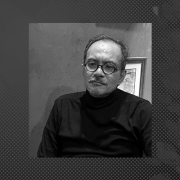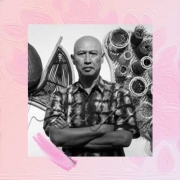Paugeran dalam Dialektika Demokrasi dan Monarki Epistemologi Kompromi: Yogyakarta sebagai Daerah Eksepsional
Oleh: Gus Nas Jogja*
Yogyakarta berdiri di atas janji yang berat: mempertahankan monarki di tengah demokrasi. Janji ini ditegakkan oleh Paugeran yang stabil. Jika sumber Paugeran dirusak, maka legitimasi monarki (dan Keistimewaan) akan runtuh, sejalan dengan prediksi bahwa rakyat akan memilih Nomokrasi murni dan mencabut UUK DIY.
Lestarinya Kesultanan dan Kadipaten sebagai Ranah Adat Budaya (Adat Recht) dalam kerangka NKRI (Positive Recht) hanya bisa terjadi jika: Struktur (Paugeran) dan Subjek (Sultan) tunduk pada kompromi agung yang telah dibentuk: UUK DIY.
Langkah politik yang sunyi dan mewening (jernih) adalah: Segera penuhi amanat Pasal 43 UUK DIY melalui Perdais. Perdais adalah ruang dialog yang struktural yang akan menentukan, apakah Kanjeng Ratu adalah evolusi yang sah ataukah destruksi yang fatal bagi Keistimewaan Yogyakarta.
Yogyakarta, sebuah anomali dalam arsitektur Republik Indonesia, bukanlah sekadar provinsi; ia adalah dialektika abadi antara Nomokrasi (hukum negara) dan Oikokrasi (hukum rumah/adat). Jantung dari eksistensi anomali ini adalah Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012 (UUK DIY). Dokumen ini adalah sebuah kompromi politik yang mencoba memberi ruang bagi “hukum adat” (Adat Recht) untuk duduk sejajar, berdampingan, tanpa harus menanggalkan martabatnya, di tengah pusaran “hukum positif” (Positive Recht) Republik.
Yogyakarta tidak dapat dipahami melalui lensa hukum positif (Positive Recht) semata. Eksistensinya adalah sebuah eksepsi, sebuah penyimpangan yang dilegitimasi dari kaidah demokrasi universal (dari rakyat, oleh rakyat). Fondasi yuridis ini, termaktub dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012 (UUK DIY), bukan hanya pengakuan atas jasa historis HB IX dan PA VIII, melainkan sebuah Kompromi Epistemologis: mengakui Paugeran Adat—sebagai sumber hukum non-negara (Adat Recht)—sebagai prasyarat tunggal bagi jabatan Kepala Daerah.
Paugeran, dalam konteks ini, berperan sebagai struktur apriori yang mendefinisikan subjek yang berhak memimpin. Ia adalah penanda identitas ganda Sultan: sebagai Kepala Adat (penjaga Paugeran) dan Kepala Daerah (pelaksana Nomokrasi). Esai ini menelisik retakan dalam struktur ini, menganalisis bagaimana Paugeran, diuji oleh dialektika birokrasi, mitologi, dan kewajiban Sayyidin Panotogomo, menentukan eksistensi keistimewaan itu sendiri.
Paugeran dan Birokrasi: Pergulatan Tata Kelola Kelembagaan serta Dualisme Kepemimpinan dan Tata Kelola Birokrasi
Dalam kerangka UUK DIY, Sultan/Adipati secara otomatis menjabat Gubernur/Wakil Gubernur, menciptakan dualisme kelembagaan yang unik. Tata kelola birokrasi di DIY harus mengakomodasi dua kutub:
1. Ranah Publik (Republik/Positive Recht): Dipimpin oleh Gubernur (Sultan) dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan modern, terikat pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus transparan, akuntabel, dan melaksanakan APBD.
2. Ranah Adat (Monarki/Adat Recht): Dipimpin oleh Sultan (Gubernur) dalam kapasitasnya sebagai Kepala Adat dan Raja, terikat pada Paugeran, dengan SOTAKER dan anggaran yang bersifat internal keraton.
Dana Keistimewaan (Danais) adalah ruang di mana dualisme ini paling rawan konflik. Danais, sebagai uang rakyat/negara yang seharusnya tunduk pada Nomokrasi, justru dikelola dengan menoleransi praktik yang dikritik sebagai glondhongan—tanpa nomenklatur anggaran yang jelas, tanpa SOTAKER (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) keraton/pakualaman yang diakui publik, dan minim kontrol publik/audit formal (seperti disyaratkan dalam APBD).
Kekaburan ini melahirkan tesis struktural: Pelanggaran Paugeran Adat –oleh Sabda Raja, melemahkan legitimasi sumber Adat Recht, sementara ketidakpatuhan terhadap regulasi transparansi Danais melemahkan legitimasi Positive Recht. Jika Paugeran dirusak, Sultan baru akan menjadi Gubernur tanpa legitimasi adat yang kokoh. Jika Danais tidak transparan, ia menjadi Gubernur yang melanggar prinsip good governance Republik. Kedua kondisi ini secara simultan merusak fondasi Keistimewaan.
Pasal 43 dan Kewajiban Struktural. Simak misalnya, UUK DIY, karena menyadari potensi konflik ini, lantas menempatkan Pasal 43 sebagai kewajiban struktural: perintah kepada Pemerintah Daerah DIY untuk membuat Perdais yang mengatur pelaksanaan keistimewaan, termasuk tata kelola kelembagaan dan pendanaan. Kegagalan melahirkan Perdais ini selama bertahun-tahun adalah mal administrasi berkelanjutan dan pengingkaran terhadap kompromi agung UUK DIY.
Perdais inilah yang seharusnya menjadi mediator yuridis-struktural yang menjembatani SOTAKER Keraton yang bersifat tertutup dengan Nomokrasi Publik yang menuntut transparansi. Ketiadaan Perdais ini membuat Paugeran, alih-alih dilindungi, justru terekspos menjadi sasaran tembak politik dan hukum.
Mitologi dan Eksistensi: Retaknya ‘Tahta untuk Rakyat’
Slogan “Tahta untuk Rakyat” yang dipopulerkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwana IX bukan sekadar lip service; ia adalah mitologi politik yang secara eksistensial membenarkan monarki di tengah republik. Mitologi ini mengandung tiga unsur filosofis:
1. Pengorbanan (Sacrifice): Penyerahan kedaulatan Keraton (1945).
2. Demokratisasi Lokal (Avant-garde): Prakarsa demokratisasi desa 1946–1948, yang mendahului Pemilu Nasional 1955.
3. Filosofi Kepemimpinan (Mandat): Sultan sebagai mandataris rakyat, bukan sebagai tuan feodal.
Namun, ketika Sultan HB X mengeluarkan Sabda Raja (2015) untuk mengubah Paugeran demi membuka jalan suksesi putrinya misalnya, mitologi ini dipertanyakan. Tindakan ini dilihat sebagai pemaksaan kehendak personal (kehendak pewarisan langsung) yang mengalahkan kehendak Paugeran Adat (struktur yang seharusnya dijaga) dan berpotensi mengabaikan kehendak rakyat (yang sepakat UUK DIY dengan asumsi Paugeran stabil).
Sayyidin Panotogomo: Kewajiban Spiritual yang Terjerat Hukum
Gelar Sultan, Sayyidin Panotogomo Khalifatullah, menempatkan Raja sebagai pemimpin agama dan tatanan serta wakil Tuhan. Ini adalah kewajiban spiritual-eksistensial yang menuntut Sultan untuk:
1. Menafsirkan Zaman: Melakukan perubahan demi Hamemayu Hayuning Bawana (memelihara keindahan alam semesta).
2. Menjaga Tatanan: Memastikan tatanan (Paugeran) tidak rusak, tetapi berevolusi secara sah dan lestari.
Sabda Raja dapat diinterpretasikan secara eksistensial: Sultan, dengan kesadaran penuh atas posisinya sebagai penafsir zaman, memilih evolusi Paugeran (kesetaraan gender) sebagai bentuk Hamemayu Hayuning Bawana. Ia memilih tradisi yang bernapas, bukan tradisi museum.
Namun, secara struktural-yuridis, kewajiban Sayyidin Panotogomo ini kini berbenturan dengan Nomokrasi. Tindakan spiritual Raja harus tunduk pada persyaratan yuridis yang disepakati (UUK DIY). Jika tafsiran zaman (perubahan Paugeran) tidak diikuti dengan konsensus struktural (Perdais), maka tindakan itu menjadi kontra-yuridis.
Kewajiban spiritual yang dilaksanakan tanpa legitimasi struktural yang baru (Perdais) akan menciptakan kerawanan sosio-kultural (friksi internal keraton, masalah pertanahan SG/PAG) dan resistensi demokrasi dari faksi-faksi yang menolak.
Eksistensi Adat Recht di Bawah Ancaman Destruksi
Keistimewaan DIY hidup karena ekosistem kebudayaan yang mengakar kuat di Paugeran. Paugeran berfungsi sebagai DNA kultural yang memberi legitimasi sosio-spiritual kepada Sultan. Pelanggaran Paugeran (Poin 1), secara filsafat struktural, berarti menghapus legitimasi Kesultanan yang telah disepakati sejak Perjanjian Giyanti (1755).
Jika legitimasi Adat Recht ini runtuh, maka tidak ada lagi alasan filosofis bagi Positive Recht untuk tetap mempertahankan monarki. Monarki tanpa Paugeran yang diakui secara luas hanyalah feodalisme telanjang yang bertentangan dengan semua nilai demokrasi. Inilah prediksi destruksi: rakyat akan memilih Nomokrasi murni dan menuntut pencabutan UUK DIY, mengubah Yogyakarta menjadi provinsi biasa, seperti yang terjadi pada Kasunanan Surakarta.
Esensi dari krisis ini terletak pada kesenjangan antara kehendak eksistensial Sultan –melanjutkan dinasti melalui putri, dan kewajiban strukturalnya –menjaga kompromi UUK DIY.
Jalan keluar yang sunyi dan mewening adalah kembali ke amanat UUK DIY: Segera penuhi Pasal 43 melalui Perdais.
Perdais harus menjadi instrumen hukum yang:
1. Mengakui/Merevisi Paugeran: Secara resmi dan struktural mengakui Paugeran yang baru (jika mayoritas rakyat/DPRD sepakat dengan evolusi Kanjeng Ratu), sehingga status Kanjeng Ratu (sebagai evolusi yang sah) mendapatkan legitimasi Positive Recht.
2. Memperjelas Tata Kelola Danais: Menyediakan nomenklatur anggaran, SOTAKER, dan mekanisme audit yang transparan bagi penggunaan Danais, sehingga mengakhiri tuduhan motif transaksional dan mengembalikan martabat Tahta untuk Rakyat.
Pada akhirnya, Paugeran bukanlah dogma beku. Ia adalah kontrak sosial yang hidup antara Raja, Keraton, dan Rakyat. Jika Raja ingin menginterpretasikan Paugeran sesuai tuntutan zaman dan kesetaraan gender, ia harus memastikan bahwa interpretasi tersebut diterima secara struktural melalui instrumen Nomokrasi yang disepakati: Perdais. Hanya dengan demikian, Struktur (Paugeran) dan Subjek (Sultanah) dapat tunduk pada Kompromi Agung (UUK DIY), melestarikan Keistimewaan dan menjaga martabat Kesultanan di jantung Republik.
Wallahu A’lam.
***
Rujukan Ilmiah
UUK DIY No. 13/2012, Pasal 43: Dasar yuridis penetapan Gubernur berdasarkan Paugeran Adat.
Konsep Adat Recht vs Positive Recht: Dikembangkan oleh ahli hukum adat Belanda seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn., yang menekankan pentingnya hukum yang hidup di masyarakat (adat) di samping hukum tertulis (positif).
Sayyidin Panotogomo Khalifatullah: Gelar Sultan yang memiliki dimensi teologis dan kosmis, menempatkannya sebagai penafsir tatanan ilahi di bumi (Geertz, The Religion of Java).
Filsafat Eksistensial dan Struktural (Sartre, Lévi-Strauss): Digunakan untuk menganalisis bagaimana tindakan individu (Sabda Raja) memengaruhi struktur sosial yang mendasar (Paugeran), yang secara eksistensial mendefinisikan subjek (Sultan).
Mitologi Politik Tahta untuk Rakyat: Sebuah narasi yang membentuk legitimasi monarki di era modern, menekankan peran keraton sebagai pelayan publik (Simuh, Mistik Islam Kejawen R. Ng. Ranggawarsito).
Mal Administrasi Negara dan Good Governance: Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prosedur anggaran publik (terkait Danais).
Destruksi Legitimasi Mataram: Merujuk pada runtuhnya legitimasi Kesunanan Surakarta sebagai entitas pemerintahan setelah tidak lagi diakui sebagai Kepala Daerah, yang menjadi peringatan bagi DIY jika Paugeran dirusak.
Dialektika Struktur dan Agensi: Dalam ilmu sosial, krisis yang muncul ketika aktor (agensi, Sultan) mencoba mengubah norma institusional (struktur, Paugeran) tanpa mekanisme yang disepakati, berpotensi menghancurkan institusi itu sendiri.
—-
*Gus Nas Jogja. Budayawan.