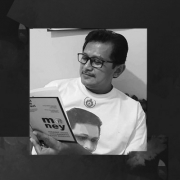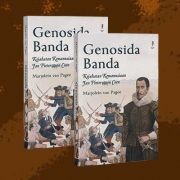Menjadi Saksi: Balada sebagai Zikir Tanah Leluhur
Oleh Abdul Wachid B.S.*
1. Menjadi Saksi Langit dan Tanah
Saya menulis bukan untuk menentukan makna tanah leluhur, apalagi menafsirkannya dengan tergesa. Saya datang sebagai orang yang menepi: berdiri di pinggir sawah, di batas kebun, atau di bawah pohon tua yang tak lagi ditanya umurnya. Di sana saya belajar mendengar, bukan hanya suara alam, tetapi juga suara manusia yang hidup di dalamnya, dengan luka, doa, dan kesabarannya.
Langit dan bumi bagi saya bukanlah sekadar bentang fisik. Keduanya adalah ruang zikir yang terus bekerja, siang dan malam, bahkan ketika manusia lupa menyebut nama-Nya. Langit tidak selalu berbicara lewat petir atau cahaya yang gemilang; sering kali ia hadir sebagai bayangan yang menunduk. Bumi pun tidak selalu bersuara lantang; ia lebih sering berbisik melalui daun yang luruh, embun yang singgah sebentar, atau langkah-langkah kecil yang nyaris tak diperhatikan.
Dalam salah satu balada, saya mencatat bagaimana kejatuhan dan ketundukan justru menjadi bahasa:
“Di balik pohon waru,
langit masih menjatuhkan airmata
yang bening dan tak beraroma.
Bumi menerimanya
tanpa banyak tanya,
seperti menerima maaf
dari seseorang yang hanya datang dalam sujud.”
Di titik itulah saya memahami: menjadi saksi bukanlah perkara melihat lebih banyak, melainkan menahan diri untuk tidak segera menyimpulkan. Saksi tidak berdiri sebagai hakim yang memutuskan makna, tetapi sebagai cermin yang membiarkan realitas memantulkan dirinya sendiri.
Balada-balada dalam Balada Langit di Tanah Leluhur ini lahir dari sikap itu, sikap menyimak. Saya tidak menempatkan kata sebagai alat untuk menguasai, melainkan sebagai wadah agar pengalaman langit dan tanah bisa lewat dengan wajar. Kata-kata, saya upayakan tetap rendah hati, seperti daun jati yang luruh tanpa protes, atau bayangan langit yang merambat pelan di punggung bumi.
Menjadi saksi, bagi saya, adalah kesediaan untuk berdiri di antara langit dan tanah, tanpa merasa lebih tinggi dari keduanya: mendengar, mencatat seperlunya, lalu memberi ruang agar pembaca kelak menemukan gema dan cahayanya sendiri.
2. Zikir yang Mengalir dari Alam, Benda, dan Manusia
Zikir, bagi saya, tidak lahir pertama-tama dari suara manusia. Ia sudah lebih dulu mengalir di semesta, sebelum lidah belajar menyebut, sebelum tubuh belajar bersujud. Alam tidak menunggu manusia saleh untuk berzikir. Ia melakukannya dengan caranya sendiri: diam, berulang, dan setia pada hukum-Nya.
Embun yang jatuh sebelum fajar, daun yang luruh tanpa keluh, air yang terus datang meski berkali-kali ditolak batu, semuanya bergerak dalam irama penghambaan yang tak mengenal jeda. Mereka tidak memerlukan kesadaran reflektif, tetapi justru karena itulah zikir mereka utuh: tak terpecah oleh niat, tak terganggu oleh pamrih.
Dalam balada-balada ini, saya berusaha mendekati zikir sebagai gerak, bukan sebagai istilah. Ia hadir sebagai pengulangan yang sabar, sebagai ketekunan yang nyaris tak disadari, sebagai kesediaan untuk terus ada meski tak diberi nama. Seperti air yang tidak memaksa karang, tetapi datang berkali-kali, hingga karang pun membuka jalan.
“Ia hanya mengulang langkahnya
seperti zikir yang tak butuh alasan.”
Pengulangan semacam itu bukan kebiasaan kosong. Ia adalah bentuk kesetiaan paling purba. Dalam tradisi sufistik, zikir bukan sekadar menyebut nama Tuhan, melainkan menyelaraskan diri dengan kehendak-Nya. Alam telah melakukannya sejak awal. Manusia justru belajar tertinggal.
Benda-benda yang hadir dalam balada, kendi yang retak, tikar pandan yang lapuk, batang kayu yang mengering, saya tempatkan bukan sebagai simbol estetis, melainkan sebagai arsip sunyi. Mereka menyimpan jejak relasi manusia dengan waktu, dengan kerja, dengan doa yang tak tercatat. Ketika benda-benda itu rusak, terbakar, atau hilang, yang sesungguhnya rapuh bukan hanya materialnya, melainkan ingatan spiritual yang pernah dititipkan padanya.
Zikir dalam konteks ini bukan lagi milik subjek yang sadar sepenuhnya, melainkan energi kepatuhan yang mengalir dari satu keberadaan ke keberadaan lain. Manusia, alam, dan benda berada dalam satu jaringan tasbih yang luas. Yang membedakan hanyalah: siapa yang masih mendengar, dan siapa yang telah memutuskan menutup telinga.
Karena itu, menulis balada bagi saya bukan usaha menciptakan zikir, melainkan mendengarkannya kembali. Kata-kata tidak saya dorong untuk bersuara lebih keras dari alam, tetapi justru untuk menepi, agar aliran itu tetap terdengar. Saya tidak ingin puisi-puisi ini menjadi khotbah. Cukup menjadi celah: tempat zikir yang telah lama bekerja bisa melintas tanpa terganggu.
Di titik ini, zikir tidak lagi tampil sebagai praktik individual semata, melainkan sebagai napas semesta. Manusia hanya salah satu simpulnya. Bila ia memilih diam dan menyimak, ia akan mendapati bahwa Tuhan tidak pernah jauh: Ia telah lebih dahulu menyapa melalui ritme hidup yang kita jalani setiap hari, sering tanpa sadar, sering tanpa nama.
Jika sebelumnya zikir terasa bergerak di antara alam dan benda, mengalir lewat embun, daun, kayu, dan air, maka pada satu titik ia seperti mencari tempat untuk berdiam. Ia turun ke tanah, mendekati langkah manusia, dan menyusup ke dalam hidup yang dijalani sehari-hari.
Zikir itu tidak puas hanya menjadi irama yang jauh. Ia ingin disentuh, dijalani, dan dipikul bersama kerja dan lelah. Di sanalah manusia rakyat hadir: bukan sebagai penyebut nama, melainkan sebagai penjaga laku. Mereka tidak sibuk menafsirkan iman, tetapi menghidupinya pelan-pelan, di sela rutinitas dan keterbatasan.
Jika alam bersujud dengan setia pada hukumnya, manusia bersujud dengan ketekunan menjalani hari. Zikir pun tidak lagi sekadar mengalir, tetapi menetap, di halaman rumah, di pasar yang riuh, di gubuk kebun yang sunyi, dan di pekarangan langgar yang sabar.
Dari sini, arah pembacaan pun bergeser dengan sendirinya. Bukan lagi tentang bagaimana zikir bergerak di semesta, melainkan tentang bagaimana ia menemukan rumahnya dalam hidup manusia.
Dan, di situlah kisah berikutnya bermula: tentang iman yang tidak dipamerkan, tetapi dijaga agar tetap bernapas, diam-diam, sederhana, dan setia.
3. Ruang Doa Rakyat: Iman dalam Kehidupan Sehari-hari
Ruang doa dalam buku ini tidak saya temukan pertama-tama di bangunan yang diberi nama tempat ibadah. Ia justru lebih sering muncul di wilayah yang nyaris tak disadari sebagai ruang spiritual: halaman rumah yang kehilangan porosnya, pasar yang riuh oleh tawar-menawar, gubuk kebun yang reyot, tikar pandan di bawah rumah panggung, atau seutas tali jemuran yang melintang sunyi di pekarangan langgar. Di tempat-tempat itulah iman bekerja secara diam-diam, tanpa pengeras suara, dan tanpa klaim kesalehan.
Rakyat menjalani doa bukan sebagai peristiwa terpisah dari hidup, melainkan sebagai cara hidup itu sendiri. Mereka bekerja, menunggu, kehilangan, dan berharap tanpa merasa sedang “beribadah”, tetapi justru di situlah laku iman menemukan bentuknya yang paling jujur. Napas yang tertahan, peluh yang jatuh, dan kesabaran yang berulang menjadi bahasa doa yang tak ditulis, tetapi dihafal oleh tanah.
Di pasar rakyat, iman tidak berdiri sebagai simbol yang dipajang. Ia diuji oleh kebutuhan, oleh suara logam dan angka, oleh hidup yang harus terus berjalan meski jawaban langit tak segera turun. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada bisik yang nyaris tak terdengar, namun tak pernah benar-benar hilang:
“Pasar bergolak oleh tawar-menawar, …
tapi ia mendengar suara
yang tak diucapkan.”
Doa di sini bukanlah pemisahan diri dari dunia, melainkan kesediaan untuk tetap menunduk di tengah keramaian. Ia hadir dalam gumaman lirih, dalam ingatan yang disimpan diam-diam, dalam tubuh yang tetap bertahan meski harapan sering datang terlambat.
Ruang doa rakyat juga terbentuk oleh kehilangan. Halaman yang tak lagi memiliki batang petung, rumah yang kehilangan tikar pandannya, atau tanah yang ditinggalkan penanda-penandanya, justru menyimpan kesaksian spiritual yang getir. Ketika tanda-tanda fisik hilang, ingatan iman diuji: apakah ia ikut lenyap, atau justru menuntut untuk dibaca ulang. Dalam balada tentang tikar pandan yang terbakar, doa tidak terdengar sebagai seruan, melainkan sebagai ratapan bumi yang pelan:
“Ini bukan sekadar rumah, …
Ini tanah air.
Ini amanah bumi …”
Kehilangan, dengan demikian, bukan selalu akhir dari doa. Ia bisa menjadi cara lain bagi iman untuk berbicara, lebih pedih, lebih jujur, dan sering kali lebih dalam.
Di gubuk kebun kopi, iman tidak memerlukan jam atau jadwal. Ia hadir dalam kesunyian, dalam gerak yang berulang, dan dalam tubuh yang menua bersama tanah. Doa diucapkan bukan dengan suara, melainkan dengan ketekunan tinggal dan menunggu:
“Ia menengadahkan tangan,
meminta bukan hujan
tetapi cahaya
agar hatinya
tak menjadi ladang yang mati.”
Di sini, ruang doa bukan dibangun, melainkan diwarisi. Ia menjadi bagian dari tanah, dari ingatan keluarga, dan dari kerja yang dilakukan tanpa jaminan hasil.
Sementara itu, di pekarangan langgar, iman hadir dalam gerak yang paling sederhana dan paling setia. Seutas tali jemuran, kain basah, langkah yang pelan, semuanya menyusun ritme doa yang nyaris tak disadari sebagai doa:
“Tali itu tampak lengkung,
membentuk busur doa
yang mengarah ke langit
tanpa anak panah.”
Tak ada khutbah, tak ada nasihat panjang. Yang ada hanyalah kesetiaan pada ritme hidup dan keyakinan sunyi bahwa Tuhan menyimak bahkan doa yang diucapkan sambil bekerja.
Melalui balada-balada ini, ruang doa rakyat saya hadirkan bukan sebagai romantisasi kemiskinan atau katalog budaya, melainkan sebagai kesaksian tentang iman yang bertahan. Iman yang tidak berisik, tidak menuntut panggung, tetapi terus bernapas di tengah hidup yang rapuh.
Di sanalah iman tidak berdiri sebagai slogan, melainkan sebagai cara hidup: cara bertahan, cara berharap, dan cara menunduk dengan wajar di hadapan kenyataan.
4. Benda dan Tabir: Cahaya dari Kegelapan
Dalam puisi-puisi ini, benda tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu dibaca dengan cara yang lebih hening. Batang petung, tikar pandan, gubuk reyot, daun jati, tali jemuran, embun di ujung alang-alang, semuanya bekerja sebagai tabir: menutupi sekaligus menyingkap cahaya.
Benda-benda itu tidak menjelaskan dirinya. Mereka diam, tetapi justru karena kediamannya, hikmah menjadi mungkin hadir. Dalam “Balada Batang Petung yang Hilang”, petung bukan sekadar bambu penyangga halaman, melainkan poros makna yang runtuh ketika manusia lupa membaca tanda:
“yang tubuhmu lapuk bukan karena waktu,
tapi karena lupa kami
pada arti tegakmu
yang tak pernah tunduk selain kepada-Nya.”
Ketegakan petung adalah etika spiritual. Ketika ia hilang, yang patah bukan hanya benda, melainkan kesanggupan manusia untuk berdiri di hadapan makna. Inilah tabir pertama: lupa, yang menjadikan cahaya terdengar, tetapi tak lagi terlihat.
Tikar pandan yang terbakar menghadirkan tabir berikutnya. Ia menghampar sabar sepanjang generasi, menyimpan dengkur, tangis, dan doa-doa rumah tangga, hingga api datang bukan sebagai takdir alam, melainkan akibat mata yang tamak dan tangan yang kehilangan zikir:
“Ia menghampar sabar
seperti doa ibu
yang tak pernah rampung.”
Ketika tikar itu menjadi abu, cahaya justru lahir dari kehilangan. Nenek yang menggenggam sisa anyaman menyebut satu per satu nama cucunya, menjadikan puing sebagai mihrab terakhir. Di sini, benda membuka tabir bahwa rumah bukan bangunan, melainkan amanah.
Gubuk di ujung kebun kopi adalah tabir yang lebih dalam. Ia reyot, tak memiliki jam, dan tak mengenal pengeras suara. Namun justru di sanalah ayat-ayat dibaca oleh angin dan kayu lapuk:
“Tak ada pengeras suara.
Hanya desir daun dan suara kayu lapuk
yang mengeja alif–lam–mim
di sela-sela hembusan napas.”
Gubuk tidak memamerkan kesalehan. Ia menyembunyikannya. Cahaya tidak datang sebagai kilat, tetapi sebagai keteguhan seorang petani yang meminta agar hatinya “tak menjadi ladang yang mati.” Tabir di sini adalah kesederhanaan, yang hanya bisa ditembus oleh tafakur.
Daun jati yang luruh dan embun yang menghilang sebelum siang juga bekerja sebagai tabir waktu. Yang gugur, yang basah sesaat, yang lenyap tanpa suara, semuanya mengajarkan bahwa cahaya tidak selalu menetap:
“segala yang jatuh adalah zikir,
segala yang kering menyimpan cahaya
dari langit yang ditutup kabut rahasia.”
Cahaya tidak berada di puncak kemegahan, melainkan di kesediaan untuk luruh, untuk mengering, untuk hilang setelah menunaikan tugasnya.
Bahkan tali jemuran di pekarangan langgar, benda yang nyaris tak diperhitungkan, menjadi lengkung doa yang paling jujur. Ia menahan sarung basah, kesabaran perempuan tua, dan waktu yang berjalan pelan:
“tali itu tampak lengkung,
membentuk busur doa
yang mengarah ke langit
tanpa anak panah.”
Tak ada serangan, tak ada tuntutan. Doa dilepaskan tanpa target selain pasrah.
Menulis balada, dengan demikian, adalah membuka tabir-tabir ini satu per satu. Bukan untuk menelanjangi cahaya, tetapi agar pembaca belajar merabanya dari balik gelap. Sebab dalam puisi-puisi ini, cahaya tidak pernah datang dengan sorak, ia hadir sebagai keteguhan benda, kesabaran laku, dan zikir yang tak bersuara.
Di situlah puisi bekerja: bukan memindahkan manusia dari gelap, melainkan membimbing mata agar terbiasa melihat cahaya yang lahir dari kegelapan itu sendiri.
5. Balada sebagai Jalan Menuju Diri
Bagi saya, balada bukan tujuan estetik, melainkan jalan pulang: jalan yang tidak lurus, sering berbelok, kadang licin oleh air mata, kadang berdebu oleh lupa. Ia membawa saya menelusuri kegelapan yang tidak selalu jahat, tetapi gelap yang menyimpan tanda. Dari sanalah cahaya kerap datang: bukan sebagai kilat yang mengagetkan, melainkan sebagai sesuatu yang jatuh perlahan dan nyaris tak disadari, “seperti ayat pertama / yang gugur dari langit / sebelum semesta sempat mengeja.”
Saya menulis balada bukan untuk menemukan diri yang utuh, sebab keutuhan sering justru menjauhkan manusia dari Tuhan. Yang saya cari adalah retak-retak kesadaran: momen ketika tubuh, ingatan, dan iman saling bersua dalam kefanaan. Dalam balada, tubuh menjadi bahasa: napas dihitung, sujud memanjang, tulang melemah. Ada saat ketika kesadaran hadir lewat hal yang sangat kecil, nyaris remeh, namun justru menentukan arah batin: “Tetesan air di ujung hidung saat sujud,” yang mengingatkan bahwa manusia selalu berada di tepi antara jatuh dan ditopang.
Ketika menulis tentang embun di ujung alang-alang, saya sedang belajar bahwa hidup tidak selalu harus lantang. “Embun jatuh diam-diam / di ujung alang-alang yang digerakkan sunyi,” dan dari keheningan itulah pagi menemukan wajahnya. Air tidak memaksa batu; ia hanya datang berkali-kali, sampai jalan terbuka dengan sendirinya. Kesabaran semacam ini adalah pelajaran batin yang tidak diajarkan, tetapi dialami.
Balada juga membawa saya berhadapan dengan kehilangan sebagai guru yang paling jujur. Batang petung yang hilang dari halaman masa kecil, misalnya, bukan sekadar lenyapnya sebuah benda, melainkan runtuhnya poros makna. “Batang petung itu telah hilang / tapi bukankah kita pun tengah patah,” dan dari kepatahan itulah pertanyaan tentang diri muncul dengan telanjang: sejauh mana saya masih berdiri tegak, dan kepada siapa sebenarnya saya bersandar.
Dalam kefanaan, balada bekerja sebagai cermin yang merendah. Gigi yang copot di subuh hari, tubuh yang tak lagi sekuat dulu, napas yang harus disadari satu per satu, semuanya adalah tanda bahwa hidup tidak sedang berkurang, melainkan sedang mengajar. Saya teringat larik yang menyelinap pelan: “napas yang dihitung malaikat,” bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menenangkan, bahwa setiap tarikan dan hembusan telah berada dalam penjagaan.
Balada, dengan demikian, menjadi tafakur yang berjalan. Ia tidak memberi jawaban, tetapi memperlambat langkah agar pertanyaan bisa tinggal lebih lama di dada. Dalam balada, saya tidak sedang menjelaskan iman; saya sedang mengalaminya, melalui embun, melalui gubuk reyot, melalui pohon yang berdiri sebagai saksi, melalui benda-benda yang “tak berbicara tentang iman, / tetapi menjaga agar ruang/tidak menjadi pongah.”
Maka balada adalah jalan menuju diri yang tidak berhenti pada diri. Ia membawa saya dari kesadaran fana menuju kefanaan yang justru mengajarkan keabadian. Dari gelap menuju cahaya, minadz dzulumāti ilā n-nūr, bukan sebagai slogan, melainkan sebagai pengalaman batin yang terus berulang. Jika pada akhirnya pembaca menemukan dirinya sendiri di dalam balada, di sela sunyi, di antara larik-larik yang menunduk, maka balada telah menjalankan tugasnya sebagai zikir: mempertemukan yang sementara dengan Yang Maha Kekal, tanpa suara, tanpa klaim, dan tanpa merasa selesai.
Pada akhirnya, balada mengantar saya pada kesadaran yang paling hening: bahwa pulang bukan selalu berarti kembali, dan sampai bukan selalu berarti tiba. Ada kehidupan yang dijalani tanpa sorak, tanpa penanda waktu, seperti gubuk reyot di ujung kebun kopi yang “tak punya jam / namun tahu kapan matahari menunduk.” Di situlah manusia belajar meletakkan dirinya bukan sebagai pusat, melainkan sebagai hamba yang sekadar singgah.
Dalam balada, saya menyaksikan bagaimana doa tidak selalu diucapkan, tetapi dihidupi. Tubuh yang membungkuk, napas yang melambat, dan tangan yang menengadah bukan untuk meminta dunia, melainkan agar hati tidak menjadi ladang yang mati. Maka pulang pun menjadi bentuk penyerahan paling jujur: “Ia pulang tak pernah benar-benar pulang,” sebab yang dicari bukan rumah di peta, melainkan tempat di hadapan-Nya.
Balada, pada titik ini, tidak lagi berbicara tentang perjalanan ke luar, tetapi tentang menjadi: melebur dalam nama-nama yang disebut diam-diam, hingga diri perlahan tanggal dari klaim-klaimnya. Seperti petani tua itu, manusia akhirnya belajar bahwa hidup yang dijalani dengan pasrah akan berbuah bukan dalam kemegahan, melainkan dalam keberlanjutan doa: “sebelum bumi menjadikannya / sebatang pohon kopi/yang tak pernah berhenti / berbuah doa.”
Di titik inilah balada berhenti menjadi cermin, dan mulai menjadi jalan. Diri tidak lagi dicari, sebab ia telah luluh dalam laku yang sederhana: duduk, menunduk, mendengar. Yang tersisa bukan jawaban, melainkan kesiapan, seperti napas yang diperlambat, seperti gubuk yang menunggu senja, seperti tali jemuran yang tetap menggantung meski angin berlalu. Dalam kesunyian itu, balada tidak mengajak melangkah lebih jauh, tetapi mengajarkan cara berhenti dengan khusyuk, sebelum kesaksian berikutnya dibuka oleh waktu.
6. Undangan untuk Menjadi Saksi Bersama
Epilog ini tidak saya maksudkan sebagai penutup yang merapikan semuanya ke dalam kesimpulan. Saya justru menempatkannya sebagai ambang, seperti pintu kayu yang dibiarkan setengah terbuka, agar pembaca tidak segera merasa sampai. Sebab dalam balada, sampai adalah berhenti mendengar. Dan saya menulis justru untuk memperpanjang kesediaan mendengar itu.
Dalam balada-balada saya, “tanah” tidak pernah sekadar menjadi latar, dan “langit” tidak hadir sebagai hiasan metaforis. Keduanya adalah subjek kesaksian. “Tanah” mencatat jejak kaki, sisa peluh, doa-doa yang jatuh tanpa suara. “Langit” menurunkan cahaya, tetapi juga menyimpan jarak, agar manusia belajar menengadah tanpa menguasai. Di antara keduanya, zikir dan doa bergerak, tidak selalu dalam lafaz, sering kali justru dalam laku yang nyaris tak dianggap ibadah.
Saya ingin mengundang pembaca memasuki posisi yang sama: bukan sebagai penafsir yang berdiri di luar, melainkan sebagai saksi yang ikut terlibat. Saksi yang tidak tergesa menyimpulkan, tidak sibuk menghakimi, tetapi bersedia hadir bersama hal-hal kecil yang sering disingkirkan dari perhatian. Dalam salah satu balada, kesaksian itu bahkan lahir dari sesuatu yang paling rapuh:
“Bayi dari dalam gentong cahaya, …
Bayi itu tak lahir
dari rahim wanita,
tapi dari bumi yang pasrah
dan doa-doa yang ditanam
oleh para pejalan sunyi.”
Bayi itu bukan sekadar metafora kelahiran, melainkan isyarat bahwa kesaksian selalu bermula dari ketakberdayaan. Dari sesuatu yang belum mampu berbicara, tetapi justru membawa doa paling jujur. Seperti itulah posisi pembaca yang saya harapkan: memasuki balada bukan dengan kesiapan menjelaskan, melainkan dengan kerendahan untuk menerima.
Kesaksian juga tidak selalu hadir di ruang terang. Ia sering tumbuh di wilayah duka, di pinggir kehilangan, di tempat-tempat yang membuat manusia ingin segera pergi. Namun balada justru mengajak berhenti di sana, meneduhkan diri, dan memandang kembali dengan mata yang dilunakkan. Sebab bahkan dalam hujan kuburan pun, masih ada laku yang setia menjaga kemanusiaan:
“Payung tua
berdiri miring di antara batu nisan, …
seperti kenangan …”
Payung tua itu bukan alat pelindung semata, melainkan simbol kesetiaan kecil yang bertahan di tengah kefanaan. Ia mengajarkan bahwa menjadi saksi tidak selalu berarti berkata-kata lantang; kadang cukup dengan tetap berdiri, tetap meneduhi, ketika yang lain memilih berlalu.
Maka balada, bagi saya, bukanlah teks yang menuntut pembaca memahami maksud penyair. Ia adalah ruang perjumpaan: antara pengalaman penyair dan pengalaman pembaca, antara yang telah ditulis dan yang akan terus hidup dalam tafakur masing-masing. Setiap orang dipersilakan menemukan cahayanya sendiri, sebagaimana setiap balada lahir dari gelap yang berbeda-beda.
Balada Langit di Tanah Leluhur saya hadirkan sebagai napas bumi yang belum selesai dihirup, sebagai zikir yang tidak mengenal titik akhir, sebagai cahaya yang justru lahir dari kesediaan tinggal sejenak dalam kegelapan. Jika ada yang ingin saya titipkan kepada pembaca, barangkali hanya ini: marilah menjadi saksi bersama: dengan hormat, dengan kesabaran, dan dengan kesediaan untuk tidak segera selesai.***
—
*Penulis adalah penyair dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.