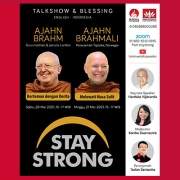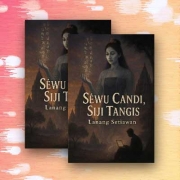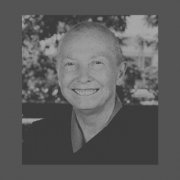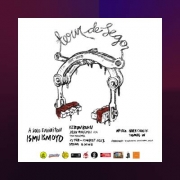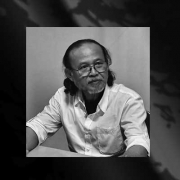Menjadi Indonesia: Suara Kebangsaan dalam Sastra
Oleh: Abdul Wachid B.S.*
1. Pendahuluan
Bulan Agustus bukan sekadar pengingat tanggal Proklamasi. Ia adalah waktu yang diselubungi kenangan, harapan, dan pertanyaan: sudah sejauh mana kita benar-benar merdeka, sebagai bangsa dan sebagai manusia Indonesia? Setiap tahun, gema kemerdekaan kembali membangkitkan ingatan kolektif atas perjuangan panjang menuju kemerdekaan, tetapi juga menjadi ruang refleksi tentang situasi kebangsaan hari ini, yang diwarnai tantangan disintegrasi, krisis keadaban, dan kekaburan identitas.
Dalam momen seperti ini, kita layak mengajukan pertanyaan mendasar: Apa makna menjadi Indonesia dalam konteks kekinian? Apakah “Indonesia” hanya sebuah entitas administratif dan geografis? Ataukah ia adalah kesadaran kultural dan batiniah yang tumbuh dari sejarah, pergulatan nilai, dan imajinasi bersama?
Sastra Indonesia, dalam terang pertanyaan itu, memiliki fungsi yang lebih dari sekadar cermin realitas. Ia adalah ruang artikulasi suara kebangsaan. Di dalam puisi, cerpen, novel, dan esai-esai sastra, tersembunyi jejak-jejak kritik sosial, kerinduan akan keadilan, serta upaya merawat persatuan dalam keragaman. Sastra bukan hanya “menggambarkan” Indonesia, tetapi turut membentuk dan menghidupkan makna menjadi Indonesia melalui bahasa yang menyentuh kesadaran terdalam kita.
Sastrawan Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga kini telah meletakkan fondasi naratif yang menegaskan bahwa “menjadi Indonesia” bukanlah keadaan yang selesai, melainkan proses yang terus berlangsung, dengan seluruh ketegangan, konflik, dan rekonsiliasi nilai di dalamnya. Dalam konteks ini, sumbangan sastra menjadi vital: ia menanamkan empati, menggugat kekuasaan yang korup, dan menggali ulang akar-akar kultural bangsa yang kian terlupakan.
Sebagai penulis, saya memandang bahwa menjadi Indonesia adalah panggilan untuk menumbuhkan kembali kesadaran kolektif kita sebagai bangsa; bukan hanya lewat politik dan hukum, tetapi melalui imajinasi, bahasa, dan perenungan kultural yang dalam. Sastra menjadi media yang membangkitkan ruh kebangsaan itu, karena ia bekerja dalam dimensi batin, bukan sekadar dalam tataran wacana publik.
Sebagaimana ditegaskan oleh Goenawan Mohamad, “Sastra yang besar adalah yang membentuk kesadaran, bukan yang sekadar menyenangkan” (Mohamad, Kesusastraan dan Kekuasaan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993). Dan kesadaran itu, di tengah krisis identitas dan disorientasi bangsa, adalah bekal utama untuk merawat keberlangsungan Indonesia sebagai cita-cita dan rumah bersama.
2. Menjadi Indonesia: Dari Proklamasi ke Kesadaran Kultural
Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukanlah garis akhir dari sebuah perjuangan. Ia adalah tonggak awal dari proses panjang bernama “menjadi Indonesia.” Menjadi berarti bertumbuh, berproses, dan berubah. Ia bukan keadaan yang statis, tetapi suatu perjalanan menuju pemaknaan diri sebagai bangsa; dari masyarakat terjajah menuju masyarakat merdeka, dari keragaman etnis menuju kesadaran sebagai bangsa yang utuh.
Proklamasi kemerdekaan secara politis memang menyatukan wilayah dan penduduk Nusantara dalam satu entitas yang disebut “Indonesia.” Namun, secara kultural dan psikologis, proses menjadi Indonesia terus berlangsung, bahkan hingga hari ini. Karena menjadi bangsa bukan sekadar persoalan hukum dan teritori, tetapi soal kesadaran kolektif yang tumbuh dari pengalaman sejarah, bahasa, dan narasi yang kita bagi bersama.
Dalam konteks inilah, pemikiran Benedict Anderson menjadi relevan. Ia menyebut bangsa sebagai “imagined community,” yaitu komunitas yang dibayangkan secara mental oleh orang-orang yang bahkan tidak saling mengenal secara pribadi, tetapi merasa satu dalam ikatan simbolik sebagai sebuah bangsa. “The nation is imagined,” tulis Anderson, “because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members … yet in the minds of each lives the image of their communion” (Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso, 2006: 6).(“Bangsa itu dibayangkan karena para anggotanya, bahkan dalam bangsa terkecil sekalipun, tidak akan pernah mengenal sebagian besar sesamanya … tetapi dalam benak masing-masing hidup citra tentang kebersamaan mereka.”)
Imajinasi kebangsaan inilah yang sejatinya dibentuk dan diperkaya oleh sastra. Lewat karya sastra, kita menemukan narasi tentang penderitaan rakyat kecil, tentang keragaman adat dan budaya, tentang perlawanan terhadap ketidakadilan, serta tentang harapan-harapan akan masa depan yang lebih baik. Semua itu menjadi bahan bakar bagi kesadaran kolektif kita sebagai “orang Indonesia.”
Sastra membantu kita membayangkan “Indonesia” sebagai rumah bersama. Dalam cerpen-cerpen Idrus, kita menyaksikan bagaimana penderitaan rakyat di masa revolusi menjadi kisah yang manusiawi, bukan sekadar heroisme yang kaku. Dalam puisi-puisi Chairil Anwar, kita melihat pemberontakan batin melawan ketertindasan dan pencarian jati diri sebagai manusia merdeka. Novel-novel Pramoedya Ananta Toer menghadirkan potret panjang sejarah kolonialisme dan lahirnya kesadaran nasional yang penuh luka, tetapi juga harapan.
Sastra, dengan kata lain, tidak hanya mengisahkan tentang Indonesia, tetapi ikut merumuskan maknanya. Lewat bahasa dan simbol, sastrawan Indonesia menyusun mozaik identitas nasional yang inklusif. Mereka tidak sekadar menarasikan sejarah, tetapi mentafsirkan ulang pengalaman kolektif bangsa dalam bentuk yang menyentuh kesadaran batin pembacanya.
Dalam suasana kebangsaan yang tengah diuji oleh polarisasi sosial, ujaran kebencian, dan komodifikasi identitas, karya sastra menawarkan ruang renung dan empati. Ia mengajak kita keluar dari kotak-kotak sempit primordialisme, dan menengok kembali nilai-nilai yang menyatukan kita: kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman yang saling menghormati.
Menjadi Indonesia, oleh karena itu, bukan sekadar soal status kewarganegaraan atau penghafalan sejarah. Ia adalah proyek budaya dan batin yang terus diperjuangkan. Dan dalam perjuangan itu, sastra memainkan peran penting: menyusun imajinasi kebangsaan, merawat kesadaran multikultural, dan menjaga bara semangat proklamasi tetap menyala di ruang batin kita yang terdalam.
3. Sastra sebagai Suara Kebangsaan
Sejak awal kelahirannya, sastra Indonesia telah berperan sebagai saksi dan sekaligus penggerak sejarah kebangsaan. Dalam karya-karya yang lahir dari ruang sunyi batin sastrawan, kita menemukan gema kegelisahan zaman, denyut kesadaran sosial, dan panggilan untuk membayangkan masa depan bangsa. Sastra tidak hadir dalam kekosongan, ia lahir dari konflik, harapan, dan pergulatan kolektif suatu masyarakat yang tengah mencari jati dirinya.
Pada masa penjajahan, kita menemukan roman-roman awal Balai Pustaka seperti Sitti Nurbaya (1922) karya Marah Rusli dan Salah Asuhan (1928) karya Abdul Muis, yang tidak hanya menjadi produk sastra, melainkan juga menjadi dokumen budaya yang merekam ketegangan antara nilai tradisi dan modernitas, antara kolonialisme dan cita-cita emansipasi. Dalam Salah Asuhan, misalnya, kisah Hanafi dan Corrie menjadi alegori tentang kegagapan identitas bangsa terjajah yang terhimpit oleh keinginan menjadi modern dan keharusan menjaga akar budaya sendiri.
Memasuki era revolusi dan kemerdekaan, suara kebangsaan dalam sastra menguat dengan munculnya puisi-puisi Chairil Anwar. Puisinya bukan hanya ekspresi individual, tetapi juga bentuk pembangkangan terhadap narasi resmi yang membelenggu kebebasan berpikir. Dalam puisinya yang terkenal, “Karawang-Bekasi,” Chairil menulis:
Kami yang kini terbaring antara Karawang-Bekasi
tidak bisa teriak ‘Merdeka!’ dan angkat senjata lagi.
…..
(Anwar, Aku Ini Binatang Jalang, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. ke-21, 2009: 88).
Puisi ini bukan sekadar ratapan duka para pejuang yang gugur, melainkan juga peringatan bahwa kemerdekaan yang dinikmati generasi penerus adalah warisan dari darah dan pengorbanan. Chairil meletakkan kesadaran kebangsaan bukan di tataran slogan, tetapi dalam perenungan eksistensial tentang arti hidup dan mati demi tanah air.
Pada dekade-dekade berikutnya, sastrawan seperti W.S. Rendra membawa sastra ke ruang publik sebagai teater kritik sosial. Puisi-puisi Rendra, baik dalam bentuk pembacaan puisi maupun teater mini kata, menjadi wahana perlawanan terhadap tirani dan ketimpangan. Dalam puisinya “Sajak Pertemuan Mahasiswa”, Rendra menggugat:
…..
Kenapa maksud baik dilakukan
tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya.
Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota.
Perkebunan yang luas
hanya menguntungkan segolongan kecil saja.
Alat-alat kemajuan yang diimpor
tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya.
Tentu, kita bertanya:
“Lantas maksud baik saudara untuk siapa?”
…..
(Rendra, Potret Pembangunan dalam Puisi, Bandung: Pustaka Jaya, Cet.ke-3, 2013: 45).
Melalui sajak ini, Rendra menggugat alienasi manusia dalam sistem kekuasaan yang tidak lagi mengindahkan suara rakyat. Sastra menjadi alat untuk membongkar kebekuan, sekaligus mengembalikan bahasa kepada rakyat yang tersisih dari percakapan politik formal.
Namun suara kebangsaan dalam sastra tidak hanya hadir dalam teriakan atau kemarahan. Ia juga muncul dalam bisikan lirih kerinduan akan keadilan dan persatuan. Dalam cerpen dan novel Ahmad Tohari, terutama trilogi Ronggeng Dukuh Paruk (Gramedia, 1982), kita menyaksikan bagaimana nasib individu terjerat dalam pusaran sejarah nasional, dan bagaimana tragedi politik meninggalkan luka yang dalam di tubuh rakyat kecil. Melalui tokoh Srintil, Tohari merekam getirnya menjadi “orang kecil” di tengah pertarungan ideologi besar yang sering tidak berpihak pada kemanusiaan.
Sastra, dengan demikian, tidak hanya mencatat fakta-fakta sosial-politik, tetapi menafsirkan ulang makna-maknanya. Ia menampilkan konflik SARA, ketimpangan sosial, dan luka sejarah; bukan untuk memperkeruh, melainkan untuk membuka ruang penyembuhan kolektif. Sastra menawarkan semacam “jalan sunyi” menuju kesadaran kebangsaan yang lebih jernih, yang tidak mudah digoda oleh populisme, chauvinisme, atau intoleransi.
Sebagaimana dikemukakan Edward Said, “Great literature does not only celebrate the nation but constantly interrogates and redefines it” (“Sastra besar tidak sekadar merayakan bangsa, tetapi juga mempertanyakan dan mendefinisikan kembali apa artinya menjadi bagian dari bangsa itu”), (Said, Culture and Imperialism, London: Vintage Books, 1994: 254).
Dalam konteks Indonesia, karya-karya sastra dari masa ke masa justru menjadi ruang di mana makna “Indonesia” dinegosiasikan ulang: apakah kita masih satu bangsa jika ketimpangan merajalela? Apakah kita masih Indonesia jika bahasa kebencian dan diskriminasi terus menjalar?
Sastra tidak berhenti pada penggambaran, ia menawarkan tafsir dan arah. Ia menuntun bangsa untuk berpikir ulang tentang siapa kita, dari mana kita datang, dan ke mana kita hendak pergi. Menjadi Indonesia, melalui sastra, adalah mengasah kepekaan terhadap penderitaan sesama, memelihara akal sehat, dan menjaga nurani dari kekuasaan yang membutakan. Di tengah krisis identitas dan narasi palsu yang membanjiri ruang publik, sastra hadir sebagai suara yang jernih dan tegas: untuk mengingatkan, menegur, dan membimbing kita agar tetap manusia, dan tetap Indonesia.
4. Refleksi atas Situasi Kebangsaan Kini
Kebangsaan Indonesia hari ini tengah berada di persimpangan jalan yang rumit. Polarisasi politik yang kian mengeras, maraknya disinformasi, serta menguatnya intoleransi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan nilai-nilai kebinekaan yang menjadi fondasi republik ini. Dalam lanskap sosial semacam itu, sastra hadir bukan sekadar sebagai cermin, tetapi sebagai sumur refleksi batin yang dalam: mengajak kita menakar kembali makna kemanusiaan dan kebangsaan secara jernih dan mendalam. Sastra menjadi laboratorium nurani tempat bangsa ini diuji: apakah ia masih sanggup mendengar jerit kemanusiaan di tengah kebisingan kontestasi politik?
K.H.A. Mustofa Bisri, melalui buku puisi Aku Manusia (Mata Air, 2016), menawarkan laku kesaksian spiritual yang menembus batas agama, etnis, dan ideologi. Puisinya bukan sekadar renungan individual, melainkan suara hati seorang warga bangsa yang merindukan kemanusiaan dalam wujudnya yang paling tulus. Dengan bahasa yang tenang, Gus Mus mengingatkan bahwa agama sejatinya adalah jalan cinta kasih, bukan alat untuk menciptakan permusuhan. Puisi-puisinya menjadi semacam doa panjang bagi bangsa, agar tidak kehilangan rasa malu untuk menjadi manusia.
Seno Gumira Ajidarma, dalam kumpulan cerpen Saksi Mata (Bentang, 1994) dan esai-esai dalam Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara(Bentang, 1997), menegaskan posisi sastra sebagai ruang tanding atas kekuasaan yang menindas. Seno memanfaatkan teknik naratif eksperimental dan simbolisme yang tajam untuk membongkar represi negara terhadap warganya. Dalam karya-karyanya, suara-suara yang disingkirkan negara mendapatkan artikulasinya. Di saat kebenaran tak mendapat tempat di media dan forum resmi, sastra menurut Seno justru menjadi ruang alternatif yang menyuarakan yang bisu dan membela yang terinjak.
Adapun Leila S. Chudori melalui novel Laut Bercerita (Gramedia, 2017) menghidupkan kembali fragmen sejarah yang hampir dilupakan: penculikan dan penghilangan paksa aktivis menjelang Reformasi 1998. Dengan gaya penceritaan yang intim dan mengalir, Leila merajut narasi kesaksian dari sisi terdalam kemanusiaan; mengisahkan bagaimana kekuasaan merenggut bukan hanya tubuh, tetapi juga impian dan cinta. Novel ini tidak berhenti sebagai karya sastra, melainkan menjelma menjadi ruang memorial kolektif yang menuntut keadilan yang belum selesai.
Sastra Indonesia kontemporer, melalui suara-suara semacam itu, meneguhkan bahwa ia tidak hanya bergerak dalam ruang estetika, melainkan juga etika. Ia tidak sekadar menghibur atau mengalihkan, tetapi mencerdaskan batin dan mengasah kesadaran. Di tengah derasnya arus teknologi informasi yang seringkali memperkeruh realitas dengan polarisasi, hoaks, dan manipulasi naratif, karya sastra justru menawarkan ruang jeda; tempat kita belajar memahami kenyataan secara lebih utuh dan manusiawi.
Refleksi kebangsaan melalui sastra bukanlah tugas elitis, melainkan proses kolektif menyemai kepekaan. Ketika institusi pendidikan kehilangan arah, ketika media kehilangan objektivitas, ketika politik kehilangan nurani, sastra menyodorkan seberkas cahaya dari ruang batin: bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, kita harus lebih dahulu menjadi manusia yang utuh. Di sanalah sastra memainkan peran profetiknya; sebagai suara hati bangsa yang tidak tunduk pada hiruk-pikuk pasar dan kekuasaan.
Dalam konteks ini, sastra berperan membangun semacam moral imagination, yakni kemampuan membayangkan kehidupan bersama yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat. Ia mempertemukan antara sejarah dan harapan, antara luka dan pengampunan, antara kenyataan dan kemungkinan. Maka, membaca karya sastra Indonesia kontemporer bukan sekadar mengikuti alur cerita atau permainan diksi, melainkan memasuki ruang kontemplasi atas arah bangsa ini ke depan.
Apabila bangsa ini hendak bangkit dengan wajah yang lebih teduh dan berkeadaban, maka literasi sastra harus menjadi bagian dari pembentukan karakter warga negara. Karena melalui sastra, kita tidak hanya belajar menulis dan membaca, melainkan belajar mencintai tanpa syarat, menyimak tanpa menghakimi, dan merangkul tanpa merasa paling benar. Sastra adalah pendidikan empati yang diam-diam membentuk kepribadian kebangsaan kita; lembut tapi tegas, kritis namun penuh kasih, rasional tetapi tetap spiritual.
5. Membangun Kesadaran Kebangsaan Lewat Sastra
Di tengah gelombang globalisasi yang mengikis batas geografis dan menggoyahkan identitas kolektif, literasi sastra memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kebangsaan. Kesadaran ini tidak dapat dibentuk secara instan atau melalui slogan semata, melainkan tumbuh dari pengalaman batiniah dan imajinatif. Sastra memungkinkan kita mengalami Indonesia sebagai rasa, bukan sekadar data.
Membaca dan menulis sastra bukanlah semata praktik estetik, tetapi juga praksis kebangsaan. Melalui puisi, cerpen, dan novel, kita diajak menyelami hidup orang lain, memahami luka dan harapan dari berbagai latar sosial dan budaya. Martha C. Nussbaum menyebut pengalaman ini sebagai imaginative empathy, yaitu kemampuan membayangkan dunia dari sudut pandang orang lain melalui karya sastra, yang menurutnya menjadi landasan bagi kebajikan demokratis. Dalam bukunya Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (Princeton: Princeton University Press, 2010), Nussbaum menyatakan, “Literary imagination is an essential tool in cultivating citizens who can understand people different from themselves.” (hlm. 95). Terjemahannya: “Imajinasi sastra adalah alat penting dalam membentuk warga negara yang mampu memahami orang lain yang berbeda dari dirinya.”
Dalam konteks Indonesia, proses menjadi bangsa tidak hanya lahir dari peristiwa-peristiwa politik seperti Proklamasi, melainkan juga dari kerja kultural yang berlangsung terus-menerus. Di sinilah komunitas-komunitas sastra memainkan peran sebagai laboratorium kesadaran nasional. Di ruang-ruang seperti sanggar, pesantren, sekolah, taman kota, hingga media sosial hari ini, komunitas sastra menyuburkan ruang artikulasi kebangsaan yang bersifat partisipatif dan egaliter.
Misalnya, Komunitas Rumah Dunia di Serang yang digagas Gol A Gong (Heri Hendrayana Harris) bukan hanya menjadi pusat literasi, tetapi juga tempat warga lintas identitas merayakan Indonesia melalui karya sastra. Di Yogyakarta, komunitas jalanan seperti Senja Bersastra di Malioboro telah lama menjadi ruang kritik sosial dan perayaan kebhinnekaan. Bahkan di ruang digital, platform seperti basabasi.co dan mojok.co terus menghidupkan narasi kebangsaan yang segar, inklusif, dan kritis.
Literasi sastra adalah investasi kebangsaan. Sebab, ia membentuk karakter yang toleran dan berpikir majemuk. Seperti dikatakan Italo Calvino dalam esainya “Why Read the Classics?” (London: Vintage Books, 1999), “The novel teaches you to see the world not as a single perspective but from many viewpoints” (hlm. 183). Terjemahannya: “Novel mengajarkan kita untuk melihat dunia bukan dari satu sudut pandang, melainkan dari berbagai perspektif.” Kemampuan untuk melihat dari banyak sudut pandang inilah yang menjadi fondasi penting dari masyarakat Indonesia yang plural.
Pendidikan nasional yang baik tidak cukup hanya mengajarkan angka dan rumus, tetapi juga harus mendidik rasa dan nurani. Menjadi Indonesia, pada akhirnya, bukan hanya perkara administratif, tetapi juga perkara batin dan imajinasi. Dan sastra adalah medan latihan terbaik untuk membentuk keduanya secara serentak: nalar dan rasa, logika dan empati.
6. Penutup
“Menjadi Indonesia” bukanlah suatu titik akhir yang telah selesai dicapai pada 17 Agustus 1945. Ia adalah sebuah kerja budaya yang terus bergerak, merawat keberagaman sembari merajut kesatuan, menyadari luka sembari menumbuhkan harapan. Dalam perjalanan itu, sastra hadir bukan sebagai pelengkap hiburan atau pelarian dari kenyataan, melainkan sebagai suara nurani dan hati bangsa.
Sebagai sebuah ekspresi batiniah dan imajinatif, sastra menyimpan daya yang tak dimiliki pidato politik atau laporan statistik, yakni kemampuannya menyentuh kesadaran terdalam manusia dan menyalakan empati. Ia tidak berbicara dengan bahasa kuasa, tetapi dengan bahasa pengalaman yang paling konkret: luka, cinta, kehilangan, dan harapan. Dalam pandangan Goenawan Mohamad, sastra memiliki watak subversif justru karena ia bergerak di wilayah yang tak bisa dijangkau oleh kekuasaan, yakni ruang batin dan pengalaman yang memungkinkan kita “merasakan keberadaan orang lain” (Marxisme, Seni, dan Pembebasan, Tempo & Grafiti Pers, 2011). Dalam kerangka kebangsaan, kemampuan inilah yang menjadi dasar etis dan emosional untuk membangun Indonesia sebagai rumah bersama; bukan hanya dari segi administratif dan hukum, tetapi dari empati dan tanggung jawab sebagai sesama warga bangsa.
Kesanggupan sastra untuk membayangkan ulang Indonesia menjadi amat penting, terutama ketika wacana kebangsaan kian direduksi menjadi slogan kosong, politik identitas yang sempit, atau distorsi sejarah yang manipulatif. Dalam situasi demikian, sastra tampil sebagai penanda arah moral, karena ia tumbuh dari kesaksian, kejujuran batin, dan cinta pada kemanusiaan. Edward Said dalam esainya “The World, the Text, and the Critic” menyatakan bahwa tugas intelektual (termasuk sastrawan) bukanlah memperkuat kekuasaan, melainkan mewakili suara-suara yang terpinggirkan: “The role of the intellectual is not to consolidate authority, but to represent all those people and issues that are routinely forgotten or swept under the rug” (Cambridge: Harvard University Press, 1983: 27). (Peran intelektual bukan untuk mengukuhkan kekuasaan, tetapi mewakili semua orang dan persoalan yang kerap dilupakan atau disapu ke bawah karpet).
Dalam semangat itu, sastra Indonesia sejatinya telah memainkan peran sebagai ruang kontemplasi, kritik, dan perlawanan terhadap ketidakadilan, sekaligus membentuk rasa kebangsaan yang inklusif. Ia merintis jalan pelan tapi pasti; bukan dengan bendera dan semboyan, melainkan dengan bahasa, imajinasi, dan kejujuran nurani.
Kita diajak bukan sekadar untuk membaca sastra sebagai teks, tetapi untuk mendengarkan suara kebangsaan yang bergema di dalamnya. Mendengarkan Chairil Anwar yang meneriakkan keberanian eksistensial dalam puisi “Aku”; menyimak W.S. Rendra yang melantangkan kritik sosial melalui teater dan sajaknya; merenungkan puisi Gus Mus yang lirih namun menghujam, mengajak kita kembali pada nilai-nilai ketauhidan dan kemanusiaan; hingga menyelami nestapa sejarah dan pergulatan identitas dalam Laut Bercerita karya Leila S. Chudori; semua itu adalah jejak yang menunjukkan bahwa sastra bukan hanya estetika, melainkan etika dan politik nurani.
Karya-karya itu membentuk semacam batin kolektif bangsa, menjadi cermin dan arah. Di tengah zaman yang penuh disinformasi, banalitas, dan krisis etika, sastra adalah jalan sunyi yang mengantar kita kembali kepada dasar-dasar kemanusiaan dan kebangsaan: kejujuran, keberagaman, keadilan, serta kasih sayang sebagai fondasi peradaban.
Maka, kita rawat kebangsaan ini bukan hanya dengan simbol-simbol seremonial, tetapi dengan keberanian mendengar suara yang paling jujur dari bangsa, yakni suara sastranya. Sebab di dalamnya bersemayam nurani yang tak pernah padam, dan hati yang senantiasa mencintai Indonesia yang adil, majemuk, dan beradab.
—-
*Abdul Wachid B.S., Penyair, Guru Besar Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.