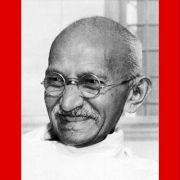Membaca Tegal: Ladang Yang Menolak Kering
Oleh Tirto Suwondo
Tegal, sebagai sebuah kota/kabupaten di Pantai Utara Bagian Barat Provinsi Jawa Tengah, tidaklah boleh diasosiasikan hanya seturut katanya: tegal(an), ladang (bukan sawah), huma (yang kering). Sebab, kota yang telah berusia lebih dari 440 tahun itu, sampai saat ini tetap eksis sebagai wilayah yang diperhitungkan. Bukan saja karena Tegal menjadi ikon warteg, moci, rahim marinir, Jepangnya Indonesia, dan wayang golek cepak, melainkan juga karena Tegal –dengan bekal bahasa Jawa Dialek Tegal yang khas– memiliki tradisi kreatif bersastra yang unik: dinamika, antusiasme, dan inovasi sastrawannya paradoks dengan denotasi kotanya; mereka mampu menjadikan tegal/ladang sebagai tak sekadar place tetapi juga space yang menolak/tak mau kering.
Belakangan ini, tanpa menafikan mereka yang mapan di tempat/ruang lain, sastrawan yang kini tetap mukim di Tegal agaknya telah membuat “ke-gila-an” tersendiri. Coba bayangkan. Kurang dari tiga tahun (2019–2021) mereka, yang rata-rata bergulat dalam dua-bahasa (Indonesia dan Jawa-Tegalan), berhasil memproklamasikan tiga model yang diklaim sebagai Genre Baru Puisi Tegalan. Pertama, Wangsi, yakni puisi hasil perpaduan antara wangsalan (cangkriman, parikan?) dan puisi; kedua, Kur 267, yakni kemasan puisi pendek berbahasa Tegalan (yang diserap dari model Haiku Jepang) yang “setiap larik/barisnya hanya 2 suku kata, 6 suku kata, dan 7 suku kata”; dan ketiga Puisi Tegalerin, yakni puisi hasil perpaduan jenis puisi dari dua negara yang berbeda (Puisi Jawa-Tegalan-Indonesia dan Soneta-Italia) yang terdiri 4 bait, 12 baris, dan berpola 2-4-2-4.

Buku Puisi 2-4-2-4, Telik Sandi Tegalerin. Editor Lanang Setiawan.

Buku Antologi Puisi 2-4-2-4
Sungguh itu tindakan yang berani dan “gila”, bahkan boleh dibilang “terlalu berani” atau “terlalu gila” (sebagai ungkapan decak kagum). Saya katakan begitu karena di benak saya bertanya: sudahkah dipertimbangkan dengan matang kriteria (estetik dan ekstraestetik) yang menjadi dasar klaim bahwa ia adalah genre baru? Tetapi, saya tahu dan sadar, era ini adalah era demokrasi, era dekonstruksi atas kemapanan, era penolakan relasi kuasa dominatif-superior, era yang menempatkan keberagaman pendapat (siapa pun) pada ruang tertinggi akal sehat kita. Karenanya, klaim genre baru itu sah-sah saja dan harus dihargai; dan soal keberlangsungannya pasti akan teruji dan diuji oleh sejarah. Soal kelak sejarah akan mengukuhkan atau melenyapkannya bukanlah hal penting yang perlu dipikirkan sekarang; yang jelas tindakan kreatif-inovatif ini telah menorehkan sejarah tersendiri bagi perjalanan sejarah perkembangan sastra-puisi Tegalan-Indonesia.
Karena itu pula, sekali lagi, klaim Genre Baru Puisi Tegalan oleh Lanang Setiawan dan kawan-kawan itu sah kehadirannya, sama sahnya ketika Serat Rijanto (R.B. Soelardi, 1920) diklaim sebagai genre baru novel Jawa modern, atau geguritan “Kowe Wis Lega?” (St. Iesmaniasita, 1954) yang diklaim sebagai genre baru puisi Jawa yang benar-benar modern dan terbebas dari tradisi. Atau, jika kita tengok perkembangan sastra Indonesia, hal yang sama tampak pada klaim tentang “kebaruan” Puisi Mbeling oleh Remy Silado mulai 1974 di Majalah Aktuil, kebaruan Teater Sampakan model Gandrik Yogyakarta yang memberi ruang penonton aktif dalam pentas, atau ketika Chairil Anwar, Iwan Simatupang, Danarto, Putu Wijaya, Linus Suryadi AG, dan Budi Darma yang diklaim sebagai sastrawan pembawa corak baru dalam sastra Indonesia. Analog dengan fakta itu jelas bahwa klaim lahirnya Genre Baru Puisi Tegalan menjadi sebuah keniscayaan.
Hanya saja, agar klaim genre baru itu bertahan dan menjadi tonggak yang mampu membangun sejarah perkembangannya tersendiri, haruslah ada pihak atau tokoh (akademisi atau siapa pun) yang selalu menyuarakan dan tak henti-henti mambangun narasi dialogis tentangnya. Hal ini sama halnya ketika di belakang Chairil Anwar ada HB Jassin, di balik Iwan Simatupang ada Dami N. Toda, di balik Linus Suryadi “Pengakuan Pariyem” ada Bakdi Sumanto, dan seterusnya. Nah, saya kira, tokoh-tokoh seperti Tri Mulyono, Muarif Essage, Dina Nurmalisa, Maufur, Atmo Tan Sidik, dan kawan lainnya bisa berada di belakang dan menjadi backing keberlangsungan genre baru puisi tegalan (Wangsi, Kur 267, Puisi Tegalerin).
Di samping itu, berbagai informasi menyebutkan, di balik lahirnya klaim Genre Baru Puisi Tegalan, nama Lanang Setiawan agaknya sangat dominan (meski tak menafikan peran rekan-rekan seperti Muarif Essage, Dwi Ery Santoso, M. Ayyub, Ria Candra Dewi, dan lain-lain di Komunitas Sastrawan Tegal). Penyair (Lanang Setiawan) penerima Hadiah Rancage yang sangat getol mengangkat tinggi-tinggi nama dan tradisi kota Tegal melalui seni-sastra-puisi bermedium bahasa lokal (Jawa-Tegalan) ini agaknya berupaya paling keras dalam melakukan kreasi dan inovasi atas puisi Tegalan.



Beberapa puisi-puisi Tegalan
Karena itu, saya kira, dalam konteks Sastra Tegalan, kalau selama ini Dwi Ery Santoso telah menyandang gelar dan dipredikati Presiden Penyair Tegalan, agaknya Lanang Setiawan layak pula menyandang gelar dan dipredikati Pembaharu (Inovator) Puisi Tegalan. Kalau berkat usahanya mengembangkan Soneta (dari Eropa) dalam kancah sastra Jawa modern R. Intojo kemudian dijuluki Bapak Soneta dalam Sastra Jawa Modern, apa salahnya jika Lanang Setiawan dijuluki Bapak Pembaharu Puisi Tegalan karena memang telah berinovasi dan membidani lahirnya Genre/Jenis Baru Puisi Tegalan.


Foto Lanang Setiawan dan buku puisinya
Hal tersebut sekaligus menjawab sebagian pertanyaan dan harapan Hasan Aspahani di Kompas (8 Agustus 2021) “Wahai, Para Inovator Sastra, di Manakah Kalian?” yang kemudian ditanggapi oleh Binhad Nurrohmat (22 Agustus 2021) “Fundamentalisme Puisi”, Warih Wisatsana (5 September 2021) “Lapis Realitas Penyair Kini”, dan Hikmat Gumelar (19 September 2021) “Kelamnya Habitat Sastra Kita”. Nah, sebagian jawaban atas pertanyaan itu ada di Tegal berkat hadirnya klaim Genre Baru Puisi Tegalan dalam waktu tiga tahun terakhir ini. Hanya saja, saya kira, persoalan ini masih perlu dibawa dan diuji publik secara lebih luas.
Yogyakarta, 11 Oktober 2021
*Tirto Suwondo. Peneliti Balai Bahasa DIY-