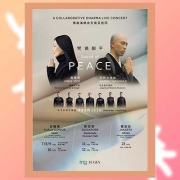Imajisme Transendental dalam Perpuisian: Membaca Tanda-tanda Tuhan melalui Puisi
Oleh Abdul Wachid B.S.*
1. Pendahuluan: Pengantar tentang Imajisme dalam Sastra
Imajisme adalah aliran dalam sastra yang menekankan penggunaan citraan yang jelas, padat, dan langsung. Gerakan ini dipelopori oleh Ezra Pound pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap kecenderungan puisi yang terlalu berbunga-bunga dan bertele-tele. Ezra Pound menetapkan tiga prinsip dasar imajisme:
1. Langsung kepada pokok persoalan – Puisi harus menghindari abstraksi yang berlebihan dan menyajikan pengalaman secara konkret;
2. Menggunakan bahasa yang ekonomis – Setiap kata dalam puisi harus memiliki fungsi yang jelas dan tidak boleh ada kata yang mubazir;
3. Menciptakan ritme yang alami – Puisi sebaiknya mengikuti pola bahasa yang alami, bukan aturan metrik yang kaku (Pound, A Retrospect, 1918).
Dalam kata-katanya, Pound menyatakan: “Direct treatment of the ‘thing’ whether subjective or objective. To use absolutely no word that does not contribute to the presentation. To compose in the sequence of the musical phrase, not in sequence of a metronome.”; “Perlakuan langsung terhadap ‘benda’ baik yang subjektif maupun objektif. Menggunakan kata-kata yang betul-betul berkontribusi pada penyajian. Menyusun dengan urutan frasa musikal, bukan urutan metronom.” (Pound, A Retrospect, 1918:8).
Ezra Pound memandang bahwa puisi yang menggunakan citraan yang kuat, jelas, dan langsung memiliki daya ungkap yang lebih besar daripada puisi yang bersifat abstrak atau terlalu berbunga-bunga. Imajisme memfokuskan pada kemampuan untuk “menyentuh” pembaca melalui gambaran konkret yang dapat dirasakan oleh indra. Aliran ini berkembang dalam sastra Inggris dan Amerika, mempengaruhi penyair seperti T.S. Eliot dan William Carlos Williams. Ezra Pound, sebagai tokoh utama dalam gerakan ini, berfokus pada kekuatan citraan dalam menggambarkan pengalaman yang langsung dan nyata, tanpa keterbatasan metafora yang rumit.
Di luar tradisi Barat, imajisme juga menginspirasi banyak penyair di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun penyair Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip imajisme secara eksklusif, pengaruhnya tampak jelas dalam gaya puisi modern Indonesia, terutama yang dipelopori oleh penyair seperti Chairil Anwar. Meskipun Chairil Anwar tidak secara langsung menyebut dirinya sebagai penganut imajisme, puisi-puisinya yang padat, tajam, dan kaya citraan menggambarkan ciri-ciri yang sangat mirip dengan gaya imajistik.
2. Imajisme dalam Perpuisian Indonesia
Di Indonesia, imajisme memiliki kekhasan tersendiri yang dipengaruhi oleh budaya lokal dan konteks keagamaan. Chairil Anwar, yang dikenal dengan puisi-puisinya yang penuh gairah dan kejujuran ekspresif, sering kali menggunakan citraan yang langsung dan menyentuh realitas kehidupan. Seperti halnya Ezra Pound, Chairil Anwar menghindari simbolisme yang bertele-tele dan mengutamakan kekuatan gambar visual yang langsung. Misalnya, dalam puisi “Senja di Pelabuhan Kecil”, Chairil Anwar menggunakan citraan yang mengarah pada perasaan dan peristiwa-peristiwa konkret, dengan sedikit ruang untuk interpretasi yang kabur.
Namun, berbeda dengan tradisi Barat yang lebih banyak menekankan estetika dan formalitas bahasa, imajisme dalam perpuisian Indonesia sering kali lebih berbicara tentang pengalaman hidup sehari-hari yang bisa ditangkap dalam citraan yang lebih personal. Banyak penyair Indonesia juga menggabungkan imajisme dengan tradisi budaya dan keagamaan, menjadikannya sebagai cara untuk menggali makna lebih dalam dari alam semesta dan kehidupan manusia.
Dalam konteks ini, imajisme berperan lebih dari sekadar teknik sastra; ia menjadi medium untuk merenungkan kehidupan, termasuk hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam perspektif ini, imajisme bukan hanya tentang gambaran visual yang kuat, tetapi juga tentang makna yang lebih dalam yang bisa ditemukan melalui perenungan atas fenomena alam dan eksistensi manusia. Setelah Chairil Anwar, penyair Indonesia yang mengeksplorasi imajisme sebagai dasar perpuisiannya adalah Goenawan Mohamad (sejak buku puisi Parikesit), Sapardi Djoko Damono (sejak buku puisi Duka-Mu Abadi), dan Abdul Hadi W.M. (sejak buku puisi Laut Belum Pasang).
3. Imajisme dalam Perspektif Al-Qur’an: Tafakur atas Ayat-ayat Kauniyah
Dalam Islam, setiap fenomena alam dipandang sebagai ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat dijadikan bahan renungan bagi manusia. Firman Allah dalam Al-Qur’an menyatakan:
“Akan Kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur’an itu benar” (QS. Fussilat: 53).
Ayat ini mengajarkan bahwa setiap unsur alam—udara, cahaya, embun, dan fajar—bukan hanya realitas fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual yang lebih dalam. Setiap elemen alam adalah bagian dari wahyu Tuhan yang dapat dibaca oleh mereka yang memiliki kesadaran spiritual. Konsep ini mendorong kita untuk membaca alam bukan hanya dengan mata fisik, tetapi juga dengan mata hati.
Fenomena alam dapat dijadikan bahan tafakur, yaitu renungan mendalam yang tidak hanya mencakup aspek fisik atau rasional, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual dan transendental. Dalam hal ini, imajisme dalam puisi bukan hanya berfungsi sebagai teknik estetika, tetapi juga sebagai medium tafakur dan kesadaran transendental, yang mengajak pembaca untuk merenungkan hubungan antara alam, Tuhan, dan kehidupan manusia.
4. Dua Puisi sebagai Contoh: “Udara Subuh” dan “Takdir Fajar”
Sebagai contoh penerapan imajisme dalam perspektif transendental, dua puisi saya berikut ini menunjukkan bagaimana imajisme berfungsi sebagai sarana membaca tanda-tanda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
Sajak Abdul Wachid B.S.
UDARA SUBUH
Udara subuh menyusup lirih,
menyentuh jendela dengan jemari,
seperti bisikan yang nyaris letih,
di rumah-rumah yang sunyi berdiri.
Fajar merambat pelan di tanah,
melewati ilalang yang dingin resah,
seakan menampung doa yang basah,
di telapak waktu yang terus pasrah.
Embun jatuh di ujung daun,
luruh di tanah yang diam menunggu,
seperti langkah yang letih bertahun,
namun tak henti mencari rindu.
Lalu langit melahirkan cahaya,
bening dan hangat di ufuk teduh,
seperti tangan ibu yang sedia berjaga,
menuntun pagi dari lelap yang luruh.
2025
Sajak Abdul Wachid B.S.
TAKDIR FAJAR
Di sahar yang lirih,
udara melagukan sunyi yang panjang,
angin mengetuk pintu-pintu langit,
mengantar rintihan yang belum selesai.
Di tepi fajar shadiq,
cahaya tipis merambat di cakrawala,
seperti seutas benang halus
menjahit gelap dengan harapan.
Lalu subuh pun mengecup bumi,
menyentuh dedaunan dengan embun,
dan dalam sejuknya yang bening,
takdir hari ini kembali lahir.
2025
5. Analisis Imajisme Transendental dalam Dua Puisi
Dalam kedua puisi di atas, citraan yang digunakan tidak hanya mendeskripsikan fenomena alam, tetapi juga memiliki makna simbolik yang mendalam, mengarah pada pemahaman spiritual yang lebih luas.
1. Udara subuh, sebagai metafora kesadaran dalam puisi pertama bukan hanya menggambarkan kesejukan fisik, tetapi juga simbol kehadiran Ilahi yang membangunkan manusia dari tidur. Sunyi dan lirihnya udara subuh mencerminkan ketenangan spiritual yang muncul sebelum dunia kembali sibuk. Dalam konteks ini, udara subuh menjadi simbol dari proses pembersihan hati yang terjadi pada saat fajar menyingsing, ketika kesadaran manusia terbangun dan merenungkan kebesaran Tuhan.
2. Fajar shadiq sebagai batas antara gelap dan terang dalam puisi “Takdir Fajar”, fajar shadiq digambarkan sebagai benang halus yang menjahit gelap dengan harapan. Transisi dari malam ke pagi ini adalah simbol dari perubahan spiritual, di mana gelap (kegelapan jiwa atau kebingungannya) disatukan dengan terang (pencerahan Ilahi). Fajar bukan hanya sebuah fenomena fisik, tetapi sebuah tanda bahwa setiap perubahan membawa harapan baru yang diberikan Tuhan.
3. Embun sebagai simbol kepasrahan. Embun yang jatuh di ujung daun, mencerminkan kepasrahan manusia kepada takdir. Seperti embun yang akhirnya menyatu dengan tanah, manusia pun harus menerima segala ketetapan Allah dengan hati yang lapang. Embun mengajarkan tentang kelembutan hati, ketundukan yang tidak dipaksakan, tetapi lahir secara alami dari dalam diri.
4. Cahaya pagi sebagai anugerah Ilahi. Langit yang melahirkan cahaya, dalam kedua puisi ini tidak hanya menggambarkan proses alamiah terbitnya matahari, tetapi juga merupakan simbol kasih sayang Tuhan yang selalu hadir untuk menuntun manusia dari kegelapan menuju terang. Cahaya pagi dalam konteks ini adalah pengingat bahwa dalam setiap kegelapan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar, memberi pencerahan, dan memandu umat-Nya menuju kebenaran.
6. Kesimpulan: Imajisme dalam Perspektif Transendental
Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa imajisme dalam perpuisian tidak hanya berfungsi sebagai teknik estetika, tetapi juga sebagai sarana tafakur yang mendalam. Dengan memahami fenomena alam melalui citraan yang kuat dan langsung, puisi-puisi tersebut mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh dari sekadar permukaan, dan memahami makna transendental yang tersembunyi di balik setiap peristiwa alam.
Puisi-puisi yang dibangun dengan prinsip imajisme, seperti yang telah dijelaskan, mengundang pembaca untuk merenung, menyelami makna yang lebih dalam, dan merenungkan kebesaran Tuhan melalui simbolisme alam. Setiap elemen alam seperti udara, embun, fajar, dan cahaya pagi bukan hanya gambaran fisik, tetapi juga memiliki makna yang mengarah pada kesadaran spiritual, yang bisa ditemukan jika kita membaca dengan hati dan tidak hanya dengan indera.
Dalam konteks ini, imajisme transendental menawarkan dimensi baru dalam pembacaan puisi, yaitu puisi sebagai sarana penghubung antara dunia fisik dan spiritual. Ia bukan hanya berbicara tentang pengalaman manusia dalam batas-batas waktu dan ruang, tetapi juga mengajak pembaca untuk mengenal lebih jauh tentang diri mereka sendiri, hubungan mereka dengan Tuhan, dan makna kehidupan itu sendiri.
Penyair yang mengintegrasikan imajisme dalam karya mereka memberikan kepada pembaca kesempatan untuk melihat dunia ini dari perspektif yang lebih dalam, di mana alam semesta bukan hanya berisi benda-benda mati, tetapi juga tanda-tanda Tuhan yang bisa dipahami melalui pengalaman estetik dan spiritual. Dalam hal ini, puisi menjadi medium yang tidak hanya menggambarkan dunia, tetapi juga membawa pembaca untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detil kehidupan, mengingatkan kita bahwa setiap peristiwa di dunia ini sarat dengan makna spiritual yang bisa diungkapkan melalui bahasa yang sederhana namun dalam.
Dengan demikian, imajisme transendental bukan hanya sekadar gaya sastra, tetapi juga sarana untuk meresapi hidup dan menemukan kedamaian melalui hubungan kita dengan Tuhan dan alam. Melalui puisi, kita dapat membaca tanda-tanda kebesaran-Nya yang tersembunyi di dalam keseharian kita. Imajisme transendental membuka mata kita untuk melihat lebih dalam, untuk memahami lebih jauh, dan untuk menyentuh dimensi-dimensi spiritual yang seringkali terabaikan dalam kehidupan yang sibuk dan materialistis.***
—-
Daftar Pustaka
Al-Qur’an, QS. Fussilat: 53.
Damono, Sapardi Djoko. 1999. Sihir Rendra: Permainan Makna. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Pound, Ezra. 1918. A Retrospect. New York: New Directions.
Mohamad, Goenawan. 1981. Seks, Sastra, Kita. Jakarta: Sinar Harapan.
—-
*Penulis adalah seorang penyair, dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto.