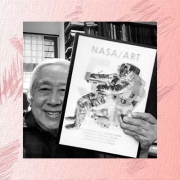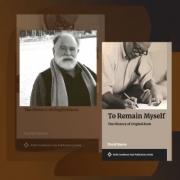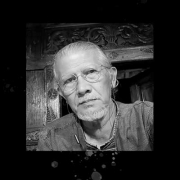Dialektika Genosida dan Ekosida dalam Kebiadaban Manusia
Oleh: Gus Nas Jogja*
Preludium: Ketika Langit Malu Menatap Bumi
Di hadapan mimbar sejarah yang retak, kita berdiri memegang dua belah pisau yang sama tajamnya: Genosida dan Ekosida. Satunya menyayat nadi kemanusiaan (humanity), yang lainnya memutus napas alam semesta (ecosystem).
Pertanyaan “mana yang lebih biadab?” sejatinya adalah sebuah upaya untuk mengukur kedalaman neraka di dalam jiwa manusia.
Secara filosofis, keduanya bukan sekadar kejahatan; keduanya adalah Ontologi Pelenyapan. Jika Genosida adalah upaya menghapus “Wajah” sesama manusia dari kanvas eksistensi, maka Ekosida adalah upaya merobek “Rahim” yang memungkinkan wajah-wajah itu ada.
Di era disrupsi hari ini, perdebatan ini bukan lagi sekadar retorika akademik, melainkan ratapan puitis di atas tanah yang sedang sekarat.
Genosida: Pembantaian Wajah-Wajah Tuhan
Genosida adalah puncak dari hubris (kesombongan) manusia. Secara spiritual, membunuh satu nyawa dengan sengaja karena identitasnya adalah upaya “membunuh Tuhan” dalam diri manusia tersebut. Emmanuel Levinas, filosof etika, menyatakan bahwa etika dimulai saat kita menatap “Wajah” orang lain. Genosida adalah penolakan total terhadap wajah itu.
Sejarah mencatat luka mendalam dari Holocaust hingga Rwanda, dan kini bayang-bayang genosida modern yang dibungkus dengan istilah “pembersihan populasi” di berbagai belahan dunia demi akses sumber daya.
Secara politis, genosida adalah instrumen Power Politics yang paling primitif. Ia menggunakan ketakutan sebagai bahan bakar untuk melenyapkan subjek politik agar objek (tanah dan harta) dapat dikuasai tanpa perlawanan.
Genosida terasa lebih biadab karena ia memiliki Kecepatan Luka. Ia adalah jeritan yang seketika, darah yang mengalir panas, dan kursi makan yang tiba-tiba kosong di sebuah rumah. Ia adalah pengkhianatan terhadap kontrak persaudaraan kosmis.
Ekosida: Pembunuhan Terhadap Ibu dari Segala Napas
Jika genosida adalah pembunuhan terhadap anak, maka ekosida adalah pembunuhan terhadap ibu. Ekosida—penghancuran ekosistem secara sistematis—adalah bentuk kebiadaban yang bekerja dalam Kesunyian yang Panjang.
Pengerukan nikel, minyak, dan emas di Aceh, di Papua, di Morewali yang mengabaikan kedaulatan ekologis adalah bentuk ekosida nyata.
Hilangnya keanekaragaman hayati bukan hanya soal hilangnya pohon, tapi hilangnya kode genetik kehidupan. Berdasarkan data lingkungan 2025, laju kepunahan spesies saat ini 1.000 kali lebih cepat dari laju alami akibat corporate greed.
Secara filosofis, ekosida adalah Bunuh Diri Kolektif. Manusia yang melakukan ekosida adalah anomali biologis yang menghancurkan rumahnya sendiri demi sekerat emas. Soren Kierkegaard mungkin akan melihat ini sebagai “Keputusasaan yang Mematikan”. Ekosida terasa lebih biadab karena sifatnya yang irreversible (tak terpulihkan). Nyawa manusia yang hilang dalam genosida meninggalkan sejarah; namun alam yang hilang dalam ekosida meninggalkan ketiadaan. Tanpa alam, tidak ada panggung bagi sejarah.
Dialektika Kebiadaban: Mana yang Lebih Kelam?
Mencoba membandingkan keduanya adalah sebuah paradoks. Namun, jika kita menyelam lebih dalam ke dalam nalar Tekno-Sufisme, kita akan menemukan bahwa keduanya adalah satu paket Monster dan raksasa kegelapan.
Genosida bersifat Antroposentris: Ia menyerang eksistensi manusia. Ia adalah kejahatan moral yang akut.
Ekosida bersifat Kosmosentris: Ia menyerang fondasi kehidupan itu sendiri. Ia adalah kejahatan ontologis yang kronis.
Secara politis, ekosida sering kali menjadi pendahulu bagi genosida. Di Aceh, di Papua, di Morewali, penghancuran hutan dan sungai (ekosida) secara perlahan menciptakan kemiskinan dan kelaparan yang ujung-ujungnya menyebabkan hilangnya suatu generasi (genosida terselubung). Naomi Klein dalam The Shock Doctrine membuktikan bahwa kehancuran alam seringkali diikuti oleh penghancuran martabat manusia demi modal.
Puisi Bencana:
Nyanyian Tanah dan Darah
Genosida adalah air mata yang jatuh ke tanah
Ekosida adalah tanah yang kehilangan kemampuan untuk menampung air mata
Genosida adalah mematikan lampu di dalam kamar
Ekosida adalah menghancurkan matahari agar lampu tak lagi punya daya
Mana yang lebih biadab?
Kebiadaban sejati terletak pada Ketidakpedulian
Ketika kita melihat hutan Papua, Morewali, dan Aceh digunduli demi nikel, timah, emas dan kita diam, kita sedang melakukan ekosida. Ketika kita melihat rakyat ditindas atas nama pembangunan dan kita berpaling, kita sedang membiarkan genosida karakter terjadi.
Solusi Spiritual: Meruwat Kehidupan
Dalam timbangan Tuhan, tidak ada skala untuk mengukur kebiadaban mana yang lebih berat, karena keduanya adalah pengkhianatan terhadap Amanah. Indonesia harus bangkit dengan sebuah filosofi baru: Ekologi Kemanusiaan! Sebuah kesadaran bahwa kita tidak bisa menyelamatkan manusia tanpa menyelamatkan alam, dan kita tidak bisa memuliakan alam jika kita masih saling membantai antar sesama.
Genosida dan Ekosida adalah dua wajah dari satu koin bernama Keserakahan. Melawan keduanya adalah Ibadah Terbesar manusia modern. Kita harus menjadi Khalifah yang tidak hanya menjaga “Wajah” sesama, tapi juga menjaga “Napas” semesta.
Selamat tinggal zaman kengerian, selamat datang era pemulihan.
Labirin Kausa: Ketika Darah dan Getah Menjadi Satu Tinta
Melanjutkan penelusuran pada relung terdalam kebiadaban ini, kita harus menyadari bahwa Genosida dan Ekosida bukanlah dua garis paralel yang tak pernah bertemu. Dalam realitas politik global, keduanya adalah Spiral Kematian yang saling mengunci.
Secara filosofis, Genosida sering kali merupakan “puncak gunung es” dari sebuah proses Ekosida yang telah berlangsung lama. Ketika sebuah korporasi menghancurkan sungai di pedalaman Aceh, pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi dan Maluku serta Papua, mereka tidak hanya membunuh ikan; mereka sedang membunuh memori kolektif, cara hidup, dan kedaulatan pangan masyarakatnya. Inilah yang disebut oleh Rob Nixon sebagai “Slow Violence” atau Kekerasan Pelan-pelan. Ekosida adalah genosida yang dicicil melalui perusakan paru-paru dunia, hingga suatu kaum mati bukan karena peluru, melainkan karena ketiadaan udara dan air bersih.
Perbandingan Ontologis: Kematian Subjek vs Kematian Panggung
Mari kita pertajam timbangan ini melalui diksi yang lebih esensial:
1. Genosida adalah Kematian Aktor: Ia adalah tragedi di mana para pemain di atas panggung kehidupan dipaksa turun secara brutal. Ia adalah hilangnya suara dalam sebuah orkestra. Kebiadabannya terletak pada peniadaan eksistensi subjek.
2. Ekosida adalah Kehancuran Panggung: Ia tidak membunuh aktor secara langsung, melainkan meruntuhkan lantai panggung, membakar tirai, dan meracuni udara di dalam gedung teater. Kebiadabannya terletak pada peniadaan panggung keberadaan.
Jika kita menggunakan kacamata Martin Heidegger, Ekosida adalah Dasein (keberadaan di dunia) yang kehilangan Welt (dunia). Manusia bisa bertahan hidup dari genosida dengan cara bersembunyi atau melawan, namun manusia tidak bisa bersembunyi dari ekosida. Tidak ada tempat persembunyian ketika matahari menjadi musuh dan air menjadi racun. Dalam konteks ini, Ekosida memiliki dimensi Kebiadaban Kosmis karena ia menghapus kemungkinan bagi generasi mendatang untuk lahir.
Data Proyektif: Genosida Struktural Berwajah Ekosida
Data intelijen ekonomi menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah kaya mineral seperti Aceh Tengah, Bangka Belitung, Morewali, juga Papua, “konspirasi” relokasi paksa adalah bentuk hibrida dari keduanya.
Pertama, Ekosida sebagai Instrumen: Penggundulan hutan menciptakan banjir bandang yang menghancurkan pemukiman.
Kedua, Genosida sebagai Hasil: Rakyat yang kehilangan rumah, tanah, dan harapan hidup, perlahan-lahan mengalami kepunahan identitas kultural dan biologis.
Secara politis, Ekosida sering kali “dipilih” oleh para tiran modern dan okigarki busuk karena ia lebih mudah disamarkan sebagai “bencana alam” atau “efek samping pembangunan”. Genosida fisik terlalu berisiko di bawah sorotan kamera internasional, namun membiarkan rakyat mati perlahan karena ekosistem yang hancur sering kali luput dari meja mahkamah internasional. Inilah Kebiadaban yang Paling Pengecut.
Ratapan Pohon Terakhir dan Manusia Terakhir
“Jika Genosida adalah sebuah puisi tentang sebuah rumah yang dibakar habis, maka Ekosida adalah puisi tentang bumi yang menolak untuk menumbuhkan rumput di atas bekas rumah itu.”
Secara puitis, Genosida adalah darah yang mengering di atas batu. Ia tragis, namun batu itu tetap ada sebagai saksi. Sedangkan Ekosida adalah batu yang hancur menjadi debu, saksi yang ikut mati bersama korbannya. Ekosida adalah Ketiadaan yang Mutlak. Ia adalah kebiadaban yang tidak menyisakan ruang bahkan untuk sebuah batu nisan.
Epilog: Menuju Etika “Eco-Humanitas”
Maka, jawaban atas pertanyaan “mana yang lebih biadab?” adalah: Keduanya adalah dua tangan dari raga yang sama bernama “Antroposentrisme Biadab”. Sebuah ideologi yang menganggap manusia (atau kelompok tertentu) adalah penguasa absolut yang berhak memusnahkan apa pun di luar dirinya.
Indonesia seluruhnya, dari Sabang sampai Merauke, harus menjadi pionir dalam menghidupkan kembali Etika Ekologi: sebuah ajaran untuk meruwat raksasa keserakahan agar kita tidak menjadi pelaku genosida terhadap sesama manusia, dan tidak menjadi pelaku ekosida terhadap alam yang merupakan manifestasi dari Nur Ilahi.
Darah manusia adalah suci, getah pohon adalah suci. Menjaga keduanya adalah tugas utama para Khalifah di bumi.
Rahayu, Rahayu, Rahayu.***
Daftar Pustaka dan Rujukan Ilmiah
Levinas, Emmanuel. (1961). Totality and Infinity. (Filsafat tentang wajah orang lain).
Higgins, Polly. (2010). Eradicating Ecocide. (Pelopor hukum ekosida internasional).
Lemkin, Raphael. (1944). Axis Rule in Occupied Europe. (Pencetus istilah Genosida).
Boff, Leonardo. (1995). Cry of the Earth, Cry of the Poor. (Tegangan antara ekologi dan keadilan sosial).
Data Laporan Lingkungan Global 2025. The State of Biodiversity and Human Conflict.
————
*Gus Nas Jogja, budayawan.