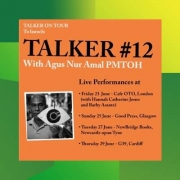Konsep ‘Being’ dalam Ontologi Royce serta Implikasinya terhadap Dunia Digital
Oleh M. Wildan*
Di era teknologi digital yang merevolusi cara manusia hidup, berpikir, dan berinteraksi, pertanyaan tentang being menjadi semakin relevan. Teknologi tidak hanya mengubah lanskap sosial dan ekonomi, tetapi juga menantang cara manusia memahami dirinya dan keberadaannya di dunia. Esai ini akan menelusuri pemikiran filsuf Idealisme Absolut secara kronologis dan tematik, lalu mengaitkannya dengan kondisi dunia digital saat ini.
Josiah Royce (1855-1916) tidak pernah menjadi bintang dalam parade filsafat dunia. Namanya kerap tenggelam di antara kegemilangan Kant, kegelisahan Kierkegaard, pemberontakan Nietzsche atau kompleksitas Heidegger. Namun justru dalam keheningan itulah Royce menawarkan sesuatu yang khas: filsafat sebagai jalan spiritual, bukan hanya intelektual. Sebuah pencarian akan keberadaan yang tidak selesai di ujung logika, melainkan melebur dalam kesetiaan.

Josiah Royce (1855-1916. (Sumber: Istimewa)
Royce hidup di Amerika yang sedang membentuk identitasnya: negara muda dengan semangat individualisme dan optimisme industri. Tapi Royce tidak sibuk memoles ego manusia modern; ia justru memeriksa retakan terdalamnya: keterasingan, kehilangan makna, dan kehampaan spiritual. Ia bertanya: apakah mungkin hidup manusia bermakna tanpa komunitas? Apakah ada jalan bagi jiwa modern untuk tetap setia pada sesuatu yang lebih dari sekadar diri sendiri?
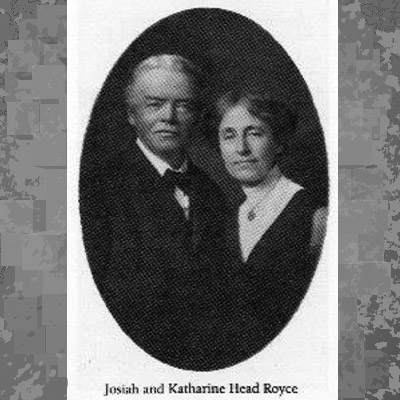
Josiah Royce dan Katharine Head Royce. (Sumber: Istimewa)
Royce memulai pencariannya lewat The Religious Aspect of Philosophy (1885), buku awal yang menyelidik fondasi spiritual dari pengetahuan. Baginya, untuk memahami dunia secara utuh, kita harus mengakui keberadaan “Absolute Knower”, satu pusat kesadaran yang memberi makna pada segala pengalaman.
Gagasan ini berkembang dalam magnum opus-nya, The World and the Individual (dua jilid, 1899–1901), di mana ia memformulasikan idealisme metafisik yang khas. Dunia, menurut Royce, bukan sekadar kumpulan fakta, melainkan jejaring ide yang saling terkait secara koheren. Realitas bukan benda, melainkan sistem makna yang diinterpretasikan oleh “The Absolute”—bukan sebagai entitas otoriter, tapi sebagai Interpreter Agung yang memahami dan menyatukan semua perspektif individu.
“To be is to be interpreted,” tulis Royce. Menjadi berarti dimaknai. Kita tidak eksis sebagai entitas tertutup, melainkan sebagai simpul dalam jejaring spiritual yang lebih besar.
Di awal abad ke-20, Royce menggeser fokus dari metafisika ke etika. Dalam The Philosophy of Loyalty (1908), ia memperkenalkan loyalitas bukan sebagai sikap pasif, melainkan sebagai prinsip moral yang dinamis. Loyalitas adalah dedikasi aktif terhadap suatu tujuan yang lebih tinggi dari ego entah itu kebenaran, keadilan, atau cinta kasih.
Bagi Royce, kehidupan etis adalah kehidupan yang “setia” bukan hanya dalam pengertian personal, tapi spiritual. Seorang manusia menjadi utuh ketika ia mengabdikan dirinya kepada sesuatu yang tak bisa ia miliki sepenuhnya. Sejenis pengorbanan yang justru memunculkan makna.
Dan dalam kerangka itu, loyalitas menjadi bukan sekadar kebajikan, tapi jalan menuju eksistensi yang otentik.
Pada 1913, Royce menerbitkan The Problem of Christianity, sebuah buku yang tidak terlalu bicara soal doktrin agama, melainkan tentang struktur spiritual kehidupan bersama. Di sini ia memperkenalkan konsep Beloved Community, komunitas ideal di mana manusia hidup dalam pengampunan, cinta, dan kesetiaan timbal balik.
Komunitas ini bukan lembaga formal, melainkan struktur batiniah, ruang spiritual tempat jiwa-jiwa yang retak menemukan tempat untuk tumbuh dan disembuhkan. Royce percaya bahwa keselamatan tidak datang dari penghakiman, tapi dari hubungan yang penuh kasih.
Gagasan ini kelak dihidupkan kembali oleh Martin Luther King Jr., yang menyebut Beloved Community sebagai utopia etis-politik dalam perjuangan hak sipil.
Josiah Royce tidak membangun sistem untuk menaklukkan dunia. Ia menulis untuk menyembuhkan luka eksistensial. Dalam The Spirit of Modern Philosophy (1892), ia menelusuri jejak pemikiran Barat modern, tapi selalu dengan nada kontemplatif: filsafat sebagai cermin jiwa, bukan sekadar permainan logika.
Di tengah dunia yang dipenuhi kecemasan, perpecahan, dan hiruk-pikuk digital, Royce menawarkan sesuatu yang langka: keheningan yang bermakna. Ia memberi kita keberanian untuk bertanya ulang: bukan apa yang kita miliki, tapi pada apa kita setia.
Karena mungkin, pada akhirnya, hidup bukan soal menjadi pemenang dalam persaingan bebas, melainkan menjadi makhluk yang setia pada cinta, pada makna, pada komunitas, dan pada kemanusiaan itu sendiri.
Ontologi Royce
Josiah Royce mengajar di Harvard University, di mana ia menjadi salah satu tokoh penting dalam jajaran filsuf Amerika terkemuka. Ia mulai mengajar di Harvard pada tahun 1882 dan bertahan di sana sampai akhir hayatnya pada 1916. Di kampus itulah Royce menjadi kolega dekat William James dan berdialog intens dengan Charles Sanders Peirce, dua pendiri utama pragmatisme Amerika.
Di Harvard, Royce dikenal bukan hanya karena ceramah-ceramahnya yang dalam dan filosofis, tapi juga karena kemampuannya menjembatani metafisika idealis dengan semangat pragmatisme yang tumbuh di Amerika waktu itu. Meski sering diasosiasikan dengan idealisme Hegelian, Royce juga membuka jalan bagi dialog dengan pragmatisme dan teologi, menjadikan Harvard pada masa itu pusat penting bagi pertemuan gagasan besar tentang makna, etika, dan keberadaan.

Josiah Royce (1855-1916. (Sumber: Istimewa)
Salah satu fokus penting Royce saat memberikan kuliah itu adalah tentang “being” atau keberadaan telah menjadi inti dari filsafat sejak masa pra-Sokrates. Apakah yang dimaksud dengan “ada”? Apakah makna terdalam dari keberadaan, dan bagaimana manusia memahaminya?
Royce menyampaikan serangkaian kuliah yang kemudian dibukukan dalam The World and the Individual (1899) jilid 1 dan 2. Royce memulai penjelajahan metafisikanya dengan kritik terhadap tiga konsep ‘being’ yang dominan dalam tradisi filsafat Barat.
Pertama Realisme, doktrin ‘being as independent existence’ bahwa sesuatu ada secara mandiri, lepas dari kesadaran manusia. Royce menolak gagasan ini sebagai ilusi logis: begitu kita berbicara atau memikirkan sesuatu, ia telah masuk ke dalam kesadaran. Doktrin kedua, ‘being as immediately given’ yakni apa yang langsung hadir dalam pengalaman. Royce menilai pengalaman langsung terlalu mentah dan tidak cukup untuk menghasilkan makna, karena makna baru muncul melalui struktur konseptual. Doktrin ketiga, ‘being as the object of true ideas’ pandangan pragmatis yang melihat keberadaan sebagai sesuatu yang dikonfirmasi oleh ide yang benar atau berguna. Royce menganggap pendekatan ini terlalu fungsional dan kurang menjangkau koherensi logis dalam sistem pengetahuan. Realisme, simpul Royce, tejebak dalam makna eksternal.
Kedua Mistisisme. Mistisisme dimulai di India dengan Upanishad dan Vedanta. Di Yunani, mistisisme tampak dalam dialog Plato tentang jiwa dan gagasan Aristoteles tentang Tuhan yang dihayati dalam batin. Royce mengkritik bahwa mistisisme terjebak dalam aspek makna internal dan meniadakan ide-ide terbatas. Realisme dan mistisisme, simpul Royce, beemuara pada ‘reductio ad absordum’ akan ide terbatas yang riil. Keduanya terjebak dalam self contradictory.
Ketiga Rasionalisme Kritis Immanuel Kant. Basis epistemologi Kant: bagaimana individu mengkritik struktur dasar subyek untuk mengetahui. Royce mengkritik apakah kebenaran hanya valid? Apa yang abadi hanya bentuk? Apa prinsip yang benar yang hanya universal? Apa Tuhan hanya bentukan akal belaka?
Sebagai alternatif, Royce menawarkan konsep keempat yang ada: ‘being as the fulfillment of the internal meaning of an idea’. Rpyce dengan demikian membangun satu semesta yang disebutnya ‘The Fourth Conception of Being’. Konsep ini sepenuhnya berbeda dgn ide terbatas (realisme), kesatuan makna (mistisisme) dan validitas-validitas (rasionalisme kritis).
Dalam konsep keempat Royce segala sesuatu ada jika dan hanya jika ia mewujudkan makna internalnya secara penuh dan koheren dalam kesadaran total.
Realitas, jelas Royce, adalah kehendak konkret yang dijelmakan dalam kehidupan riil dan utuh dimana ide-ide yang terbatas mencari Tuhan.
Maka dalam visi Royce, makna tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem pengetahuan universal yang diketahui oleh ‘the Absolute Knower’ sebuah pikiran Ilahi atau kesadaran semesta. Being, bagi Royce, adalah realisasi dari potensi makna dalam jaringan kebenaran yang konsisten dan abadi.
Maka kebenaran teori makna internal ide dengan solusi problem yang ada bisa dijelaskan pada perspektif bhw ide itu benar bila berkorespondensi dengan pengungkapan menjadi yang ada, yg terminal akhirnya menjadi individu yang utuh;
“What gives true ideas their truth or in other words, to be real is to be the object or a true idea. Therefore what is, or what is real, is as such the complete embodiments, in individual form and in final fulfilment of the inteenal meaning of finite ideas”

William James and Josiah Royce near James’s country home in Chocorua, New Hampshire, in September 1903. (Sumber: https://www.iowasource.com)
***
Sebelum menyusun sistem idealismenya sendiri, Josiah Royce terlebih dahulu bergumul dengan pemikiran Kant. Bagi Royce, Kant adalah tokoh besar yang membuka jalan bagi refleksi modern tentang hubungan antara subjek dan objek, namun filsafat Kant masih menyisakan dualisme yang tak terjembatani. Kritik Royce terhadap Kant setidaknya mencakup empat hal.
Pertama, Royce menolak konsep Kant tentang thing-in-itself (Ding an sich). Kant beranggapan bahwa ada realitas noumenal yang tidak dapat diakses langsung oleh pikiran manusia. Royce menganggap ini sebagai kontradiksi: jika sesuatu benar-benar tidak bisa dimaknai atau dikenali oleh kesadaran, maka ia tidak bisa dikatakan “ada” secara bermakna. Bagi Royce, to be is to be interpretable.
Kedua, Royce mengkritik pembatasan Kant terhadap rasio. Kant hanya membolehkan akal bekerja dalam ranah fenomenal, sementara metafisika dilarang sebagai pengetahuan yang sahih. Royce menolak batasan ini dan percaya bahwa refleksi rasional mampu menjangkau kebenaran absolut, asalkan ditopang oleh logika koherensi.
Ketiga, sistem Kant menurut Royce tidak cukup koheren sebagai suatu totalitas makna. Kant berhenti pada kategori dan struktur pengetahuan, namun gagal membangun jaringan makna yang saling terhubung dalam satu sistem semesta. Royce ingin seluruh ide saling terintegrasi dalam sistem logis yang utuh dan abadi.
Keempat, Royce memandang etika Kant terlalu formal dan kering. Imperatif kategoris, meski menjunjung rasionalitas moral, kurang menyentuh dimensi hidup nyata. Royce menawarkan konsep kesetiaan terhadap komunitas sebagai dasar moralitas yang lebih manusiawi dan terwujud dalam praktik sosial.
Dengan demikian, Royce bergerak melampaui Kant menuju idealisme sistemik di mana seluruh realitas adalah makna yang dimengerti oleh the Absolute Knower. Keberadaan bukan sekadar keberadaan benda, tetapi pemenuhan dari makna internal dalam sistem kesadaran yang menyeluruh.
Perbandingan dengan Heidegger
Melangkah ke abad ke-20, Martin Heidegger menerbitkan karya pentingnya Sein und Zeit (Being and Time, 1927). Ia memulai dengan keluhan klasik bahwa filsafat Barat terlalu lama melupakan pertanyaan tentang being. Heidegger membedakan antara Sein (keberadaan itu sendiri) dan Seiendes (entitas yang ada). Ia menyatakan bahwa untuk memahami being, kita harus memulainya dari Dasein, manusia sebagai entitas yang memahami dan mempermasalahkan keberadaannya sendiri.
Heidegger tidak menganggap being sebagai substansi tetap, melainkan sebagai sesuatu yang terungkap dalam keterlibatan manusia dengan dunianya. Ia menyebut proses ini sebagai ‘aletheia’, penyingkapan. Being adalah horizon makna yang terbuka, selalu dalam proses menjadi, tidak pernah final. Dasein berada dalam dunia melalui keterlemparan (Geworfenheit), keberlakuan (Befindlichkeit), dan pengertian (Verstehen). Being itu sendiri bersifat temporal: manusia memahami keberadaannya dalam rentang waktu, masa lalu (fakta-fakta dirinya), masa kini (tindakan), dan masa depan (kemungkinan-kemungkinan eksistensial).
Heidegger oleh karenanya hadir di panggung filsafat Eropa dengan niat membongkar warisan metafisika Barat. Ia menyatakan bahwa selama ini filsafat terlalu fokus pada entitas, bukan pada being itu sendiri. Dalam Being and Time, Heidegger memulai analisisnya dari Dasein manusia sebagai entitas yang menyadari dan mempertanyakan keberadaannya.
Maka sekali lagi menurut Heidegger, being bukan sesuatu yang statis atau substansial, tetapi proses pengungkapan (aletheia). Being selalu terbuka, selalu sedang berlangsung, dan bersifat temporal. Dasein mengalami being melalui waktu: masa lalu (faktisitas), masa kini (keputusan), dan masa depan (kemungkinan). Being tidak hadir sebagai objek, melainkan sebagai horizon makna dalam kehidupan eksistensial manusia.
Inilah titik bedanya. Royce menempatkan being dalam sistem makna dan kesadaran absolut. Sebaliknya, Heidegger, filsuf eksistensial Jerman, berusaha membongkar fondasi metafisika tradisional dan menawarkan pendekatan yang lebih fenomenologis dan eksistensial.
Krisis Ontologi di Era Digital
Dalam esainya ‘The Question Concerning Technology’, Heidegger mengkritik pandangan teknologi sebagai sekadar alat. Ia memperkenalkan konsep Gestell atau enframing, yakni cara teknologi modern membingkai dunia sebagai sumber daya yang siap dieksploitasi. Dalam pandangan ini, segala sesuatu: alam, tubuh, bahkan manusia diubah menjadi data, objek kalkulasi, dan bahan produksi. Teknologi menyelubungi being; ia menjauhkan manusia dari cara-cara pengungkapan yang lebih otentik.
Sebaliknya, jika kita menafsirkan pemikiran Royce dalam konteks digital, teknologi dapat dilihat sebagai ekstensi kesadaran kolektif. Internet, big data, dan kecerdasan buatan menjadi medan baru tempat makna disusun, dikomunikasikan, dan dijalin. Dalam pandangan idealisme Royce, keberadaan dalam dunia digital bisa dipahami sebagai bagian dari realisasi ide universal jika dan hanya jika ia diarahkan oleh kesetiaan terhadap nilai-nilai etis dan struktur makna koheren.
Namun, Royce juga akan mengingatkan bahwa sistem digital ini harus diresapi oleh niat baik dan pengabdian terhadap komunitas moral. Tanpa itu, teknologi bisa menjadi sarana fragmentasi makna dan dominasi algoritmik.
Menuju Sintesis Kritis
Dari uraian di atas, tampak bahwa Royce menekankan sistem dan logika koherensi, sementara Heidegger lebih tertarik pada proses eksistensial dan keterbukaan terhadap pengungkapan. Royce ingin membangun struktur makna universal; Heidegger justru menggugat struktur dan menekankan keterbatasan manusia dalam memahami being secara total.
Namun, dalam menghadapi dunia digital, keduanya saling melengkapi. Kita membutuhkan kesetiaan terhadap nilai-nilai universal dan komunitas sebagaimana ditegaskan Royce, sekaligus kewaspadaan terhadap reduksi eksistensial yang diperingatkan Heidegger. Dengan demikian, manusia digital tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi penafsir being di tengah dunia yang terus berubah.
Pertanyaan tentang ‘being’ jelas tidak dapat diselesaikan sekali waktu. Ia harus terus diperbarui seiring perkembangan zaman. Dalam dunia digital yang serba cepat, manusia sering kehilangan momen untuk merenungkan keberadaannya. Di sinilah filsafat menjadi penting.
Melalui Royce dan Heidegger, kita diajak untuk tidak hanya bertanya “apa yang ada?” tetapi juga “bagaimana keberadaan itu dimaknai dan dijalani?” Teknologi modern dapat menjadi medan realisasi makna, atau sebaliknya, menjadi tirai yang menutupi misteri being. Tugas kita adalah membuka kembali horizon itu dengan kesetiaan, dengan keberanian, dan dengan berpikir.
——————–
Referensi Utama:
Josiah Royce, The Religious Aspect of Philosophy (1885)
Josiah Royce, The World and the Individual, Vol. I & II (1899–1901)
Josiah Royce, The Philosophy of Loyalty (1908)
Josiah Royce, The Problem of Christianity (1913)
Josiah Royce, The Spirit of Modern Philosophy (1892)
John E. Smith (ed.), Royce’s Basic Writings (Harper, 1961)
Frank M. Oppenheim, Reverence for the Relations of Life: Reimagining Pragmatism via Josiah Royce’s Interactions with Peirce, James, and Dewey (2004).
Heidegger, M. (1927). Sein und Zeit (Being and Time).
Heidegger, M. (1954). Die Frage nach der Technik (The Question Concerning Technology).
Dreyfus, H. (1991). Being in the World: A Commentary on Heidegger’s Being and Time.
Feenberg, A. (1999). Questioning Technology.
*Alumni Fakultas Filsafat UGM