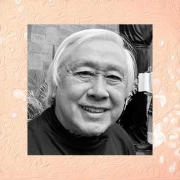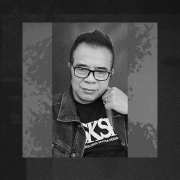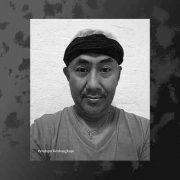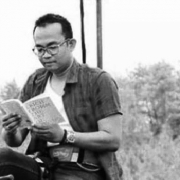Kemerdekaan dan Kedaulatan: Bagaimana Pengalaman Indonesia?
Oleh Joss Wibisono
Kemerdekaan yang diproklamasikan, tidak serta merta berarti kedaulatan. Dalam sejarah, kemerdekaan memang urusan negara yang memproklamasikannya, tetapi tidaklah begitu halnya dengan kedaulatan. Kedaulatan ternyata lebih menyangkut pengakuan negara lain, terutama si bekas penjajah: sedikit banyak si bekas penjajah merestui kemerdekaan wilayah jajahan yang memproklamasikan kemerdekaannya. Masalahnya, pengakuan itu kebanyakan dilakukan oleh negara-negara yang pernah mengalami penjajahan. Walaupun mungkin lumayan banyak, negara-negara baru ini biasanya belum begitu berpengaruh. Pengaruh tetap dimiliki oleh negara-negara lama, tidak sedikit di antaranya pelaku penjajahan. Dan jangan heran kalau negara-negara berpengaruh ini sering memihak pelaku penjajahan. Di sinilah kedaulatan menjadi penting karena selain sangat diinginkan oleh negara yang baru merdeka, kedaulatan juga merupakan tarik-ulur antara negara-negara berpengaruh dan negara-negara yang baru merdeka.
Soal kedaulatan, belakangan kembali menjadi pembicaraan ketika Israel menghajar Gaza, semula sebagai pembalasan terhadap aksi penculikan dan pembunuhan yang dilakukan Hamas (berkuasa di Gaza) terhadap para kolonis Israel. Tatkala Israel terus membabi buta dan banyak negara menilai Israel telah melakukan genosida di Gaza, maka beberapa negara Eropa (bekas penjajah) dan Australia serta Kanada melakukan pembalasan dengan mengakui kedaulatan Palestina. Tentu saja Amerika tetap memihak Israel, dan menolak mengakui Palestina. Alhasil, walaupun bertambahnya pengakuan itu penting, tanpa pengakuan Amerika, Palestina tetap belum dianggap mencapai kedaulatan penuh.
Sebenarnya, 80 tahun silam Amerika pernah berkelakuan lain. Waktu itu Amerika memihak Indonesia yang berupaya memperoleh pengakuan internasional, termasuk pengakuan Belanda sebagai bekas penjajahnya. Berkat tekanan Amerika, Belanda akhirnya mengakui juga kemerdekaan Indonesia, walau Belanda menyebutnya sebagai “soevereiniteitsoverdracht” (penyerahan kedaulatan). Peristiwa bersejarah pada akhir 1949 yang berlangsung serempak di Amsterdam maupun di Jakarta itu sekarang sudah tidak begitu kita kenal lagi. Tapi sebelum membahasnya lebih lanjut, terlebih dahulu perlu dibahas perbedaan istilah yang ada antara Belanda dan Indonesia. Paling sedikit ada tiga perbedaan istilah antara Indonesia dengan Belanda yang bisa dikemukakan.
Perbedaan pertama, adalah peristiwa bersejarah 27 Desember 1949. Seperti sudah tertera di atas orang Belanda menyebutnya sebagai soevereiniteitsoverdracht yang berarti penyerahan kedaulatan. Dalam dokumen yang ditandatangani oleh Ratu Juliana dan satu persatu anggota kabinet Belanda di bawah Perdana Menteri Willem Drees, juga tertera terjemahan bahasa Indonesia: penjerahan kedaulatan (ejaan zaman itu). Pihak Indonesia dipimpin oleh Wakil Presiden Mohamad Hatta dan beberapa tokoh lain yang memimpin RIS, Republik Indonesia Serikat, seperti Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamid.
Di balik nama resmi dokumen: “Penjerahan Kedaulatan” yang jelas-jelas hanya merupakan terjemahan bahasa Belanda, di Indonesia beredar satu istilah lain: pengakuan kedaulatan. Tak pelak lagi, kita menganggap waktu itu berlangsung pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia yang sudah diproklamasikan empat tahun sebelumnya, pada 17 Agustus 1945. Hasil terpenting pengakuan kedaulatan ini adalah RIS, Republik Indonesia Serikat yang ternyata dibubarkan pada Agustus 1950, belum lagi setahun setelah penandatanganannya. Kalau hasil terpenting perundingan terakhir antara Indonesia dan Belanda ini saja sudah dihapus, lalu apa yang tersisa? Tidaklah mengherankan kalau kita tetap menjunjung tinggi proklamasi 17 Agustus 1945. Baru pada 2023, yaitu 74 tahun kemudian, Belanda mengakui 17 Agustus, walaupun apa yang disebut pengakuan yang “volledig en zonder voorbehoud” (sepenuhnya dan tanpa syarat) itu masih ditambah bahwa pengakuan itu hanya de facto, bukan pengakuan de jure. Artinya kesepakatan lain yang waktu itu dicapai antara Indonesia dengan Belanda tidak ikut berubah.
Sampai di sini jelas bahwa bagi satu istilah Belanda, ternyata di Indonesia paling sedikit ada dua istilah yang setara. Ini berbeda dengan istilah “agresi militer” yang kita gunakan untuk menyebut serangan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Orang Belanda, paling sedikit sampai awal 2022 ketika terbit laporan penelitian Belanda terhadap perang kemerdekaan Indonesia, selalu menyebutnya sebagai “politionele acties” yang berarti aksi polisi. Jelas istilah ini bertujuan untuk menyempitkan makna, bukan tentara yang didatangkan (karena dengan demikian berarti perang antara dua negara) melainkan polisi untuk membereskan masalah dalam negeri. Sebaliknya dengan menyebut agresi militer Indonesia jelas menunjuk apa adanya, bahwa tentara, dan bukan polisi yang ingin (kembali) menguasai republik muda yang belum lama diproklamasikan. Harus diakui bahkan sebelum hasil penelitian diumumkan, di Belanda juga beredar istilah lain, misalnya koloniale oorlog atau perang kolonial. Mulai 2022 pemerintah Belanda resmi menggunakan istilah Onafhankelijkheidsoorlog yang berarti perang kemerdekaan. Dengan demikian istilah politionele acties telah dikubur.
Di Belanda politik yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch terhadap petani Jawa antara 1830 sampai 1870 disebut Cultuurstelsel (sistem budi daya). Ini istilah ketiga. Sebaliknya, orang Indonesia menyebutnya sebagai Tanam Paksa. Para petani Jawa dan Sunda selama periode itu dipaksa menanam tanaman-tanaman tertentu (misalnya kopi atau nila) dan harus menjualnya kepada NHM, Nederlandse Handelsmaatschappij, pada tingkat harga yang sudah mereka tentukan. NHM dapat dikatakan merupakan penerus VOC selama abad ke 19. Di Belanda hanya pakar sosiologi Jan Breman yang menggunakan istilah Tanam Paksa, dalam terjemahan bahasa Belanda gedwongen teelt.
Bagaimana harus memaknai perbedaan istilah antara Indonesia maupun Belanda ini? Istilah-istilah Belanda: cultuurstelsel, politionele acties dan soevereiniteitsoverdracht pertama-tama merupakan ciptaan para penentu kebijakan. Sebaliknya istilah Indonesia justru lebih mencerminkan sisi orang yang menjadi sasaran kebijakan itu, dan terutama bagaimana mereka mengalami kebijakan-kebijakan kolonial tertentu. Dengan begitu istilah-istilah Belanda berlawanan dengan istilah-istilah Indonesia. Misalnya istilah “cultuurstelsel” lebih menekankan aspek stelsel yang berarti sistem, sementara istilah Indonesia “Tanam Paksa” menekankan bagaimana orang-orang Indonesia mengalami politik pertanian ini. Perbedaan istilah ini muncul karena orang Indonesia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakannya.
Harus diakui bahwa pengakuan kedaulatan tidak begitu memperoleh perhatian dalam buku-buku pelajaran sejarah Indonesia. Dalam delapan buku pelajaran sejarah SMA, semua secara rinci menguraikan latar belakang bersejarah proklamasi 17 Agustus 1945. Hanya satu buku yang membahas soal kedaulatan, dengan menyebutnya sebagai “serah terima kedaulatan”, terjemahan istilah bahasa Belanda “sovereiniteitsoverdracht”. Penjelasannya tidak sampai dua halaman, dan ternyata mengandung beberapa kesalahan. Misalnya disebut bahwa dokumen kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Wilhelmina. Jelas para penulis tidak tahu-menahu bahwa setahun sebelumnya, pada 1948, Ratu Wilhelmina sudah berabdikasi alias menyerahkan takhta kerajaan Belanda kepada putrinya Juliana. Karena tidak mencantumkan pergantian ratu, buku itu juga tidak mencatat pelbagai dugaan kenapa Wilhelmina turun takhta: dia kesulitan mengakui telah kehilangan Hindia Belanda.
Buku pelajaran sejarah ini menyebut satu per satu nama 13 anggota delegasi di bawah pimpinan Wakil Presiden Mohamad Hatta, termasuk di dalamnya Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo Subianto yang sebelum terpilih minimal harus ikut pemilihan presiden sampai sebanyak empat kali. Untuk pihak Belanda, tidak hanya Perdana Menteri Willem Drees yang membubuhkan tanda tangan, melainkan juga segenap anggota kabinet Belanda. Sebagai orang Indonesia kita jelas sangat ingin tahu siapa saja anggota delegasi Indonesia yang berbuat serupa. Atau mungkin hanya akan terlihat tanda tangan Hatta? Sayangnya halaman yang memuat tanda tangan orang-orang Indonesia tidak terlihat pada pameran dokumen bertajuk Het Geheugenpaleis (istana ingatan) digelar oleh Nationaal Archief, Den Haag pada bulan Juni 2014. Ketika saya minta tolong kepada seorang petugas untuk membuka halaman yang memuat nama-nama Indonesia, dengan ketus dia berkata bahwa saya harus mengajukan permohonan pembalikan halaman dengan menulis surel. Benar-benar langkah rumit bagi satu hal yang sederhana dan mudah yaitu membalik halaman. Karena tidak berencana datang kembali ke Den Haag, hanya untuk melihat tanda tangan delegasi Indonesia pada dokumen pengakuan kedaulatan, maka tidak saya kirim surel.
Uraian yang menyeluruh dan tanpa satu pun kesalahan tertera pada Sejarah Nasional Indonesia, jilid enam, karangan Sartono Kartodirdjo cs. Inilah karya standar sejarah Indonesia, dapat disejajarkan dengan karya standar Loe de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan den tijdens de Tweede Wereldoorlog (kerajaan Belanda selama Perang Dunia II). Dalam buku itu istilah soevereiniteitsoverdracht diterjemahkan menjadi pengakuan kedaulatan yang dalam bahasa Belanda akan berarti soevereiniteitserkenning. Menurut para penulis karena berkat proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai negara merdeka Indonesia sudah berdaulat. Baru pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.
Harus diakui bahwa sebagai negara yang memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia bukanlah negara pertama yang memilih sendiri tanggal kelahirannya, dalam arti tidak didikte kalangan lain. Tapi negara mana yang pertama kali di dunia menyatakan kemerdekaannya? Di sini seorang peminat sejarah berkesempatan untuk membandingkan Plakkaat van Verlatinghe, alias plakat pengabaian yaitu pernyataan kemerdekaan Belanda dari Spanyol pada 1581, dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesudah itu kita juga akan membandingkan Vrede van Münster (perdamaian Münster di Jerman) pada 1648 dengan Pengakuan Kedaulatan Indonesia pada 1949.
Plakaat van Verlatinghe ditandatangani di Den Haag pada tanggal 26 Juli 1581. Begitu pada awal 2018 plakat ini terpilih sebagai “Pronkstuk van Nederland” alias peninggalan utama sejarah Belanda, segera saya berpendapat bahwa plakat ini dapat disetarakan dengan naskah proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan begitu jelas bahwa orang Belanda sudah terlebih dahulu menuntut kemerdekaannya. Lebih dari itu, Belanda bukan hanya negara pertama yang menuntut kemerdekaannya; Belanda juga lebih dahulu dalam berbentuk republik, jelas bentuk negara yang berani pada saat itu. Mungkinkah para bapak bangsa Indonesia diilhami oleh Plakkaat van Verlatinghe? Selama menjalani pendidikan tinggi di Belanda, pasti mereka menjadi tahu atas pernyataan kemerdekaan Belanda ini.
Perdamaian Münster, sebenarnya merupakan bagian Perdamaian Westfalen, ditandatangani oleh Spanyol dan Belanda. Dengan penandatanganan ini sebagai bekas penguasa Belanda, Spanyol mengakui Republiek van Venigde Provinciën sebagai negara berdaulat. Pada 1949, sejarah berulang di Amsterdam dan Jakarta, tatkala pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia. Akhirnya Belanda mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat, persis seperti Spanyol mengakui Belanda tiga abad sebelumnya.
Harus diakui bahwa lebih banyak perbedaan ketimbang persamaan antara Plakkaat van Verlatinghe dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, juga antara Perdamaian Münster dengan pengakuan kedaulatan pada 1949. Adalah Staten Generaal (MPR Belanda) yang memutuskan untuk tidak lagi mengakui Raja Spanyol Felipe II, dan juru tulis Jan van Asseliers ditugasi untuk membuat plakat berisi keputusan itu. Dalam empat hari dia mencetak naskah itu dalam plakat yang mencapai 20 halaman. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dirundingkan oleh sekelompok orang beranggotakan enam orang Indonesia dan tiga orang Jepang. Tatkala orang-orang Indonesia tidak juga dapat bersepakat mengenai isi proklamasi, ketiga orang Jepang mengundurkan diri. Mereka sudah sangat mengantuk dan tidak berminat campur tangan dalam masalah internal Indonesia. Akhirnya keenam orang Indonesia itu hanya punya waktu selama beberapa jam untuk menyusun naskah proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 mereka mulai berunding pada jam dua dini hari dan pembacaan naskah proklamasi berlangsung pada jam 10 pagi. Tidak adanya waktu merupakan penyebab mengapa naskah proklamasi itu hanya berisi dua kalimat. Perdamaian Münster yang berisi pengakuan Spanyol atas Belanda (sebagai republik) merupakan akhir perang kemerdekaan Belanda yang berlangsung selama 80 tahun, dan perjanjian Münster dicapai 67 tahun setelah dimaklumkannya Plakkaat van Verlatinghe. Antara Proklamasi 17 Agustus dan pengakuan kedaulatan terdapat jarak selama lima tahun.
Dalam bukunya mengenai Plakkaat van Verlatinghe, Anton van Hooff menyejajarkan peninggalan utama sejarah Belanda ini dengan serangkaian dokumen yang sangat penting bagi sejarah dunia: Bill of Rights (dokumen berdirinya parlemen Inggris tahun 1689), Declaration of Independence (pernyataan kemerdekaan Amerika tahun 1776), serta Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara, Prancis 1789). Walaupun isi Proklamasi Indonesia jelas lebih singkat dibandingkan dokumen-dokumen lain, sebenarnya makna sejarahnya sebanding dengan Plakkaat van Verlatighe. Plakat ini juga sempat tidak diakui Spanyol, sebagaimana Belanda sempat tidak mengakui 17 Agustus 1945. Inilah kenyataan sejarah yang tidak terbantahkan lagi.
Patut disayangkan Belanda tidak merayakan hari kelahirannya pada tanggal 26 Juli, berbeda sekali dengan Indonesia yang selalu meriah dan hingar-bingar merayakan setiap tujuh belas Agustus. 27 Desember tidak pernah dirayakan, hanya satu kali saja pada 1949, tatkala Presiden Sukarno tiba kembali di Jakarta dari Yogyakarta. Mungkin akan merupakan gagasan yang baik jika salah satu kunjungan kenegaraan seorang presiden Indonesia ke Belanda berlangsung pada tanggal 27 Desember. Akankah Belanda menerima gagasan ini? Satu-satunya kunjungan kenegaraan seorang presiden Indonesia berlangsung September 1970. Pada 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kunjungan kenegaraan pada saat-saat terakhir, sedangkan Presiden Abdurrahman Wahid serta Presiden Joko Widodo hanya melakukan kunjungan kerja selama sehari. Jelas sudah tiba saatnya bagi seorang presiden Indonesia melakukan kunjungan kenegaraan ke Belanda, dan ingin saya usulkan supaya kunjungan itu berlangsung pada tanggal 27 Desember.
Bisalah dipahami kalau 27 Desember 1949 dianggap penting oleh Belanda, karena pada hari itu sang negeri induk secara definitif dan resmi kehilangan Hindia. Di Belanda banyak orang harus menanggung kehilangan ini, sampai sekarang. Karena itu bisa dimaklumi kalau pengakuan kedaulatan memperoleh perhatian cukup dalam sejarah Belanda. Segenap petualangan Belanda di Nusantara layak memperoleh perhatian dalam sejarah Belanda, termasuk dalam buku sejarah untuk sekolah-sekolah Belanda.
Tetapi Indonesia bukan hanya korban penjajahan. Di Timor Portugis (nama asli wilayah itu) Indonesia menjelma menjadi pelaku kejam penindasan terhadap bangsa lain. Di Timor Leste, Indonesia merupakan negara pertama anggota (bahkan tuan rumah) KTT Asia-Afrika, yaitu organisasi negara-negara yang merdeka dari penjajahan, yang berubah menjadi penjajah untuk kemudian dipaksa dunia internasional melakukan dekolonisasi. Betapa sebuah langkah yang begitu memalukan, diperbuat oleh satu negara yang sebelumnya berjuang melawan kolonialisme. Karena menduduki Timor Leste sambil melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia keji, jelas Indonesia telah berkhianat terhadap perjuangan kemerdekaannya sendiri. Walau demikian kemerdekaan Timor Leste tidaklah terjadi pada 20 Mei 2002, seperti dinyatakan resmi oleh PBB dan diakui oleh Indonesia. Timor Leste berpegang teguh pada 20 November 1975 sebagai hari kemerdekaannya dari penjajahan Portugal, jadi sebelum Indonesia masuk pada Desember 1975 untuk berkuasa selama 24 tahun. Bagi Timor Leste 20 Mei merupakan hari pemulihan kemerdekaan. Dengan demikian Indonesia memasukkan diri dalam kelompok negara bekas penjajah yang kesulitan mengakui kenyataan sejarah.
Dokumen apa yang merupakan saksi bagi pengalaman paradoksal Indonesia di Timor Leste? Bisa jadi surat Presiden B.J. Habibie yang dikirim kepada DPR yang mengizinkan dilangsungkannya jajak pendapat, eufemisme Jakarta bagi referendum. Atau mungkin laporan PBB tentang hasil referendum itu. Semoga dokumen-dokumen ini dapat dibaca oleh masyarakat Indonesia, supaya mereka dapat memahami sejarah mereka sendiri.
Bulak Sumur, sepekan setelah 80 tahun Proklamasi
***
*Joss Wibisono, Sastrawan dan sejarawan.