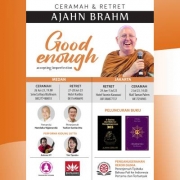Gita Si Ari-Ari
Oleh Elizabeth Inandiak
Pengantar redaksi: Elizabeth Inandiak, (62 tahun Juni ini) akan menerbitkan sebuah buku tentang pengalamannya 30 tahun tinggal di Indonesia. Elizabeth berasal dari Perancis. Ia tinggal di Yogja. Ia dikenal sebagai sastrawan, penerjemah, wartawati yang mempelajari kebudayaan Jawa dan menghasilkan banyak buku. Pada tahun 2002, ia menerbitkan buku berjudul Les Chants de lile a dormer debout le Livre de Centhini. Buku tentang Serat Cethini ini kemudian meraih penghargaan terbaik pada Prix de La Francophonie 2003. Buku ini selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Centhini: Kekasih yang Tersembunyi.
Elizabeth juga pernah menulis buku mengenai dongeng tentang sebuah pohon beringin keramat berjudul: Lahirnya Kembali Beringin Putih. Elizabeth sering bertemu juru kunci Gunung Merapi – Mbah Maridjan – saat Mbah Maridjan masih hidup. Dialog-dialog dan perbincangannya dengan Mbah Maridjan kemudian dia bukukan dengan judul: Babad Ngalor-Ngidul. Minat Elizabeth terhadap dunia arkeologi nusantara makin meluas. Terakhir ia tertarik menekuni situs Muoro Jambi. Muoro Jambi—di zaman Sriwijaya diduga adalah pusat pendidikan Buddha Mahayana yang besar. Di situlah Atisha, cendikia dari Universitas Nalanda India pernah tinggal dan belajar. Elizabeth menulis buku tentang Muoro Jambi berjudul: Mimpi-Mimpi Pulau Emas.
Pertama kali Elizabeth datang ke Indonesia adalah awal 1988. Saat itu sebagai wartawati majalah bulanan Actuel Paris ia ditugaskan mereportase pesantren dan komunitas-komunitas penghayat kebatinan di Yogyakarta.Umurnya 28 tahun saat itu tapi pengalaman travelingnya sudah malang melintang. Pada tahun 1988, Majalah Kebudayaan Dewan Kesenian Yogya: Citra Yogya, edisi Mei-Juni 1988 menurunkan wawancara penyair (alm) Linus Suryadi Agustinus dengan Elizabeth. Wawancara yang oleh Linus diberi judul: Sosok pembangkang Generasi “Punk” Perancis itu menarik. Karena Elizabeth menjelaskan bagaimana pengalamannya menjadi wartawati sejak umur 18 tahun di tahun 1977 – sejak di harian Liberations.
Sebagai wartawati ia berkelana dari New York sampai Rusia. Ia meliput kondisi apartheid di Afrika sampai kehidupan-kehidupan bawah tanah kaum muda di Moskow dan Leningrad. Ia juga menulis novel, skenario film. Sebagai generasi yang tumbuh dalam kultur punk rock ,ia mengikuti bagaimana pemberontakan-pemberontakan sub kultur punk rock di Eropa dan awal munculnya hip hop di Amerika. Dari wawancara itu ia juga mengemukakan pandangannya tentang bahasa, kebudayaan dan imigran. Dalam wawancara itu – ia mengatakan bahwa dirinya selalu berada dalam perjalanan menuju satu tempat dan kemudian meninggalkan tempat itu. Tapi baru saat di Yogya ia merasa ingin menetap. Ia merasa ada yang membuatnya krasan.
Artikel yang dikirim ke situs BWCF adalah bagian dari buku otobiografinya tentang pengalaman menetap di Indonesia. Artikel ini berkisah perasaan batinnya setelah ia melahirkan di Yogya. “Tulisan ini saya tulis dalam Bahasa Perancis beberapa minggu setelah saya melahirkan tahun 1991,” katanya. Berikut tulisan Elizabeth:
***
Rumah sakit Bestheda – Yogyakarta- Indonesia- 9 Juni 1991
Pagar besi itu menjulang tinggi mengurungku seperti kandang di kebun binatang. Hujan hangat berdebu turun beberapa jam setelah lahirnya jiwa leluasa ini. Tetesan air deras menyembur ke tanah dan melepaskan aroma memabukkan dari pohon kamboja yang terperangkap dalam getah selama kemarau panjang. Gas buangan dari lalu lalang motor terurai di tengah hujan dan menempel di kulitku seperti perban bekas yang guri. Kurasakan di lengan telanjangku endapan perkotaan berpawai asap cengkeh itu yang membasahi udara siang dan malam.
Aku sedang duduk di teras kamar rumah sakit. Menganggur. Menatap pagar besi yang memisahkanku dari jalan, tidak terjamah, terbentang di hadapan ribuan muka. Mereka lewat, menyentuh jeruji kandangku, mengamatiku. Mata mereka bersinar, penuh kantuk, senyum hamba, pemberontakan kelu, teror mental. Beberapa, yang kuyakini tertidur, tiba-tiba tergugah menatap yang tak kasat mata. Mereka berjejal-jejalan di bawah spons raksasa hangat di langit sambil berusaha secara samar-samar untuk menggali sepotong kecil keberadaan dalam zat yang mengalir dari kerumunan mereka. Kubiarkan diriku diserbu ribuan mata raya itu tanpa tahu bagaimana caranya untuk melawan jumlah besar mereka.
Aku memesan es teh kepada si kaki lima yang memarut es batu di balik pagar besi itu. Ditambah mie soto usus kerbau yang kutelan dengan rasa bahagia, membiarkan keramaian jalan masuk ke perutku sedangkan rahimku telah ditinggalkan oleh si bayi. Aku memikirkan ayahnya yang menjelang subuh pergi mengubur ari-ari yang diserahkan bidan di dalam kantong plastik tadi malam. Ari-ari itu semestinya dikeluarkan dari kantong plastiknya, ditempatkan di gerabah kecil bersama kelopak bunga, kelapa parut, minyak kayu putih, ikan asin, kacang mete, beras merah, garam, kunyit, jarum dan benang. Kemudian gerabah itu dibungkus kain putih dan diletakkan di atas tanah di sebelah kiri pintu rumah kami.
Berpikir hal ini, aku kebanjiran kesayuan tak berhingga yang membuatku khawatir ayahnya lupa menyalakan lampu minyak dan dupa di atas tanah agar si ari-ari tak menangis nanti malam. Sampai hari ini juga aku meragukan kisah bahwa kelopak janin ini merupakan adik bayi kami, kesadaran nabati yang akan terus membeberkan kehidupan sejajar di bawah tanah. Namun kini, kesedihan dari perpisahan yang langgeng ini merasuki hatiku seperti duka yang tak dapat terhibur. Dan air mata berlinang di mukaku sedangkan hujan riang rintik-rintik turun.
Aku ingat, di sekitarku, dalam embun malam hangat, di bawah kipas angin yang baling-baling bengkoknya menusuk nyamuk, segerombolan perawat riang yang tanpa lelah memijat pinggulku, menggerakkan sebuah stetoskop dari kayu di atas perutku, dan selama berjam-jam menyuapiku dengan telur rebus selaku infus. Semalam suntuk berlalu dalam suasana gaib. Sebuah cairan ajaib yang berputar di rahimku lalu mengalir ke muara pinggulku: nyeri. Mengerikan saat dia mengejutkanku. Keinginan yang tak tertahankan untuk meninggalkan segalanya, berkemas, kembali. Ulah hati yang selama bertahun-tahun selalu membawaku pulang.
Berulang kali aku pergi ke pinggiran bumi dengan harapan tersesat, tidak pernah pulang. Dari daerah pinggiran Kota Moskow yang dingin sekali pada masa Uni Soviet, hingga Ghetto Soweto atau Bronx yang membara pada masa Apartheid dan kelahiran HipHop. Ya, aku telah menjelajahi begitu banyak kejanggalan. Aku mencintai begitu banyak orang yang terluka dengan keinginan tak terkendali untuk memikul stigma mereka hingga mengasingkan diriku ke kedalaman kelainan mereka. Karena aku yakin bahwa aku tidak hanya berdiri dari diriku sendiri tetapi dari arus manusia yang jauh-jauh dan tak terbatas. Sejak kecil aku sudah menyaksikan mereka hanyut dalam tubuhku, terbawa kegilaan mereka tanpa aku bisa ikut serta. Itu sakit.
Rasa sakit seseorang yang ingin menjadi ganda. Derita sesosok aku yang bercita-cita menjadi sosok yang lain. Itulah petualangan hakiki, pikirku dulu. Tapi di mana petualangan jika pulang tetap mungkin? Sampai kemudian aku tiba di sini, di mayapada ini. Saat itu, bagiku, Jawa merupakan sebuah pulau halimunan yang mengapung serupa perahu mabuk penyair Arthur Rimbaud yang suryanya berbayang kengerian mistis. Sepulang dari Jawa aku berkata, “Rasanya kukena pesona.” Itu bukan guna-guna kepulauan tropis. Bukan pula sihir asmara yang mencoba menegur tubuhku. Kalau begitu, apa itu aji ampuh di hatiku? Itu adalah ilmu pesona yang paling agung. Cinta kasih tanpa kekasih. Aku merasa dicintai tetapi tanpa mengetahui oleh siapa. Demikianlah aku kembali ke Jawa, sekali, dua kali, dan selamanya. Untuk mencari kekasih yang tersembunyi ini.
Malam ini aku benar-benar mengalami pengasingan dalam rahimku yang kerasukan gelombang gelap rasa nyeri. Namun cukup satu napas dalam-dalam, lalu nyeri itu terbentang, berdaulat, lalu tenggelam di perairan teduh tempat bayi mengambang. Kemudian datanglah sukacita: tidur. Satu menit tersenyum tulus yang akan mencerahkan wajah gadis kecilku nanti. Lalu spiral nyeri itu kembali berputar. Aku seorang yogini. Semalam semata.
Hujan baru saja berhenti di balik pagar besi. Aku harus ke kasir rumah sakit untuk membayar. Ibu-ibu yang telah bersalin harus menunjukkan bukti pembayaran sebelum bayi masing-masing diserahkan kepada mereka oleh ketua perawat, ditambah bonus sekaleng susu formula serta botol susu buatan Italia, berdot silikon. Kamar bayi adalah oven. Semua keadaan luar diciptakan kembali di dalam: gelombang panas, suara berisik, pencahayaan berlebih. Orok-orok tidur telentang di bawah lampu neon yang menyilaukan, dalam kemeresek radio kecil yang dibawa setiap perawat di kantong jasnya. Gadis kecilku terbaring di samping bayi laki-laki yang mukanya merah merang, basah kuyup karena air matanya, seolah dia sudah tahu: ibunya telah pergi bersama saudara kembarnya. Tanpa dinamakan. Perempuan itu, Ibu si bayi laki-laki bermuka merah merang itu, tidak mampu membayar untuk dua bayinya. Salah satunya ditinggalkan sebagai jaminan.
Kukira aku tidak memperhatikannya, karena aku begitu silau melihat gadis kecilku. Tetapi, Bu, dari hari kelegahan agung melahirkanku, aku teringat dengan sangat jelas bayangan si bayi tanpa nama ini. Yang terbelah. Yang menantikan kembalinya saudara kembarnya yang mustahil. Si bayi tanpa nama ini yang ditelan dalam kerumunan Tanah Jawa.
*Penulis adalah sastrawan, penerjemah dan wartawati