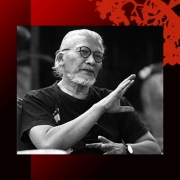Di Balik Gema Ledakan Angka
Oleh Bambang Supriadi*
Di sebuah ruangan tempat berlangsungnya Pra Kongres Badan Perfilman Indonesia 2026, digemakan satu capaian penting dalam perfilman Indonesia saat ini, yaitu ledakan jumlah penonton film nasional. Data yang disampaikan oleh Bappenas dan Kementerian Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa dalam tren beberapa tahun terakhir, jumlah penonton bioskop Indonesia diperkirakan berada di kisaran 80 juta orang per tahun. Angka ini dibacakan seolah menjadi tonggak baru bahwa perfilman Indonesia telah kembali menjadi primadona publik.
Capaian ini juga dianggap sebagai bukti keberhasilan sektor non migas, terutama dalam kerangka ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru nasional. Film disejajarkan dengan pariwisata, kuliner, dan fesyen sebagai penyumbang nilai tambah ekonomi. Dalam narasi ini, penonton bukan lagi publik, melainkan indikator produktivitas dan pasar yang terus diperluas.
Namun angka tersebut tidak menunjuk pada satu tahun kalender yang spesifik. Ia merupakan proyeksi dari tren pasca pandemi, terutama dari perbandingan antara tahun 2023 dan 2024. Laporan industri menunjukkan bahwa jumlah penonton bioskop pada 2023 berada di kisaran 55 juta, lalu melonjak hingga sekitar 82 juta pada 2024. Keberhasilan sejumlah film pada 2025 memang memperkuat kesan ledakan, namun tanpa sistem rekapitulasi nasional yang terbuka, capaian tersebut tetap tidak dapat dibaca sebagai angka kolektif yang terverifikasi.
Bahkan, narasumber dari Kementerian Ekonomi Kreatif mengakui bahwa data riil yang konsisten, terbuka, dan dapat diverifikasi masih sulit diperoleh, baik dari jaringan bioskop maupun platform distribusi. Sejalan dengan penjelasan tersebut, muncul pertanyaan: jangan-jangan yang dikumandangkan hanyalah keberhasilan strategi promosi dan pemasaran, bukan angka statistik yang sebenarnya. Sehingga, angka 80 juta tidak salah jika dipahami sebagai indikasi arah pasar, bukan ukuran pasti yang sepenuhnya akurat. Meskipun demikian, capaian ini menempatkan film nasional kurang lebih sejajar dengan film blockbuster yang pernah beredar di Indonesia, menandakan bahwa produk lokal dicintai di dalam negeri.
Di sisi lain, capaian yang masih prediktif itu nampaknya dilihat dengan kacamata kuda. Sebuah cara pandang sektoral yang menutup kompleksitas, hanya melihat laju angka, bukan kondisi mereka yang menarik gerobaknya. Juga belum mencerminkan sudut pandang 2 yang lebih holistik dari ekosistem perfilman secara menyeluruh. Terlebih jika sudut pandangnya hanya dari sisi pengembangan ekonomi dan perolehan pajak semata, sementara kesejahteraan para kreator yang sesungguhnya menghidupkan karya tersebut tidak terjamah.
Para kreator bagai “sapi perah” yang susunya terus-menerus diambil, tetapi pemeliharaannya dan kesehatan mereka luput dari perhatian. Dalam konteks ini, angkaangka megah itu lebih mirip trofi pajak dan laporan keuangan yang dipajang untuk dinikmati publik. Sebuah penghiburan bagi pemerintah dan penguasa angka-angka. Hal yang sungguh sama sekali tidak menggambarkan keadilan dan keseimbangan bagi pekerja kreatif.

“Botol Susu Melimpah, Tubuh Kerontang”
Oleh karena itu, BPI tidak seharusnya terbuai oleh angka penonton semata. Jika merujuk pada mandatnya, BPI memiliki tanggung jawab yang jauh lebih luas dalam mengelola ekosistem perfilman dari hulu ke hilir, mulai dari memberikan masukan kebijakan kepada Pemerintah dan lembaga legislatif, melakukan penelitian untuk pengembangan seni dan teknologi perfilman, memfasilitasi pendanaan serta mendukung proses produksi, menentukan strategi dan kebijakan distribusi dan eksibisi di dalam maupun di luar negeri, hingga melindungi karya dan kekaryaan perfilman.
BPI juga bertugas meningkatkan kompetensi dan memperluas jaringan profesi, menyusun serta menegakkan kode etik, serta menyelenggarakan sidang etik guna menjaga integritas dan keberlanjutan dunia perfilman Indonesia secara menyeluruh.
Cakupan mandat tersebut menunjukkan bahwa orientasi BPI tidak dapat direduksi menjadi sekadar capaian di hilir saja. Angka penonton memang penting sebagai indikator dinamika industri dan pergerakan ekonomi, tetapi bukan satu-satunya ukuran kesehatan perfilman nasional. Ekosistem yang kuat ditentukan oleh keberlanjutan para pelakunya, oleh 3 profesionalisme kerja, serta oleh adanya perlindungan yang memadai terhadap hak dan martabat kreator.
Dengan demikian, BPI tidak boleh memusatkan orientasinya semata pada perolehan nilai ekonomi, melainkan pada pembangunan ekosistem yang adil, profesional, dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan konkret seperti jam kerja yang adil, royalti yang layak, perlindungan hak ekonomi, dan lain-lain. Tanpa perhatian pada aspek tersebut, pertumbuhan hanya akan menjadi statistik, bukan kemajuan yang substantif.
Setiap capaian seharusnya dapat dirasakan secara nyata oleh para pelaku di dalamnya, bukan hanya dipresentasikan sebagai angka yang impresif di ruang publik. Keberhasilan yang sehat adalah keberhasilan yang menguatkan manusia di balik proses kreatif. Jika film semata-mata diukur melalui grafik dan laporan, maka pelaku di baliknya berisiko dipandang sebagai komponen biaya produksi, bukan sebagai subjek bermartabat yang menjadi fondasi utama perfilman Indonesia.
***
*Dosen Film, Fakultas Film dan Televisión, Institut Kesenian Jakarta.