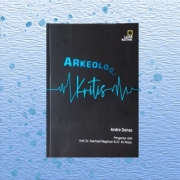Puisi sebagai Ayat Sosial: Membaca Puisi-Puisi Abang Patdeli Abang Muhi
Oleh Abdul Wachid B.S.*
I. Puisi dan Perintah Membaca
Membaca puisi, bagi saya, tidak pernah berhenti pada urusan keindahan bahasa atau kecakapan metafora. Ia lebih sering hadir sebagai pengalaman batin: pelan, kadang mengganggu, dan tidak jarang memaksa kita berhenti sejenak untuk menimbang ulang cara kita memandang dunia. Ada puisi yang selesai ketika larik terakhir ditutup. Namun ada pula puisi yang justru baru mulai bekerja setelah pembacaan usai: menyelinap ke kesadaran, mengusik nurani, dan diam-diam mengajukan pertanyaan etis yang tidak ringan.
Dalam horison pengalaman semacam inilah puisi-puisi Abang Patdeli Abang Muhi saya dekati. Puisi seperti “Senyum” atau “Orang Seperti Kita” tidak tampil sebagai pertunjukan retorika yang riuh, melainkan sebagai sapaan kemanusiaan yang tenang, bersahaja, tetapi mengendap. Ia berbicara tentang hal-hal yang tampak sederhana (senyum, manusia kecil, sikap diam), namun justru dari kesederhanaan itulah pembaca diajak memasuki lapisan makna yang lebih dalam: relasi antarmanusia, luka sosial yang kerap disembunyikan, serta martabat yang sering tergerus oleh mekanisme kuasa.
Di titik inilah perintah iqra’ menemukan relevansinya yang lebih luas. Iqra’ tidak semata saya pahami sebagai ajakan membaca teks suci, melainkan sebagai etika membaca realitas. Membaca keadaan, membaca bahasa yang dipakai penguasa, membaca sikap diam orang-orang kecil, bahkan membaca senyum yang barangkali menyimpan kepedihan. Puisi, dalam konteks ini, menjadi salah satu medium paling jujur untuk menjalankan etika membaca tersebut karena ia tidak hanya menyodorkan fakta, tetapi juga menghadirkan getaran nurani.
Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Paul Ricoeur bahwa teks (termasuk teks sastra) tidak berhenti pada maksud pengarangnya, melainkan membuka “dunia kemungkinan” yang mengajak pembaca untuk bersikap dan menafsir secara etis (Ricoeur, Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, 1976). Puisi, dengan demikian, bukan sekadar sesuatu yang dibaca, tetapi sesuatu yang menuntut keterlibatan kesadaran pembacanya. Ia bekerja di wilayah antara bahasa dan tanggung jawab.
Puisi-puisi Abang Patdeli bergerak di wilayah tersebut. Ia menangkap tanda-tanda sosial yang kerap luput dari pembacaan dangkal: praktik kuasa yang banal, bahasa yang kehilangan akal budi, serta manusia yang perlahan terdesak ke pinggir sejarahnya sendiri. Namun yang menarik, kritik yang hadir tidak menjelma menjadi teriakan amarah tanpa arah. Ada jarak batin, ada pengendalian bahasa, dan ada kesadaran moral yang membuat puisi-puisi itu tetap berpijak pada kemanusiaan.
Berangkat dari pengalaman membaca itulah esai ini disusun. Saya mengajukan satu tesis awal: puisi-puisi Abang Patdeli Abang Muhi dapat dibaca sebagai ayat sosial, yakni tanda-tanda kemanusiaan yang menuntut pembacaan etis. Ia menyuarakan kritik yang bersifat profetik, dalam arti berani menyingkap kemunafikan dan ketimpangan; namun pada saat yang sama menjaga horison raḥmaniyah (kasih sayang yang menghormati martabat manusia). Puisi tidak hadir untuk menghakimi, melainkan untuk menyadarkan; tidak untuk merendahkan, tetapi untuk mengingatkan.
Pada tahap awal ini, pembacaan dilakukan dengan sikap fahm: pemahaman yang jujur, terbuka, dan reflektif. Saya tidak sedang mencari vonis makna yang final, melainkan membuka diri pada kemungkinan bahwa puisi, seperti ayat-ayat kehidupan, selalu menyimpan lebih banyak makna daripada yang dapat kita kuasai dalam satu kali baca.
Semua puisi Abang Patdeli Abang Muhi yang dianalisis dalam esai ini diunduh dari situs: https://borobudurwriters.id/sajak-sajak/puisi-puisi-abang-patdeli-abang-muhi/
II. Penyair, Latar Sosial, dan Horison Kesaksian
Membaca puisi, pada akhirnya, selalu bersinggungan dengan pengalaman hidup penyairnya. Namun dalam kerangka hermeneutik, pengalaman tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat untuk “mengunci” makna, melainkan sebagai horison kesaksian: ruang asal tempat kepekaan bahasa, keberanian bersuara, dan tanggung jawab moral dibentuk secara perlahan sebelum hadir sebagai teks.
Abang Patdeli Abang Muhi lahir di Kampung Sebangan, Simunjan, Sarawak, pada 12 Oktober 1962. Ia tumbuh sebagai anak jati Simunjan, sebuah wilayah yang menyimpan denyut budaya Melayu Sarawak dengan segala ketegangan dan kehalusan relasi sosialnya. Latar ini penting dicatat bukan untuk mengurung puisinya dalam identitas geografis, melainkan untuk menandai dari mana sensibilitas sosial, kultural, dan bahasa itu berangkat.
Lintasan hidup Abang Patdeli menunjukkan perjalanan yang khas. Ia pernah menjadi “guru sandaran” dan wartawan akhbar sebelum berkiprah panjang di Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Jabatan demi jabatan yang diembannya (mulai dari Pegawai Perancang Bahasa, Ketua Bahagian Penyelidikan Sastera, Ketua Akademi DBP, hingga kini sebagai Pengarah Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastera) menempatkannya di pusat pertemuan antara bahasa, kuasa, dan kebijakan kebudayaan. Posisi ini menuntut kecermatan dan integritas, sebab bahasa di ruang institusional tidak pernah sepenuhnya netral.
Di bidang akademik, Abang Patdeli menempuh pendidikan Sarjana Muda Komunikasi dan Psikologi di Universiti Kebangsaan Malaysia, melanjutkan MA dalam Arts Management di City University London, dan meraih gelar Doktor Falsafah Peradaban Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kombinasi latar komunikasi, psikologi, pengelolaan seni, dan peradaban Melayu tersebut beresonansi dalam karya-karyanya: bahasa hadir dengan kesadaran fungsi, sementara kritik disampaikan dengan kendali etis dan kedalaman reflektif.
Selain sebagai penyair, Abang Patdeli dikenal sebagai penulis, penyunting, dan penggiat sastra yang produktif, serta diiktiraf sebagai Sasterawan Sarawak ke-6. Orientasi kulturalnya tampak dalam sejumlah karya dan tulisan yang menaruh perhatian pada relasi sastra, identitas, dan kearifan lokal kawasan Borneo–Kalimantan, antara lain melalui tulisan tentang Sumbangan Borneo-Kalimantan terhadap sastra Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia; karya kreatif seperti Tukang Ensera; serta keterlibatannya sebagai penulis dan penyunting kumpulan cerpen. Dalam ranah kritik dan refleksi, ia menulis makalah dan esai seperti Mencari Kearifan Lokal dalam Cerpen-cerpen Sarawak dan Kalimantan Timur; serta kolom-kolom pemikiran sastra di majalah Dewan Sastera, termasuk refleksi tentang pencarian jati diri Melayu dalam medan fikir sastra.
Keterlibatan Abang Patdeli dalam dunia sastra juga tidak berhenti pada kerja tulis dan institusional. Ia aktif membaca puisi di ruang publik lintas negara. Dalam peluncuran antologi Ibu, Aku Anakmu di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Jakarta, misalnya, ia tampil bersama penyair Indonesia dan Singapura, membacakan puisinya di hadapan khalayak. Peristiwa semacam ini memperlihatkan bahwa puisi baginya bukan sekadar teks yang selesai di halaman, melainkan suara yang diuji dalam ruang sosial.
Pengalaman lintas peran (penyair, penyunting, pengelola bahasa, akademisi, dan pembaca puisi di ruang publik) membentuk Abang Patdeli sebagai saksi zaman. Ia tidak berdiri di luar realitas sosial-politik, tetapi juga tidak larut menjadi corong kekuasaan. Ketegangan inilah yang kelak terasa dalam puisi-puisinya: kewaspadaan terhadap “penjilatan”, kritik atas “ketakburan”, serta empati terhadap manusia biasa yang kerap terdesak oleh sistem.
Dalam kesadaran pembacaan semacam ini, biografi Abang Patdeli diposisikan secukupnya sebagai latar kesaksian, bukan sebagai pembenar ataupun penentu makna akhir puisi. Pengetahuan tentang latar sosial, tanggung jawab institusional, dan orientasi kulturalnya membantu pembaca lebih peka terhadap nada dan arah kritik, tanpa mengalihkan perhatian dari kerja utama puisi itu sendiri.
Dari titik inilah pembacaan dapat diarahkan sepenuhnya ke wilayah teks: bagaimana bahasa bekerja sebagai kesaksian sosial, bagaimana kritik dirumuskan melalui citraan dan ironi, serta bagaimana nilai kemanusiaan dinegosiasikan dalam baris-baris puisi Abang Patdeli Abang Muhi.
III. Puisi: Bahasa sebagai Kesaksian
Puisi tidak pernah lahir di ruang hampa. Ia muncul dari perjumpaan antara pengalaman historis dan kesadaran bahasa, antara realitas sosial yang dialami dan kata-kata yang dipilih untuk menyatakannya. Dalam horison inilah puisi dapat dipahami sebagai ayat sosial: tanda yang tidak hanya bermakna secara estetik, tetapi juga mengandung kesaksian, peringatan, dan penilaian etik atas kehidupan bersama. Ia bukan ayat normatif yang menggurui, melainkan ayat kebudayaan yang mengajak manusia membaca kembali zamannya dengan kesadaran nurani.
Dalam perspektif hermeneutika Paul Ricoeur, teks sastra adalah diskursus yang terlepas dari niat langsung pengarangnya, lalu membuka “dunia di depan teks” (the world in front of the text), yakni ruang kemungkinan makna yang menuntut keterlibatan etis pembaca (Interpretation Theory, 1976). Puisi tidak berhenti pada apa yang dimaksudkan penyair, tetapi menghadirkan kemungkinan makna yang mengundang pembaca untuk menafsir dan bersikap. Sementara itu, Gadamer mengingatkan bahwa pemahaman selalu terjadi dalam fusi cakrawala (Horizontverschmelzung): cakrawala pengalaman teks bertemu dengan cakrawala pengalaman pembaca (Gadamer, Truth and Method, 2004). Dengan demikian, puisi sebagai ayat sosial bekerja bukan hanya melalui apa yang dikatakan, tetapi melalui cara bahasa memanggil kesadaran etis pembacanya.
Puisi-puisi Abang Patdeli Abang Muhi bergerak secara konsisten dalam medan ini. Bahasa ditempatkan bukan sebagai ornamen, melainkan sebagai ruang kesaksian: tempat relasi kuasa, krisis nilai, dan luka sosial dipertemukan dengan tanggung jawab moral kata.
Hal ini tampak jelas dalam “Penjilat”. Sejak awal, puisi ini membangun dunia makna yang keras dan tidak nyaman:
“demi pangkat dan darjat
demi kuasa yang tidak kekal lama
ada sida-sida yang sejak sekian lama
kerjanya hanya membodek dan menjilat”
Metafora “menjilat” bekerja sebagai tanda sosial yang sangat konkret. Ia bukan sekadar cercaan moral individual, melainkan representasi relasi kuasa yang timpang. Dalam logika semiotik-hermeneutik Ricoeur, metafora di sini tidak hanya mengganti makna, tetapi menghasilkan makna baru; membuka cara pandang lain tentang kekuasaan sebagai relasi yang saling menghinakan. Bahkan, puisi ini menyingkap paradoks moral ketika yang “di atas” justru membutuhkan kehinaan itu:
“yang di atas juga rela dirinya dijilat yang di bawah
kerana beliau sedar yang di bawah hanya pandai menjilat”
Bahasa di sini menjadi ayat sosial yang bersaksi bahwa kerusakan etika bukanlah kecelakaan personal, melainkan hasil dari sistem yang menormalisasi kehinaan. Kematian si penjilat dengan “lidahnya yang terjelir” bukan sekadar hukuman alegoris, tetapi simbol bahwa bahasa yang diperalat untuk kepalsuan pada akhirnya akan memakan dirinya sendiri.
Kesaksian sosial dengan nada berbeda muncul dalam “Bahasa Apa Itu?” Puisi ini menghadirkan pengalaman sehari-hari yang sederhana, namun sarat makna hermeneutik. Pertanyaan seorang anak menjadi titik retak dalam kesadaran orang dewasa: “apa kita tidak punya kata-kata sendiri?”
Dalam kerangka pemahaman Gadamerian, pertanyaan ini adalah pertanyaan sejati (bukan untuk dijawab secara teknis), melainkan untuk mengguncang horison pemahaman yang sudah mapan. Bahasa Inggris yang berderet di ruang publik Putrajaya tidak lagi netral; ia menjelma simbol kuasa dan penanda keterasingan. Ketika sang ayah mengakui keterbatasannya, “aku pun tidak tahu maknanya”; puisi ini menjadi ayat sosial tentang krisis jati diri linguistik. Bahasa puisi bersaksi bahwa kolonisasi tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi sering bekerja secara halus melalui penyingkiran bahasa jiwa bangsa.
Dimensi ayat sosial yang berangkat dari pengalaman kolektif tampak kuat dalam “Orang Seperti Kita”. Repetisi frasa “orang seperti kita” membangun subjek komunal; bukan pahlawan, melainkan mereka yang biasa, diam, dan kerap diremehkan:
“hanya kerana kita orang kecil
yang kerdil dan
tidak banyak bicara”
Namun, puisi ini tidak berhenti pada narasi korban. Dalam logika hermeneutika, teks ini membuka kemungkinan dunia di mana kesabaran memiliki batas etis:
“kalau bertubi-tubi dihina-dina
dan diinjak-injak maruah diri kita
pasti akan hilang sabar
lantas siap siaga untuk berlaga.”
Ayat sosial di sini bekerja sebagai pencatatan psikologi kolektif: dari diam menuju kesadaran harga diri. Puisi tidak mengglorifikasi kekerasan, tetapi menegaskan bahwa martabat manusia adalah nilai yang tidak boleh dinegosiasikan tanpa batas.
Kritik terhadap elite dan figur berkuasa menemukan bentuk alegorisnya dalam “Takbur” dan “Hanya dengan Empat Butir Kata”. Dalam “Takbur”, kata-kata pongah menjadi sebab kehancuran:
“tercekik dek tulang-tulang kata pongah mereka sendiri.”
Bahasa, yang semula digunakan untuk memamerkan kuasa, berbalik menjadi saksi kejatuhan. Sementara dalam “Hanya dengan Empat Butir Kata”, mitos perjuangan runtuh bukan oleh serangan luar, melainkan oleh pengakuan bahasa itu sendiri:
“dia sendiri yang membuka pekung busuk di dada.”
Dalam perspektif Ricoeurian, ini menunjukkan bagaimana teks membuka kebenaran simbolik: bahwa kebohongan politik pada akhirnya runtuh oleh narasi yang tidak lagi sanggup menutupi dirinya sendiri. Puisi berfungsi sebagai ayat sosial yang mencatat kejatuhan moral tanpa harus menyebut nama.
Namun, ayat sosial dalam puisi-puisi Abang Patdeli tidak semata bernada gugatan. Dalam “Senyum”, bahasa dipulihkan ke fungsi etik paling dasar:
“kuntuman-kuntuman cantik manis itu
bisa mencairkan hati yang beku
bisa mendamaikan jiwa yang lara.”
Di sini, puisi membuka dunia kemungkinan lain: bahwa perlawanan terhadap kekerasan sistemik juga dapat hadir dalam bentuk tindakan kecil yang manusiawi. Senyum menjadi simbol etika keseharian; ayat sosial yang mengingatkan bahwa kemanusiaan harus terus dirawat, bahkan di tengah kerapuhan zaman.
Dengan demikian, puisi-puisi Abang Patdeli Abang Muhi dapat dibaca sebagai rangkaian ayat sosial yang hidup. Bahasa dalam puisinya bukan hanya mencerminkan realitas, tetapi mengujinya secara moral. Melalui metafora, dialog, repetisi, dan alegori, puisi membuka ruang tafsir di mana pembaca diajak mengalami fusi cakrawala: antara teks, pengalaman sosial, dan kesadaran etiknya sendiri.
Di titik inilah puisi melampaui ekspresi individual. Ia menjadi ruang kesaksian bersama (tempat bahasa tidak hanya berkata), tetapi bersaksi; tidak hanya menggambarkan, tetapi menuntut sikap. Puisi, dengan demikian, tidak selesai dibaca. Ia menunggu untuk dihidupi.
IV. Profetisitas dalam Puisi
1. Kritik dan Etika Profetik Bahasa
Dalam tradisi profetik, kritik bukanlah luapan kebencian, apalagi pelampiasan dendam simbolik. Kritik justru merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap kehidupan bersama. Ia lahir dari keberanian menyuarakan kebenaran, dari kejujuran menatap realitas apa adanya, dan dari keberpihakan pada martabat manusia yang kerap terinjak oleh kuasa. Dalam horison inilah profetisitas puisi-puisi Abang Patdeli Abang Muhi menemukan pijakannya: bukan sebagai propaganda ideologis, melainkan sebagai amar makruf nahi mungkar estetik: seruan etik yang bekerja melalui bahasa, metafora, dan imajinasi moral.
Puisi profetik tidak berteriak dari mimbar kekuasaan. Ia bersaksi dari dalam luka sosial. Ia tidak menunjuk dengan jari telunjuk, melainkan membuka tabir agar pembaca sendiri melihat, menimbang, dan mengambil sikap. Kritik yang dihadirkan bukan sekadar pembongkaran keburukan, melainkan upaya menjaga agar nurani tidak tumpul oleh kelaziman yang keliru. Dalam pengertian ini, bahasa puisi memikul tanggung jawab etis: setiap kata tidak hanya menyampaikan makna, tetapi juga membawa konsekuensi moral. Hal ini sejalan dengan pandangan Paul Ricoeur bahwa bahasa simbolik selalu menuntut pertanggungjawaban etis karena ia membentuk cara manusia memahami dan menilai dunia (Interpretation Theory, 1976).
2. Kuasa dan Mentalitas Feodal
Kritik terhadap kuasa dan mentalitas feodal tampil sangat kuat dalam “Penjilat” dan “Takbur”. Dalam “Penjilat”, Abang Patdeli membangun alegori yang getir tentang relasi kuasa yang tidak sehat; relasi yang memelihara kehinaan sebagai mata uang sosial. Sejak larik awal, puisi ini telah menempatkan pembaca pada lanskap moral yang suram:
“demi pangkat dan darjat
demi kuasa yang tidak kekal lama
ada sida-sida yang sejak sekian lama
kerjanya hanya membodek dan menjilat”
Yang dikritik bukan semata figur “penjilat”, melainkan sistem feodal yang memungkinkan, bahkan merayakan perilaku tersebut. Relasi atas–bawah digambarkan sebagai relasi yang saling merusak: yang di bawah kehilangan martabat karena menjilat, yang di atas kehilangan kehormatan karena menikmati jilatan. Profetisitas puisi ini terletak pada keberaniannya menyingkap paradoks itu tanpa kompromi:
“yang di atas juga rela dirinya dijilat yang di bawah
kerana beliau sedar yang di bawah hanya pandai menjilat”
Bahasa di sini bekerja sebagai penghakiman moral yang tenang namun tak terelakkan. Puisi tidak memanggil aparat hukum, melainkan memanggil kesadaran etik. Kematian si penjilat dengan “lidahnya yang terjelir” menjadi simbol profetik: lidah yang sepanjang hidup diperalat untuk kepalsuan, pada akhirnya menjadi saksi kebinasaan dirinya sendiri.
Nada profetik yang sejenis, dengan medan alegori berbeda, hadir dalam “Takbur”. Kesombongan kuasa tidak dikritik melalui figur personal semata, melainkan melalui hubungan antara manusia dan realitas yang lebih luas, antara keangkuhan bahasa dan hukum moral semesta:
“tercekik dek tulang-tulang kata pongah mereka sendiri.”
Kata-kata pongah, sumpah retoris, dan lagak kuasa yang seolah menundukkan alam justru berbalik menjadi sebab kehancuran. Profetisitas puisi ini tampak pada kesadarannya bahwa kuasa yang kehilangan hikmah akan berhadapan dengan hukum moral yang melampaui kehendak manusia. Tuhan tidak tampil sebagai penghukum tergesa-gesa, melainkan sebagai Penunda murka: memberi ruang belajar yang sering kali disia-siakan manusia.
3. Pengkhianatan Amanah dan Kata
Jika “Penjilat” dan “Takbur” mengkritik struktur kuasa, maka “Jejaka yang Gemar Bersumpah” menggeser sorotan ke wilayah yang lebih personal, namun tidak kalah sosial: pengkhianatan amanah dan kata. Puisi ini menegaskan bahwa profetisitas tidak hanya relevan di ranah politik dan kekuasaan publik, tetapi juga dalam etika relasi antarmanusia.
Sumpah dalam puisi ini bukan sekadar janji asmara, melainkan simbol kepercayaan. Ketika sumpah diucapkan dengan membawa nama Tuhan tetapi dilanggar tanpa rasa bersalah, yang dikhianati bukan hanya pasangan, melainkan tatanan moral itu sendiri. Repetisi sumpah yang tidak pernah diniatkan untuk ditepati menyingkap wajah profetik puisi ini: bahasa yang kehilangan kebenaran akan berubah menjadi kekerasan simbolik. Hal itu tampak jelas ketika si jejaka
“bersumpah
untuk setia bersama si nona
…
dan jika dia mungkir janji
dia reda dihukum-Nya
dan jika dia melanggar sumpah
dia rela dilaknati-Nya.”
Sumpah yang diucapkan dengan penuh retorika religius itu ternyata tidak disertai komitmen moral. Kata-kata suci diperalat sebagai instrumen bujuk rayu, bukan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Di sinilah profetisitas puisi bekerja: bukan dengan menghakimi dari luar, melainkan dengan membiarkan kata-kata si jejaka sendiri menjadi saksi atas kepalsuannya.
Doa si nona di akhir puisi (agar si jejaka “dimakan sumpahnya sendiri”) bukanlah kutukan emosional, melainkan keyakinan profetik bahwa kata memiliki konsekuensi. Dalam logika moral puisi ini, bahasa tidak pernah netral; ia akan kembali kepada penuturnya sebagai kesaksian.
4. Bahasa dan Manipulasi Moral
Dimensi profetik puisi Abang Patdeli mencapai ketajaman simboliknya dalam “Hanya dengan Empat Butir Kata”. Di sini, bahasa ditampilkan secara telanjang sebagai alat manipulasi moral dan politik. Bukan serangan dari luar yang meruntuhkan topeng kuasa, melainkan bahasa itu sendiri:
“dia sendiri yang membuka pekung busuk di dada.”
Puisi ini bekerja seperti nubuat yang digenapi oleh subjeknya sendiri. Kata-kata yang semula digunakan untuk membangun mitos perjuangan, legitimasi, dan citra diri, pada akhirnya justru menjadi alat pembongkaran. Profetisitas puisi ini terletak pada keyakinannya bahwa kebohongan memiliki usia, dan bahasa yang diperalat terlalu lama akan kehilangan daya tutupnya.
“Empat butir kata” menjadi simbol kehancuran total narasi palsu. Tanpa menyebut nama, puisi ini mengajukan kritik moral yang tajam terhadap mentalitas Machiavellian: tujuan menghalalkan cara, meski harus mengorbankan manusia dan martabat bersama.
5. Puisi sebagai Hikmah Moral
Dalam keseluruhan puisi-puisi ini, profetisitas tidak hadir sebagai kemarahan yang meledak-ledak, melainkan sebagai hikmah yang tegas. Abang Patdeli tidak mengubah puisi menjadi pamflet ideologis. Ia menjaga jarak dari propaganda justru dengan mempercayakan kritik pada kekuatan bahasa dan simbol.
Pada tahap ḥikmah, puisi-puisi ini mengajak pembaca merenung: bahwa kuasa tanpa moral melahirkan kehinaan; bahwa sumpah tanpa niat adalah pengkhianatan; bahwa bahasa yang diperalat akan menelanjangi penuturnya sendiri. Inilah amar makruf nahi mungkar estetik: kritik yang tidak memaksa, tetapi menuntut kesadaran.
Dengan demikian, profetisitas dalam puisi Abang Patdeli Abang Muhi bukanlah klaim kesucian, melainkan kesetiaan pada kebenaran. Puisi menjadi ruang di mana bahasa dipanggil kembali ke tugas asalnya: menjaga amanah makna, membela martabat manusia, dan mengingatkan bahwa setiap kata, cepat atau lambat, akan dimintai kesaksian.
V. Rahmaniyah di Balik Bahasa yang Tegas
Jika pada bagian sebelumnya puisi-puisi Abang Patdeli Abang Muhi dibaca dari horison profetisitas (kritik, pembongkaran, dan peringatan moral), maka pada tahap ini kita berhadapan dengan sisi lain yang tidak kalah mendasar: raḥmaniyah. Namun perlu ditegaskan sejak awal, raḥmaniyah yang bekerja dalam puisi-puisi ini bukanlah kelembutan sentimental yang meninabobokan, melainkan kasih sayang yang berakar pada akal budi, tanggung jawab etik, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Raḥmah, dalam pengertian ini, bukan sikap permisif terhadap ketidakadilan, melainkan penolakan terhadap dehumanisasi. Ia hadir sebagai pembelaan terhadap nurani kolektif, sebagai ikhtiar menjaga manusia agar tidak sepenuhnya larut menjadi korban atau pelaku kekerasan simbolik. Karena itu, bahasa yang tegas, bahkan keras, justru dapat menjadi medium kasih sayang yang paling jujur, sejauh ia diarahkan untuk menyelamatkan kemanusiaan.
1. Empati terhadap Manusia Kecil
Dimensi raḥmaniyah paling jelas terasa dalam “Orang Seperti Kita”. Puisi ini tidak berangkat dari posisi heroik, melainkan dari kesadaran akan kerentanan. Subjek lirik tidak menampilkan diri sebagai pahlawan moral, melainkan sebagai bagian dari barisan manusia kecil yang kerap disisihkan:
“Orang seperti kita
selalunya dilirik sebelah mata
hanya kerana kita orang kecil
yang kerdil dan
tidak banyak bicara.”
Nada yang digunakan tenang, hampir datar, namun justru di situlah kekuatannya. Tidak ada ratapan berlebihan, tidak ada tuntutan emosional yang histeris. Raḥmah hadir sebagai pengakuan atas luka sosial yang dialami “orang seperti kita”: mereka yang lemah, polos, dan kerap memilih diam demi menjaga harmoni. Akan tetapi, puisi ini tidak memuliakan kepasrahan secara naif. Pada bait-bait akhir, raḥmaniyah justru menuntut keberanian etik: ketika martabat diinjak berulang kali, bangkit menjadi keharusan moral.
Dengan demikian, empati dalam puisi ini bukan empati yang melanggengkan ketertindasan, melainkan empati yang mengingatkan bahwa kesabaran pun memiliki batas kemanusiaannya.
2. Bahasa, Jati Diri, dan Raḥmah Kultural
Raḥmaniyah juga menjelma dalam kepedulian terhadap bahasa dan jati diri, sebagaimana tampak dalam “Bahasa Apa Itu?” Puisi ini memindahkan kritik dari arena kuasa politik ke ruang yang lebih subtil namun menentukan: bahasa sebagai rumah makna. Pertanyaan polos seorang anak (tentang istilah-istilah asing yang mendominasi ruang publik) menjadi cermin kegagalan orang dewasa menjaga bahasa jiwa bangsanya.
Ketika sang ayah akhirnya mengakui keterbatasannya sendiri, “aku pun tidak tahu maknanya”; puisi ini memperlihatkan raḥmah dalam bentuk kejujuran. Tidak ada penghakiman terhadap anak, tidak pula glorifikasi terhadap diri sebagai pendidik yang serba tahu. Sebaliknya, raḥmaniyah muncul sebagai kesadaran kritis bahwa pengabaian bahasa sendiri adalah bentuk kekerasan kultural yang halus, tetapi berjangka panjang.
Kasih sayang di sini bukan nostalgia romantik terhadap masa lalu, melainkan kepedulian aktif agar generasi berikutnya tidak tercerabut dari akar makna. Raḥmah bekerja sebagai dorongan etis untuk merawat bahasa, bukan meminggirkannya demi kemudahan dan prestise semu.
3. Senyum sebagai Sisa Harapan Kemanusiaan
Jika dua puisi sebelumnya bergerak di wilayah empati sosial dan kesadaran kultural, maka “Senyum” menghadirkan raḥmaniyah dalam bentuk paling sederhana sekaligus paling esensial. “Senyum” dalam puisi ini bukan basa-basi sosial, melainkan sedekah batin:
“kerana kuntuman-kuntuman cantik manis itu
bisa mencairkan hati yang beku
bisa mendamaikan jiwa yang lara.”
Bahasa puisi ini lembut, nyaris tanpa kritik eksplisit. Namun justru di situlah letak kekuatannya. Setelah pembaca digiring melewati lanskap kuasa, pengkhianatan, dan manipulasi bahasa, “Senyum” hadir sebagai pengingat bahwa kemanusiaan tidak sepenuhnya runtuh. Masih ada ruang kecil bagi tindakan sederhana yang menyembuhkan, meski tidak menyelesaikan segalanya.
Raḥmaniyah dalam “Senyum” bukan eskapisme, melainkan bentuk perlawanan sunyi terhadap kekerasan dunia: menghadirkan kasih tanpa pamrih, bahkan ketika waktu sendiri terasa semakin sempit.
4. Kritik Keras sebagai Kasih Sayang Preventif
Dibaca secara keseluruhan, raḥmaniyah dalam puisi-puisi Abang Patdeli tidak pernah berdiri terpisah dari ketegasan. Kritik yang keras, sindiran yang tajam, dan alegori yang getir justru berfungsi sebagai kasih sayang preventif: upaya mencegah kerusakan yang lebih dalam pada nurani manusia.
Pada tahap sintesis ‘aql dan raḥmah, puisi-puisi ini menunjukkan bahwa akal budi tanpa kasih akan menjelma sinisme, sementara kasih tanpa akal akan terjerumus menjadi sentimentalitas kosong. Raḥmaniyah yang sejati menuntut keberanian berkata benar, sekaligus kesediaan menjaga martabat bahkan bagi mereka yang sedang dikritik.
Dengan demikian, bahasa yang tegas dalam puisi Abang Patdeli Abang Muhi bukanlah negasi kasih sayang, melainkan justru bentuk tertingginya. Ia mengingatkan bahwa mencintai manusia berarti berani menegur, menyadarkan, dan (pada saat yang sama) tetap membuka ruang harapan bagi kemanusiaan yang lebih beradab.
VI. Penyair sebagai Saksi Zaman
Dalam keseluruhan puisi Abang Patdeli Abang Muhi, terasa satu benang merah yang mengikat beragam tema, nada, dan bentuk ungkapannya: kesadaran bahwa menulis bukan sekadar ekspresi personal, melainkan amanah. Puisi-puisi itu, jika dibaca lintas teks, membentuk satu kesaksian moral yang utuh; bukan kumpulan suara yang tercerai, melainkan satu napas etis yang konsisten menanggapi zamannya.
Penyair dalam posisi ini tidak menempatkan diri sebagai penghibur kekuasaan. Ia tidak memoles luka sosial dengan bahasa manis agar terasa wajar, tidak pula meredam kegelisahan publik demi kenyamanan simbolik. Namun, ia juga tidak berdiri sebagai hakim moral yang menjatuhkan vonis dari menara tinggi. Sikap yang diambil justru lebih subtil dan, karena itu, lebih berisiko: menjadi saksi nurani.
Sebagai saksi, penyair tidak selalu hadir dengan suara lantang. Kadang ia berbicara melalui sindiran, alegori, atau ironi; kadang ia memilih bahasa yang tenang dan sederhana. Tetapi kesaksiannya tidak pernah netral. Ia berpihak pada akal budi, pada martabat manusia, dan pada kebenaran yang kerap disembunyikan di balik bahasa kekuasaan. Dalam puisi-puisi kritik seperti “Penjilat” dan “Takbur”, kesaksian itu tampil sebagai pembongkaran mentalitas feodal. Dalam “Jejaka yang Gemar Bersumpah”, ia menjelma sebagai peringatan etis tentang kata dan amanah. Sementara dalam puisi-puisi yang lebih lembut seperti “Senyum” atau “Orang Seperti Kita”, kesaksian itu hadir sebagai empati terhadap luka-luka yang jarang mendapat panggung.
Menulis, dalam horison ini, adalah tanggung jawab etis. Kata tidak diperlakukan sebagai permainan retoris atau alat sensasi, melainkan sebagai beban makna yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap puisi menjadi upaya menjaga agar bahasa tidak sepenuhnya jatuh menjadi instrumen manipulasi, kebohongan, atau kekerasan simbolik. Ketika bahasa dijaga, akal budi pun dirawat; dan ketika akal budi dirawat, kemanusiaan memperoleh peluang untuk bertahan.
Lebih jauh, kepengarangan Abang Patdeli Abang Muhi dapat dibaca sebagai amal kultural. Ia tidak sekadar menulis untuk zamannya sendiri, melainkan menyumbangkan kesadaran etik bagi ruang publik yang lebih luas. Dalam tradisi sastra yang bermartabat, penyair memang tidak diukur dari seberapa sering ia dipuji atau diundang ke panggung, melainkan dari keberaniannya bersuara ketika diam justru lebih aman. Keberanian inilah yang membuat puisi-puisinya tidak lekas usang, karena yang disaksikan bukan peristiwa sesaat, melainkan pola-pola moral yang terus berulang dalam sejarah manusia.
Dengan demikian, penyair sebagai saksi zaman tidak menawarkan solusi instan, tidak pula menjanjikan keselamatan dunia. Ia hanya memastikan satu hal yang sangat mendasar: bahwa nurani tidak sepenuhnya dibungkam, bahwa masih ada kata yang bersedia berdiri di hadapan kekuasaan, kepalsuan, dan kelupaan. Dalam kesediaan itulah, puisi menjadi amanah; dan penyair, dengan segala keterbatasannya, tetap memilih setia menjaganya.
VII. Di Antara Sastra Malaysia dan Indonesia
Pembacaan terhadap puisi-puisi Abang Patdeli Abang Muhi dalam esai ini sejak awal dilakukan secara imanen: berangkat dari dalam teks, dari cara kata bekerja, dari etika yang disarankan oleh puisi itu sendiri. Namun, sebuah pembacaan yang matang tetap memerlukan satu gerak keluar yang singkat dan terukur. Bukan untuk mengklaim keunggulan, bukan pula untuk membandingkan secara hierarkis, apalagi menjejalkan sejarah sastra. Gerak keluar ini semata-mata dimaksudkan untuk menegaskan relevansi lintas wilayah bahasa, menempatkan gagasan profetik–etiknya dalam peta kesusastraan serumpun, serta menunjukkan bahwa pembacaan ini tidak berdiri di ruang hampa sejarah.
Dalam konteks sastra Malaysia, Abang Patdeli tampil sebagai penyair yang setia pada bahasa Melayu baku yang retoris dan berlarik panjang. Kesetiaan ini, penting ditegaskan, tidak bergerak ke arah nostalgia atau folklorisme. Bahasanya bersifat naratif–argumentatif, dekat dengan tradisi puisi wacana yang pernah kuat dalam sastra Malaysia, sebagaimana terlihat pada karya-karya Usman Awang, A. Samad Said, atau Latiff Mohidin pada periode tertentu. Namun, yang membedakan Abang Patdeli dari banyak penyair sezamannya ialah arah gerak bahasanya. Bahasa puisinya tidak berhenti pada nasionalisme bahasa atau retorika kebangsaan, melainkan melangkah ke wilayah etika bahasa: bagaimana kata bekerja dalam relasi sosial, bagaimana ia bisa mengkhianati amanah, atau justru menyelamatkan martabat manusia. Di titik ini, ia sezaman dengan arus utama, tetapi tidak sepenuhnya serupa dengannya.
Dari dimensi gagasan, posisi Abang Patdeli menjadi semakin tegas. Dalam peta puisi Malaysia kontemporer, ia bukan penyair eksperimental yang menantang bentuk demi bentuk, bukan pula penyair liris yang menutup diri dalam keintiman perasaan personal. Ia memilih jalur yang kian jarang digarap secara konsisten: puisi sebagai kesaksian moral. Puisinya berani menyebut kuasa, berani menyingkap kemunafikan, dan berani mempersoalkan kerusakan bahasa, namun semua itu dilakukan tanpa jatuh menjadi pamflet ideologis. Kritik dalam puisinya bekerja melalui alegori, ironi, dan kesabaran etis, bukan melalui teriakan atau slogan.
Relasinya dengan puisi Indonesia justru memperlihatkan kekuatan posisi ini secara lebih terang. Meskipun ditulis dalam bahasa Melayu-Malaysia, puisi-puisi Abang Patdeli sepenuhnya terbaca oleh pembaca Indonesia. Bahasa Melayu–Indonesia di sini berfungsi sebagai jembatan, bukan batas. Tema-tema yang diangkat (kritik terhadap kuasa, pengkhianatan amanah, manipulasi bahasa, dan pembelaan terhadap manusia kecil) beresonansi kuat dengan tradisi puisi kritik sosial Indonesia. Ia beririsan dengan semangat kesaksian Taufik Ismail, keberanian etis Rendra, dan dalam beberapa puisi, ironi moral yang mengingatkan pada Gus Mus (K.H. A. Mustofa Bisri), tanpa meniru diksi atau gaya mereka. Dengan demikian, Abang Patdeli lebih tepat dibaca sebagai penyair serumpun daripada penyair regional semata.
Dari sudut gagasan yang dibicarakan dalam esai ini, kekuatan Abang Patdeli terletak pada kemampuannya berbicara dari konteks Malaysia sambil menghadirkan persoalan yang bersifat universal. Kritik kuasa, etika bahasa, raḥmah, dan martabat manusia bukanlah tema lokal atau temporer, melainkan persoalan lintas nasional dan lintas zaman. Justru karena keberangkatannya yang kontekstual itu, puisinya menjadi relevan bagi sastra Indonesia, layak dibaca dalam diskursus sastra Asia Tenggara, dan sah ditempatkan dalam tradisi sastra bermartabat yang berani bersuara.
Catatan kontekstual ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan Abang Patdeli pada hierarki tertentu. Ia hanya ingin menegaskan satu hal yang sederhana tetapi mendasar: bahwa puisi-puisi Abang Patdeli berdiri dalam satu garis kesaksian yang menjadikan bahasa sebagai amanah dan puisi sebagai kerja nurani. Di mana pun ia ditulis, puisi semacam ini pada akhirnya berpulang pada tugas yang sama: menjadi saksi zaman, ketika zaman kerap lupa pada dirinya sendiri.
VIII. Membaca Puisi, Membaca Kemanusiaan
Pada akhirnya, membaca puisi-puisi Abang Patdeli Abang Muhi adalah membaca kembali wajah kemanusiaan kita sendiri. Puisi-puisi itu tidak hadir sebagai ornamen estetika yang berdiri jauh dari kehidupan, melainkan sebagai cermin batin yang memantulkan luka, kegelisahan, harapan, dan martabat manusia dalam keseharian yang kerap kita anggap biasa. Di hadapan puisi-puisi ini, pembaca tidak sedang diajak mengagumi kecanggihan bahasa, melainkan diajak berhenti sejenak dan menimbang ulang cara kita bersikap sebagai manusia.
Dalam “Senyum”, misalnya, bahasa puisi tidak diarahkan untuk melukiskan kebahagiaan yang sentimental. “Senyum” justru dihadirkan sebagai kerja nurani yang sadar dan disengaja. Ia bukan basa-basi sosial, melainkan laku batin yang dipetik dari taman keikhlasan, yang mampu mencairkan kekerasan hati dan meredakan luka yang tersembunyi. Puisi ini mengingatkan bahwa kemanusiaan sering kali diselamatkan oleh gestur-gestur kecil yang tulus, bukan oleh jargon besar atau seruan moral yang gemuruh.
Sementara itu, “Orang Seperti Kita” membawa pembaca berhadapan dengan realitas manusia kecil yang kerap diremehkan, dimanipulasi, dan dipinggirkan. Namun puisi ini tidak berhenti pada ratapan atau keluhan. Dengan nada yang jernih dan lugas, ia menegaskan bahwa kesabaran pun memiliki batas, dan bahwa martabat manusia tidak bisa selamanya dinegosiasikan. Puisi ini menolak dehumanisasi tanpa kehilangan kejernihan, dan merawat harga diri kolektif tanpa terjerumus pada dendam.
Dari dua puisi ini (dan sesungguhnya dari keseluruhan puisi yang dibaca dalam esai ini) tampak bahwa kepengarangan Abang Patdeli Abang Muhi berpijak pada satu sikap mendasar: kritik yang tajam tidak pernah dilepaskan dari kasih sayang, dan empati tidak pernah dijadikan alasan untuk membenarkan ketidakadilan. Puisi bekerja sebagai ruang perenungan etis, tempat akal, iman, dan nurani saling meneguhkan tanpa saling meniadakan.
Dengan demikian, membaca puisi-puisi ini bukanlah upaya mencari siapa yang paling bersalah, melainkan kesempatan untuk bercermin dan bertanya secara jujur: di manakah posisi kita dalam struktur kuasa, dalam bahasa yang kita ucapkan, dan dalam relasi kita dengan sesama? Puisi tidak menawarkan vonis, tetapi membuka jalan kesadaran, bahwa memperbaiki dunia selalu bermula dari keberanian membaca diri sendiri, dengan rendah hati, sebagai manusia.
Sebagai penutup, saya ingin menghadirkan puisi utuh “Senyum” yang mewakili eksistensi penyair, etika, dan raḥmaniyah dalam puisinya:
Senyum
Untuk ke sekian kalinya
akan kugubah kuntum-kuntum senyum
yang tulus-mulus
yang kupetik dari taman nurani
yang harum mewangi
kerana kuntuman-kuntum cantik manis itu
bisa mencairkan hati yang beku
bisa mendamaikan jiwa yang lara
bisa menjadi penawar rindu, dan
bisa menjalin cinta kasih sesama insan.
Jika aku masih punya waktu
akan aku sedekahkan senyuman
seindah rembulan purnama
untuk setitis ganjaran-Nya.
Istanbul, Turkiye, 26 Januari 2018
—-
Daftar Pustaka
Abang Patdeli Abang Muhi. 2026. Berbagai puisi: “Penjilat”; “Bahasa Apa Itu?”; “Senyum”; “Takbur”; “Jejaka yang Gemar Bersumpah”; “Lelaki Berida III”; “Orang Seperti Kita”; “Siapa Sangka dalam Diam”; “Aku Tiba-tiba Diminta Baca Puisi”; “Hanya dengan Empat Butir Kata”. Sumber: https://borobudurwriters.id/sajak-sajak/puisi-puisi-abang-patdeli-abang-muhi/, dan dokumen pribadi.
Gadamer, Hans-Georg. 2004. Truth and Method. Terjemahan oleh Joel Weinsheimer & Donald G. Marshall. London–New York: Continuum. (Edisi asli 1960).
Ricoeur, Paul. 1976. Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. Fort Worth: Texas Christian University Press.
Ricoeur, Paul. 1981. Hermeneutics and the Human Sciences. Ed. & trans. John B. Thompson. Cambridge: Cambridge University Press.
—-
*Penulis adalah penyair, Ketua Sekolah Kepenulisan Sastra Pedaban (SKSP) dan Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.