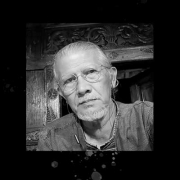Gastronomi Politik: Dialektika Rendang, Gudeg, dan Gado-Gado dalam Cawan Demokrasi Indonesia
Oleh: Gus Nas Jogja*
Mukadimah:
Meja Makan sebagai Altar Peradaban
Demokrasi bukanlah sekadar bilik suara yang dingin atau tumpukan kertas suara yang mati. Demokrasi adalah sebuah perjamuan agung. Di atas meja kebangsaan kita, terhidang narasi-narasi rasa yang lebih tua dari republik ini sendiri. Jika politik sering kali dipandang sebagai perebutan kuasa yang gersang, maka melalui Rendang, Gudeg, dan Gado-Gado, kita akan menemukan bahwa Indonesia adalah sebuah “Alkimia Rasa”. Inilah esai tentang bagaimana lidah bernegosiasi dengan takdir, dan bagaimana piring-piring kita bicara tentang kedaulatan, kesabaran, dan keberagaman yang melampaui diksi para politisi.
I. Rendang: Filosofi Ketahanan dan Kedaulatan Mental
Rendang bukan sekadar daging yang dimasak dalam santan; ia adalah manifestasi dari filsafat Musyawarah dan Mufakat yang mengeras menjadi karakter. Secara antropologis, Rendang adalah simbol dari Ketangguhan Mental (Resiliensi).
Rendang adalah tarian api yang sabar. Di dalam kuali besar, daging menyerahkan keangkuhannya pada rempah-rempah yang tajam. Ia adalah proses dekonstruksi materi menuju esensi. Santan yang putih melambangkan kemurnian niat, yang perlahan menghitam oleh panasnya cobaan, namun di puncak kegelapan itu, ia melahirkan kelezatan yang abadi.
Dalam berbagai pidatonya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto sering menekankan pentingnya Indonesia “berdiri di atas kaki sendiri” (Berdikari). Rendang adalah personifikasi dari kedaulatan itu—ia tak lekang oleh waktu, tak butuh pengawet kimia, karena ia diawetkan oleh dedikasi rempah lokal.
Namun, oposisi melihat Rendang ini mulai kehilangan “pedasnya”. Kritikus sering berujar secara puitis: “Jangan sampai Rendang kita dimasak dengan santan impor, di mana dagingnya adalah daging pinjaman, dan rempahnya hanya sekadar kosmetik pencitraan.” Kedaulatan Rendang terancam jika api kearifan lokal padam oleh disrupsi modal asing yang hanya ingin memakan hasilnya tanpa mau melewati proses “mengaduk” yang melelahkan.
II. Gudeg: Estetika Kesabaran dan Politik Kedalaman
Jika Rendang adalah api, maka Gudeg adalah tanah. Ia mewakili filosofi Jawa tentang Alon-Alon Waton Kelakon. Gudeg adalah antitesis dari banalitas modern yang menuntut kecepatan.
Gudeg adalah bentuk “peribadatan waktu”. Nangka muda yang getir harus bertransformasi menjadi manis melalui rendaman daun jati dan rahasia bumbu yang meresap hingga ke sumsum. Ia adalah simbol dari Manusia Lenting di Jogja: mereka yang tetap “berhati nyaman” meski dihimpit beban overload. Gudeg hadir dalam kebersahajaan cokelat yang dalam, seperti doa yang dibisikkan di tengah malam.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sering menggunakan metafora “Akar Rumput” dan “Sabar dalam Perjuangan”. Gudeg adalah politik yang tidak mengejar headline esok pagi, melainkan politik yang menyiapkan fondasi untuk seratus tahun ke depan. Ia adalah strategi “Wong Cilik” yang pelan namun pasti meresap ke dalam sendi bangsa.
Oposisi menyindir bahwa kesabaran Gudeg sering kali disalahgunakan untuk menutupi kelambanan birokrasi. Kritik puitis mereka berbunyi: “Kemanisan Gudeg jangan sampai menjadi candu yang meninabobokan rakyat di tengah ketidakadilan. Jangan sampai nangka yang direbus terlalu lama itu hancur menjadi bubur yang tak berdaya, kehilangan tekstur perlawanan, dan hanya menyisakan rasa manis yang semu di lidah penguasa.”
III. Gado-Gado: Manifestasi Pluralisme dan Dialektika Ruang
Gado-Gado adalah potret paling jujur dari demokrasi kita. Ia adalah pertemuan dari berbagai fragmen yang berbeda—sayuran hijau yang segar, tahu-tempe yang bersahaja, kentang yang padat, dan saus kacang yang menyatukan segalanya.
Gado-Gado adalah Heterotopia di atas piring. Setiap elemen di dalamnya tetap mempertahankan identitasnya masing-masing. Bayam tetap bayam, tauge tetap tauge. Saus kacang itu adalah “Pancasila”—zat perekat yang mengubah perbedaan menjadi harmoni tanpa menghapus keunikan individu.
Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau tokoh-tokoh koalisi sering menyuarakan “Kebhinekaan yang menyatu”. Gado-Gado adalah koalisi besar yang harus memastikan setiap sayuran (partai) mendapatkan porsi saus (kekuasaan) yang adil tanpa menutupi rasa asli masing-masing.
Kritik oposisi menyerang dari sudut “Kerapuhan Persatuan”. Mereka berujar: “Demokrasi Gado-Gado kita hanyalah tumpukan sayuran yang dipaksa bersatu oleh siraman saus pragmatisme. Ketika sausnya hambar (tak ada ideologi), maka sayurannya akan tercerai-berai, saling busuk dalam perbedaan, dan hanya menyisakan sisa-sisa yang dibuang ke tong sampah sejarah.”
IV. Alkimia Rasa dalam Lensa Nobelis
Para pemenang Nobel mengingatkan kita bahwa keutuhan manusia tercermin dalam piringnya:
Pablo Neruda (Nobel Sastra 1971): Mengingatkan bahwa makanan adalah cara bumi bicara pada manusia [4]. Rendang, Gudeg, dan Gado-Gado adalah dialek-dialek kejujuran tanah air kita.
Amartya Sen (Nobel Ekonomi 1998): Menegaskan bahwa demokrasi yang gagal memberi makan rakyatnya dengan keberagaman rasa adalah demokrasi yang cacat secara moral [5].
Epilog:
Meja Makan sebagai Sajadah Kebangsaan
Indonesia adalah perjamuan yang tak pernah usai. Kita sedang “memasak” masa depan kita sendiri. Jogja yang Overload, Bali yang Sepi, dan Sumatera yang Banjir, semuanya bermuara pada satu meja makan demokrasi. Kita adalah bangsa yang sedang belajar bahwa untuk menjadi “Istimewa”, kita harus berani digodok oleh waktu, berani dicampur dalam perbedaan, dan berani tetap pedas dalam memegang prinsip.
“Demokrasi yang sejati tidak ditemukan dalam debat di televisi, melainkan dalam kerelaan kita berbagi piring yang sama, meski lidah kita mengecap rasa yang berbeda-beda. Karena di hadapan lapar, kita semua adalah satu; di hadapan rasa, kita semua adalah hamba.”
***
Catatan Kaki
[1] Konsep “Resiliensi Rendang” merujuk pada ketahanan protein melalui karamelisasi suhu rendah, metafora ketahanan mental masyarakat Minangkabau.
[2] Memayu Hayuning Bawana merupakan prinsip kosmologi Jawa untuk memperindah dunia melalui harmoni manusia, alam, dan Tuhan.
[3] Konsep Heterotopia Michel Foucault menggambarkan ruang fisik yang menampung elemen-elemen berbeda secara ontologis.
[4] Merujuk pada Odas Elementales, di mana objek harian dipandang sebagai representasi martabat.
[5] Capability Approach Sen menekankan hak atas gizi dan keragaman pangan sebagai fondasi kebebasan.
Rujukan Ilmiah
Anderson, Benedict. (1983). Imagined Communities. London: Verso.
Foucault, Michel. (1967). Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias.
Lévi-Strauss, Claude. (1964). The Raw and the Cooked. New York: Harper & Row.
Sen, Amartya. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
———-
*Gus Nas Jogja, budawayan.