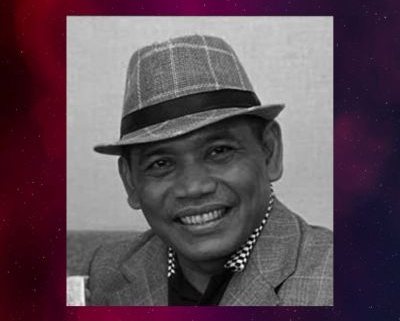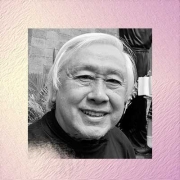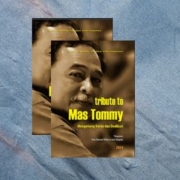Keistimewaan Yogyakarta dalam Epistemologi Sabda Raja: Krisis Laku dan Legitimasi
Oleh: Gus Nas Jogja*
Yogyakarta, sebuah entitas yang secara fundamental kontra-yuridis terhadap doktrin demokrasi mutlak di Indonesia, adalah sebuah parabel eksistensial yang berhasil dilegitimasi oleh sejarah. Kedaulatannya bersandar pada Undang-Undang Keistimewaan (UUK DIY) No. 13 Tahun 2012—sebuah Konsensus Agung yang secara formal mengangkat Paugeran Adat (sumber Adat Recht) menjadi prasyarat bagi jabatan Gubernur (representasi Positive Recht).
Namun, konsensus ini goyah oleh Sabda Raja 2015. Tindakan Sultan Hamengku Buwana X, yang mengubah Paugeran patrilineal, bukan sekadar keputusan internal; ia adalah retakan epistemologis yang menguji fondasi filosofis Keistimewaan. Pertanyaannya: Ketika Subjek (Sultan/Gubernur) yang diangkat oleh Struktur (Paugeran/UUK DIY) justru menghancurkan struktur itu sendiri, akankah legitimasi ganda ini tetap tegak, ataukah ia akan runtuh, meninggalkan fragmen feodalisme telanjang?
Esai ini akan meninjau krisis ini melalui Filsafat Hukum Mataram, menimbang Sabda Raja dengan neraca Nitipraja (Hukum Tata Negara) dan Sabdatama (Filsafat Moral Spiritual) yang diwariskan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Tujuannya adalah untuk memahami apakah Paugeran yang baru ini adalah Evolusi Laku yang sah, ataukah Destruksi Struktural yang fatal.
Historiografi Kraton dan Dualisme Teks: Dari Giyanti ke Piagam, Kontrak Kultural dan Politik
Historiografi Kraton adalah rangkaian panjang kontrak. Perjanjian Giyanti 1755 adalah kontrak pertama: membagi kedaulatan Mataram dan menetapkan Paugeran Patrilineal sebagai hukum yang menang untuk menjamin stabilitas Dinasti Hamengku Buwana. Paugeran, sejak saat itu, menjadi Struktur Apriori—teks abadi yang mendefinisikan siapa yang boleh menafsirkan Jagad Gumelar (tatanan semesta).
Kontrak kedua yang paling krusial terjadi pada 19 Agustus 1945. Melalui Piagam Kedudukan, Sultan HB IX melakukan aksi eksistensial tertinggi: melepaskan kedaulatan absolut takhta feodal, memilih menjadi Abdi Rakyat dalam bingkai Republik.
Inilah yang melahirkan identitas ganda Sultan yang diakui UUK DIY: Sultan Adat (pemegang Adat Recht) dan Gubernur Republik (pemegang Positive Recht). Krisis Sabda Raja terletak pada diskontinuitas ini: Sultan baru, yang lahir dari Paugeran yang diubah, dituding tidak memiliki identitas tunggal yang sama dengan Sultan yang menandatangani Piagam 1945.
Ekosistem Kebudayaan Jawa: Panggung Nitipraja dan Sabdatama
Nitipraja adalah Hukum Keteraturan dan Kritik Tata Kelola, sedangkan Sabdatama adalah ucapan mulia seorang Raja. Untuk menguji legalitas tindakan Raja, kita harus kembali ke Nitipraja. Karya Sultan Agung ini adalah cetak biru Tata Kelola Kelembagaan yang menekankan bahwa legitimasi Raja harus dibuktikan melalui kemampuan mewujudkan adil dan bener dalam penyelenggaraan negara.
Sultan Agung menegaskan kewajiban Raja terhadap Nitipraja:
“Sang Nata kudu nindakake adil lan bener, amarga adil iku lampahing negara, lan bener iku dhasaring paugeran.”
(Sang Raja harus bertindak adil dan benar, karena adil itu adalah jalannya negara, dan benar itu adalah dasar dari paugeran.)
Dalam konteks modern, adil dan bener dalam tata kelola birokrasi diterjemahkan menjadi transparansi dan akuntabilitas.
Pelanggaran Nitipraja dalam Danais. Polemik Dana Keistimewaan (Danais) adalah bukti pelanggaran prinsip Nitipraja. Danais adalah uang publik yang harus tunduk pada Positive Recht (UU Keuangan Negara), tetapi ia dikelola dengan kritik glondhongan (tanpa nomenklatur, SOTAKER Keraton/PA, dan audit yang memadai). Kegagalan ini menunjukkan inkonsistensi struktural yang melemahkan keistimewaan.
Kegagalan untuk menuntaskan Perdais Pasal 43 UUK DIY adalah bentuk pembangkangan yuridis terhadap Nitipraja. Perdais seharusnya menjadi mediator yang secara hukum menetapkan SOTAKER Keraton agar Danais yang merupakan implementasi Tahta untuk Rakyat dapat diaudit dan akuntabel. Ketiadaan Perdais membuat Sultan/Gubernur secara struktural melanggar Nitipraja (keteraturan yuridis), bahkan saat ia berjuang untuk laku spiritual (Sabda Raja).
Sabdatama: Filsafat Laku, Pamrih, dan Pergolakan Sayyidin Panotogomo
Gelar Sayyidin Panotogomo Khalifatullah menuntut Sultan melakukan laku (perbuatan spiritual) yang sejati. Di sinilah Sabdatama—kitab moral Mataram—digunakan untuk menguji motivasi Raja. Sabdatama membedakan antara laku sejati (tujuan mulia) dan pamrih (kepentingan pribadi atau ambisi).
Sultan Agung mengingatkan tentang bahaya pamrih ketika seorang Raja mengubah tatanan:
“Paugeran iku saka Gusti, nanging tatanan iku saka Nata. Yen Nata ngowahi paugeran, kudu kanthi laku kang sejati, ora mung amarga pamrih.”
(Paugeran itu dari Tuhan, tetapi tatanan itu dari Raja. Jika Raja mengubah paugeran, harus dengan perbuatan yang sejati, tidak hanya karena kepentingan pribadi.)
Sabda Raja dapat diinterpretasikan sebagai keberanian eksistensial untuk menafsirkan Tatanan (Hamemayu Hayuning Bawana) demi kesetaraan gender. Ini adalah laku sejati yang sejalan dengan semangat Sabdatama dan Tahta untuk Rakyat. Namun, karena perubahan Paugeran ini secara implisit membuka jalan bagi suksesi putrinya, ia rentan dituding sebagai aksi yang didorong pamrih (kepentingan mewariskan jabatan Gubernur dengan Danais), yang secara spiritual melukai Sabdatama.
Semiotika dan Eksistensi: Dekonstruksi Tahta untuk Rakyat
Penolakan Paugeran baru seringkali menggunakan narasi spiritual Union Kosmis –hubungan Sultan-Ratu Kidul, sebagai basis. Tudingan bahwa Sultanah tidak dapat menjadi pasangan Ratu Kidul adalah bukti ketidakmampuan memahami Semiotika Jawa .
Tindakan Sayyidin Panotogomo dalam Sabda Raja adalah pemurnian spiritual yang radikal. Ia menanggalkan tafsir literal-patriarkis Union Kosmis dan kembali ke esensi metaforis perkawinan prinsip. Sultanah — Feminim Duniawi, menjalin Union Prinsip yang setara dengan Ratu Kidul — Feminim Kosmis, bertujuan untuk harmoni dan kesuburan yang lebih inklusif. Secara spiritual, ini adalah laku yang sah dan progresif.
Tahta untuk Rakyat: Semiotika yang Terancam Reduksi
“Tahta untuk Rakyat” adalah revolusi semiotika terbesar (Poin 3.1) yang mengubah Tahta –simbol absolut, menjadi medium pelayanan. Namun, semiotika mulia ini terancam reduksi:
1. Reduksi Yuridis: Kekaburan Danais (Poin 3.2) mereduksi Tahta untuk Rakyat menjadi Tahta untuk Transaksi, mencoreng laku sejati.
2. Reduksi Eksistensial: Kritik terhadap suksesi putri sebagai pamrih mereduksi Tahta untuk Rakyat menjadi Tahta untuk Dinasti, mengkhianati Sabdatama.
Sabda Raja, yang merupakan aksi eksistensial yang mulia (kesetaraan), kini terjerat dalam krisis struktural dan etis (Danais dan pamrih) yang mengancam meruntuhkan seluruh semiotika keistimewaan.
Paugeran dan Kehendak untuk Lestari
Paugeran, sumber Adat Recht yang diakui UUK DIY, kini berada di persimpangan jalan: Di satu sisi didorong oleh Evolusi Etis — Sayyidin Panotogomo, di sisi lain terancam oleh Kekosongan Struktural (Ketiadaan Perdais).
Jika Paugeran (sumber adat) dianggap cacat dan Nitipraja (hukum negara) diabaikan –melalui non-transparansi Danais, maka Nomokrasi akan menuntut haknya secara penuh. Resistensi Demokrasi akan memuncak, dan ancaman pencabutan UUK DIY akan menjadi keniscayaan filosofis, mengubah Yogyakarta menjadi provinsi biasa.
Langkah politik yang paling sunyi dan wening adalah memenuhi kewajiban Nitipraja dan Positive Recht: Segera menuntaskan Perdais Pasal 43 UUK DIY. Perdais adalah instrumen yuridis-struktural yang akan:
1. Melegitimasi Adat Recht yang Baru: Secara resmi mengesahkan Paugeran yang inklusif gender di mata hukum Republik.
2. Memenuhi Nitipraja: Memastikan tata kelola Danais transparan dan akuntabel.
Hanya dengan menyelaraskan Spiritualitas Sabdatama dengan Struktur Nitipraja, Kanjeng Ratu dapat menjadi simbol Evolusi Paugeran yang sah, dan Keistimewaan Yogyakarta dapat berdiri tegak, lestari, dan berintegrasi penuh dalam bingkai Republik Indonesia.
Wallahu A’lam.
***
Rujukan Ilmiah
UUK DIY No. 13/2012, Pasal 43: Hukum positif yang mengikat Paugeran Adat (sumber Adat Recht) pada jabatan Gubernur.
Sultan Agung Hanyokrokusumo: Raja Mataram ketiga, arsitek kebudayaan Jawa; pencetus karya-karya filosofis-yuridis Nitipraja dan Sabdatama.
Nitipraja dan Sabdatama (Manuskrip): Sumber utama Filsafat Hukum Mataram. Nitipraja fokus pada tatanan negara dan keadilan, sementara Sabdatama fokus pada etika, laku, dan spiritualitas Raja.
Sayyidin Panotogomo Khalifatullah: Gelar Sultan yang memiliki dimensi teologis, menempatkannya sebagai penafsir Tatanan (Jagad Gumelar) di bumi.
Filsafat Eksistensial (Sartre) dan Struktural (Foucault): Digunakan untuk menganalisis konflik antara laku subjek (Sabda Raja) dan struktur yang mengikat (Paugeran lama).
Konsep Hamemayu Hayuning Bawana: Prinsip tertinggi dalam etika Jawa, menjadi justifikasi filosofis bagi setiap tindakan Raja.
Mal Administrasi Negara dan Good Governance: Prinsip akuntabilitas publik yang dilanggar oleh ketiadaan Perdais dan transparansi Danais.
Union Kosmis/Semiotika Jawa: Interpretasi hubungan Sultan-Ratu Kidul sebagai penyatuan prinsip kosmis (Maskulin-Feminim), bukan biologis (Van Vollenhoven, Anderson).
—-
*Gus Nas Jogja, budayawan.