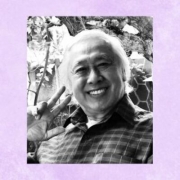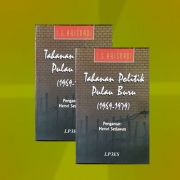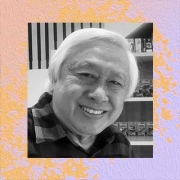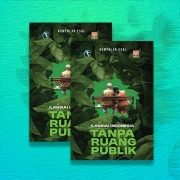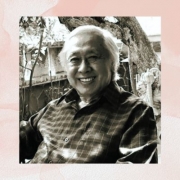Antara Istana dan Jalanan: Seni Melawan Dinasti dan Masa Depan Indonesia
Oleh: Hadi Aktsar*
Jika Niccolò Machiavelli hidup di Indonesia hari ini, mungkin saja ia akan duduk santai sambil menyeruput espresso di sebuah warung kopi di bilangan Harmoni, Jakarta, tersenyum tipis sambil memandang ke arah Istana Merdeka. Bukan karena kagum atau bangga, tapi karena segala strategi kekuasaan yang ia tulis dalam “The Prince” lima abad lalu benar-benar terjadi di Nusantara modern. Ia menyaksikan betul bagaimana kekuasaan dirawat, diwariskan, bahkan dipertahankan dengan segala cara: tersaji di depan mata, tanpa harus menjadi seorang staf ahli istana. Dinasti politik Indonesia hari ini telah menjadi pertunjukan terbuka, bukan lagi intrik tersembunyi di balik tirai kekuasaan, melainkan tontonan sehari-hari yang disajikan gratis kepada rakyat dengan penuh percaya diri.
Jejak Panjang Politik Dinasti: Dari Soeharto, SBY, hingga Jokowi
Dalam The Prince, Machiavelli berkata: “Siapa pun yang merebut kekuasaan harus segera menciptakan sistem yang membuatnya sulit digulingkan.”
Di Indonesia, kalimat ini menemukan relevansinya semenjak 32 tahun Soeharto berkuasa. Soeharto mungkin saja menjadi sosok pertama yang benar-benar membangun dinasti politik dengan kesadaran penuh: mengakar di birokrasi, militer, dan ekonomi, menjadikan nama Cendana sebagai simbol kekuasaan yang hampir mustahil digoyang. Anak-anak Soeharto duduk di kursi bisnis strategis, teman dekat menguasai perusahaan negara, dan loyalis disebar di seluruh lapisan birokrasi. Rakyat dibuat bungkam, asal perut mereka tak pernah lapar.
Reformasi 1998 memang berhasil meruntuhkan singgasana Soeharto, tetapi tidak meruntuhkan budaya dinasti. Dalam era demokrasi elektoral, keluarga politik menemukan cara baru untuk bertahan: melalui partai, jaringan bisnis, dan citra. Dengan gaya demokratis, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian membangun dinasti politik Cikeas, dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pewaris yang dipersiapkan secara sistematis melalui partai Demokrat.
Kini Jokowi, yang awalnya dielu-elukan sebagai presiden yang pro rakyat, pelan tapi pasti juga membangun panggung politik untuk Gibran Rakabuming Raka, yang dalam waktu singkat berhasil menduduki kursi calon wakil presiden dan menjadi bagian dari jantung kekuasaan nasional. Naiknya putra sulung Jokowi sebagai wakil presiden bukanlah sekedar kebetulan atau “kemauan rakyat” seperti yang diklaim oleh para pendukungnya. Jokowi yang lahir sebagai sosok di luar lingkaran oligarki, justru berhasil membangun politik dinasti di tengah sistem demokrasi prosedural. Jika sejarah mengajarkan sesuatu, maka ia mengajarkan bahwa kekuasaan cenderung diwariskan seperti harta pusaka. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia, yang meski menganut demokrasi elektoral, masih sangat rentan terhadap oligarki keluarga. Politik kerap menjadi ruang tertutup yang hanya dapat diakses oleh mereka yang “dekat dengan lingkar kekuasaan.”
Machiavelli, dalam The Prince, pernah menulis: “It is much safer to be feared than loved when, of the two, either must be dispensed with.” Kekuasaan, dalam logika Machiavelli, bukan tentang cinta rakyat atau keadilan moral. Ia adalah tentang kemampuan menciptakan stabilitas, atau setidaknya ilusi tentang stabilitas, agar kekuasaan terus berlangsung. Maka dinasti politik bukanlah sekadar strategi keluarga, melainkan instrumen mempertahankan pengaruh dalam jangka panjang. Tidaklah berlebihan jika hari ini kita patut bertanya: Apakah Prabowo, setelah dilantik sebagai presiden, akan melanjutkan tradisi ini? Apakah kekuasaan akan kembali menjadi milik keluarga dan lingkaran dalam, atau akan memberi ruang baru bagi rakyat untuk menentukan masa depannya?
Ketika Rakyat sudah Mulai Lapar: Dari Demo di Jalanan hingga Seni Akar Rumput
Ketegangan antara penguasa dan rakyat semakin menguat sejak Agustus 2025. Dari Pati, Jawa Tengah, bara api keresahan wong cilik mulai menyala. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat pascapandemi memicu gelombang demonstrasi besar-besaran. Dalam hitungan hari, protes menyebar ke berbagai kota: dari Medan hingga Makassar, dari kampus-kampus hingga desa-desa. Demonstrasi ini bukan hanya tentang pajak, tetapi tentang perasaan yang dikhianati. Rakyat merasa Negara lebih sibuk melayani agenda elite ketimbang mendengar suara yang paling lirih.
Tak lama setelah itu, pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa muncul kegelisahan baru. Di satu sisi, banyak masyarakat yang mendukung langkah Prabowo, terutama mereka yang merasa Sri Mulyani sudah terlalu lama menjabat dan perlu regenerasi. Purbaya adalah teknokrat baru, wajah segar yang “bersih”, dan punya rekam jejak di bidang ekonomi. Di sisi lain, Sri Mulyani punya reputasi kuat melawan praktik rente, mafia anggaran, dan kebijakan fiskal yang hanya menguntungkan segelintir elite. Tanpa dirinya, kelompok bisnis besar yang punya kedekatan politik mungkin lebih mudah melobi kebijakan pajak, subsidi, atau insentif yang lebih menguntungkan mereka. Pihak-pihak yang mendorong narasi populis (misalnya saja “bebaskan rakyat dari pajak yang mencekik”) bisa merasa lebih diuntungkan tanpa sosok seketat beliau.
Sebagai seorang pengamat budaya, saya melihat demonstrasi dan penjarahan rumah-rumah para pejabat yang terjadi akhir-akhir ini tidak semata-mata sebagai peristiwa politik. Ia adalah ritual perlawanan. Rakyat menyalurkan kemarahan dan kekecewaannya dengan cara-cara simbolik sebisa mereka: turun ke jalan, menyanyikan yel-yel, membawa spanduk dengan kata-kata sarkastik, menolak tunduk pada narasi resmi negara. Demonstrasi, seperti dalam sejarah Indonesia, sering kali lahir dari ketegangan kultural yang lebih dalam, bukan sekadar kebijakan teknis fiskal. Ia lahir dari jurang antara kehidupan sehari-hari rakyat kecil yang berjuang dibawah teriknya Matahari dengan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat dari kursi-kursi empuk dengan ruang berpendingin udara di Senayan.
Dalam situasi ini, kebijakan prioritas pemerintahan baru menjadi sorotan tajam. Salah satu program unggulan Prabowo adalah “Makan Bergizi Gratis,” sebuah program dengan niatan mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Tetapi niatan baik tidak selalu bertemu dengan kenyataan yang baik. Di lapangan, implementasi program ini tersendat oleh infrastruktur distribusi yang buruk, anggaran yang membengkak, dan birokrasi yang tidak siap. Efisiensi anggaran menjadi mantra pemerintah, tapi efisiensi tanpa keberpihakan sosial hanyalah cara elegan untuk mengabaikan kelompok yang paling rentan.
Saya tidak meragukan niat baik pemerintah. Tetapi jika Negara sungguh ingin membangun masa depan bangsa yang lebih baik, mengapa tidak dimulai dari hal yang lebih fundamental: meningkatkan kesejahteraan guru, memperkuat kompetensi para pendidik, dan memastikan akses pendidikan gratis serta fasilitas pendidikan yang merata dari Sabang sampai Merauke? Generasi emas Indonesia tidak akan pernah lahir hanya dengan perut kenyang, tetapi dengan akal sehat dan daya kritis yang tumbuh dari pendidikan yang adil dan bermutu.
Dalam kondisi sosial-politik yang rapuh ini, saya teringat pada Giovanni Boccaccio, seorang pemikir dan sastrawan Italia abad ke-14. Dalam karyanya yang monumental, “Decameron“, Boccaccio menunjukkan bagaimana rakyat kecil bertahan dari krisis—wabah Black Death, tekanan politik, dan ketidakadilan—melalui cerita dan seni. Ia menulis: “Art and stories are the only shelters left to humankind when power forgets its people.” Boccaccio tidak sedang meromantisasi keadaan. Ia sedang menggambarkan kenyataan bahwa kebudayaan rakyat adalah benteng terakhir ketika negara gagal melindungi warganya.
Hal yang sama kita lihat hari ini di Indonesia. Ketika Negara semakin jauh dari suara rakyat, para seniman akar rumput—dari lantunan puisi para penyair di kampung, lukisan mural di jembatan kota hingga kelompok teater desa, dari musisi jalanan, hingga pelaku tari tradisi—masih menjadi penjaga bara kesadaran kolektif. Mereka mungkin tidak punya panggung besar atau dana melimpah, tetapi karya-karya merekalah yang berbicara paling jujur tentang ketimpangan, kemarahan, dan harapan. Sayangnya, meski Dana Abadi Kebudayaan telah dianggarkan, akses terhadap sumber daya ini masih terkonsentrasi pada elite budaya dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Seniman akar rumput seringkali hanya menjadi penonton dari kebijakan budaya yang seharusnya mereka nikmati.
Kebudayaan, seperti yang diyakini para pemikir humanis Renaisans, bukan sekadar hiasan negara. Ia adalah jantung dari sebuah peradaban. Dante Alighieri pernah mengangkat bahasa lokal Italia sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni Latin. Boccaccio mengangkat cerita rakyat sebagai cara melawan ketakutan dan ketidakadilan. Hari ini, di Indonesia, seniman-seniman lokal memegang peran serupa: menjaga jiwa bangsa ketika negara sibuk dengan tubuhnya sendiri.
Trump, BRICS, dan ASEAN: Taring Indonesia di Kancah Global
Sementara itu, peta politik global juga bergerak cepat dan tak kalah berbahaya. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dengan agenda “America First” membuka babak baru ketegangan geopolitik dunia. Kebijakan proteksionis dan nasionalismenya bisa berdampak pada rantai pasok global, arus investasi, hingga keamanan kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, langkah Indonesia bergabung dengan BRICS dapat dibaca sebagai upaya memperluas jejaring ekonomi-politik global di luar bayang-bayang Barat. Tetapi langkah ini tidak boleh berhenti pada diplomasi simbolik; ia harus diiringi dengan penguatan posisi strategis Indonesia di ASEAN.
Saya bersama 11 pemuda lain perwakilan Indonesia menghadiri YSEALI (Young South East Asian Leaders Initiative) Summit di Penang, Malaysia, pada awal September lalu. YSEALI Summit ini adalah sebuah program tahunan dari US Mission to ASEAN untuk memfasilitasi para tokoh penggerak dan pemimpin muda di Asia Tenggara untuk membicarakan, merumuskan lalu kemudian bersama-sama mencari solusi akan tantangan-tantangan regional di kawasan ASEAN. Selama summit berlangsung, saya bertemu dengan banyak anak muda hebat se-Asia Tenggara. Dari petani muda yang berhasil mengembangkan teknologi pangan di desa pelosok Filipina, pekerja sosial di Myanmar yang mengurus warga sipil akibat kudeta militer sejak 2021, hingga diplomat muda dari Timor Leste yang peduli tentang peningkatan digital literacy di daerahnya. Saya sadar, bahwa ternyata kita tidak pernah sendirian. Ada banyak komunitas, penggerak akar rumput dan tokoh-tokoh underrated di luar sana yang selama ini terus konsisten berjuang di jalannya masing-masing.
Pertanyaan besar yang menggantung adalah: Mungkinkah ASEAN suatu hari menjadi seperti Uni Eropa? Jawabannya mungkin tidaklah sesederhana itu. Tetapi Indonesia memiliki modal untuk memainkan peran kepemimpinan regional, asalkan berani melepaskan diri dari politik dalam negeri yang sempit dan memandang dunia secara lebih visioner. Machiavelli menulis: “The wise man does at once what the fool does finally.” Pemimpin yang cerdas adalah mereka yang tidak menunggu krisis datang, tetapi mengantisipasi perubahan sejak dini.
Awal September lalu, Media internasional memandang kemunculan Prabowo dalam foto sejajar dengan Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong Un secara kontras: media Cina menyorotnya sebagai simbol naiknya posisi strategis Indonesia di kancah geopolitik Asia, seolah menandakan kedekatan diplomatik dan potensi peran Indonesia dalam blok non-Barat; sementara media Jepang justru meng-crop foto tersebut, menghapus sosok Prabowo dan lebih menyoroti tiga pemimpin besar itu sebagai figur utama, mencerminkan prioritas geopolitik mereka sendiri. Kontras ini memperlihatkan bagaimana citra Indonesia di panggung dunia sangat bergantung pada framing media asing, bukan hanya pada kekuatan simbolik, tetapi juga pada seberapa jelas arah kebijakan luar negeri Indonesia ditunjukkan.
Narasi geopolitik pemerintahan Prabowo saat ini bergerak pada poros “kedaulatan strategis”, di mana Indonesia ingin tampil sebagai kekuatan mandiri yang tidak sepenuhnya berpihak pada blok Barat maupun Timur. Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, intensifnya hubungan dengan Tiongkok dan Rusia, serta retorika kemandirian pangan dan pertahanan menandakan keinginan untuk memperluas jejaring global tanpa kehilangan posisi sebagai pemimpin ASEAN. Namun, narasi ini juga sarat risiko jika tidak diimbangi dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberanian mengambil sikap jelas dalam isu-isu besar global seperti konflik Palestina, Ukraina, dan Laut Cina Selatan. Karena itu, dukungan publik seharusnya bukan berbentuk “mengamini” begitu saja, melainkan mengawal agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap berbasis pada kepentingan rakyat, bukan elit politik atau oligarki. Indonesia harus tetap menjadi jangkar stabilitas ASEAN, memanfaatkan BRICS untuk memperkuat posisi ekonomi Global South, dan menjaga keseimbangan diplomatik agar tidak terseret menjadi pion blok kekuatan besar.
Politik luar negeri yang kuat tidak akan bertahan jika politik dalam negeri rapuh. Demokrasi tidak akan berkembang jika diskusi hanya dimonopoli oleh elite. Dan di sinilah peran warga sipil, terutama anak muda, menjadi sangat penting. Dalam era media sosial, percakapan politik tidak lagi terbatas pada ruang parlemen atau meja redaksi. Ia sebaiknya juga tumbuh subur di warung-warung kopi, di Tiktok, di ruang-ruang seni komunitas. Inilah bentuk-bentuk perlawanan kultural yang mungkin tidak spektakuler, tapi tahan lama.
Epilog: Mengawal Demokrasi dari Warung Kopi
Demonstrasi memang penting, tetapi perlawanan kultural jauh lebih panjang napasnya. Ia membentuk opini, membangun kesadaran, dan menumbuhkan imajinasi politik yang lebih sehat. Seniman, aktivis, mahasiswa, dan warga biasa memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan diskursus politik yang kritis. Seperti Boccaccio yang menggunakan cerita untuk melawan keputusasaan, kita pun bisa menggunakan budaya untuk melawan apatisme.
Machiavelli memberi kita kacamata tajam untuk membaca kekuasaan apa adanya. Ia tidak membungkusnya dengan moralitas, tidak mengagungkan romantisme politik. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan akan selalu mencari cara untuk bertahan. Namun Boccaccio mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah segalanya. Ada dunia lain yang lebih dalam: dunia rakyat, dunia cerita, dunia kebudayaan. Dunia ini sering tak terlihat, tapi ia selalu ada, menjadi fondasi yang menopang sebuah bangsa.
Dalam konteks Indonesia hari ini, kedua pemikiran ini penting dibaca bersamaan. Politik dinasti akan terus ada. Manuver kekuasaan akan terus terjadi. Tapi rakyat tidak boleh diam. Seniman tidak boleh bungkam. Anak muda tidak boleh kehilangan ruang. Karena seperti kata Machiavelli, “The people are more stable than princes.” Dan seperti kata Boccaccio, “Stories survive longer than kings.” Kekuasaan akan datang dan pergi, tetapi cerita rakyat akan tetap hidup, diwariskan, dan menjadi kompas moral bangsa.
Kita tidak boleh menyerahkan masa depan sepenuhnya pada elit politik. Masa depan harus terus diperbincangkan, diperdebatkan, dan diperjuangkan: di jalanan, di ruang kelas, di sanggar tari, di studio musik, di setiap sudut warung kopi. Selama kita masih mau berbicara, bercerita, berkarya dan berpikir kritis, maka kekuasaan tidak akan pernah sepenuhnya menang.
Bekasi, 12 Oktober 2025
——
*Hadi Aktsar. Peneliti dan praktisi kebudayaan.