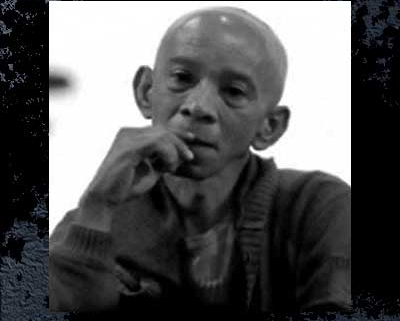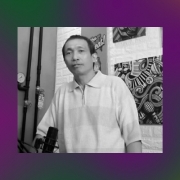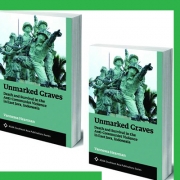“Seni-tersurat” dan “Penonton-tersirat”(Mau kemana Sumatera?)
Dari Festival Pekan Nan Tumpah VII – 2025
Oleh Afrizal Malna*
Saya menikmati dinamika penonton yang memenuhi Fabriek Padang, tempat dimana festival “Pekan Nan Tumpah ke VII” dibuka malam hari, 24 Agustus 2025. Mereka terus mengalir memasuki ruang bekas pabrik seng ini sejak sore hari. Sebagian besar mereka merupakan generasi dari kalangan Gen Z. Generasi yang ruang komunikasi dan informasi mereka total dibentuk dalam media sosial dan teknologi digital. Performa tubuh mereka merupakan update identitas melalui foto selfie maupun aksi dalam media sosial yang berlangsung terus-menerus, terutama Tik Tok dengan dramaturgi jaringan teknologi media. Hidup dengan latar performa kota yang ditandai oleh dramaturgi cahaya dalam dominasi lampu-lampu LED, sekaligus sebagai ikon kultur urban. Live, klik, action …
Dramaturgi ruang Fabriek Padang menghadirkan ruang sebagai tempat terbuka. Identitas ruang bergantung pada isi dan bagaimana isi itu dihadirkan. Begitu juga penonton dibiarkan menentukan dirinya sendiri dalam memilih peristiwa seni yang mau ditontonnya, dan memilih sendiri lokasi yang membuatnya merasa nyaman. Mereka bebas pergi kalau peristiwa seni yang ditontonnya dirasa tidak menarik, atau ada hal lain yang lebih menarik perhatian mereka. Mereka bebas ngobrol bahkan menerima telepon masuk saat pertunjukan sedang berlangsung.
Perubahan penonton seperti ini, dimana mereka tidak lagi bisa dipisahkan dari smartphone di tangan mereka, merupakan fenomena yang tampaknya tidak cocok lagi dengan konsep ruang seperti Taman Budaya. Karena konsep ruang Taman Budaya umumnya merupakan ruang yang mendikte penonton, bersama bentuk-bentuk pertunjukan yang memaksa penonton patuh pada ruang yang membelenggu kehadiran mereka.
Sebagian mereka nyatanya merupakan penonton yang tidak lagi menggunakan tubuh sebagai kesaksian pertama dari tontonan yang mereka tonton, walau tubuh mereka hadir dalam ruang tontonan. Karena nyatanya mereka menonton melalui kamera smartphone yang dibiarkan terus merekam apa yang mereka saksikan. Hasil rekaman ini kemudian akan menjadi banyak pecahan maupun fragmen-fragmen yang akan mereka posting satu-persatu melalui akun media sosial mereka. Menyaksikan sebuah pertunjukan, kini menjadi sama dengan menyaksikan ratusan smartphone yang hampir seluruh monitornya menyala merekam pertunjukan yang sedang berlangsung. Sebuah fenomena dimana penonton sebenarnya mulai menghadirkan teaternya sendiri di tengah sebuah pertunjukan yang sedang mereka tonton. Apakah yang bisa kita baca dari fenomena ini, serta pengaruh signifikannya dalam memandang seni pertunjukan masa kini?
Komunitas Seni Nan Tumpah sebagai penyelenggara festival “Pekan Nan Tumpah” ini tampaknya cukup menyadari perubahan performa penonton masakini itu. Karena itu festival dibuat seperti pasar terbuka dimana berbagai produk dihadirkan dalam peristiwa ini. Produk-produk yang bisa dikonsumsi hadir bersama dengan pameran, pertunjukan (teater, tari, musik, performance art, tradisi), buku, maupun kerajinan tangan. Di samping itu Komunitas Seni Nan Tumpah juga menjalin hubungan kreatif dengan generasi ini melalui berbagai workshop yang mereka selenggarakan di sekolah-sekolah tingkat SMA, terutama di Padang.

Penonton Pekan Nan Tumpah, 24 Agustus 2025. Foto: Afrizal Malna
Penonton yang tersirat dan seni terserah
Percakapan dimulai dari Azuza dan David. Mereka berdua merupakan peserta magang juga panitia dalam festival ini yang sering saya ajak ngobrol. Azuza berasal dari Pekanbaru, David dari Padang. Azuza sudah tidak tahu nama-nama Melayu klasik, begitu juga David sudah tidak tahu nama-nama Minang klasik. Tetapi keduanya bersemangat memberi tahu destinasi-destinasi wisata maupun tempat kuliner yang perlu dikunjungi. Salah satu di antaranya adalah restoran “Lamun Ombak”.
Kami bertiga menduga-duga makna “lamun ombak” sebagai ombak yang melamun, atau melamun di depan ombak, atau …. Ternyata keduanya salah. Edi Utama, sebagai pakar dan penggiat seni budaya Minang menjelaskan bahwa “lamun ombak” dalam konteks makanan merupakan metafor untuk sesuatu yang dianggap nikmat, seperti berada dalam gulungan ombak. Dalam konteks yang lain, ungkapan ini sama maknanya dengan “penderitaan yang panjang.
Edi Utama melanjutkan bahwa komunikasi dalam budaya Minang berada dalam dua tataran antara “yang tersurat” dan “yang tersirat” sebagai dua hal yang berbeda. Ketika saya mencoba menyampaikan hal ini kepada Mahatma Muhammad sebagai Direktur Festival Pekan Nan Tumpah, ia membenarkan pendapat Edi Utama. Apakah beda keduanya?
Menurut “AI Overview” dari pelacakan Google “tersurat dan tersirat” adalah:
“Tersurat berarti makna atau informasi yang dituliskan secara langsung, jelas, dan eksplisit dalam suatu teks, sehingga mudah dipahami pembaca. Sementara itu, tersirat merujuk pada makna atau informasi yang tersembunyi, tidak tertulis secara langsung, dan perlu disimpulkan atau ditafsirkan oleh pembaca berdasarkan konteks dan pemahaman menyeluruh terhadap teks tersebut.
Tersurat (eksplisit):
- Makna atau informasi langsung tertulis dalam teks.
- Mudah dipahami tanpa perlu penafsiran mendalam.
- Mengacu pada makna denotasi atau arti kata sebenarnya.
Tersirat (implisit):
- Makna atau informasi tersembunyi dan tidak ditulis secara langsung.
- Membutuhkan pemahaman dan penafsiran dari pembaca.
- Sering kali menggunakan makna konotasi, kiasan, atau simbol.
Contoh
Tersurat: Kalimat “Tempat tinggalku sangat menyenangkan” secara langsung menyatakan bahwa rumah tersebut adalah tempat yang menyenangkan.
Tersirat: Dalam puisi penggunaan “sambal tomat pada mata” tidak berarti sambal sungguhan, tetapi memiliki makna tersirat tentang rasa sakit atau pedih yang menetes.”
Mungkin penjelasan AI itu terlalu sederhana, namun cukup untuk kita bisa memiliki tatapan lain menghadapi frasa-frasa seperti “lamun ombak” ini.
Edi Utama dan Mahatma Muhammad adalah generasi yang berbeda, namun keduanya masih mewarisi model komunikasi tradisi Minang. Bahasa, ruang, maupun media yang membentuk mereka berdua masih sama. Yaitu bahasa Minang, ruang nyata, dan masih terhubung dengan media cetak. Tetapi generasi seperti David maupun Azuza adalah gen Z yang ruang dan medianya sudah berbeda, walau masih menggunakan bahasa Minang. Bahasa Minang yang satu merupakan bahasa yang masih merepresentasi kehadiran tubuh, sementara generasi kini sudah merepresentasi tubuh teknologi. Generasi dimana “yang-tersirat” kemungkinan besar tidak lagi hadir dalam ruang komunikasi mereka.
Menghadirkan pertunjukan tradisi (terutama musik dan tari) dalam festival ini, yang tidak melulu berbasis tradisi Minang, juga melahirkan respon penonton yang menarik untuk mengamatinya. Sore hari, 25 Agustus 2025, ada beberapa pertunjukan berbasis tradisi. Yang pertama, pertunjukan yang berangkat dari tradisi Mentawai (Komunitas Sinuruk Mattaoi), kemudian “Gemulai Harmoni Nusantara” dari SMK Negeri 4 Sijunjung. Ketika keduanya tampil bergantian, pagar yang membatasi penonton di dalam Fabriek Padang dan di luar, gambarannya mulai berubah. Beberapa pengendara motor mulai berhenti dan menonton suara-suara dari Mentawai, dari tradisi tarian Sunda, maupun suara dari pertunjukan Reog sebagai suara-suara yang non-Minang.
Bunyi-bunyian yang dihasilkan pertunjukan mereka telah menggoda para penonton di luar sana. Namun ketika pertunjukan berubah menjadi Tari Piring dari tradisi Minang (yang sudah menjadi rutin mereka dengar dan lihat), para pengendara motor itu kembali pergi melanjutkan perjalanan mereka.

Penonton dalam pameran Pekan Nan Tumpah. Foto: Dokumen Komunitas Seni Nan Tumpah
Keberagaman, perbedaan, bukan lagi merupakan order politik untuk identitas budaya. Fenomena ini sudah dengan sendirinya hadir dalam media sosial sebagai ruang nyata dimana generasi masa kini tumbuh bersamanya. Karena itu pendekatan wilayah sebagai pendekatan identitas budaya yang tunggal, bahwa Sumatera Barat total identik dengan Minang, bukan lagi kebijakan yang diorder oleh generasi masakini. Minangkabau hadir bukan karena ia mendominasi Sumatera Barat, melainkan karena ia dibiarkan tumbuh bersama dengan budaya-budaya lain yang saling berlintasan, saling mewarnai dan saling memperkuat satu sama lainnya. Fenomena seperti ini masih bisa kita saksikan di Sawahlunto sebagai fenomena budaya kreol. Budaya yang tumbuh dan berkembang melalui buruh-buruh tambang yang ikut membawa budaya asal mereka. Menghasilkan campuran baru sebagai budaya kreol sejak masa pertambangan batubara di masa kolonial, serta percampuran berbagai bahasa lokal yang kemudian disebut sebagai “bahasa tansi”.1
“Seni Terserah” sebagai kategori liar yang dipantulkan oleh kerja kuratorial festival ini (kurator: Nessya Fitryona, Jumaidil Firdaus, Angelique Maria Cuaca; dan Direktur Artistik Yusuf Fadly Aser), bisa menjadi awal terciptanya batas nol untuk memulai sesuatu yang lebih terbuka dalam menerima masadepan maupun menerima masalalu.
Seni terserah bisa menjadi tindakan anomali dalam menghadapi kekuasaan algoritma yang membentuk arah identitas kita. Tetapi juga bisa menjadi tindakan terbuka bahwa identitas bukanlah sebuah lanskap yang mempersempit ruang kerja budaya sebagai ruang monokultur. Melainkan sebagai ruang antar budaya dan sebagai lintas budaya; ruang pertemuan yang tidak terhindarkan saling membuat irisan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Pekan Nan Tumpah menyiapkan sejumlah diskusi, dialog, maupun workshop untuk bagaimana “seni terserah” menjadi tatapan praktik penciptaan dalam festival ini, dan diselenggarakan sebelum festival berlangsung. Hasil dari berbagai pertemuan ini kemudian mereka terbitkan sebagai sebuah buku “Sebelum Dunia Punya Istilah Kami Sudah Melakukannya di Halaman Rumah”. Buku yang tebal ini memuat banyak tulisan yang melibatkan nama-nama lintas disiplin seperti Adi Wicaksono, Agung Hujatnikajennong, Edy Utama, Hoirul Hafifi, Kusen Alipah Hadi, Nasrul Azwar, Rama Thaharani, maupun Yudi Ahmad Tajudin.
“Seni terserah” dalam festival ini menjadi tantangan baru tidak hanya dalam konteks kerja kuratorial festival Nan Tumpah, tetapi juga untuk penonton menemukan dirinya kembali sebagai orang lain, sebagai diri sendiri, sebagai masalalu, maupun sebagai lampu neon dalam perspektif “penonton tersirat”.
Bahwa di balik “penonton tersirat” ini ada sebuah kecemasan yang dirawat, terutama dalam kehidupan teater di Sumatera. Dalam sebuah laman, saya menemukan tulisan yang dibuat oleh Redaksi Marewai:
“Sudah hampir 6 tahun belakangan ini kelompok teater di Sumatera Barat mati suri, atau lebih tepatnya tidak ada lagi pertunjukan teater yang dihelat secara kolektif. Baik itu berbentuk Festival maupun berbentuk Temu teater ataupun acara bersama dari kelompok-kelompok teater yang ada di Sumatera Barat. Alek Teater yang dulu jadi wadah pekerja seni teater Sumatera Barat, enam tahun belakangan ini sudah tidak terdengar lagi di panggung utama teater Taman Budaya Sumatera Barat. Sepanjang tahun 2020 – 2021, yang tercatat aktif menampilkan pementasan hanya beberapa kelompok teater saja.”2
Pernyataan itu disampaikan untuk mengiringi sebuah workshop penyutradaraan dan dramaturgi di Taman Budaya Padang, Maret 2021, dengan narasumber Mahatma Muhammad, S. Metron, dan Dede Pramayoza. Mungkin dengan harapan workshop penyutradaraan dan dramaturgi ini bisa berkontribusi memecahkan masalah teater. Dalam laman yang lain, DNU menulis:
“Kurang lebih 10 tahun terakhir nyaris tak terdengar gaung aktivitas teater, teater hampir kehilangan gairah. Kalaupun ada paling hanya satu dua pertunjukan, dalam skala lokal satu dua kelompok berusaha untuk tetap menggeliat menunjukkan eksistensi, namun suasana semarak sebagaimana yang terjadi di masa pertengahan 1980-an hingga 1990-an tidak lagi dapat ditemui.” 3
Pernyataan ini dipantulkan dalam diskusi yang diselenggarakan Penastri (Perkumpulan Nasional Teater Nasional) di Gedung Kesenian Palembang, 29 Juni 2025, dengan pembicara antara lain Metron Masdison SS dan Ari Pahala.4

Pertunjukan tari Siska Aprisia. Foto: Dokumen Komunitas Seni Nan Tumpah.
Penonton gen Z mungkin tidak mengenal sama sekali ekosistem yang diresahkan oleh seniman-seniman teater di atas mereka, yang pernah dibesarkan oleh ekosistem media cetak maupun Taman Budaya. Kian menyurutnya kehidupan teater yang dicemaskan itu, mungkin juga merupakan representasi bahwa ekosistem teater maupun penonton teater sedang berubah. Maka, pantulan “seni terserah” dalam festival Pekan Nan Tumpah ini bisa dibaca sebagai sebuah tantangan baru untuk menemukan penonton tersirat dari dunia masa kini.
Indomie untuk semua rasa salah paham
“Saya tidak ingin tinggal di Padang. Sekarang saya tinggal di Yogya. Di sini tidak ada yang mengundang saya. Sebagai penari perempuan, di sini saya dipandang negatif, perempuan murahan,” kira-kira inilah yang muncul dari percakapan saya dengan seorang penari dan koreografer perempuan asal Padang, Siska Aprisia yang pernah pentas di Perancis maupun Jerman. Sebuah stigma terhadap dunia profesi tari untuk seniman perempuan yang sebenarnya khas patriarkis, tetapi ini justru berlangsung dalam budaya matrilineal Minangkabau.5 Memantulkan kemungkinan adanya arah yang sedang berubah dari budaya garis ibu ini. Dan berkelindan bersama dengan sejumlah hambatan untuk mengalami peristiwa seni sebagai produksi pengetahuan indrawi.
Kerja koreografi Siska juga sebenarnya bukan sesuatu yang asing untuk komunitas tradisi Minang, karena masih berpijak pada Ulu Ambek (salah satu jenis silat Minang). Pernyataan Siska itu terhubung dengan dua orang koreografer perempuan sangat terkenal yang juga berasal dari Sumatera Barat, yaitu Huriah Adam dan Gusmiati Suid. Keduanya meninggalkan Sumatera Barat dan berkarya di Jakarta. Keduanya pemberontak.
Padang bukan Yogyakarta, juga bukan Jakarta. Dan Pekan Nan Tumpah mungkin sedang membuat Padang yang lain. Pameran seni rupa yang jadi bagian utama festival ini, merupakan ruang yang selalu penuh oleh penonton setiap harinya. Awalnya hadirin, yang mayoritas datang dari kalangan gen Z, tampak datang untuk memang sekedar foto selfie. Tetapi kemudian mulai terjadi percakapan ringan, mulai ada pertanyaan kecil, mulai melihat adanya dunia yang berbeda. Dan inilah arti kehadiran sebuah pameran untuk penonton. Dalam katalog yang masih berupa format PDF, kita bisa menemukan profil program hingga profil karya seluruh seniman yang berpartisipasi dalam festival ini dari berbagai disiplin dan media.
“Seni terserah” mungkin bisa banal, liar, juga bisa lelah dan putus asa. Tetapi ia seperti sebuah awal tsunami: laut yang tiba-tiba dikosongkan, ikan-ikan di dasarnya menggelepar, lalu sekita datang gelombang tinggi yang menenggelamkan kota. Mungkin ini berlebihan, tetapi premisnya tidak berubah: “Apakabar Sumatera?” Masih ingat Tan Malaka yang ditembak, Hatta yang tersingkir, Sjahrir yang mati di negeri pengasingan, DN. Aidit yang ditembak mati, pemberontakan PRRI? Atau letusan gunung Toba purba, Krakatau, Tsunami Aceh, gempa Padang, dan juga Orangutan? Sitor Situmorang, Agam Wispi, Bachtiar Siagian, Basuki Resobowo yang tersingkir? (untuk menyebut beberapa nama). Walau Pekan Nan Tumpah tidak digagas sebagai representasi seni di Sumatera. Tetapi kerja kuratorialnya sangat menarik untuk dipantulkan ke dalam konteks ekosistem seni di Sumatera masakini.
“Kalau kamu paham semua ini, mungkin kamu salah paham” merupakan ungkapan yang mendasar dalam mempertanyakan memori Sumatera. Apakah ungkapan ini memang merupakan tema utama yang disodorkan dalam festival Pekan Nan Tumpah, yang uraiannya dibuat oleh Mahatma Muhammad? Saya kira tidak semata-mata begitu. Ini masih bagian dari lanskap berpikir model Minangkabau. Dalam program Nan Tumpah yang lain, juga digunakan frasa seperti “lain sakit lain diobat”. Sebuah model dialektika yang dilakukan justru untuk merayakan perluasan ruang berpikir, dan bukan untuk menemukan anti tesis. Atau sebaliknya sebagai ajang “silat lidah” di warung kopi.
Pertunjukan “Indomie rasa rendang” yang dipentaskan Komunitas Seni Nan Tumpah, membawa isu dimana “indomie” yang tidak datang dari Minang membuat irisan baru dengan rasa rendang. Produk yang pada gilirannya memantulkan tegangan sebagai reduksi budaya, manipulasi identitas kuliner, dan juga langkah memperluas pasar. Yang tersirat, yaitu identitas, adalah budaya-tak-benda yang tak bergerak; dan yang tersurat, yaitu indomie, terus melangkah untuk menguasai masa depan.
Panggung pertunjukan Komunitas Seni Nan Tumpah, yang penuh oleh benda-benda, aktor, multimedia, dan teknologi cahaya, tetap membuat pertunjukan sebagai sesuatu yang tersirat. Walau hampir semua benda yang dihadirkan di atas panggung dikenal oleh penonton sebagai gambaran ruang pabrik. Tetapi tetapi ada jarak yang dijaga antara penonton dengan pertunjukan. Penonton tidak bisa ikut masuk ke atas panggung dan mendekat ke arah aktivitas aktor. Juga tidak sebaliknya: benda-benda pertunjukan dan aktor turun meninggalkan panggung dan masuk ke ruang penonton.
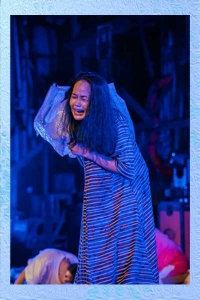
Pertunjukan Komunitas Seni Nan Tumpah. Foto: Dokumen Komunitas Seni Nan Tumpah
Membiarkan panggung sebagai sesuatu yang tersirat, dimana komunikasi tidak berlangsung berhadap-hadapan, mungkin bisa disebut sebagai bagian dari wabah kematian seni pertunjukan di masakini. Hal yang sama juga terjadi pada pertunjukan tari Siska Aprisia (“Lidah yang Tersangkut di Kerongkongan Ibu”). Pertunjukan Siska menghadirkan rumah terbuat dari bilah-bilah kayu dan bambu dengan halaman dalam dan halaman luar. Lantai halaman luar menggunakan bambu yang membuat tubuh Siska ikut bergerak, karena efek lenting dari bilah bambu. Dalam pertunjukan ini, penonton juga tidak diajak masuk untuk bisa merasakan ruang dalam rumah maupun lantai bambu di halaman luar rumah.
Material pertunjukan yang digunakan Komunitas Seni Nan Tumpah maupun yang digunakan Siska Aprisia sebenarnya sangat memprovokasi penonton untuk mengalami tekstur maupun berbagai sensasinya yang tersembunyi. Siska yang merepresentasi tubuh sebagai arsip dari pengalaman-pengalaman traumatik, penghakiman sosial, kekerasan domestik, dan yang paling depan menghadapi budaya patriarki, tetap membiarkan penonton sebagai subjek eksternal dalam eksklusivitas pengalaman yang justru sedang ditawarkan dalam pertunjukan.
Pertunjukan Arung Wardhana (“Chaos: metode riset artistik & autobiografi dalam performa yang terus menerus kandas”) seakan-akan hadir sebagai jawaban atas pertunjukan Komunitas Nan Tumpah maupun Siska Aprisia. Arung membuka pertunjukan di ruang dimana penonton hilir-mudik datang dan pergi. Ruang sirkulasi penonton berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya.
Pilihan ruang seperti itu membuat penonton gagal memahami bahwa sebuah pertunjukan sedang berlangsung. Arung terkesan mulai panik melihat penonton lewat begitu saja meninggalkan dirinya. Tujuh mikrofon telah disiapkan untuk penonton bisa curhat dan didengar oleh penonton. Tawaran yang sekali lagi membuat penonton gagal memahami bahwa sebuah pertunjukan sedang berlangsung. Karena membiarkan penonton masuk ke dalam ruang pertunjukan dan menggantikan aktor dan bicara menggunakan mikrofon, mungkin merupakan konvensi pertunjukan yang tidak umum untuk mereka.
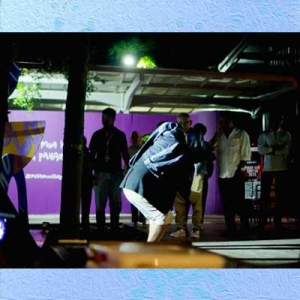
Pertunjukan Arung Wardhana. Foto: Dokumen Komunitas Seni Nan Tumpah.
Pertunjukan Arung diselamatkan oleh seorang penonton (ia mahasiswa) yang tiba-tiba sadar, lalu mengambil, menggunakan mikrofon, dan berteriak: “kampus taik!!!” – “Dosen taik!!!”, karena ia sudah datang untuk mengikuti ujian, tetapi dosen penguji membatalkannya dengan semena-mena. Seorang penonton lain, seorang suami, juga curhat. Ia menangis, air matanya membasahi pipinya. Penonton tercengang. Kemudian ia berteriak: “mintuo bangsat”, “tante bangsat”, sambil menghapus air matanya. Karena ia merasa lelah bekerja sepanjang hari, dan ketika pulang, selalu ditanya “kenapa belum punya anak?”
Penonton terkejut dengan dua pernyataan yang sangat pribadi yang justru datang dari penonton di dalam pertunjukan Arung itu. Kedua orang penonton itu telah membuat pertunjukan Arung Wardhana selamat. Dengan cepat Arung mengambil momen ini dan mulai menggulirkan agenda-agenda pertunjukannya. Namun di luar dugaan, dalam adegan ketika Arung berkali-kali membenturkan kepalanya ke cermin, seorang penonton perempuan menghentikannya. Penonton itu meminta Arung menghentikan kekerasan. Memaksa Arung berjanji untuk tidak melakukan kekerasan terhadap diri sendiri. Kemudian penonton itu memecahkan cermin yang digunakan Arung menjadi berkeping-keping.
Penonton ini saya kira merepukan representasi dari “seni terserah” sebagai tindakan anomali, dan “kalau kamu paham, mungkin kamu salah paham”. Frase ini pernah menjadi agenda utama yang diusung oleh Pop Art, terutama oleh Andy Warhol melalui karyanya yang menggunakan kaleng sup dan kardus bungkusan sabun. Karya untuk mengubah “seni tersirat” menjadi “seni tersurat” untuk premis “satu rasa untuk semua orang”.6 Seni tidak lagi serumit seni modern yang membutuhkan kritikus sebagai jembatan antara karya seni dan penonton. Seni hadir dalam hubungan langsung antara penonton dan karya. Maka wacana “salah paham” tidak lagi bermain dalam medan kebenaran seni, melainkan dalam medan “pasca-seni”.
Lewat pertunjukan Arung Wardhana, ruang pertunjukan mulai dihadirkan sebagai platform untuk penonton mementaskan narasinya sendiri. Dengan cara ini ruang pertunjukan menjadi inklusif, jarak antara penonton dan pertunjukan tidak ada lagi. Karena penonton menonton dirinya sendiri yang sudah tidak lagi menjadi dirinya, diri yang sudah menjadi tubuh publik, diri yang sudah menjadi tubuh tontonan. Dan ini bisa menjadi metode dimana pertunjukan merupakan platform untuk seseorang bisa keluar-masuk ke berbagai biografi, termasuk biografi dirinya sendiri, kemudian mengalami sejarah sebagai pengetahuan indrawi .
Masih banyak pertunjukan lain yang berlangsung dalam Pekan Nan Tumpah dari 24 sampai 30 Agustus 2025, di Fabriek Padang ini. Dan di luar sana, di beberapa kota: Makassar, Surabaya, Semarang, Palembang, Medan, Kediri, Yogyakarta, Solo, Lampung, Ternate, Bandung, Jakarta, kota-kota lain, demonstrasi mulai berlangsung. Korban mulai berjatuhan. Mereka membawa tuntutan “17+8” kepada DPR dan pemerintah. Dan aparat keamanan tetap bekerja dengan dramaturgi kekerasan yang sama yang sangat memalukan.***
—-
*Afrizal Malna, Penulis dan Pengamat Seni Pertunjukan
—–
1Lihat Dipna Videlia Putsanra: “Mengenal Bahasa Tansi Sawahlunto yang Jadi Warisan Budaya Tak Benda”, https://tirto.id/mengenal-bahasa-tansi-sawahlunto-yang-jadi-warisan-budaya-tak-benda-c9B9#google_vignette.
2Redaksi Marewai: “Teater Sumatra Barat Kembali Menggeliat; Catatan Workshop Teater UPTD Taman Budaya Sumatera Barat”, https://marewai.com/teater-sumatra-barat-kembali-menggeliat-catatan-workshop-teater-uptd-taman-budaya-sumatera-barat/.
3DNU: “Ekosistem Teater Sumatera Selatan di Ambang Mati: Siapa yang Bertanggung Jawab?” https://www.ketikpos.com/pariwisata-kebudayaan/95913021474/ekosi…er-sumatera-selatan-di-ambang-mati-siapa-yang-bertanggung-jawab.
4 Sebagai catatan, Sumatera memiliki beberapa festival seperti “Pekan Teater Sumatera” (Padang), “Festival Teater Sumatera” (Palembang), Pekan Apresiasi Teater (Padangpanjang), “Ajang Teater Sumatera” (Riau), maupun Pekan Nan Tumpah yang lebih bersifat lintas disiplin dan lintas media. Serta sejumlah kelompok maupun komunitas teater yang masih aktif dan banyak mengisi festival ini seperti: Teater Tonggak (Jambi), Teater Senyawa (Bengkulu), Teater Umak (Palembang), Suku Seni Riau (Riau), Komunitas Berkat Yakin – KoBER (Lampung), Komunitas Seniper Unimed (Sumatera Utara), Teater Dewan Kesenian Belitung (Bangka Belitung), Komunitas Seni Hitam Putih (Padangpanjang), Studi Teater (Palembang), Teater Tonggak (Jambi), Rumah Seni Glinyoeng (Aceh), Teater Dulmuluk Harapan Jaya (Palembang), Komunitas Seni Tanda Tanya (Aceh), Teater Oncak (Sumut), Teater Selembayung (Riau), Payung Sumatera (Sumatera Barat), Komunitas Seni Nan Tumpah (Padang Pariaman), Rumah Sunting (Pekanbaru), Medan Teater (Medan), Komunitas Seni Tanda Tanya (Nanggroe Aceh Darussalam), Teater Rumah Mata (Sumatera Utara), Teater Satu (Lampung), Dian Arza Art Laboratory (Lampung), Teater Art in Revolution – AiR (Jambi), Teater Sakata (Padangpanjang).
5Iva Ariani: “Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia)”, Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 1, Februari 2015.
6 Lihat Afrizal Malna: “Tragik Satu Rasa Untuk Semua-Aku, Esai-esai Senirupa”, basabasi, Yogyakarta, 2019.
——-