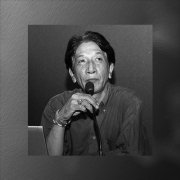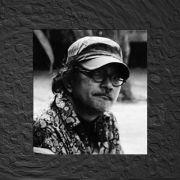Nasionalisme dalam Film Indonesia
Oleh Purnawan Andra*
Nasionalisme di Indonesia selalu hadir dalam bentuk yang berlapis. Ia bukan semata slogan politik atau ritual peringatan setiap Agustus, melainkan juga imajinasi kolektif yang diproduksi dan dinegosiasikan terus-menerus lewat budaya, termasuk film.
Sejak era awal perfilman, layar telah berfungsi sebagai cermin sekaligus laboratorium bagi identitas nasional. Dari propaganda kolonial hingga euforia pascakemerdekaan, dari film perjuangan era Orde Baru hingga kebangkitan sinema pasca-1998, nasionalisme selalu menemukan wajah barunya.
Kini, di tengah derasnya arus globalisasi digital, film Indonesia kembali ditantang: bagaimana menyampaikan gagasan kebangsaan tanpa terjebak pada retorika lama, melainkan dengan bahasa yang relevan untuk generasi kini?
Imajinasi Sosial
Jika menengok sejarah, film pertama yang sering dirujuk sebagai nasionalis adalah Darah dan Doa (1950) karya Usmar Ismail. Film ini bukan sekadar kisah Divisi Siliwangi, melainkan pernyataan bahwa bangsa Indonesia mampu bercerita dengan suaranya sendiri. Di film ini, nasionalisme dipresentasikan lewat narasi perjuangan bersenjata.
Pada era Orde Baru, film seperti Janur Kuning (1979) digunakan sebagai alat hegemoni politik, dengan nasionalisme dipersempit menjadi loyalitas tunggal terhadap negara. Film menjadi medium pedagogi ideologis. Namun setelah reformasi, ruang narasi menjadi lebih cair. Nasionalisme tidak lagi dimonopoli oleh negara, melainkan diproduksi secara plural oleh berbagai suara.
Di sinilah gagasan Arjun Appadurai tentang mediascapes dalam bukunya yang berjudul Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization (University of Minnesota Press, 1996) menjadi relevan. Appadurai memperkenalkan lima “landscapes” atau -scapes (ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, financescapes, ideoscapes) sebagai cara memahami arus globalisasi budaya.
Dalam hal ini mediascapes berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi gambar, narasi, dan media massa yang membentuk horizon imajinasi sosial. Menurutnya, media tidak sekadar menyebarkan informasi, tapi juga membentuk horizon imajinasi sosial.
Film Indonesia kontemporer menghadirkan nasionalisme bukan lagi sebagai ideologi tunggal, melainkan mosaik imajinasi yang beragam. Misalnya, film animasi Battle of Surabaya (2015) memperlihatkan pertempuran 10 November bukan sebagai cerita hitam putih, melainkan sebagai pengalaman kemanusiaan yang kompleks.
Nasionalisme di sini tidak hanya tentang heroisme, tetapi juga tentang luka, kehilangan, dan solidaritas lintas bangsa. Imajinasi ini penting, karena ia menggeser nasionalisme dari sekadar kewajiban politik menjadi pengalaman emosional yang lebih luas.
Citra Baru
Masuk ke dekade kini, film Jumbo (2025) menandai babak baru. Sebagai animasi Indonesia pertama yang menembus box office regional, Jumbo tidak mengangkat kisah perjuangan kemerdekaan, tetapi tema universal berupa harga diri, persahabatan, dan keberanian anak yang diremehkan.
Namun justru di situlah letak relevansinya. Nasionalisme hari ini bukan hanya mengenang masa lalu, melainkan membuktikan bahwa kita mampu berdiri setara dengan lainnya.
Keberhasilan Jumbo adalah bentuk lain dari kebanggaan kolektif. Bukan karena benderanya ditemukan dan atau dikibarkan di akhir cerita, melainkan karena kualitas artistik dan teknologinya diakui dunia.
Seperti kata Jacques Rancière dalam bukunya The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible (2004), politik seni terletak pada distribution of the sensible yaitu tentang bagaimana karya mengatur apa yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Jumbo mendistribusikan citra baru tentang Indonesia, dengan tidak lagi berada di pinggiran industri kreatif, tetapi telah menjadi bagian dari lingkaran utama.
Selain itu, film seperti Gundala (2019) karya Joko Anwar memperlihatkan bagaimana nasionalisme bisa dikaitkan dengan krisis kontemporer. Alih-alih sekadar meniru model superhero Barat, Gundala mengangkat isu ketidakadilan sosial, korupsi, dan rakyat kecil yang terpinggirkan. Nasionalisme di sini bukan slogan patriotik, melainkan solidaritas terhadap yang lemah.
Dengan bahasa budaya populer, film ini menawarkan moralitas politik yang lebih relevan dengan kondisi sosial Indonesia saat ini. Perspektif ini sejalan dengan gagasan Martha Nussbaum tentang capabilities yang menyatakan bahwa kebebasan sejati sebuah bangsa diukur dari sejauh mana warganya memiliki kapasitas hidup bermartabat. Film yang menyoal ketidakadilan adalah bagian dari proyek moral nasionalisme.
Menarik juga mencermati film dokumenter dan pendek yang mengusung isu lokal sebagai wajah kebangsaan. Misalnya, film The Seen and Unseen (2017) karya Kamila Andini yang menafsir ulang kosmologi Bali melalui relasi anak kembar, atau You and I (2023) karya Fanny Chotimah tentang persahabatan dua transgender tua di Bandung.
Meski tidak secara eksplisit berbicara tentang “Indonesia”, film-film ini menunjukkan wajah nasionalisme kultural, dengan keberanian mengakui keragaman, memberi ruang bagi yang terpinggirkan, dan menegaskan bahwa kebangsaan bukan hanya tentang mayoritas, tetapi juga tentang minoritas yang tetap jadi bagian dari diri bangsa. Inilah yang disebut Rancière sebagai politik egaliter yang menggeser batas siapa yang berhak tampil dan didengar.
Pembacaan Ulang
Konteks HUT RI hari ini menuntut pembacaan ulang. Nasionalisme yang relevan bukanlah semata mengulang kisah perang atau tokoh besar, melainkan kemampuan menghadirkan imajinasi kebangsaan dalam konteks sosial-ekonomi-politik mutakhir. Krisis iklim, migrasi tenaga kerja, ketidakadilan gender, hingga penetrasi budaya digital adalah isu yang membentuk realitas bangsa kini.
Film tari Mahendraparvata (2022), misalnya, mempertemukan penari Jawa dan Kamboja di situs warisan dunia, menegaskan bahwa nasionalisme tidak harus berarti isolasi, melainkan kemampuan berdialog dengan peradaban lain tanpa kehilangan akar. Ini sejalan dengan konsep Appadurai tentang cultural flows yaitu ketika nasionalisme justru hidup ketika mampu bernegosiasi dalam arus global.
Kita juga perlu menyadari bahwa film dapat menjadi arena kontestasi makna nasionalisme. Di satu sisi, ada produksi negara yang mencoba meneguhkan identitas resmi. Di sisi lain, sineas independen mengajukan narasi tandingan, dengan memaknai nasionalisme sebagai perjuangan melawan ketidakadilan sosial, perlawanan ekologis, atau perayaan tubuh minoritas.
Dialektika inilah yang membuat perfilman Indonesia kaya. Tidak ada satu wajah tunggal nasionalisme, melainkan beragam tafsir yang saling berdialog, bersaing, bahkan bertentangan. Dan justru dalam keberagaman itu, kebangsaan menemukan vitalitasnya.
Pada akhirnya, film Indonesia menunjukkan bahwa nasionalisme adalah proses yang tak pernah selesai. Ia bergerak dari layar ke ruang publik, dari festival ke media sosial, dari bioskop ke obrolan sehari-hari. Film adalah jendela, juga pintu yang membuka dunia baru tentang siapa kita, apa yang kita perjuangkan, dan bagaimana kita ingin dikenang.
Di tengah gempuran budaya global, film Indonesia tidak sekadar bertahan, tetapi juga menawarkan narasi alternatif tentang kebangsaan. Ia mengingatkan bahwa menjadi Indonesia bukan hanya soal bendera dan lagu, melainkan soal keberanian membayangkan masa depan yang lebih adil, beragam, dan bermartabat.
Film, dengan demikian, bukan hanya hiburan. Ia adalah kerja kultural yang memproduksi nasionalisme sebagai pengalaman estetik sekaligus etis. Dari Darah dan Doa hingga Jumbo, dari narasi perang hingga kisah fantasi animasi, layar lebar selalu menjadi medan di mana “diri” bangsa dipertaruhkan dan dipulihkan. Merayakan kemerdekaan melalui film berarti merayakan kemampuan kita untuk terus bercerita dengan diri, imajinasi, dan teknologi, bahwa kita ada, bergerak, dan terus hidup sebagai bangsa.
—-
*Purnawan Andra, bekerja di Kementerian Kebudayaan.