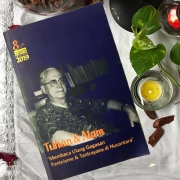Sutardji Calzoum Bachri: Antara Mantra dan Makna, Puisi dan Pembebasan Bahasa
Oleh Tengsoe Tjahjono*
Mukadimah: Dalam Napas Puisi, Sutardji Masih Bernyanyi
Pada tanggal 24 Juni 2025, Sutardji Calzoum Bachri genap berusia delapan puluh empat tahun. Usia yang tak hanya menandai panjangnya hidup biologis seorang penyair, tetapi juga ketahanan spiritual seorang peziarah bahasa yang tak pernah letih menafsir dan menyeberangi batas-batas diksi. Ia tidak sekadar bertahan, tetapi tetap bernyanyi dalam ritme puisinya sendiri—yang eksentrik, magis, kadang absurd, dan selalu orisinal. Ia tidak hanya masih hidup, tetapi hidup dalam puisi. Ia tidak hanya menulis, tetapi menubuh dalam puisi, menjelma tubuh bahasa yang merapal dan meronta, menari dan melawan.
Sutardji tidak menulis untuk menjadi dikenal, tetapi menulis agar kata kembali menemukan asal-usulnya. Ia hadir sebagai sabda yang mencipta, bukan sekadar menyampaikan. Ketika dunia hari ini dipenuhi dengan informasi yang deras dan instan, ketika algoritma dan kecerdasan buatan mulai menggantikan naluri rasa, Sutardji berdiri sebagai oase spiritual yang menawarkan keheningan dalam hiruk pikuk digital. Ia tetap percaya pada mantra. Bagi Sutardji, puisi bukanlah medium untuk menyampaikan pesan moral atau pengajaran sosial semata, melainkan wahana transendensi yang mengantar manusia pada yang purba dan puri: suara ilahi yang belum ternoda oleh struktur dan pengertian.
Dalam kredonya yang termasyhur, ia pernah menyatakan bahwa kata harus dibebaskan dari makna, sebab kata bukan alat tetapi makhluk. Dalam kerangka post-strukturalisme, kita bisa membaca ini sebagai usaha radikal untuk meruntuhkan hegemoni tanda atas makna—sebuah dekonstruksi terhadap relasi antara signifier dan signified sebagaimana dipahami Saussure. Sutardji menolak menjadikan bahasa sebagai alat komunikasi; baginya bahasa adalah tubuh yang hidup, yang bernyawa, yang menggeliat. Maka, dalam puisinya, kita temukan bukan narasi, tetapi suara. Bukan alur, tetapi getar. Bukan pesan, tetapi gema.
Lebih jauh lagi, dari perspektif teohumanistik, puisi Sutardji bukan sekadar permainan estetika atau eksperimentasi linguistik, melainkan bentuk doa, nyanyian suci yang berangkat dari dan menuju ke dimensi spiritual manusia. Ia percaya bahwa manusia adalah makhluk puisi, dan puisi adalah manifestasi terdalam dari kerinduan manusia pada asalnya. Dalam dunia yang makin menjauh dari keheningan batin, Sutardji menawarkan jalan pulang. Ia menolak tunduk pada zaman, tetapi memilih untuk menjadi suara yang menyela zaman.
Dan ketika kita membaca puisi-puisinya yang masih ia bacakan sendiri di berbagai perhelatan hingga usia senjanya, kita tidak hanya melihat seorang penyair yang gigih. Kita menyaksikan seorang pertapa bahasa, seorang dukun aksara, seorang nabi sunyi yang memanggil kita kembali kepada mantra yang menyembuhkan, kepada puisi yang membebaskan dari segala belenggu.
Sutardji masih bernyanyi, dan barangkali, selama bahasa masih mengalir di tubuh manusia, nyanyiannya tak akan pernah usai.
Sutardji dan Kredo Puisi: Puisi Sebagai Pembebasan Bahasa
Kredo Sutardji Calzoum Bachri, yang pertama kali dimuat dalam Horison edisi Desember 1974, merupakan tonggak revolusioner dalam sejarah perpuisian Indonesia modern. Pernyataan tegasnya, bahwa: “Kata-kata bukan untuk mengangkut makna. Kata harus bebas dari beban ide.” (Kredo Puisi, 1974) bukan hanya menantang konvensi sastra, tetapi juga mengguncang akar-akar epistemologis bahasa dalam puisi Indonesia. Kredo itu melepaskan kata dari fungsi komunikatif dan beban ideologisnya, mengembalikannya kepada asal-muasal magis dan spiritualnya sebagai mantra. Dalam hal ini, Sutardji bukan sekadar penyair, melainkan penyihir kata.
Mengapa kredo ini muncul? Secara historis, latar belakang kemunculannya dapat dibaca sebagai reaksi terhadap dominasi puisi sosial-politik yang sarat pesan moral pada dekade sebelumnya. Dalam arus besar sastra yang cenderung “membebani” puisi dengan tugas menyuarakan penderitaan rakyat atau memobilisasi ideologi, Sutardji justru memilih jalan sunyi: puisi sebagai ruang kebebasan kata dan pengalaman batin yang primordial. Ia menginginkan kata kembali seperti sebelum Adam menamai benda-benda—belum dibebani sistem makna, belum dicengkeram oleh gramatika kuasa.
Pendekatan ini sangat sejalan dengan prinsip post-strukturalisme. Jacques Derrida, misalnya, menegaskan bahwa makna selalu tertunda (différance) dan tidak pernah final atau stabil. Dalam konteks itu, ketika Sutardji menulis larik absurd seperti: “aku ke kau ke kau aku / akulah kauku kaulah ku ke kau” (Ana Bunga) ia sedang melakukan dekonstruksi terhadap fungsi representasional bahasa. Ia menggiring kata untuk menari di luar sintaksis yang lazim, membiarkannya mabuk dalam kekacauan musikal dan ritmis, sebuah bahasa Dionysian, kata Nietzsche—yang penuh gairah, irama, dan pengulangan-pengulangan magis.
Kebebasan kata seperti ini juga muncul dalam puisi “Belajar Membaca”, di mana kata-kata seperti “Kakikaukah Kakiku” dan “Lukakakukakiku Lukakakukakikaukah” menjadi semacam litani fonetik yang terus membangun ritme nyaris mistik:
“Kalau Lukaku Lukakau
Kakiku Kakikaukah
Kakikaukah Kakiku
Kakiku Luka Kaku”
Puisi ini tidak lagi bisa dibaca dengan pendekatan semantik tradisional, melainkan harus “didengar”—sebagai rapalan, sebagai mantra, sebagai suara tubuh kata itu sendiri. Inilah bentuk puisi yang tidak berorientasi pada pemahaman intelektual semata, tetapi pemahaman puitik yang bersifat intensional dan spiritual.
Dalam Kredo Puisi, Sutardji secara eksplisit menyatakan bahwa ia ingin “mengembalikan puisi kepada mantranya”, sebab mantra, menurutnya, adalah bentuk awal dari puisi. Ia pun tidak ragu merombak struktur konvensional puisi, memecah kata, memutar susunan sintaksis, bahkan menampilkan permainan visual dalam tipografi sebagaimana tampak dalam puisi “Tragedi Winka & Sihka”:
Bentuk puisi ini tersusun dari repetisi kata “kawin”, “winka”, dan “sihka” yang membentuk struktur menurun secara visual—seolah-olah membangun semacam totem fonetik yang menghunjam dan mengendap di bawah sadar pembaca.
Menurut kritikus sastra A. Teeuw, kredo Sutardji bukanlah bentuk nihilisme bahasa, melainkan justru upaya “menyelamatkan puisi dari kematian komunikasi semu” (Teeuw, 1980). Teeuw melihat keberanian Sutardji sebagai bentuk kontemplasi linguistik yang radikal, sebanding dengan puisi eksperimental Eropa dan Amerika Latin.
Sementara itu, Sapardi Djoko Damono menyebut puisi-puisi Sutardji sebagai “penjelajahan dalam wilayah arkais bahasa Indonesia” (Damono, 1983). Artinya, Sutardji menelusuri jejak bahasa sebelum ia menjadi bahasa dalam pengertian rasional dan modern. Ia menyentuh wilayah di mana kata-kata bukan lagi alat untuk menyampaikan makna, tetapi tubuh sakral yang memiliki getaran spiritual.
Dalam pendekatan teohumanistik, bahasa Sutardji dapat dibaca sebagai bahasa peralihan antara yang manusiawi dan yang ilahi. Kata menjadi jembatan antara dunia fana dan metafisika. Puisi, dengan demikian, adalah bentuk pemujaan. Maka dalam puisi “Mantera”, kita dapati larik-larik yang menjelma doa: “lima percik mawar / tujuh sayap merpati / sesayat langit perih / dicabik puncak gunung” (Mantera).
Larik-larik ini tidak bisa ditafsir secara harfiah. Ia mengundang pembaca untuk masuk ke dalam dunia tak sadar kolektif, tempat simbol-simbol spiritual bekerja tanpa mediator rasional. Puisi menjadi bentuk perjumpaan batin yang menggetarkan, bukan narasi yang mengajar.
Dengan kredo puisinya, Sutardji telah membuka ruang baru dalam sastra Indonesia—ruang yang mengakui bahwa bahasa bukan milik akal, tetapi milik tubuh, ritme, dan batin manusia. Maka tak heran jika puisi-puisi Sutardji bukan untuk dibaca dalam sunyi pustaka, melainkan untuk dilafalkan, digumamkan, dan bahkan dipanggil sebagai mantra zaman.
Tubuh dan Trauma: Puisi sebagai Tempat Luka Berdiam
Puisi-puisi Sutardji Calzoum Bachri bukan semata permainan bunyi dan struktur linguistik, melainkan saksi yang mendalam atas luka sejarah, luka sosial, dan luka eksistensial manusia Indonesia. Dalam puisinya, bahasa bukan hanya alat ekspresi estetis, melainkan tubuh yang menyimpan jejak penderitaan. Kata-kata menjadi reservoir air mata, dan puisi menjadi altar di mana trauma kolektif dikidungkan dengan gamang, getir, dan sekaligus penuh pengharapan.
Dalam sajak “Tanah Air Mata”, Sutardji menubuh sebagai saksi luka bangsanya:
Tanah airmata tanah tumpah dukaku
mata air airmata kami
airmata tanah air kami
Di sini, metafora “tanah air mata” menggantikan idiom “tanah air beta”. Penjungkirbalikan itu bukan tanpa maksud. Ia menegaskan bahwa nasionalisme sejati bukan dibangun dari jargon megah atau simbol formal seperti bendera dan lagu kebangsaan, tetapi dari derita kolektif yang diam-diam menyatu dalam tubuh rakyat: kaum tergusur, mereka yang hidup di pinggir, dan mereka yang ditelan sejarah diam-diam.
Puisi ini membuka ranah teohumanistik, karena air mata bukan sekadar reaksi psikis atas derita, tetapi bentuk sublimasi spiritual—jiwa yang menanggung tubuh, seperti Kristus yang menanggung salib. Dalam airmata, manusia dipertemukan dengan batasnya; dan justru di batas itu, ilahi hadir. Maka, puisi Sutardji menjadi semacam liturgi penderitaan yang membangkitkan kesadaran, bukan sekadar empati.
Lebih jauh, dalam puisi “Ayo”, Sutardji berbicara kepada penguasa dan militer, bukan dengan retorika propaganda, tetapi dengan bahasa air mata yang tak bisa dibungkam:
jangan kalian simbahkan gas airmata pada lautan airmata
jangan letupkan peluru / logam akan menangis
Ini bukan sekadar larik puitik, tetapi seruan etis yang sangat tajam. Larik tersebut menghadirkan paradoks yang menyakitkan: air mata ditanggapi dengan gas air mata; duka dijawab dengan logam dan pentungan. Dalam konteks post-struktural, puisi ini mencairkan struktur relasi kekuasaan dan membalikkan wacana kekuatan: logam, senjata, pentungan, semua akhirnya “menangis”, karena tidak bisa lagi menahan arus etika yang muncul dari tubuh rakyat. Di sini estetika menjadi alat untuk mengekspos kekerasan simbolik maupun fisik yang dibungkus dalam narasi resmi negara.
Sutardji tidak berhenti pada luka yang besar, ia juga merekam trauma yang subtil, bahkan absurd, sebagaimana dalam sajak “Jembatan”:
Wajah orang tergusur. Wajah yang ditilang malang. Wajah legam para pemulung yang memungut remah-remah pembangunan…
Tapi siapakah yang akan mampu menjembatani jurang di antara kita?
Di tengah pembangunan fisik—jalan raya, jembatan, gedung megah—Sutardji justru melihat jurang batin antarmanusia. “Jembatan” dalam puisi ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan simbol kemanusiaan yang hilang. Ia bertanya dengan getir: siapa yang akan menjembatani jurang sosial, empati, dan kemanusiaan? Inilah lirik yang memuat tragedi pascamodern: manusia saling menjauh justru ketika teknologi dan kota membesar.
Salah satu puisi yang juga menunjukkan bagaimana Sutardji menggubah luka menjadi bahasa tubuh adalah “Wahai Pemuda Mana Telurmu?”:
Apa gunanya merdeka / Kalau tak bertelur
Apa gunanya bebas / Kalau tak menetas?
Dalam ironi dan metafora telur, Sutardji menegur generasi muda yang pasif. Kata “bertelur” bukan hanya berarti reproduksi biologis, tetapi melambangkan kelahiran gagasan, visi, dan tindakan konkret. Tubuh menjadi tempat lahirnya sejarah baru. Ia ingin agar manusia tidak hanya menjadi konsumen sejarah, tetapi juga produsen makna. Maka, tubuh dalam puisi ini bukan hanya ruang biologis, tetapi politis dan profetik.
Dalam pendekatan teohumanistik, tubuh-tubuh dalam puisi Sutardji—baik tubuh penyair, tubuh rakyat, maupun tubuh kata—menjadi semacam medium spiritual. Penderitaan tak hanya dicatat, tetapi diolah menjadi liturgi, menjadi mantra, menjadi kidung perlawanan yang tidak frontal tetapi dalam dan menggugah.
Dari semua ini, tampak jelas bahwa puisi-puisi Sutardji bukanlah permainan fonetik yang kosong. Ia adalah tubuh puisi yang mengandung ingatan sosial, luka sejarah, dan renungan spiritual. Dalam tubuh puisi itulah luka menemukan tempatnya untuk berdiam dan—barangkali—disembuhkan melalui bahasa.
Tubuh Manusia dan Bahasa Imanensi
Dalam dunia puisi Sutardji Calzoum Bachri, tubuh bukan sekadar tema, tetapi menjadi medium sekaligus teks. Tubuh adalah bahasa itu sendiri—tempat makna tidak dideklarasikan secara langsung, tetapi digerakkan melalui ritme, pengulangan, dan perjumpaan inderawi. Salah satu puisi yang paling ekspresif dalam hal ini adalah puisi “Satu”, di mana tubuh menjadi tempat translasi spiritual antara aku dan engkau:
kuterjemahkan tubuhku ke dalam tubuhmu
ke dalam rambutmu kuterjemahkan rambutku
…
daging kita satu arwah kita satu
walau masing jauh / yang tertusuk padamu berdarah padaku
Puisi ini membongkar dikotomi tradisional antara tubuh dan jiwa. Daging bukanlah kuburan roh, melainkan tempat Roh menjelma, saling menerjemah, saling menghayati. Dalam pendekatan teohumanistik, tubuh di sini adalah liturgi: sesuatu yang dikuduskan oleh cinta, pengorbanan, dan keintiman eksistensial. Cinta bukan perasaan, melainkan kesatuan yang konkret: darah, jemari, usus, kelamin—semuanya menyatu sebagai bahasa imanensi.
Dalam kerangka post-strukturalisme, kita bisa menafsirkan tubuh dalam puisi Sutardji sebagai teks yang terbuka, sebagaimana dikatakan Roland Barthes dalam The Pleasure of the Text (1973): “The text is a tissue of quotations drawn from the innumerable centers of culture.” Tubuh, dalam puisi Sutardji, tidak memiliki pusat tunggal makna, tetapi selalu bergerak, menafsir dan ditafsir, menjadi arena intertekstualitas biologis.
Puisi-puisi lain juga memperlihatkan bagaimana tubuh menjadi locus bagi imanensi makna. Dalam puisi “Belajar Membaca”, tubuh—dalam hal ini kaki yang luka—menjadi medan permainan bunyi dan makna:
Kakiku Luka
Luka Kakiku
Kakikau Lukakah / Lukakah Kakikau
…
Lukakakukakiku Lukakakukakikaukah
Di balik permainan repetitif dan bunyi yang menyerupai mantra, larik-larik ini menyimpan keterkejutan eksistensial. Luka menjadi pusat semantik. Tubuh yang terluka bukan hanya merintih, tetapi juga menjadi teks yang harus “dibaca”. Di sinilah tubuh menjadi arena perjumpaan antara manusia dengan realitas terdalamnya: rasa sakit, kebingungan, dan usaha untuk memahami diri sendiri melalui bahasa. Julia Kristeva dalam Powers of Horror (1982) menyebut momen seperti ini sebagai abjection—ketika tubuh dan bahasa saling menolak dan saling membutuhkan, seperti luka yang menolak tapi tak terhindarkan.
Tubuh juga menjadi ladang pertanyaan eksistensial dalam puisi “Wahai Pemuda Mana Telurmu?”:
Setelah kupikir-pikir / manusia ternyata burung berpikir
Setelah kurenung-renung / manusia adalah burung merenung
Di sini, tubuh manusia dimetaforakan sebagai burung—bukan sekadar makhluk bebas yang bisa terbang, tetapi yang memiliki potensi bertelur, melahirkan gagasan, melanjutkan kehidupan. Tubuh bukan sekadar wadah pasif, tetapi ladang kesadaran dan aksi. Dalam teohumanistik, tubuh seperti ini bukanlah objek biologis, tetapi pohon makna, tempat di mana benih-benih spiritual dan historis bertunas.
Puisi “Ping Pong” juga menyiratkan gerakan tubuh dan bahasa sebagai satu tarikan irama:
ping di atas pong / pong di atas ping
ping ping dibilang pong / pong pong bilang ping
[…]
kutakpunya ping / kutakpunya pong
Larik-larik ini tidak menyampaikan makna literal, tetapi menjadi simulasi gerak tubuh—seperti permainan ping pong itu sendiri. Dalam permainan ini, makna bergerak terus-menerus, saling berganti dan tak pernah menetap. Tubuh penyair menjadi raket dan bola, sementara bahasa menjadi ruang permainan. Ini adalah contoh bagaimana Sutardji menciptakan puisi yang berlangsung di tubuh, bukan di kepala.
Akhirnya, tubuh dalam puisi Sutardji adalah tempat segala kemungkinan tinggal. Ia bukan hanya simbol erotik, tetapi juga simbol politik, spiritual, dan linguistik. Ia adalah jembatan antara makna dan absurditas, antara luka dan pengharapan, antara manusia dan yang Ilahi. Tubuh menjadi puisi, dan puisi menjadi tubuh. Di sanalah imanensi berlangsung—tak di awan, tak di surga, tetapi di sini, dalam daging, dalam tulang, dalam getar bahasa.
Puisi, Kata, dan Kesunyian Spiritual
Dalam dunia perpuisian Sutardji Calzoum Bachri, kata bukanlah sekadar alat komunikasi, tetapi jejak pencarian spiritual. Di balik bunyi-bunyi yang tampak seperti permainan linguistik, tersembunyi kesadaran akan keterbatasan manusia dalam memahami hakikat hidup, Tuhan, dan diri sendiri. Inilah wajah lain dari Sutardji: bukan sekadar pendobrak bahasa, tetapi penyair sufi, seorang peziarah sunyi yang merapal kata sebagai cara meraba Tuhan dalam gelap.
Dalam puisi “Walau”, Sutardji dengan jujur dan gamblang menuliskan:
walau penyair besar
takkan sampai sebatas allah
…
walau huruf habislah sudah
alifbataku belum sebatas allah
Pernyataan ini adalah bentuk pengakuan keterbatasan. Ia sadar bahwa sebesar apa pun usaha penyair, kata-kata tak akan pernah cukup untuk menjangkau Yang Maha Mutlak. Dalam pendekatan teohumanistik, larik ini mencerminkan spiritualitas yang tidak dogmatis, melainkan penuh kerendahan hati. Bahasa menjadi nyanyian pengembaraan—suatu bentuk via negativa, yakni pencarian ilahi lewat pengakuan akan ketiadaan kepastian.
Namun, pengakuan ini tidak membuat Sutardji menyerah. Justru di dalam keterbatasan kata, ia menemukan ruang kontemplasi. Dalam larik “jiwa membumbung dalam baris sajak”, Sutardji menempatkan puisi sebagai kendaraan rohani. Meskipun kata tidak dapat menjangkau Allah, namun ia bisa membumbung, menjadi doa, menjadi perih yang bernyanyi.
Dimensi kesunyian spiritual ini juga terasa dalam puisi “Bayangkan”:
bayangkan kalau tak ada anak-anak di bumi / aku kan lupa bagaimana menangis katanya
…
dan ditembaknya kepala sendiri / bayangkan
Puisi ini memperlihatkan ruang batin yang hampa, kehilangan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Wiski, tangis, anak-anak, dan pistol menjadi simbol spiritualitas yang runtuh, kesendirian eksistensial yang ditarik hingga titik absurditas. Di sinilah Sutardji membangkitkan kembali kesadaran bahwa makna hanya muncul ketika manusia dihadapkan pada batas, pada keputusasaan. Sebagaimana dikatakan Viktor Frankl, “manusia menemukan makna dalam penderitaan ketika semua bentuk lain runtuh.”
Sutardji tidak berhenti pada kesunyian yang menyesakkan. Dalam puisi “Mantera”, ia menghadirkan spiritualitas sebagai peristiwa bahasa yang magis:
lima percik mawar / tujuh sayap merpati / sesayat langit perih / dicabik puncak gunung
…
kau jadi Kau!
Di sini, transformasi spiritual terjadi dalam dan melalui mantra. Kata “kau” menjadi “Kau”—huruf kapital yang melambangkan puncak pencarian, kemungkinan perjumpaan dengan Yang Ilahi. Dalam tradisi mistik Timur (seperti Jalaluddin Rumi atau Rabiah al-Adawiyah), pencarian Tuhan tidak selalu melalui tafsir rasional, tetapi melalui rapalan batin yang repetitif, penuh kasih, dan menggetarkan.
Dalam puisi “Tanah Air Mata”, meskipun secara permukaan ia berbicara tentang bangsa dan tanah air, tapi lapis terdalamnya adalah ratapan spiritual:
kami coba simpan nestapa / kami coba kuburkan duka lara
tapi perih tak bisa sembunyi / ia merebak kemana-mana
Kesedihan di sini bukan hanya sosial, tapi juga metafisis. Perih yang tak bisa sembunyi itu adalah simbol dari dosa kolektif, kehilangan kasih, dan kehampaan spiritual yang tersebar ke mana-mana. Kata dalam puisi ini bukan pernyataan, tetapi tangis yang tak bisa ditampung oleh kata mana pun.
Dalam pandangan pascamodern religius seperti yang ditawarkan John D. Caputo (The Prayers and Tears of Jacques Derrida, 1997), tangis dan doa menjadi bentuk bahasa yang paling jujur ketika manusia menyadari kerapuhan kata-kata. Sutardji, tanpa menyebut nama Tuhan secara eksplisit, telah membawa puisinya menuju ruang spiritualitas tak bernama—tempat perih, cinta, kerinduan, dan kata menjadi satu.
Puisi sebagai kesunyian spiritual adalah kekuatan tersembunyi dalam karya-karya Sutardji. Ia bukan penyair yang berkoar di mimbar ideologi, melainkan seorang pengembara yang diam-diam mengukir puisi sebagai zikir.
Komitmen Humanistik: Dari Anak-anak sampai Kaum Tergusur
Salah satu dimensi paling kuat dan menyentuh dari puisi-puisi Sutardji Calzoum Bachri adalah komitmennya terhadap kemanusiaan—suatu keberpihakan puitik terhadap mereka yang terpinggirkan, tertindas, atau terlupakan dalam pusaran zaman. Ia memang dikenal sebagai pendobrak bentuk dan kredo bahasa, tetapi di balik eksperimen estetiknya, tersembunyi suara lirih kaum kecil, nyaringnya jeritan sunyi anak-anak, dan suara resah para pemuda yang merindu keadilan. Dalam tubuh puisinya, estetika dan etika menyatu: keindahan bukanlah hiasan, tetapi seruan kemanusiaan.
Dalam puisi “Bayangkan”, Sutardji memetakan kehampaan spiritual dan moral manusia modern yang tersesat dalam pusaran konsumerisme dan kekerasan:
bayangkan kalau tak ada anak-anak di bumi / aku kan lupa bagaimana menangis katanya
direguknya wiski / sambil mereguk tangis
lalu diambilnya pistol dari laci
bayangkan kalau aku tak mati-mati katanya / dan ditembaknya kepala sendiri
Puisi ini menggambarkan alienasi eksistensial yang akut. Wiski, anak-anak, dan tangis menjadi metafora nilai-nilai dasar yang hilang dari jantung masyarakat modern: kasih, kepolosan, dan rasa iba. Dalam larik tersebut, “anak-anak” menjadi simbol harapan dan kesadaran nurani, sementara pistol menjadi lambang keputusasaan sosial. Sutardji menyuarakan ironi tragis: jika manusia lupa cara menangis, maka dunia telah kehilangan esensinya sebagai tempat tinggal manusia.
Komitmen humanistik itu menjadi semakin eksplisit dalam puisi “Jembatan”, di mana Sutardji menulis dengan nada retoris namun penuh luka:
Wajah orang tergusur. Wajah yang ditilang malang.
Wajah legam para pemulung yang memungut remah-remah pembangunan.
…
siapakah yang akan mampu menjembatani jurang di antara kita?
Puisi ini berfungsi sebagai kritik sosial sekaligus panggilan batin. Ia menggarisbawahi kontradiksi besar dalam pembangunan bangsa: jembatan dibangun secara fisik, tapi jurang sosial justru menganga makin lebar. Sutardji mempertanyakan nurani kolektif bangsa: apakah kita benar-benar satu bangsa bila tidak saling menjembatani? Dalam pendekatan humanisme kritis, pertanyaan ini merupakan refleksi mendalam akan kegagalan politik dalam merawat empati dan kesetaraan sosial.
Nada serupa juga terasa dalam puisi “Wahai Pemuda Mana Telurmu?”, di mana Sutardji menyindir generasi muda yang diam dan tak bertindak:
Apa gunanya merdeka / Kalau tak bertelur
Burung jika tak bertelur / sia-sia saja terbang bebas
…
Wahai para pemuda / wahai garuda / menetaslah!
Di sini, metafora “telur” digunakan untuk menyimbolkan produktivitas sosial, kreativitas politik, dan lahirnya generasi pembaru. Sutardji tidak hanya menggugah intelektual para pemuda, tetapi juga menggugat mereka agar bangkit, bersuara, dan menetas sebagai penentu masa depan. Puisi ini secara tersirat menjadi manifestasi etos tanggung jawab kultural dalam bingkai keindahan simbolik.
Sementara dalam puisi “Ayo”, Sutardji menulis dengan nada profetik:
para muda yang raib nyawa / karena tembakan
yang pecah kepala / sebab pentungan
mereka telah nyempurnakan bakat gemilang sebagai airmata
Puisi ini menjadi bentuk peringatan terhadap arogansi kekuasaan. Ia mengangkat keberanian para pemuda yang kehilangan nyawa, namun justru karena itu menjadi simbol sejarah dan air mata kolektif bangsa. “Ayo” bukan hanya ajakan aksi, tetapi panggilan empati: agar aparat, penguasa, dan rakyat sama-sama membaca ulang luka bersama sebagai bagian dari kewargaan.
Komitmen humanistik Sutardji juga hadir secara subtil dalam penghormatan pada yang dilupakan. Dalam puisi “Tanah Air Mata”, misalnya, ia menulis:
di balik etalase megah gedung-gedungmu / kami coba sembunyikan derita kami
tapi perih tak bisa sembunyi / ia merebak ke mana-mana
Kata-kata ini menggambarkan pengalaman invisibilitas kaum kecil dalam narasi besar bangsa. Etalase pembangunan sering kali menyilaukan, menutupi derita riil yang terjadi di belakang layar kemajuan. Melalui larik-lariknya, Sutardji mengulurkan tangan pada yang tertinggal, yang terluka, yang dibungkam.
Dalam pendekatan sosiologis-simbolik, puisi-puisi ini adalah bentuk resistensi terhadap dominasi narasi tunggal negara dan pasar. Sutardji, lewat puisi, membangun ruang tanding wacana. Ia menciptakan ruang estetika untuk empati, suara sunyi untuk yang tak terdengar.
Mantra dan Masa Depan: Merawat Daya Cipta Puisi
Bagi Sutardji Calzoum Bachri, mantra bukan sekadar gaya, melainkan fondasi epistemologis puisi dan cara hidup sebagai penyair. Ia tidak menulis puisi untuk menyampaikan pesan, tetapi untuk merapalkan ulang kenyataan. Mantra adalah bahasa yang tidak disusun oleh logika, melainkan oleh ritme batin, getaran bunyi, dan kekuatan pengulangan. Dalam Kredo Puisinya, Sutardji menegaskan bahwa kata-kata harus dibebaskan dari beban pengertian, karena mereka adalah makhluk, bukan alat.
Dalam puisi “Ping Pong”, ia menulis:
kutakpunya ping
kutakpunya pong
Larik ini memancarkan filsafat kekosongan identitas tunggal. Ia menolak biner-biner usang—ping dan pong, subjek dan objek, aku dan kau, kanan dan kiri. Penyair di sini tidak berpihak pada satu sisi, tetapi melampaui dikotomi, memilih menjadi liminal, makhluk antara yang tak berhenti bergerak. Dalam perspektif post-strukturalis, Sutardji memerankan apa yang disebut Derrida sebagai kehadiran tertunda (deferred presence): tak pernah tunggal, tak pernah final. Dalam dunia modern yang terlalu cepat memilih kubu dan terlalu mudah memberi label, puisi-puisi Sutardji adalah ruang kebebasan simbolik yang menolak dipenjarakan oleh sistem.
Namun, liminalitas itu tidak berarti apatis. Sebaliknya, ia penuh panggilan kepada masa depan. Dalam puisi “Wahai Pemuda Mana Telurmu?”, Sutardji memberi kritik keras tapi penuh cinta kepada generasi muda. Metafora “bertelur” dalam konteks ini bukan sekadar reproduksi biologis, melainkan kreativitas historis: melahirkan gagasan, menetas visi, menumbuhkan peradaban. Sutardji menyadari bahwa puisi tidak bisa berdiri sendiri dalam ruang estetik—ia harus membumi, menjelma sebagai tindakan kreatif dan transformatif.
Dalam puisi “Satu”, ia menunjukkan bahwa daya cipta tidak bisa hanya bertumpu pada rasio. Ia perlu tubuh, darah, dan keintiman eksistensial:
aku terjemahkan jemariku ke dalam jemarimu
ke dalam darahmu kuterjemahkan darahku
daging kita satu arwah kita satu
Ini bukan sekadar puisi cinta, tetapi ritual translasi kemanusiaan. Dalam menghadapi masa depan yang dipenuhi kecanggihan teknologi dan kecemasan eksistensial, puisi ini mengingatkan bahwa yang hakiki tetaplah perjumpaan manusiawi, penghayatan tubuh, dan roh yang menyatu.
Sutardji juga mengisyaratkan bahwa puisi adalah bentuk perlawanan terhadap kekakuan sistem, terhadap penyeragaman makna. Dalam puisi “Tragedi Winka & Sihka”, permainan kata dan visual tipografi menggambarkan siklus hidup-manusia sebagai sesuatu yang absurd sekaligus berirama. Kata-kata seperti “kawin,” “winka,” dan “sihka” diturunkan secara vertikal dan diulang dalam variasi bunyi, membentuk totem liris yang menghidupkan mantra modern. Di sini, puisi adalah gerak spiritual dan biologis yang tak henti melingkar—sebuah warisan oral nusantara yang dibalut dalam gaya avant-garde.
Dalam puisi “Mantera”, Sutardji tidak hanya menyuarakan kata sebagai makna, tetapi sebagai kekuatan pencipta:
tiga menyan luka / mengasapi duka / puah! / kau jadi Kau!
Dalam larik ini, Sutardji menghidupkan kembali fungsi puisi sebagai penciptaan ontologis. Kata “puah!” menjadi kata performatif, semacam fiat lux dalam dunia puisi, yang mampu “mengubah yang kau menjadi Kau” — dari manusia fana menjadi simbol ilahi. Di sinilah kita menyaksikan Sutardji sebagai penyair-dukun, yang tak hanya mengolah bahasa, tapi merapal realitas.
Sebagai bentuk komitmen terhadap masa depan puisi, Sutardji tidak pernah berhenti menyuarakan puisi sebagai daya hidup. Dalam puisinya yang lebih mutakhir seperti dalam “Kecuali” (2021), ia masih menunjukkan kesegaran imajinasi dan kesetiaan pada bentuk eksperimental, menggabungkan kritik sosial, absurditas kontemporer, dan humor surealis. Meski usia menua, daya ciptanya tak pernah padam.
Maka dari itu, dalam dunia yang semakin dibanjiri oleh kata-kata instan, opini bising, dan narasi-narasi algoritmis, puisi Sutardji justru menjadi oasis kontemplatif dan kreatif. Mantra yang ia bangun tidak hanya merawat bahasa, tetapi merawat kemanusiaan—yang tak melulu logis, tapi mistik; tak selalu biner, tapi ambigu; tak tunggal, tapi jamak.
Penutup: Syair, Sutardji, dan Suara Abadi
Sutardji Calzoum Bachri bukan hanya seorang penyair. Ia adalah tonggak. Ia adalah palu yang memecah beku bentuk puisi Indonesia modern dan membangkitkannya menjadi tubuh hidup yang bernapas, menari, dan merapal. Dengan Kredo Puisi yang monumental, ia membebaskan kata dari jeruji makna sempit dan menempatkannya kembali pada kedudukan primordial: sebagai mantra, sebagai makhluk spiritual, bukan sekadar alat komunikasi. Dalam tubuh renta yang tetap bertenaga membaca puisi di berbagai forum, Sutardji bukan hanya hadir sebagai penulis, tetapi sebagai penjaga lidah puisi itu sendiri.
Sebagaimana ia tulis dalam “Ana Bunga”:
tetes lilin mengusapusap punggungku / Ana Bunga / Oh hewan meleleh / Aku cinta yang padakau!
Lilin itu adalah puisinya sendiri: membakar perlahan tapi memberi cahaya, meleleh dalam cinta pada bahasa, manusia, dan Indonesia. Sutardji telah menulis bukan dari kepala, tapi dari tubuh dan napasnya. Ia adalah puisi itu sendiri—yang terus menyala bahkan ketika dunia berubah, bahkan ketika sunyi lebih banyak hadir daripada tepuk tangan.
Kontribusi Sutardji bagi perkembangan sastra Indonesia tidak hanya terletak pada eksperimen estetiknya, tetapi juga pada pergeseran paradigma kepenyairan. Ia mengajarkan bahwa puisi tidak harus tunduk pada struktur naratif atau ideologis. Ia mengembalikan puisi kepada kebebasan, kepada gerak, kepada spiritualitas kata. Dalam hal ini, Sutardji adalah revolusioner linguistik dan teopoetik yang merintis jalan bagi pembacaan puisi di luar makna literal, menuju dunia pengalaman bunyi, rasa, dan tubuh.
Melalui puisi-puisi seperti “Ping Pong”, “Mantera”, “Tanah Air Mata”, hingga “Wahai Pemuda Mana Telurmu?”, Sutardji merintis bentuk-bentuk baru dalam kepenyairan Indonesia: puisi tipografi, puisi-mantra, puisi-aksara, puisi-nyanyian, dan puisi-jeritan batin. Ia memberi ruang bagi bunyi, bagi absurditas, bagi kehadiran yang selama ini dikecualikan dari puisi konvensional. Ia memindahkan fokus puisi dari apa yang dikatakan menjadi bagaimana kata itu hadir, berdenyut, dan mengalir.
Tak terhitung penyair Indonesia pasca-1980-an yang terilhami oleh keberaniannya Semangat pembebasan bahasa ala Sutardji masih hidup dan menjalar dalam berbagai eksperimentasi puisi kontemporer. Ia menjadi patron sekaligus sumur. Namun lebih dari itu, Sutardji memberi kita pelajaran etis: bahwa menjadi penyair adalah menjadi penjaga nyala batin, menjadi saksi luka zaman, menjadi pelantun cinta dalam segala bentuknya. Ia menyatukan duka dan doa, politik dan tubuh, spiritualitas dan bunyi, menjadi satu rumah kata yang kokoh.
Dalam lanskap sastra Indonesia, Sutardji bukan hanya tonggak masa lalu, tetapi juga mata air masa depan. Puisinya tak selesai dibaca. Ia mengandung energi tafsir yang tak kunjung habis. Suaranya adalah suara abadi—yang akan tetap merapal, bahkan ketika dunia kehilangan arah, bahkan ketika kata-kata lain habis terbakar.
Jika Chairil Anwar memberi kita keberanian untuk hidup seribu tahun lagi, maka Sutardji memberi kita mantra untuk menulis hidup itu: dengan keberanian membebaskan kata, dengan kesetiaan kepada bahasa sebagai tubuh rohani.
Sutardji telah menjadi jembatan antara tradisi dan eksperimentasi, antara mantra dan modernitas, antara penyair dan kemanusiaan. Maka, selama bahasa masih hidup di mulut manusia, nama Sutardji akan tetap dibaca, dirapal, dan dikenang—bukan sebagai sekadar penyair besar, tapi sebagai roh bahasa itu sendiri.
****
Daftar Referensi:
Barthes, Roland. The Pleasure of the Text. New York: Hill and Wang, 1973.
Caputo, John D. The Prayers and Tears of Jacques Derrida. Bloomington: Indiana University Press, 1997.
Derrida, Jacques. Writing and Difference. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
Derrida, Jacques. Margins of Philosophy. University of Chicago Press, 1982.
Eagleton, Terry. Literature and Politics. Oxford: Blackwell, 1986.
Kristeva, Julia. Powers of Horror: An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press, 1982.
Kristeva, Julia. Revolution in Poetic Language. New York: Columbia University Press, 1984.
Kristeva, Julia. Tales of Love. New York: Columbia University Press, 1987.
Rahardjo, Maman S. Teohumanisme dalam Kritik Sastra Indonesia. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
Ratna, Nyoman Kutha. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Sapardi Djoko Damono. Sastra Indonesia Modern: Beberapa Catatan. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
Sapardi Djoko Damono. Puisi dan Makna. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
Sapardi Djoko Damono. Sastra Lisan dan Puisi Modern Indonesia. Jakarta: Grafiti, 1986.
Sutardji Calzoum Bachri. O, Amuk, Kapak. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
Sutardji Calzoum Bachri. Gerak Esai dan Ombak Sajak. Jakarta: Bentara Budaya, 2001.
Sutardji Calzoum Bachri. Kecuali. Jakarta: Bentara, 2021.
Teeuw, A. Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1980.
—-
*Tengsoe Tjahjono, dosen FIB Universitas Brawijaya Malang