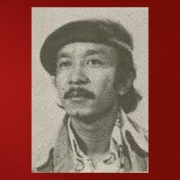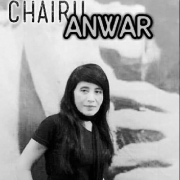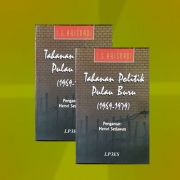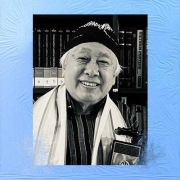Derrida di Puntung Rokok Rara Mendut
Oleh Purnawan Andra*
Dalam sejarah kebudayaan Jawa, tokoh Rara Mendut hadir bukan semata sebagai figur legenda perempuan cantik dari pesisir Jepara yang menolak tunduk pada kuasa Sultan Agung. Ia lebih dari sekadar cerita romantik atau semangat emansipatoris yang sering kali direduksi ke dalam dikotomi perempuan versus patriarki.
Rara Mendut adalah kompleksitas itu sendiri—sebuah simpul di mana tubuh, cinta, kekuasaan, dan nalar politik bertemu dalam narasi yang disampaikan secara liris, tetapi menyimpan luka epistemik yang panjang.
Membaca Rara Mendut secara dekonstruktif berarti menggugat kemapanan pengetahuan itu sendiri: siapa yang menulis sejarah? Untuk siapa tubuh perempuan diceritakan? Mengapa kisah yang membebaskan justru dibingkai dalam kerangka normatif?
Reinterpretasi
Dekonstruksi, sebagaimana ditawarkan oleh Jacques Derrida, bukanlah sekadar pembongkaran, melainkan sebuah upaya menunjukkan bahwa dalam setiap struktur makna, selalu ada kontradiksi internal yang memungkinkan reinterpretasi.
Dalam konteks Rara Mendut, dekonstruksi dapat diterapkan untuk membongkar relasi kuasa dan simbolik dalam narasi-narasi yang membentuk citra dirinya. Bukan hanya patriarki yang menjadi objek kritik, tetapi juga cara narasi budaya itu sendiri menstabilisasi makna lewat pengulangan.
Rara Mendut adalah tubuh yang terus-menerus dipertontonkan: baik dalam kesusastraan, pentas ketoprak, hingga karya film dan pertunjukan kontemporer. Tubuh itu menjadi medan tafsir yang tak selesai, dan di sinilah kekuatan dekonstruktif bekerja.
Tubuhnya bukan hanya simbol kecantikan atau resistensi terhadap kekuasaan, melainkan juga ruang tafsir bagi penonton untuk mereproduksi hasrat, kekuasaan, dan mitos. Melalui perspektif dekonstruktif, kita diajak menyadari bahwa representasi atas Rara Mendut sebagai perempuan cantik nan kuat bisa jadi merupakan perulangan dari logika yang sama: menjadikan perempuan sebagai objek simbolik, bukan subjek historis.
Cerita Rara Mendut biasanya diposisikan sebagai tragedi cinta yang heroik—seorang perempuan yang menolak dijadikan selir oleh Tumenggung Wiraguna dan memilih cinta tulus kepada Pranacitra, dengan harga hidupnya sendiri. Namun, jika kita membaca dengan cara Derridean, kita dapat menggugat oposisi-oposisi biner yang menyusun narasi ini: laki-laki/perempuan, kuasa/cinta, negara/individu.
Ketika cinta dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap negara, maka cinta pun tak lagi netral. Ia dikonstruksi sebagai senjata yang melawan, bukan sebagai afeksi murni. Maka, cinta Rara Mendut tak bisa kita baca hanya sebagai metafora kebebasan, tapi juga sebagai arena perebutan makna: siapa yang memiliki cinta, dan dalam logika apa cinta itu bisa disebut bebas?
Dalam konteks antropologi budaya, Rara Mendut adalah gambaran betapa tubuh perempuan dalam masyarakat feodal diperlakukan sebagai medium transaksi politik. Namun, di sisi lain, ia juga menjadi lokasi etika—tempat nilai-nilai seperti kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dikultuskan. Rara Mendut menjual rokok linting di pasar, namun memilih untuk tidak menjual tubuhnya.
Posisi ini mengguncang tatanan nilai, karena di tengah masyarakat yang permisif terhadap dominasi bangsawan, ia menyisipkan etika tubuh yang otonom. Namun, otonomi ini pun perlu dibaca ulang secara kritis. Apakah tubuh Rara Mendut sungguh otonom, ataukah justru dikooptasi oleh narasi budaya untuk menjadi teladan moral bagi perempuan lainnya?
Dengan pendekatan dekonstruktif, kita bisa mencermati bahwa tubuh Mendut tidak netral. Ia adalah tubuh yang dikonstruksi untuk menyampaikan pesan tertentu. Bahkan ketika ia disebut sebagai perempuan merdeka, kerap kali kemerdekaan itu dibingkai dalam moralitas yang domestik: ia tidak menjual diri, ia setia pada satu lelaki, ia mati demi cinta. Dekonstruksi mengajak kita mencurigai narasi-narasi ini: apakah benar kemerdekaan Mendut ditentukan oleh pilihan tersebut, ataukah ia tak punya pilihan lain dalam logika sistem sosial yang timpang?
Sebagaimana diungkapkan Gayatri Spivak dalam kritiknya atas representasi perempuan dalam kolonialisme, sering kali perempuan diwakili oleh “pria dari kelas atas” yang berbicara atas nama mereka. Dalam konteks ini, Mendut pun tak luput dari pengaruh tersebut: siapa yang menceritakan kisahnya? Mengapa ia selalu ditampilkan dalam bingkai laki-laki, entah sebagai kekasih, musuh, atau penyelamat?
Refleksi ini penting dalam konteks Indonesia hari ini, ketika pendidikan dan budaya populer kerap mengulang narasi yang sama atas tokoh-tokoh perempuan. Di televisi, media sosial, bahkan dalam kampanye moral, perempuan seperti Rara Mendut direproduksi sebagai simbol ketaatan, etika cinta, atau keberanian diam-diam. Namun, logika-logika simbolik itu justru menjebak: perempuan dinilai bukan berdasarkan pilihan bebasnya, tetapi berdasarkan kecocokannya dengan norma simbolik yang berlaku.
Subversi Narasi Lokal
Lebih jauh, pendekatan dekonstruktif juga bisa membuka jalan bagi pembacaan mendalam tentang bagaimana narasi lokal seperti Rara Mendut sebetulnya menyimpan subversi-subversi kecil yang selama ini tersembunyi.
Ketika Mendut menjual rokok dan menolak tunduk, ia bukan hanya menolak tubuhnya dijadikan alat politik, tapi juga menantang logika kerja yang bias gender. Ia bekerja, bukan untuk dipelihara. Ia memilih, bukan dipilihkan.
Dalam kerangka ini, kisah Rara Mendut dapat dibaca sebagai bentuk epistemologi pinggiran—suatu pengetahuan yang tumbuh dari luar pusat kuasa, tetapi yang tetap direpresi oleh dominasi narasi.
Pendidikan, seni, dan budaya hari ini perlu membuka ruang untuk membaca ulang kisah-kisah semacam ini, bukan sebagai romantisisme masa lalu, tetapi sebagai kritik terhadap cara kita menyusun wacana hari ini.
Maka, Rara Mendut bukan hanya cerita cinta yang tragis. Ia adalah tanda, dan tanda itu selalu bisa dibaca ulang, ditantang, dan dipertanyakan. Seperti yang ditekankan Derrida, tidak ada makna yang tetap. Maka tidak ada satu pun tafsir final atas tubuh, cinta, dan kematian Rara Mendut. Yang ada adalah keberanian untuk terus menafsirkan, agar sejarah tidak membatu dalam bingkai kekuasaan tunggal.
Dalam konteks hari ini, ketika tubuh perempuan masih dijadikan alat kampanye moral, ketika cinta masih diperdagangkan dalam format sinetron, dan ketika kemerdekaan perempuan masih dibatasi oleh norma sosial, kisah Rara Mendut mengajak kita untuk terus curiga, terus membaca ulang, dan terus bertanya: siapa yang bicara, atas nama siapa, dan untuk kepentingan siapa? Inilah tugas pembacaan dekonstruktif: bukan untuk merayakan relativisme, tetapi untuk mengungkap batas-batas pengetahuan yang selama ini kita anggap wajar.
Dengan begitu, membaca Rara Mendut adalah membaca diri kita sendiri: bagaimana kita memperlakukan tubuh, bagaimana kita memahami cinta, dan bagaimana kita—tanpa sadar—mewarisi logika kuasa yang kita kritik sendiri.
—–
*Purnawan Andra, alumnus Governance & Management of Culture Fellowship Program di Daegu Catholic University Korea Selatan.