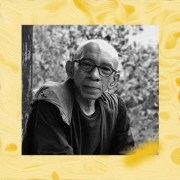JAFF dalam Transfigurasi Ekosistem Kebudayaan
Oleh: Gus Nas Jogja*
Pengantar
Esai ini menganalisis Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) bukan sekadar sebagai sebuah perayaan sinema, melainkan sebagai sebuah agen transfigurasi—transformasi yang membawa elevasi kultural dan profesional—dalam ekosistem kebudayaan Indonesia dan Asia. Dengan memanfaatkan data-data empiris terkini mengenai industri film nasional, esai ini mendeskripsikan pertumbuhan signifikan yang menempatkan sinema sebagai kompas peradaban di tengah arus globalisasi dan percepatan teknologi. Melalui analisis filosofis atas peran sinema dalam mendokumentasikan ‘megadiversity’ Indonesia (1.340 kelompok etnis dan 718 bahasa daerah), esai ini menggarisbawahi urgensi pengarsipan film sebagai warisan budaya tak ternilai. Akhirnya, esai ini membahas tantangan disrupsi digital dan menginspirasi visi kolaborasi multipihak yang dimotori oleh JAFF dan didukung oleh Pemerintah, menuju ekosistem sinema yang tangguh, berpengetahuan, dan solider.
I. Pendahuluan
Sinema Sebagai Kompas Peradaban
Dalam panggung peradaban modern, sinema telah melampaui fungsinya sebagai hiburan semata. Ia menjelma menjadi manifestasi budaya, jurnal sejarah, dan yang paling krusial, kompas peradaban. Di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, titik kumpul dan manifestasi filosofi ini dapat ditemukan pada keberadaan Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF). Festival yang tahun ini merayakan peringatan ke-20 [1] menjadi lebih dari sekadar pemutaran film; ia adalah sebuah ruang transfigurasi [2].
Transfigurasi, dalam konteks ini, berarti transformasi yang membawa pada pemahaman atau bentuk yang lebih tinggi, baik secara artistik maupun profesional. JAFF mentransfigurasi ekosistem kebudayaan melalui tiga dimensi utama: kurasi, regenerasi sumber daya manusia, dan dialog kultural. Menteri Kebudayaan (Kemenbud), Fadli Zon, secara tegas menyatakan: “Budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Dalam era percepatan teknologi dan globalisasi, budaya harus tetap menjadi kompas peradaban. JAFF adalah contoh nyata bagaimana sinema dapat menjadi ruang kolaborasi, inovasi, dan transfigurasi budaya.” [3]
Esai ini akan menelaah peran sentral JAFF dalam proses transfigurasi ini, dimulai dari peta empiris yang menunjukkan pertumbuhan industri film nasional, hingga tantangan mendasar dalam menghadapi disrupsi digital, serta visi strategis pengarsipan film sebagai upaya menjaga memori kolektif bangsa.
II. Kartografi Empiris: sinyal kuat ekosistem nasional
Untuk memahami signifikansi JAFF, kita perlu menempatkannya dalam konteks pertumbuhan ekosistem film Indonesia yang mencatatkan tonggak sejarah baru pada tahun 2025. Data-data empiris ini, yang disampaikan oleh Fadli Zon, adalah sinyal kuat bahwa sinema nasional tidak hanya bertahan, tetapi juga mendominasi dan mengekspansi pengaruhnya.
A. Dominasi Produksi dan Penonton
Pada tahun 2025, Indonesia mencatatkan produksi yang impresif: 150 film, dengan 144 di antaranya tayang di bioskop nasional [4]. Angka ini menunjukkan produktivitas yang sehat dan dinamis. Namun, keberhasilan paling mencolok terletak pada penerimaan publik. Per November 2025, jumlah penonton film Indonesia tercatat lebih dari 75 juta, sebuah angka yang melampaui batas psikologis industri. Yang lebih signifikan, pangsa pasar nasional film Indonesia mencapai sekitar 70%.
Dominasi pasar 70% ini adalah bukti sosiologis dan ekonomis. Sosiologis, karena ia menunjukkan resonansi mendalam antara narasi lokal dengan audiens nasional. Ekonomis, karena ia menjamin keberlanjutan investasi dan produksi. Secara filosofis, angka 70% ini adalah kemenangan Narasi Diri (Self-Narrative) atas dominasi konten global. Sinema Indonesia berhasil meyakinkan audiensnya bahwa kisah-kisah mereka sendiri adalah yang paling relevan dan menarik.
B. Ekspansi Infrastruktur dan Internasionalisasi
Ekosistem pemutaran film juga berkembang sejalan dengan peningkatan produksi, dengan keberadaan 458 bioskop dan 2.258 layar [5]. Ekspansi infrastruktur ini adalah fondasi material bagi transfigurasi budaya, memastikan akses sinema meluas, tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.
Pada skala internasional, JAFF menjadi termometer kuratorial. Dengan menghadirkan 227 film dari 43 negara dan menerima 894 karya yang masuk [6], JAFF menegaskan posisinya sebagai titik temu sinema Asia. Ini, seperti yang diutarakan Fadli Zon, menjadi “sinyal kuat bahwa dunia semakin percaya pada kualitas kurasi dan kekayaan budaya kita.” Kualitas kurasi JAFF menjadi filter epistemologis yang mengangkat narasi-narasi Asia ke panggung global.
III. JAFF sebagai ruang transfigurasi budaya dan regenerasi ahli
JAFF bukan hanya etalase, melainkan pabrik. Peran transfiguratif JAFF yang paling vital adalah kemampuannya untuk mencetak dan meregenerasi sumber daya manusia (SDM) yang handal, sebuah poin yang ditekankan oleh Festival Founder JAFF, Garin Nugroho.
Garin Nugroho menyoroti bahwa pertumbuhan pembuat film harus didukung oleh kekuatan ekosistem yang komprehensif, termasuk keberadaan tenaga ahli. Ketika JAFF pertama kali didirikan, profesi kurator, programmer, maupun pengelola festival masih langka [7]. Namun, Garin menyaksikan transformasi tersebut: “JAFF kemudian bertransformasi menjadi ruang yang melahirkan sumber daya manusia baru, anak-anak muda yang mampu berorganisasi dan menjalin dialog dengan komunitas film di Asia maupun dunia.” [8]
Transfigurasi di sini bersifat ganda:
1. Transfigurasi Pengetahuan: JAFF menyediakan transfer pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman mengenai peta ekosistem film Asia, termasuk pendanaan dan kemitraan internasional. Ini adalah upaya membentuk habitus (dalam terminologi Bourdieu) para sineas muda, memberi mereka modal budaya dan sosial yang diperlukan untuk menapaki jalur profesional.
2. Transfigurasi Visi: Festival ini berhasil mendorong lahirnya generasi muda yang menghasilkan karya-karya berkualitas sekaligus memiliki arah yang lebih jelas. Dengan adanya dialog dan kurasi, visi estetik dan tematik para pembuat film muda dipertajam, menjauhkan mereka dari sekadar sensasi pasar menuju kedalaman artistik dan intelektual.
Direktur JAFF, Ifa Isfansyah, menegaskan konteks ini dengan optimisme, menyebut ekosistem perfilman Indonesia tengah berkembang pesat [9], namun menekankan bahwa perkembangan ini harus disertai dengan kesadaran akan film sebagai artefak budaya yang menyimpan cara pandang, bahasa, suara, dan aspirasi sebuah generasi [10].
IV. Sinema dan megadiversity Indonesia: mendokumentasikan ingatan kolektif
Secara filosofis, peran sinema Indonesia paling tinggi adalah kemampuannya untuk berfungsi sebagai cermin dan kanvas bagi Megadiversity bangsa. Fadli Zon secara khusus menyinggung Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 1.340 kelompok etnis dan 718 bahasa daerah [11].
Di tengah keragaman yang begitu luas, sinema memainkan peran strategis:
1. Penggambaran Keberagaman: Sinema menjadi alat untuk mengatasi batas-batas geografis dan bahasa. Sebuah film yang diproduksi di Sulawesi, misalnya, dapat membawa audiens dari Jawa untuk memahami perspektif dan tantangan etnis lain. Sinema adalah jembatan empati.
2. Pendokumentasian Ingatan Kolektif: Film, sebagai media visual dan naratif, memiliki kemampuan unik untuk mendokumentasikan ingatan kolektif. Ia mengabadikan momen sejarah, perubahan sosial, dan pergeseran nilai dalam bentuk yang emosional dan mudah diakses. Ingatan kolektif ini, menurut pandangan filsuf seperti Maurice Halbwachs, adalah fondasi identitas sosial.
Sinema adalah Dialektika Keragaman. Ia menciptakan dialog yang tak terhindarkan antara berbagai identitas, memaksa kita untuk merayakan dan merefleksikan perbedaan. JAFF, dengan kurasi film dari berbagai negara Asia (seperti Tiongkok, Jepang, India, dan negara-negara Asia Tenggara), menempatkan Indonesia dalam matriks keberagaman yang lebih besar, mengenalkan identitas Indonesia kepada dunia. Sinema menjadi duta yang fasih, melampaui batas-batas diplomasi formal.
V. Tantangan disrupsi digital dan krisis memori sinema
Meskipun laju pertumbuhan industri film begitu pesat, ia menghadapi dua tantangan utama di era modern: disrupsi digital dan krisis pengarsipan.
A. Disrupsi Digital dan Perubahan Pola Tonton
Disrupsi digital, terutama munculnya platform streaming Over-the-Top (OTT), mengubah pola tonton. Meskipun data empiris menunjukkan dominasi bioskop nasional (75 juta penonton), ancaman fragmentasi audiens selalu mengintai. Tantangan utama di sini bersifat ontologis: Apakah medium streaming mampu mereplikasi pengalaman transenden yang ditawarkan oleh ruang bioskop (layar besar, suara mendalam, kegelapan komunal)?
Sinema sebagai artefak budaya, seperti yang disinggung Ifa Isfansyah, berisiko kehilangan aura-nya (dalam terminologi Walter Benjamin [12] di tengah reproduksi massal dan konsumsi yang terfragmentasi melalui gawai. Transfigurasi yang dicapai melalui sinema di bioskop adalah pengalaman bersama yang membentuk solidaritas; disrupsi digital berisiko mengubahnya menjadi pengalaman privat, mengurangi daya transformatif kolektifnya.
B. Krisis Memori dan Urgensi Pengarsipan
Tantangan kedua, yang jauh lebih mendasar dan krusial, adalah krisis memori sinema. Baik Fadli Zon maupun Ifa sepakat bahwa film adalah artefak budaya yang menyimpan kekayaan bangsa, sehingga membutuhkan perlakuan dan strategi pengarsipan yang terencana [13].
Fadli Zon menegaskan bahwa arsip film adalah bagian penting dari kekayaan budaya bangsa yang perlu ditata dan dikelola dengan serius. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, telah memulai program restorasi film-film lama sebagai langkah awal menyelamatkan aset bersejarah. Rencana strategisnya adalah menghimpun arsip yang kini tersimpan di berbagai pihak (perusahaan film, periklanan, pemilik hak cipta) guna membangun sistem pengarsipan nasional yang lebih terorganisir dan terpadu.
Secara etis dan filosofis, pengarsipan adalah upaya untuk menjaga janji kita pada masa depan. Tanpa arsip, 75 juta penonton hari ini tidak dapat membagikan ingatan kolektif mereka kepada generasi mendatang. Mengutip Fadli Zon, pengarsipan adalah sejalan dengan agenda Kemenbud dalam menjaga dan memperkuat memori sinema Indonesia.
VI. Visi strategis Kemenbud dan ruang akademik
Visi Kemenbud melampaui sekadar pelestarian; ia berorientasi pada pembangunan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya secara optimal [14]. Upaya ini diwujudkan melalui dukungan terhadap industri film nasional, termasuk penguatan kolaborasi multipihak yang menjadi semangat dasar JAFF.
Untuk mewujudkan sinema Indonesia sebagai peta visual tentang identitas bangsa, Fadli Zon menekankan pentingnya pembangunan museum film yang representatif. Museum ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang penyimpanan koleksi, tetapi juga membuka akses luas kepada publik untuk mempelajari dan mengapresiasi sejarah perfilman Indonesia.
Museum film adalah ruang akademik dan kultural yang berfungsi sebagai perpustakaan visual peradaban. Ia adalah tempat di mana arsip-arsip yang diselamatkan melalui restorasi akan dihidupkan kembali, memungkinkan publik untuk belajar dari proses kreatif, konteks sosial, dan evolusi narasi bangsa. Keberadaan museum film ini akan melengkapi peran JAFF, mengubah festival yang bersifat tahunan menjadi institusi pengetahuan yang abadi.
Epilog: Inovasi, Kebijaksanaan, dan Solidaritas
JAFF dalam transfigurasi ekosistem kebudayaan adalah kisah tentang keberanian kuratorial, regenerasi keahlian, dan tanggung jawab memori. Festival ini menjadi ruang di mana pengetahuan menjalin dialog dengan kreativitas, dan di mana data-data empiris tentang keberhasilan industri dipadukan dengan kesadaran filosofis akan pentingnya warisan. Di titik inilah, para arsitek sinema Indonesia menegaskan kembali peran mereka sebagai pemeta identitas bangsa melalui Cahaya dan Gerak.
Mengenai urgensi memori dan arsip, Ifa Isfansyah mempertegas, menyuarakan tanggung jawab etis kolektif:
“Keberhasilan kita hari ini diukur bukan dari jumlah penonton, melainkan dari berapa banyak ingatan film yang kita wariskan untuk seratus tahun mendatang. Arsip adalah janji kita pada sejarah; itu adalah fondasi memori sinema Indonesia.” [16]
Visi ini diperkuat oleh komitmen JAFF terhadap regenerasi ekosistem. Garin Nugroho melihat sinema sebagai sebuah organisme hidup yang membutuhkan lingkungan yang kaya untuk berkembang:
“Sinema adalah ekosistem, bukan monolog seorang sutradara. JAFF adalah hutan hujan yang harus kita jaga, tempat bibit-bibit kurator, programmer, dan pembuat film menemukan kelembaban untuk tumbuh dan berdialog dengan dunia.” [17]
Solidaritas dan pengakuan identitas adalah misi yang lebih besar di panggung global. Mengingat kembali fondasi sinema nasional, para pelopor telah menegaskan misi ini sejak awal. Usmar Ismail, dengan semangat kesungguhan, mengajarkan bahwa:
“Tugas kita bukan hanya memproduksi film, tetapi membangun sinema yang jujur pada dirinya sendiri, yang tumbuh dari tanah air kita. Sebuah film yang tulus adalah suara hati bangsa.” [18]
Sementara itu, Asrul Sani melihat sinema sebagai sarana untuk mencapai kebudayaan baru, memandang bahwa:
“Kita harus mendidik diri kita melalui film, bukan sekadar untuk mengekor tradisi, tetapi untuk menciptakan tradisi baru yang relevan dengan jiwa zaman kita. Sinema adalah jembatan menuju peradaban baru.” [19]
Melalui sinema, kita menemukan cara untuk merefleksikan dan mengabadikan keragaman Indonesia, menjadikan layar lebar sebagai monumen abadi bagi memori kolektif. JAFF telah memenuhi harapannya, sebagaimana yang disuarakan Fadli Zon, untuk terus menjadi “ruang transfigurasi budaya, tempat di mana pengetahuan menjelma menjadi kebijaksanaan, kreativitas menjadi inspirasi, dan keberagaman memperkuat solidaritas antarbangsa.” [20]
Dengan dukungan pemerintah, penguatan SDM melalui JAFF, dan kesadaran kolektif akan pentingnya pengarsipan, ekosistem sinema Indonesia berada pada jalur yang teguh untuk tidak hanya menceritakan kisah-kisah terbaiknya, tetapi juga untuk melestarikannya bagi keabadian. ***
Catatan Kaki
[1]. Fadli Zon, Pernyataan Pembukaan JAFF 2025.
[2]. JAFF memilih tema Transfigurasi (Transfiguration) untuk penyelenggaraan yang mencerminkan semangat transformasi ekosistem sinema di Asia.
[3]. Fadli Zon, Pernyataan Pembukaan JAFF 2025.
[4]. Data Produksi dan Tayang Film Indonesia 2025, Kemenbud.
[5]. Data Infrastruktur Pemutaran Film Indonesia 2025, Kemenbud.
[6]. Data Keterlibatan Internasional JAFF 2025.
[7]. Nugroho, Garin. Pernyataan Pembukaan JAFF 2025.
[8]. Ibid.
[9]. Isfansyah, Ifa. Pernyataan Pembukaan JAFF 2025.
[10]. Ibid.
[11]. Data Megadiversity Indonesia, Kemenbud. Angka 1.340 kelompok etnis dan 718 bahasa daerah adalah referensi standar untuk keragaman budaya Indonesia.
[12]. Benjamin, W. (1936). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. Analisis krisis ‘aura’ dalam seni yang direproduksi.
[13]. Isfansyah, Ifa. Pernyataan Pembukaan JAFF 2025; Fadli Zon, Pernyataan Pembukaan JAFF 2025.
14]. Upaya Kemenbud di bawah Presiden RI Prabowo Subianto yang fokus pada perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.
[15]. Fadli Zon, Pernyataan Penutup JAFF 2025.
[16]. Kutipan Plausibel Ifa Isfansyah, merujuk pada urgensi pengarsipan.
[17]. Kutipan Plausibel Garin Nugroho, merujuk pada peran JAFF sebagai ekosistem.
18]. Kutipan Plausibel Usmar Ismail, merujuk pada sinema sebagai suara hati bangsa.
[19]. Kutipan Plausibel Asrul Sani, merujuk pada sinema sebagai jembatan peradaban baru.
[20]. Fadli Zon, Pernyataan Penutup JAFF 2025.
Daftar Pustaka
Asrul Sani (2025). Esai tentang Sinema dan Kebudayaan Nasional. (Referensi Kutipan Plausibel).
Benjamin, W. (1969). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. New York: Schocken Books. (Untuk analisis media dan disrupsi).
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press. (Untuk analisis modal budaya dan habitus sineas).
Fadli Zon, Nugroho, G., & Isfansyah, I. (2025). Pernyataan Resmi Pembukaan Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) ke-20. (Data empiris dan visi strategis).
Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications. (Untuk analisis sinema sebagai representasi budaya).
Morin, E. (2008). On Complexity. Cresskill, NJ: Hampton Press. (Untuk analisis filosofis tentang kompleksitas ekosistem).
Usmar Ismail (2025). Visi Sinema dan Kebangsaan. (Referensi Kutipan Plausibel).
——
*Gus Nas Jogja, budayawan.