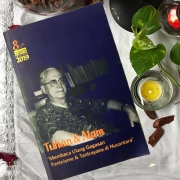Puisi-puisi Abdul Wachid B.S.
BALADA JIN PENJAGA SUMUR LANGGAR
Di balik langgar kayu tua
yang menganga sepi selepas Isya,
ada sumur kecil
berlumut hijau dan bercahaya samar
seperti mata yang tak ingin dilihat.
Tak ada yang berani menimba
kecuali mereka yang telah bersuci
dan menyebut nama-Nya
dengan nafas pelan
dan dada tunduk.
Dulu, kata Mbah Sarwan,
ada jin alim yang menjaga sumur itu.
Ia tak suka keramaian
tapi selalu tersedu
setiap santri mengaji sambil menangis.
Ia duduk di pelipir batu,
berjubah angin,
berwajah tak berbentuk,
menjaga air agar tak dicuri oleh
mereka yang haus tapi lupa adab.
Air itu bukan hanya basuhan,
tapi bagian dari zikir
yang turun dari langit
dalam bentuk tetes-tetes cahaya.
Pernah seorang pemuda pongah
menimba dengan tertawa
tanpa basmalah.
Air memercik ke wajahnya,
dan malam itu ia bermimpi:
ada tangan transparan
mengusap dahinya
dan berkata lirih,
“Air ini bukan milikmu,
ia milik mereka yang tahu
bagaimana bersyukur
tanpa suara.”
Jin itu tidak marah,
ia hanya menyelinap kembali
ke lubuk sumur,
menyanyikan ayat-ayat
yang tak dikenal manusia,
dengan nada seperti
bayi yang dilantunkan ke surga.
Dan setiap malam Jum’at,
jika langgar sepi
dan lampu gantung berkedip tiga kali,
seorang santri bisa mendengar
bunyi rantai halus dari dasar sumur,
seperti tasbih
yang digesek angin.
Itulah penjaga,
makhluk yang tak ingin disembah,
tapi menjadi saksi
bahwa air pun bisa suci
jika dijaga
oleh yang tak kasat mata.
2025
BALADA BONEKA JARAN KEPANG
Di lapangan kecil
depan masjid tua yang hampir rubuh,
anak-anak berkumpul
mengitari seorang lelaki renta
yang membawa peti kayu
dan senandung lirih dari mulutnya
berbau dupa dan malam.
Dari peti itu,
keluar boneka jaran kepang,
kuda pipih dari anyaman bambu,
matanya merah dari sisa arang,
dan tali-tali lusuh
yang melilit tubuhnya
seperti janji yang tak pernah lepas.
“Ini bukan mainan,”
bisik lelaki tua.
“Ini perantara
antara bumi yang diam
dan langit yang mendengar zikir.”
Seorang bocah,
dengan mata terkatup
dan tubuh rapuh oleh gelisah,
menunggangi boneka itu
sambil menyebut satu nama
berulang-ulang,
seperti zikir yang tak diajarkan
tapi datang dari suara leluhur.
Lalu angin berputar,
suara gamelan ghaib
bergema dari tanah,
dan si bocah jatuh dalam diam
tanpa sadar tubuhnya menari,
dililit semut,
digigit mimpi,
digerakkan oleh sesuatu
yang bukan dirinya
tapi tak membahayakan jiwanya.
Ia tidak kerasukan.
Ia berserah.
Seperti daun yang jatuh
dalam pelukan angin subuh,
anak itu menari
bukan untuk tontonan,
tapi untuk melepaskan
beban yang tak bisa ditangis
dengan mata terbuka.
Dari balik barisan orang,
seorang ibu menggenggam tasbih,
menggumam doa-doa pelindung,
dan boneka itu
seolah mengangguk
dalam gerakan samar.
Ketika musik berhenti,
anak itu rebah,
keringatnya wangi,
dan matanya basah
oleh sesuatu
yang hanya bisa disebut
sebagai rahmat
yang turun melalui permainan.
“Ini bukan sihir,”
ujar lelaki tua,
“ini adalah tanda:
bahwa tubuh bisa jadi bait,
dan gerak bisa jadi sujud,
jika hati tak menolak
untuk dipimpin oleh cahaya.”
Dan malam itu,
boneka jaran kepang
dikembalikan ke peti,
bersama sebait puisi
yang hanya bisa dibaca
oleh mereka yang pernah
menari di dalam diri sendiri
dan menemukan Tuhan
tanpa kata.
2025
BALADA BURUNG BLEDUG DI GUNUNG TUGEL
Di lereng Gunung Tugel
sebelum embun mengenal cahaya,
seekor burung bledug terbang
dari kawah yang tak terpetakan suara,
bulunya gemetar oleh kidung
yang tak pernah diajarkan manusia.
Ia bukan burung biasa.
Ia lahir dari sepi
yang direbus dalam lava malam,
dari petir yang bersujud
pada tanah yang pasrah.
Di bawah langit buta,
ia menyanyi
dengan paruh dari sabda,
dan sayap dari doa
yang tak sampai.
“Tunggulah,”
kata seorang bocah penggembala
yang belum belajar huruf
namun hafal sunyi dari padang,
“burung itu akan kembali,
membawa hikmah
yang tak bisa kau ikat
dengan pena.”
Orang-orang datang,
dari dusun,
dari pesantren,
dari kota,
membawa kamera dan keraguan,
merekam langit
dengan mata penuh debu.
Namun hanya seorang perempuan renta
di pinggir jurang sunyi
yang bersujud tanpa suara,
melihat bayangan burung itu
turun sebagai cahaya
yang tidak menyilaukan,
tapi menghapus luka.
Lalu, bledug dari kawah
menyeruak seperti nafas Nabi
di tengah peperangan batin:
menderu tapi lembut,
menghentak tapi menenangkan.
Burung itu pun membentangkan
sayapnya dari ayat-ayat ghaib,
lalu mematuk satu-satu
keangkuhan dalam dada
yang menyangka diri
paling tahu arah langit.
“Ini bukan mitos,”
kata bayangannya
di dinding kabut.
“Ini peringatan:
jangan mendaki gunung suci
dengan sepatu ego
dan tongkat ilmu yang kosong.”
Burung itu tak meninggalkan jejak
kecuali angin
yang mengubah hati,
dan gemuruh yang menyisakan
kesadaran akan Ketiadaan.
Dan malam itu,
Gunung Tugel menangis
bukan karena longsor,
tapi karena ada satu ruh
yang kembali
ke asal mulanya
tanpa gaduh,
tanpa pamit,
hanya sebaris puisi
yang menguap
bersama suluk di dada bumi.
2025
BALADA BAYANGAN TUA DI PINTU MAKAM
Malam turun di punggung mimpi,
dan angin membawa nyanyian
yang hanya dikenal
oleh jiwa yang ditinggalkan raga.
Di pintu makam tua,
seorang lelaki renta
berdiri tanpa nama,
tanpa waktu.
Jubahnya dari debu
yang mengerti sunyi.
Matanya seperti telaga
yang telah meneguk
cahaya ribuan bintang.
“Bulan menyentuh batu nisan
dengan cahaya
yang tak biasa,”
bisiknya dalam bahasa
yang tidak diajarkan
oleh kitab sekolah.
Ia menyebut namaku
dengan suara
yang lebih tua dari ingatan.
Dan aku menangis
bukan karena takut,
tapi karena mengenal
suara itu
di dalam diriku sendiri.
Ia menunjuk
pada pusara yang sunyi,
tempatku biasa ziarah
tanpa nama tertulis.
“Kau simpan duka
di balik sajadah
yang basah oleh air matamu.”
Lalu,
tanpa suara,
ia duduk
dan mulai membaca
tulisan yang terukir
bukan oleh tangan,
tapi oleh lintasan
cahaya dan doa.
“Seolah membuka hikmah
yang tersembunyi
di balik huruf-huruf kitab,”
katanya,
dan tanah pun bergetar
dalam diam.
Ia tak memberi wejangan,
tak membawa tasbih,
hanya diam
dan seberkas cahaya
mengelilingi tubuhnya
seperti zikir yang tak terputus.
“Hanya dibimbing
oleh Nur Nama-Nya
yang menyatu
dalam suluk semesta,”
katanya sebelum lenyap
menjadi bayang-bayang
yang menyatu
dengan kabut pagi.
Dan aku terbangun,
dalam peluh dan syukur.
Di depan pintu makam,
tak ada siapa-siapa.
Hanya harumnya bunga
yang tak pernah aku bawa.
2025
BALADA BAYI DARI DALAM GENTONG CAHAYA
Di tengah malam tanpa arah
seseorang menemukan gentong tua
di bawah pohon kamboja.
Tak ada yang menduga,
di dalamnya, air berpendar
dan seorang bayi menangis
tanpa suara.
Bayi itu tak lahir
dari rahim wanita,
tapi dari bumi yang pasrah
dan doa-doa yang ditanam
oleh para pejalan sunyi.
Airnya bening,
mata bayi itu menyimpan zikir
yang belum dilafalkan manusia.
“Jangan ganggu dia,”
kata seorang kakek renta
berjubah daun jati.
“Dia ruh yang dicuci
dari debu zaman.
Dia tak menangis karena lapar,
tapi karena dunia
tak sanggup lagi mendengar
suara fitrah.”
Orang-orang berdatangan,
membawa lentera,
membawa kamera,
membawa doa yang gugup.
Tapi air dalam gentong itu
mendadak gelap,
kecuali bagi seorang perempuan buta
yang membasuh wajah bayi itu
dengan tangis diam-diam.
Bayi itu bukan sekadar lahir,
tapi diturunkan
sebagai ayat
yang belum ditafsirkan.
Setiap kelopak matanya
membawa musim sujud,
dan denyut nadinya
menulis syahadat
di dalam tanah.
“Ia bukan anak kita,”
kata seorang pemuda yang tersesat,
“ia anak langit
yang dititipkan bumi
agar kita belajar lahir
kembali dengan cinta.”
Bayi itu kemudian
terangkat oleh cahaya,
seperti embun yang dihisap langit.
Gentong itu retak
dan pecah menjadi bunga,
dengan harum yang tak dikenal
oleh kalender dan sejarah.
Dan malam itu,
sebuah desa yang lupa sujud
mendadak sunyi
kecuali suara air
menyebut nama
yang tak berhuruf,
tapi hidup dalam dada
kita semua.
2025
—-
Abdul Wachid B.S., lahir 7 Oktober 1966 di Bluluk, Lamongan, Jawa Timur. Dia lulus Sarjana Sastra dan Magister Humaniora di UGM, dan lulus Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. AWBS menjadi Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.
Buku terbarunya, Kisah untuk Anak Cucu (Kumpulan Puisi Balada, Penerbit Diva Press, 2025). Melalui buku bunga rampai esai Sastra Pencerahan, Abdul Wachid B.S. menerima penghargaan Majelis Sastrawan Asia Tenggara (Mastera) sebagai karya tulis terbaik kategori pemikiran sastra, pada 7 Oktober 2021 (tepat di ulang tahunnya yang ke-55).***