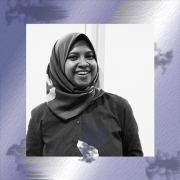Isra Mi’raj dalam Tafsir Sastra
Dialektika Cahaya, Ruang, dan Waktu
Oleh: Gus Nas Jogja
Ketika malam mencapai titik nadir keheningannya, sebuah peristiwa kosmik yang melampaui seluruh nalar fisika Newton dan mekanika kuantum meledak dalam kesunyian. Isra Mi’raj bukanlah sekadar migrasi horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu vertikal menembus tujuh samudra langit menuju Sidratul Muntaha. Dalam tafsir sastra, ia adalah sebuah Puisi Agung Tuhan yang ditulis pada lembaran semesta dengan tinta cahaya, di mana Nabi Muhammad ﷺ bertindak sebagai subjek sekaligus saksi atas realitas absolut yang tak terjamah oleh kemiskinan kata-kata.
Secara filosofis, peristiwa ini adalah proklamasi tentang kedaulatan ruh atas materi. Di saat dunia hari ini terjebak dalam disrupsi digital yang mendewakan kecepatan simulasi, Isra Mi’raj mengingatkan kita akan adanya “kecepatan cahaya batin” yang mampu melipat dimensi ruang dan waktu. Ini adalah perjalanan melampaui batas sejarah, sebuah transendensi puitis yang menghubungkan tanah yang fana dengan hamparan Arsy yang abadi.
Pertemuan Nasut dan Lahut
Dalam kacamata Bayani, Isra Mi’raj adalah manifestasi dari teks suci yang tak terbantahkan. Tafsir Jalalain dengan tegas menekankan bahwa perjalanan ini dilakukan dengan ruh dan jasad dalam keadaan terjaga (yaqazhatan). [1] Ini bukan mimpi yang menguap, melainkan kebenaran empiris-spiritual yang menantang akal sempit manusia. Sastra ketuhanan dalam peristiwa ini terlihat pada penyebutan kata Asra (memperjalankan), yang menunjukkan bahwa sang Nabi adalah subjek yang “ditarik” oleh magnet cinta Sang Khalik.
Tafsir Al-Maraghi menambahkan dimensi psikologis dalam teologi ini; bahwa peristiwa ini adalah tasliyah (penghibur) Ilahi. [2] Secara sastrawi, ini adalah metafora tentang bagaimana penderitaan bumi—kepergian Khadijah dan Abu Thalib—dijawab oleh Tuhan dengan undangan perjamuan di singgasana cahaya. Tuhan tidak mengirimkan solusi material yang dangkal, melainkan memberikan perspektif Ilahiyah bahwa setiap duka di bumi hanyalah setitik debu di bawah kaki keagungan abadi.
Manusia sebagai Mikrokosmos
Secara Burhani, Isra Mi’raj adalah argumen rasional tentang posisi manusia sebagai Khalifatullah. Nabi Muhammad ﷺ melewati lapisan langit dan bertemu dengan para nabi terdahulu—Adam, Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa, hingga Ibrahim—adalah narasi logis tentang kontinuitas intelektual dan spiritual manusia. Tafsir At-Thabari merinci pertemuan ini sebagai simbol pewarisan estafet kebenaran yang koheren. [3]
Antropologi Isra Mi’raj mengajarkan bahwa manusia bukan sekadar entitas biologis yang terbelenggu gravitasi, melainkan entitas spiritual yang memiliki kapasitas untuk “naik” (Mi’raj). Dalam tafsir sastra, ini adalah “Dialog Lintas Zaman” di mana Nabi merangkum seluruh esensi kemanusiaan. Tafsir Al-Khazin menggarisbawahi sapaan “Saudara yang Saleh” di setiap langit sebagai pengakuan antropologis bahwa harmoni bumi harus mencerminkan harmoni langit; tatanan yang dibangun di atas fondasi persaudaraan, bukan kompetisi kekuasaan yang rakus. [4]
Sidratul Muntaha dan Etika Semesta
Melalui kacamata Irfani, kita melihat Sidratul Muntaha bukan sekadar objek, melainkan simbol ekologi batiniah yang paling dalam. Pohon Bidara di batas akhir semesta adalah proklamasi bahwa puncak pencapaian spiritual manusia adalah harmoni dengan alam. Sastra ekofilsafat melihat ini sebagai teguran keras bagi manusia modern: jika di batas tertinggi langit saja Tuhan menggunakan simbol pohon yang menaungi semesta, betapa hinanya manusia yang di bumi menebang hutan demi berhala kapitalisme.
Tafsir Al-Maraghi menggambarkan pohon ini diliputi cahaya yang tak terlukiskan warnanya, menunjukkan bahwa keindahan metafisika selaras dengan kelestarian fisika. [5] Ekologi Isra Mi’raj adalah ekologi cahaya. Jantung Nabi dibersihkan dengan air zam-zam sebelum keberangkatan, melambangkan bahwa revolusi spiritual menuntut kemurnian ekologis; kesucian jiwa hanya bisa tumbuh di atas bumi yang dijaga kehijauannya.
Filosofi Ruang dan Waktu: Detik Ilahi di Tengah Disrupsi
Fisikawan mungkin berbicara tentang Wormhole atau relativitas, namun sastra Isra Mi’raj berbicara tentang Barakah. Waktu yang digunakan Nabi ﷺ sangat singkat, namun pengalaman yang didapat melampaui ribuan tahun sejarah. Secara filosofis, ini adalah kritik tajam terhadap pandangan waktu linier Barat yang mekanistik dan menjemukan.
Dalam Isra Mi’raj, waktu bersifat sirkular dan kualitatif. Tafsir Jalalain menyebutkan peristiwa ini terjadi dalam sekejap malam atau lailan. [6] Kata lailan (bentuk nakirah) dalam sastra Arab menunjukkan sebagian kecil malam yang penuh misteri. Ini adalah filsafat “Detik Ilahi”—bahwa di tangan Tuhan, satu momen bisa menjadi keabadian. Manusia modern yang dikejar oleh detak jam digital harus belajar bahwa kualitas hidup ditentukan oleh “ketinggian pendakian batin”, bukan oleh kecepatan pergerakan fisik yang hampa makna.
Dialektika Sosial: Shalat sebagai Mi’raj Harian
Hasil dari perjalanan kosmik ini bukanlah teknologi militer atau supremasi politik, melainkan perintah Shalat. Secara antropologi-sosial, shalat adalah bentuk demokrasi spiritual yang paling radikal. Dalam ruku’ dan sujud, raja dan hamba, konglomerat dan fakir, berdiri sejajar menghadap Kiblat yang sama, menghancurkan sekat-sekat kasta sosial.
Sastra shalat adalah sastra ketundukan total. Shalat disebut sebagai Mi’rajul Mu’minin. Artinya, setiap jiwa memiliki akses “jalur cepat” untuk menemui Tuhan tanpa perantara, tanpa birokrasi, dan tanpa biaya. Ini adalah desentralisasi spiritual—bahwa akses menuju Yang Maha Absolut terbuka bagi siapa saja yang mampu merundukkan egonya yang setinggi gunung di atas hamparan sajadah yang rendah.
Menanam Cahaya di Bumi yang Terluka
Isra Mi’raj dalam tafsir sastra adalah panggilan untuk kembali ke titik nol kemanusiaan. Di tengah dunia yang penuh dengan intervensi kebencian dan bayang-bayang perang nuklir, Isra Mi’raj menawarkan visi perdamaian universal. Jika Nabi ﷺ bisa merangkul para nabi dari berbagai era dan tradisi di Masjidil Aqsa, mengapa kita yang menghuni bumi yang mungil ini justru sibuk saling menghancurkan?
Perjalanan ini adalah pengingat bahwa tujuan akhir manusia bukanlah penaklukan planet-planet asing, melainkan penaklukan terhadap diri sendiri. Menulis sejarah dengan sastra Isra Mi’raj berarti menulis sejarah dengan tinta cinta, bukan dengan mesiu. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai kompas moral untuk membangun peradaban yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga luhur secara budi dan puitis dalam tindakan.
Integrasi Bayani: Teks sebagai Jembatan Realitas
Dalam wilayah Bayani, Isra Mi’raj adalah puncak dari kejujuran linguistik Tuhan. Al-Qur’an memulai narasi ini dengan tasbih: “Subhanalladzi…” (Maha Suci Dzat yang…). Diksi ini bukan sekadar pembuka, melainkan sebuah proklamasi epistemologis bahwa akal manusia harus menunduk di hadapan kemahasuciuan-Nya. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa penggunaan kata ‘Abdihi (Hamba-Nya) dalam ayat tersebut adalah gelar tertinggi yang diberikan Tuhan kepada manusia; bukan sebagai penguasa, bukan sebagai tuhan kecil, melainkan sebagai hamba yang terhubung secara organik dengan Sang Maha Pencipta. [7]
Sastra Bayani mengajarkan kita bahwa teks Isra Mi’raj adalah sebuah “Peta Jalan Transendental”. Ia memberikan struktur pada sesuatu yang tak terstruktur. Kehadiran para Nabi di Baitul Maqdis yang bermakmum kepada Rasulullah ﷺ secara Bayani adalah pengesahan teks-teks samawi terdahulu ke dalam satu muara risalah. Ini adalah bentuk “Literasi Global” yang pertama, di mana seluruh peradaban nubuwwah disatukan dalam satu barisan shalat.
Dialektika Burhani: Rasionalitas Cahaya dan Logika Ekstasi
Secara Burhani, Isra Mi’raj menantang kita untuk membangun rasionalitas baru—sebuah “Logika Ekstasi”. Jika sains hari ini berbicara tentang multi-verse atau dimensi ke-11, maka Mi’raj adalah bukti empiris-spiritual bahwa dimensi-dimensi tersebut dapat ditembus oleh kesadaran yang murni. Tafsir Al-Maraghi menggunakan pendekatan Burhani untuk menjelaskan bahwa setiap lapisan langit adalah simbol dari tingkatan ilmu pengetahuan dan realitas material yang harus dilalui manusia sebelum mencapai puncak Sidratul Muntaha. [8]
Burhani dalam peristiwa ini bukan untuk menalar “bagaimana” teknis perjalanannya, melainkan “mengapa” perjalanan itu terjadi. Logika Burhani menyimpulkan bahwa Mi’raj adalah demonstrasi tentang martabat manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diizinkan melampaui batas batas malaikat (Jibril berhenti di Sidratul Muntaha, sementara Muhammad ﷺ lanjut melampauinya). Ini adalah argumen kuat bagi antropologi Islam bahwa manusia memiliki potensi intelektual dan spiritual yang tak terbatas, jauh melampaui algoritma AI atau kecerdasan mesin manapun.
Estetika Irfani: Penyingkapan Tabir dalam Keheningan
Visi Irfani membawa kita pada kedalaman rasa (dzauq). Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad ﷺ melihat dengan “mata hati” (Al-Fu’ad). Al-Qur’an mencatat: “Ma zaghal basharu wa ma thagha” (Penglihatannya tidak berpaling dan tidak melampaui batas). Inilah etika Irfani: dalam puncak kejayaan spiritual pun, manusia harus tetap memiliki kontrol diri dan ketundukan.
Dalam kacamata Irfani, Sidratul Muntaha bukan sekadar pohon fisik, melainkan metafora tentang “Batas Pengetahuan”. Di sanalah akal berhenti dan cinta mengambil alih. Sastra Irfani menggambarkan momen ini sebagai “Perjamuan dalam Sunyi”. *Tafsir Al-Khazin* merenungkan bagaimana cahaya Tuhan menyelimuti pohon tersebut hingga tak ada lagi kata yang sanggup melukiskan warnanya. [9] Irfani mengajarkan bahwa ekologi sejati adalah ketika manusia memandang alam bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai tajalli (manifestasi) keindahan Tuhan.
Analisis Ekologi: Etika Hijau dari Langit Ketujuh
Menyambung visi Irfani, dimensi ekologi Isra Mi’raj adalah antitesis dari antroposentrisme yang merusak. Pemilihan simbol pohon (Sidrah) sebagai titik puncak pertemuan mahluk-Khalik adalah proklamasi teologis tentang kesucian alam. Esai ini memandang peristiwa Isra Mi’raj sebagai “Ekologi Nubuwwah”. Jika surga dan batas tertinggi alam semesta digambarkan dengan sungai-sungai dan pepohonan, maka merusak sungai dan hutan di bumi adalah tindakan penistaan terhadap arsitektur langit.
Etika ekologi ini menuntut kita untuk memperlakukan bumi sebagai “Sajadah Raksasa”. Sebagaimana Nabi membersihkan diri sebelum Mi’raj, kita tak boleh bersujud di atas bumi yang telah dikotori oleh limbah ketamakan. Kesucian spiritual tak terpisahkan dari kelestarian lingkungan.
Menjadi Manusia Mi’raj di Bumi Disrupsi
Pada akhirnya, Isra Mi’raj dalam tafsir sastra, antropologi, dan ekologi adalah sebuah peta jalan untuk pulang. Di tengah kebisingan era disrupsi, di mana manusia sering kali kehilangan arah dalam rimba informasi, Mi’raj menawarkan navigasi menuju pusat cahaya.
Mari kita tuliskan kembali sejarah kemanusiaan kita dengan pena Bayani yang jujur, akal Burhani yang tajam, dan rasa Irfani yang lembut. Menjadi “Manusia Mi’raj” berarti menjadi pribadi yang kakinya berpijak kuat di bumi untuk melayani sesama dan menjaga alam, namun ruhnya senantiasa terbang tinggi menggapai rida Ilahi. Karena hanya dengan pendakian batin yang konsisten, kita dapat memenangkan pertempuran melawan kegelapan zaman dan perang nuklir yang mengancam—dengan senjata cahaya, cinta, dan sajak-sajak abadi dari Sidratul Muntaha.
Puncak Irfani: Fana dan Baqa dalam Samudra Cahaya
Dalam kasta tertinggi visi Irfani, Isra Mi’raj adalah narasi tentang Fana (lenyapnya ego) dan Baqa (kekal bersama Tuhan). Di Sidratul Muntaha, ketika Jibril sang pembawa wahyu tak lagi sanggup melangkah karena sayap-sayap cahayanya akan terbakar oleh keagungan Tuhan, Nabi Muhammad ﷺ melangkah sendirian. Ini adalah metafora sastrawi yang paling dahsyat: bahwa pada titik tertentu, ilmu pengetahuan (episteme) harus berhenti dan menyerahkan tongkat estafetnya kepada cinta (eros/isyq).
Pencapaian ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan “Mikrokosmos yang menelan Makrokosmos”. Sebagaimana diungkapkan dalam Tafsir Al-Khazin, saat itu Nabi berada dalam jarak Qaba Qausaini au Adna (jarak dua ujung busur panah atau bahkan lebih dekat). [11] Secara Irfani, ini bukan kedekatan jarak spasial, melainkan kedekatan esensial. Di sinilah rahasia teologi cinta terungkap: bahwa manusia adalah cermin bagi keindahan Tuhan, dan Mi’raj adalah momen di mana cermin itu bertatap muka langsung dengan Sumber Cahayanya.
Rekonstruksi Antropologi: Manusia sebagai Jembatan Antar-Dimensi
Secara antropologis, kembalinya Nabi dari langit ketujuh ke bumi adalah bagian terpenting dari Isra Mi’raj. Jika perjalanan ini hanya berhenti di puncak ekstasi, maka ia hanya menjadi pengalaman mistis pribadi. Namun, Nabi ﷺ memilih turun kembali ke bumi, membawa “kado” berupa Shalat dan risalah kemanusiaan.
Visi Burhani melihat kembalinya Nabi sebagai tanggung jawab sosial seorang intelektual-spiritual. Manusia Mi’raj adalah manusia yang tidak asyik dengan kesalehan individunya di puncak “gunung cahaya”, melainkan manusia yang mau turun ke lembah-lembah penderitaan rakyat untuk menyembuhkan luka sosial. Antropologi Islam melalui Mi’raj menuntut kita untuk menjadi jembatan: membawa nilai-nilai langit (keadilan, kejujuran, kasih sayang) untuk membumi dalam realitas sosiologis yang carut-marut.
Ekologi Nubuwwah: Bidara Sidrah sebagai Paru-Paru Iman
Membedah simbol Sidratul Muntaha melalui Tafsir At-Thabari, kita menemukan bahwa pohon tersebut adalah sumber dari empat sungai: dua sungai batin di surga dan dua sungai lahir di bumi (Nil dan Eufrat). [12] Ini adalah analisis ekologi yang sangat tajam. Al-Qur’an secara sastrawi menghubungkan ekosistem langit dengan ekosistem bumi.
Jika sumber air di bumi (seperti Nil dan Eufrat) secara metafisika terhubung dengan pohon di langit tertinggi, maka pencemaran lingkungan adalah tindakan memutus silsilah spiritual alam semesta. Esai ini menegaskan bahwa “Dosa Ekologis” adalah penghalang Mi’raj-nya doa-doa kita. Kita tidak bisa mengharapkan kucuran rahmat dari langit jika kita terus meracuni sungai dan membabat hutan yang merupakan “saudara kembar” dari pepohonan surga. Sastra ekologi dalam Mi’raj adalah seruan untuk melakukan Taubat Ekologis massal sebelum kiamat ekosistem benar-benar tiba.
Melampaui Disrupsi dan Ancaman Nuklir
Isra Mi’raj, dalam balutan Bayani, Burhani, dan Irfani, memberikan jawaban atas kegelisahan manusia modern. Di saat perang nuklir mengancam dengan cahaya penghancur (radiasi), Mi’raj menawarkan cahaya penyembuh (nurani). Di saat disrupsi digital mencabut akar kemanusiaan kita, Mi’raj menanam kembali akar tersebut di Sidratul Muntaha.
Sastra Isra Mi’raj adalah sastra harapan. Ia mengajarkan bahwa sesempit apa pun ruang gerak kita di bumi karena ketidakadilan, langit Tuhan selalu luas untuk pendakian jiwa. Menjadi manusia yang berakal Burhani, berdasar Bayani, dan berhati Irfani adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan peradaban ini dari kehancuran.
Mari kita rayakan Isra Mi’raj bukan sekadar sebagai upacara kalender, melainkan sebagai momentum untuk meretas batas diri, melintasi ego, dan terbang menuju hadirat-Nya dengan sayap ilmu dan iman. Sebab, pada akhirnya, setiap dari kita adalah musafir cahaya yang sedang belajar jalan pulang.
Maha Suci Allah ….
—-
Catatan Kaki
[1] Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi. Tafsir al-Jalalain. (Penegasan realitas fisik dan spiritual).
[2] Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi. Juz XV. (Analisis psikologi kenabian).
[3] Ibnu Jarir At-Thabari. Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an. (Konteks historis para Nabi).
[4] Alauddin al-Khazin. Tafsir Al-Khazin. (Relasi sosiologis antar-kenabian).
[5] Al-Maraghi. Op. Cit. (Simbolisme Sidratul Muntaha).
[6] Tafsir Al-Jalalain. Surat Al-Isra ayat 1. (Analisis linguistik kata Lailan).
[7] As-Suyuthi, J. Al-Khasa’is al-Kubra. (Keistimewaan gelar hamba dalam peristiwa Mi’raj).
[8] Al-Maraghi, A. M. Tafsir Al-Maraghi. Juz XV, hal. 12-15. (Tafsir rasional lapisan langit).
[9] Al-Khazin, A. Lubab al-Ta’wil. (Deskripsi puitis cahaya di Sidratul Muntaha).
[10] Iqbal, M. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. (Diskusi tentang Mi’raj sebagai pengalaman ruang-waktu).
[11] Al-Khazin, Alauddin. Lubab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil. (Tafsir surat An-Najm tentang kedekatan Nabi dengan Tuhan).
[12] At-Thabari, Ibnu Jarir. Jami’ al-Bayan. (Penjelasan tentang asal-usul sungai bumi dari Sidratul Muntaha).
[13] Chittick, William C. The Sufi Path of Knowledge. (Diskusi tentang tingkatan eksistensi dalam tasawuf).
[14] Schuon, Frithjof. Understanding Islam. (Analisis tentang dimensi vertikal dan horizontal manusia).
[15] Sudarsono. Filsafat Islam. (Penjelasan metode Bayani, Burhani, dan Irfani sebagai epistemologi Islam).
*Rujukan Ilmiah*
Al-Ghazali. Misykat al-Anwar. (Filsafat Cahaya).
Iqbal, Muhammad. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. (Filosofi Waktu).
Nasr, Seyyed Hossein. Man and Nature. (Ekologi Spiritual).
Schimmel, Annemarie. And Muhammad Is His Messenger. (Estetika Kenabian).
Chishti, S. H. The Sufi Doctrine of Rumi. (Analisis simbolisme pohon dalam sufisme).
Lings, Martin. Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources. (Narasi puitis Isra Mi’raj).
Corbin, Henry. Alone with the Alone: Creative Imagination in the Sufism of Ibn ‘Arabi. (Filosofi visi batin).
Soleh, Khudori. Filsafat Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer. (Penjelasan Bayani, Burhani, dan Irfani).
—–
*Gus Nas Jogja, Budayawan.